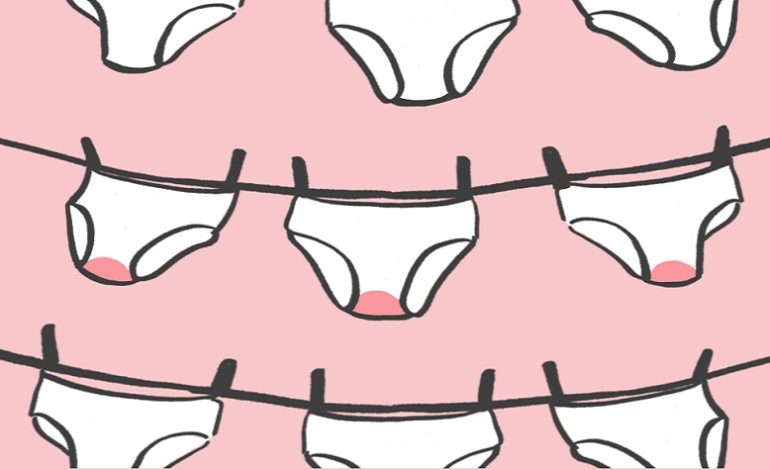Perempuan Hadapi Tantangan 2 Kali Lipat dalam Pilkada: Riset

Hasil penelitian dari organisasi yang berfokus pada kajian sosial politik berperspektif gender, Cakra Wikara Indonesia (CWI), menunjukkan saat mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah, perempuan mendapat tantangan dua kali lebih berat dibanding laki-laki. Selain harus membuktikan kapasitas mereka untuk memimpin, dalam proses pencalonan, perempuan juga harus menghadapi persoalan kultural yang masih menganggap perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin.
Dalam penelitian yang berlangsung Nov. 2019-Agt. 2020, CWI melibatkan para pemimpin daerah perempuan di Jawa, yakni Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Sri Sumarni; Bupati Jember, Jawa Timur, Farida; Walikota Batu, Jawa Timur, Dewanti Rumpoko; Walikota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini; dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa.
Dari hasil temuannya, CWI mengatakan perempuan pemimpin daerah cenderung tidak mendapat dukungan dari struktur partai di awal pencalonan karena struktur pengurus partai umumnya didominasi oleh laki-laki. Calon pemimpin perempuan perlu kerja ekstra untuk mendapatkan rekomendasi partai atau tokoh agama dan masyarakat yang masih mengedepankan laki-laki sebagai pemimpin, padahal tolok ukur elektabilitas yang menjadi acuan partai bersifat netral gender.
Peneliti CWI, Dirga Ardiansa mengatakan, calon kepala daerah perempuan sering kali dihadang isu personal, seperti status pernikahan, penampilan fisik, gaya bicara, keluwesan berkomunikasi dan lainnya yang hampir tidak pernah dipersoalkan dari seorang calon pemimpin laki-laki. Selain itu, rekam jejak yang mencakup kinerja personal perempuan sangat diperhitungkan ketika dicalonkan sebagai kepala daerah, ujarnya.
“Mereka harus bekerja lebih keras bahkan hanya untuk mendapat dukungan. Karena masih banyak yang percaya bahwa perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin. Negosiasi identitas gender dengan pelibatan tokoh agama menjadi faktor penting dalam memenangkan dukungan,” ujar Dirga dalam webinar “Perempuan Sebagai Kepala Daerah: Pola Kepemimpinan dan Kebijakan”, yang diadakan CWI (25/8).
Baca juga: Perempuan di Sumbar Jadi Kepala Daerah Cuma Ilusi?
Bupati Jember Faida, yang berlatar belakang sebagai pengusaha dan juga dokter, mengatakan tidak mendapat dukungan dari tokoh agama dan partai politik pada saat mencalonkan diri 2015 lalu.
“Saya pernah dapat pernyataan yang melecehkan dan meremehkan. Katanya, mohon maaf partai kami tidak bisa memberikan rekomendasi karena tokoh agama tidak ingin ada pemimpin perempuan,” ujar Farida, yang tidak pernah berkecimpung dalam politik sebelumnya.
“Dulu pemimpin perempuan itu disebut haram, tapi karena banyak pihak yang ingin ada perubahan, pada 2016 saya membuktikan diri bisa menang di pilkada,” ia menambahkan.
Farida memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat dukungan non-partisan seperti ibu-ibu, relawan, dan tokoh agama lainnya. Pencalonan Farida juga diiringi dengan gerakan “No Eks Birokrasi” sebagai wujud ketidakpercayaan masyarakat pada politisi birokrat yang dianggap tidak berhasil menjadi pemimpin.
Lain halnya dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang tidak mengalami hambatan berarti ketika mencalonkan diri pada 2016 lalu. Kendati demikian, dia telah menempuh jalan panjang sebagai birokrat, sehingga elektabilitasnya sebagai perempuan pemimpin tidak diragukan oleh partai atau pihak manapun. Risma pernah menjabat sebagai Kepala bagian Bina Pembangunan (2002-2005), Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (2005- 2008), dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (2008-2010) di Surabaya.
Peneliti CWI, Yolanda Panjaitan mengatakan, calon yang lain tidak mengalami proses menjadi birokrat seperti Risma cenderung menghadapi hambatan lebih besar.
Selain Risma, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa juga menjalani karier yang cukup panjang di dunia politik. Ia memulai dari organisasi keagamaan akar rumput, anggota legislatif sejak 1992, kemudian Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001) dan Menteri Sosial (2014-2018) sampai akhirnya berhasil menjadi Gubernur Jawa Timur setelah dua kali pemilihan kepala daerah gagal.
Calon kepala daerah perempuan sering kali dihadang isu personal, seperti status pernikahan, penampilan fisik, gaya bicara, keluwesan berkomunikasi dan lainnya yang hampir tidak pernah dipersoalkan dari seorang calon pemimpin laki-laki.
“Bu Khofifah mempunyai pola kepemimpinan yang akomodatif dan kolaboratif sehingga ia punya relasi yang baik dengan jajaran birokrasi maupun partai politik. Jadinya prosesnya jauh lebih lancar,” ujar Yolanda.
Menurut Yolanda, dalam melihat permasalahan kepemimpinan perempuan, patut disoroti juga bagaimana media menampilkan perempuan pemimpin dalam liputan mereka. Menurutnya, sering kali pemberitaan di media menggambarkan sisi emosional dari perempuan ketika memimpin. Baru-baru ini contohnya, banyak pemberitaan tentang Walikota Risma dan Gubernur Khofifah yang digambarkan seolah-olah berseteru dalam menangani Covid-19. Padahal ini adalah perbedaan pendapat dan kebijakan di dua tingkatan administrasi yang sebetulnya cukup sering terjadi, ujar Yolanda.
“Pemberitaan menjadi bias seolah ada ketegangan personal, tapi itu kayaknya enggak diberitakan kalau pemimpinnya laki-laki. Misalnya Gubernur Sumatera Utara pernah bersitegang dengan Gubernur Tapanuli Tengah, tapi itu tidak dibingkai sebagai bentuk ketegangan personal,” ujarnya.
Pembuat kebijakan yang inklusif
CWI melihat bahwa pola kepemimpinan yang lebih mendorong perubahan dalam kultur dan tata kelola birokrasi yang mengedepankan prinsip transparansi, disiplin (ketat menaati peraturan), dan manajemen waktu yang efisien.
Sedangkan dalam hal pola kebijakan, kepala daerah perempuan cenderung lebih detail dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Isu-isu seperti pendidikan , pasar, pelayanan kesehatan yang selama ini sering kali dianggap remeh dan “sepele” bagi kepentingan politik partai, justru menjadi program kerja utama. Sayangnya, CWI melihat kepala daerah perempuan yang bukan berasal dari kader partai cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam bekerja sama dengan partai di DPRD, sehingga implementasi beragam kebijakan cenderung lebih sulit.
Baca juga: Ruang (Ny)aman: Bola untuk Keterwakilan Perempuan Ada di Partai Politik
Dalam kasus Bupati Jember Farida misalnya, ia sering kali diberitakan oleh media punya hubungan yang buruk dengan DPRD Jember, sampai baru-baru ini bahkan dikabarkan dimakzulkan DPRD. Farida memang dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berani membatalkan izin tambang emas, dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat kecil. Sebagai perempuan pemimpin ia tidak hanya fokus melakukan kerja besar seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jember, tapi juga membuat kebijakan yang berfokus pada persoalan rumah tangga yang banyak ditanggung oleh perempuan.
Farida melakukan rehabilitasi rumah bagi warga yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni. Selain itu, sebagai seorang dokter, ia berusaha untuk terus menurunkan angka kematian bayi dan kematian ibu.
“Ini hal-hal yang suka dipikirin ibu-ibu, punya rumah layak huni, punya pasar yang enggak kumuh, pendidikan buat anak gratis dan punya pelayanan kesehatan,” ujar Farida.
Sementara itu, sadar akan perlunya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik, Bupati Karawang, Jawa Barat, Cellica Nurrachadiana, mulai mendorong para perempuan untuk berani memegang posisi camat dan kepala bagian.
“Sekarang ini sudah ada lima camat dan lima kepala bagian di Kabupaten Karawang, saya ingin keterwakilan perempuan di berbagai hal itu semakin ada,” ujar Cellica.