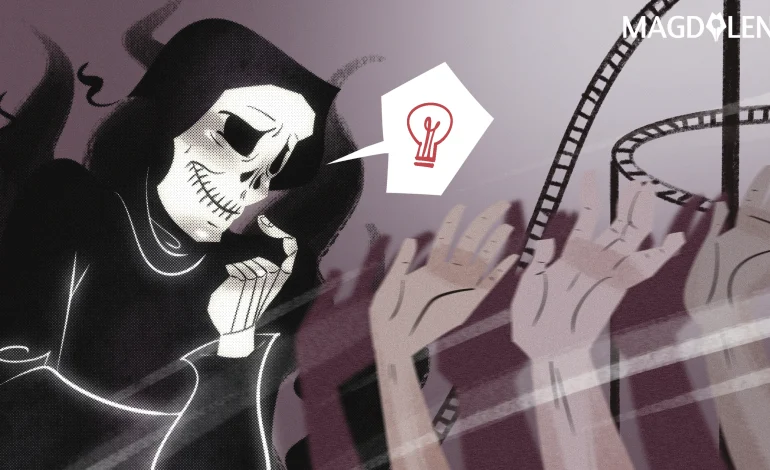Perempuan, Kabut Asap, dan Kerja yang Tak Terlihat

Di sela waktunya mengajar sebagai guru PAUD di Desa Bangsal, Sumatra Selatan, Marda Ellius juga menjual gulo puan—gula yang dibuat dari susu kerbau rawa, menyadap karet, dan mencari ikan. Semua demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
Namun, kabut asap akibat kebakaran mengacaukan segalanya. Aktivitas terganggu, mata perih, napas sesak, dan penghasilan pun menyusut drastis.
“Musim kabut asap sangat mengganggu kesehatan, aktivitas, dan perekonomian warga. Jika kabut tebal di pagi hari, jarak pandang jadi terbatas. Kami harus menunggu agak siang untuk mulai beraktivitas, termasuk memerah susu kerbau,” ujar Marda Ellius, atau akrab disapa Yeyen.
Ketika hari-hari diselimuti kabut, tak hanya matahari yang lenyap dari pandangan, tapi juga kerja-kerja penting yang dilakukan perempuan seperti Yeyen—kerja yang tak terlihat, tak dibayar, dan jarang dihitung dalam pemulihan bencana.
Kebakaran hutan kini terjadi dalam skala yang lebih luas, membakar setidaknya dua kali lipat tutupan pohon yang ada saat ini dibandingkan dua dekade yang lalu, menurut data Global Forest Watch 2023. Penelitian terbaru dari University of Maryland menunjukkan, area yang terbakar akibat kebakaran hutan meningkat sekitar 5,4 persen per tahun sejak 2001. Pada 2023, kehilangan tutupan pohon akibat kebakaran mencapai hampir 6 juta hektare, atau setara dengan luas negara Kroasia. Kebakaran juga menjadi penyebab utama hilangnya tutupan pohon secara global dibandingkan dengan penyebab lain seperti pertambangan dan perkebunan monokultur.
Di Indonesia, analisis Greenpeace Indonesia memperkirakan luas indikatif kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023 mencapai 2,13 juta hektare. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari data resmi pemerintah. Dari angka tersebut, sekitar 1,3 juta hektare merupakan area yang pernah terbakar antara 2015–2022, sementara sisanya adalah titik-titik baru.
Meski belum ada data resmi mengenai jumlah perempuan terdampak, yang jelas karhutla mengubah secara drastis kehidupan perempuan, mulai dari kesehatan, mata pencaharian, hingga beban kerja domestik yang berlipat.
Baca juga: Perempuan di Tengah Rezim Ekstraktif: Pemimpin Perlawanan untuk Lingkungan
Perempuan dan hantu kerja perawatan
Menurut UN Women (2018), kerja perawatan adalah seluruh bentuk produksi dan konsumsi jasa atau barang yang menopang kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial manusia. Ini mencakup pengasuhan anak, merawat orang sakit, lanjut usia, atau memiliki disabilitas, serta menjaga keberlangsungan rumah tangga. Sebagian besar kerja ini tidak dibayar, dan mayoritas dijalankan oleh perempuan.
Studi OECD (2019) dan Addati (2021) mencatat bahwa perempuan menghabiskan rata-rata 265 menit per hari untuk kerja perawatan, tiga kali lebih banyak dibanding laki-laki (83 menit). Ketika bencana seperti karhutla datang, beban ini melonjak tanpa disadari dan tanpa dihitung.
Perempuan seperti Yeyen tak hanya kehilangan akses terhadap sumber penghidupan seperti kebun, ikan, atau susu kerbau. Mereka juga harus merawat keluarga yang sakit karena asap, menyesuaikan ulang semua ritme rumah tangga, hingga menjaga anak-anak tetap bisa belajar meski sekolah terganggu.
Kendati demikian, kebijakan penanganan karhutla masih sering gagal mengakui kerja perawatan sebagai bagian dari tanggap darurat. Fokus lebih banyak pada pemadaman api dan distribusi masker, tanpa melihat beban berlapis yang ditanggung perempuan setiap hari.
Baca juga: Dear Prabowo, Setop Samakan Pohon Sawit dengan Tanaman Hutan
Kerentanan yang berlapis
Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa wilayah dengan populasi paling rentan akan mengalami dampak kebakaran hutan yang paling parah (Morgan, 2024). Tingkat paparan terhadap bencana tidak bisa dipisahkan dari kerentanan sosial, ekonomi, dan gender. Dalam konteks Indonesia, perempuan di wilayah-wilayah terdampak karhutla hidup dalam situasi dengan daya tahan terbatas dan ruang gerak sempit.
Di banyak desa, ketika lahan terbakar dan air mengering, perempuan juga kehilangan ruang aman mereka. Mereka dihadapkan pada dilema: tetap di rumah dengan risiko kelaparan, atau keluar rumah dan menghirup asap yang membahayakan. Sementara itu, suara mereka nyaris tak terdengar dalam proses perencanaan atau evaluasi kebijakan kebakaran hutan.
Padahal, perempuan kerap berada di garis depan: ikut memadamkan api, menjaga rumah dari kobaran api yang mendekat, hingga memikirkan strategi bertahan hidup pasca-bencana. Namun semua itu nyaris tak terlihat dalam laporan resmi atau skema bantuan.
Baca juga: Gagal Terus, Kenapa Prabowo Tak Kapok Bikin ‘Food Estate’?
Penanganan karhutla harus melampaui logika teknokratik seperti hitungan titik panas atau distribusi masker. Dibutuhkan pemetaan sosial yang menempatkan perempuan sebagai subjek, bukan hanya korban. Pemerintah dan lembaga bantuan perlu merancang intervensi berbasis peta kerentanan, yang memperhitungkan kerja perawatan, ketimpangan gender, dan kapasitas komunitas.
Redistribusi beban kerja perawatan harus menjadi bagian dari solusi. Tanpa reformasi struktural, perempuan akan terus menjadi “hantu”—tak tampak, tak terdengar, dan tak dihitung dalam siklus bencana dan pemulihan. Kabut asap akan terus menutupi bukan hanya matahari, tapi juga kontribusi dan penderitaan mereka.
Agnes Alvionita turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Sekar Banjaran Aji adalah juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia yang sekarang menjabat sebagai Koordinator Public Interest Lawyer Network (Pil-Net) Indonesia. Sekar merupakan advokat lingkungan yang menyukai pembahasan tentang litigasi iklim dan feminist political ecology.
Ilustrasi oleh Karina Tungari