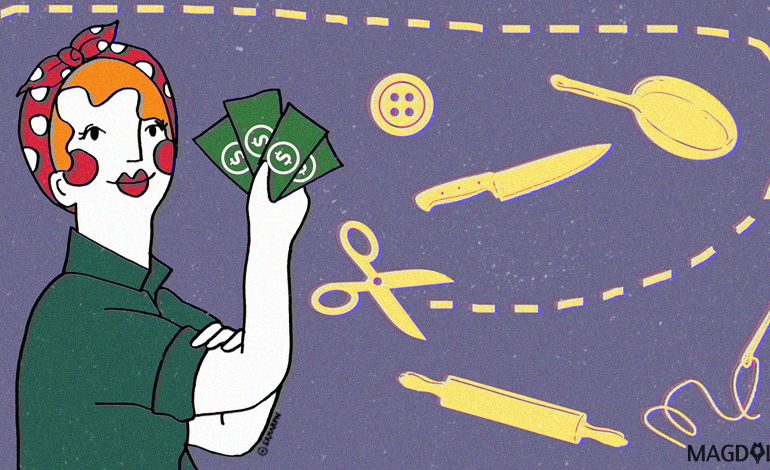Ketika Sayap Kanan Naik, ‘Global South’ yang Paling Tersungkur

Di Amerika dan Eropa, gelombang politik kanan makin menancapkan kukunya. Demokrasi liberal goyah, perlindungan hak asasi manusia (HAM) kian mengendur, dan komitmen terhadap krisis iklim merosot. Di negara-negara Global South, dampaknya justru terasa berlipat: dari memburuknya kondisi kemanusiaan, menguatnya otoritarianisme, hingga menyempitnya ruang sipil.
Indonesia turut merasakan ketegangan itu. Dalam rentang akhir Agustus 2025, aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online memadati pusat kota dalam gelombang protes yang dikenal sebagai “Prahara Agustus”. Latar belakangnya jelas: harga kebutuhan pokok melonjak, angka PHK naik, dan pengangguran meluas. Namun alih-alih merespons keresahan rakyat, pemerintah memilih menuduh massa aksi sebagai makar, bahkan “teroris”. Presiden Prabowo melabeli LSM pengkritiknya sebagai “antek asing”—retorika lama yang kembali dipakai untuk membungkam kritik.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat setidaknya 3.337 orang ditangkap, dan 1.042 lainnya harus dirawat di rumah sakit selama periode protes 25–31 Agustus. Tindakan represif ini berpadu dengan penguatan politik identitas dan konsolidasi kekuasaan eksekutif, menandai kemunduran demokrasi dan kemunculan pola kepemimpinan kanan-populis.
Baca juga: 2 Alasan Foto Prabowo Bareng Pemimpin Otoriter itu ‘Bromance’ Toksik
Dari Eropa ke Amerika: Naiknya populisme kanan
Indonesia bukan satu-satunya. Di Filipina, mantan presiden Rodrigo Duterte memimpin kampanye “war on drugs” yang menewaskan ribuan orang melalui eksekusi tanpa pengadilan. Di Uganda, undang-undang anti-LGBTQ yang ekstrem disahkan. Di Brazil, Jair Bolsonaro membuka keran deforestasi Amazon dan merampas hak masyarakat adat. Myanmar menjadi tragedi demokrasi paling nyata setelah junta militer kembali berkuasa.
Pola yang sama terlihat jelas di banyak negara Global South: kritik dibungkam, oposisi dilemahkan, minoritas didiskriminasi, dan kebebasan sipil dipersempit. Ini bukan fenomena lokal—ia mendapat “angin segar” dari perubahan politik global.
Di Eropa, partai-partai kanan kian menggeser arus utama politik. Giorgia Meloni di Italia, Marine Le Pen di Prancis, Geert Wilders di Belanda, dan Alternative für Deutschland (AfD) di Jerman menjadi wajah baru konservatisme. Austria, Swedia, dan Hungaria mengalami penguatan partai kanan dengan intensitas berbeda-beda, tapi benang merahnya sama, yaitu ada konsolidasi populisme kanan yang menantang pilar demokrasi liberal Eropa. Mereka mengusung agenda nasionalis, anti-imigran, anti-Islam, serta menolak kerangka HAM internasional.
Di Inggris, Nigel Farage dan partainya, Reform UK, mendesak deportasi massal migran dan mendorong keluar dari European Convention on Human Rights. Sementara itu, survei Financial Times menunjukkan satu dari lima anak muda Jerman kini mendukung AfD, menandakan radikalisasi politik generasi baru.
Amerika Serikat mengalami gelombang yang lebih awal. Donald Trump kembali berkuasa dengan agenda imigrasi ketat, penolakan terhadap kesetaraan gender non-biner, serta slogan Make America Great Again yang sarat nasionalisme ekonomi. Ia menarik AS keluar dari Paris Agreement, memangkas bantuan luar negeri, dan menjadikan kepentingan bisnis sebagai prioritas utama.
Biaya yang harus dibayar Global South
Kemenangan partai kanan di Global North memperlemah tekanan global atas pelanggaran HAM di negara-negara Selatan. Retorika “us vs them” memberi justifikasi bagi diskriminasi: dari kebijakan Islamofobia di India hingga persekusi LGBTQ+ di Uganda. Sementara negara-negara Pasifik, Afrika Timur, dan Asia Selatan—yang paling terdampak krisis iklim—harus menghadapi tantangan adaptasi tanpa dukungan internasional yang memadai.
Di ranah sosial, polarisasi politik yang ditanam lewat populisme kanan mudah meletup jadi konflik. Myanmar dan Sudan jadi contoh tragis ketika institusi negara gagal mencegah perang saudara. Di Indonesia, pembungkaman media dan kriminalisasi aktivis makin umum.
Secara global, kemenangan politik kanan juga menghambat pencapaian target iklim. Negara-negara Global South—yang kontribusinya terhadap emisi global paling kecil—justru menjadi korban paling terdampak oleh bencana iklim: banjir di Pakistan dan Bangladesh, kekeringan di Afrika, dan tenggelamnya negara-negara kecil di Pasifik.
Ironisnya, ketika Global South justru butuh solidaritas global yang lebih kuat, negara-negara kaya justru menarik dukungan. Bantuan luar negeri dipotong, tekanan terhadap rezim otoriter dikendurkan, dan prioritas pembangunan digeser ke dalam negeri.
Apa yang harus dilakukan? Kita tak bisa hanya mengandalkan negara. Ketika tatanan internasional melemah, masyarakat sipil harus mengambil peran lebih besar. Kita perlu menguatkan jejaring lintas negara, membangun solidaritas dari Selatan untuk Selatan, dengan memanfaatkan koneksi antarlembaga masyarakat sipil, jurnalis, akademisi, dan aktivis. Di saat tekanan global melemah, jaringan inilah yang bisa menjadi benteng pertahanan nilai-nilai demokrasi dan HAM.
Baca juga: 10 Alasan Kemenangan Trump Tak Bisa Goyahkan Aksi Iklim Dunia
Selain itu, menjaga kebebasan pers dan ruang sipil menjadi hal yang tak kalah penting—termasuk membela media independen dari serangan negara atau kelompok politik yang ingin membungkam kritik. Di sisi lain, pendidikan politik dan penguatan kesadaran HAM harus terus diperluas agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam retorika populisme yang menciptakan musuh bersama secara semu.
Naiknya politik kanan di Global North bukan sekadar dinamika domestik. Ini adalah sinyal bahaya global. Bila pusat-pusat kekuasaan dunia meninggalkan nilai-nilai HAM dan demokrasi, maka negara-negara Global South akan menjadi korban pertama dan paling terdampak.