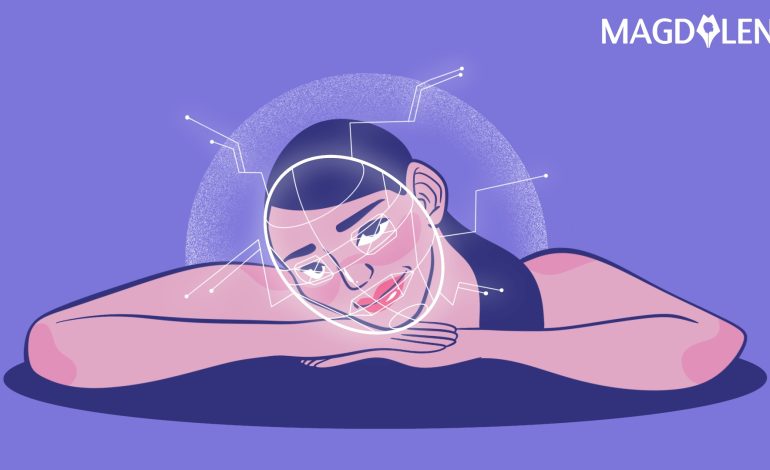Jam di dashboard menunjukkan pukul 02.30 dini hari. Lokasi penjemputan adalah sebuah kawasan hiburan malam yang populer di Jakarta Selatan. Dentuman bass terdengar samar dari luar klub saat saya menepikan mobil.
Pintu belakang terbuka. Aroma alkohol langsung meruak di dalam kabin yang sempit. Dua perempuan memapah temannya yang nyaris tak sadarkan diri untuk masuk ke kursi belakang.
“Pak, tolong antar teman saya ke kosnya, ya. Nanti ada satu teman lagi nunggu di depan kos. Tolong banget,” kata salah satu dengan wajah cemas.
Saya mengangguk. Mobil melaju menyusuri jalanan Jakarta yang lengang. Di kaca spion tengah, saya melihat perempuan itu tertidur dengan kepala terkulai di jendela. Ia tak sadarkan diri. Tak mampu mengatur tubuhnya, apalagi menjaga pakaiannya yang tersingkap sejak dipapah tadi.
Malam itu, saya berhadapan langsung dengan realitas yang sering hanya muncul sebagai imbauan klise: seorang perempuan, dalam kondisi sangat rentan, sendirian bersama seorang laki-laki asing, di ruang tertutup yang terkunci. Jika saya adalah predator, ini adalah “kesempatan emas”.
Tapi tidak ada yang terjadi. Saya hanya menyetir. Mengapa? Karena saya bukan predator.
Baca juga: Dari ‘Anker’ Cikarang Saya Belajar, Rumah Bukan Tempat Pulang tapi Alasan Bertahan
Pelecehan seksual bukan soal pakaian
Masyarakat kita sering kali terobsesi dengan narasi “pakaian sopan”. Kita sibuk menasihati kerabat perempuan kita, “Jangan pakai rok mini, nanti memancing kejahatan.”
Tapi pelecehan seksual bukan perkara godaan atau pakaian. Bukan soal jam malam atau kadar kesadaran korban. Pelecehan adalah hasil dari keputusan sadar. Nafsu mungkin muncul sepersekian detik, tapi keputusan untuk menyakiti adalah pilihan utuh.
Kita, laki-laki, dibesarkan dengan kebohongan bahwa “khilaf” adalah alasan. Padahal itu cuma dalih. Buktinya malam itu, semua kondisi yang sering disebut sebagai “penyebab” pelecehan ada di depan saya, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Karena saya bisa mengendalikan diri. Karena saya tahu itu salah.
Saya teringat satu laporan BBC Indonesia tahun 2019: “Mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik adalah perempuan berhijab, bercelana panjang, dan kejadian terjadi di siang bolong.” Apa lagi yang perlu dibuktikan? Jika pakaian tertutup dan waktu siang hari pun tak cukup mencegah kekerasan, maka masalahnya jelas bukan pada korban, melainkan pada pelaku.
Dalam kelas psikologi dulu, dosen saya pernah menjelaskan konsep tangga moralitas. Ada orang yang tidak mencuri karena takut ditangkap—moralitasnya tergantung kamera CCTV atau kehadiran satpam. Ada pula yang tidak mencuri karena tahu itu salah, bahkan jika tidak ada satu pun mata yang melihat.
Baca juga: Bagi Laki-laki Ini Cuma Perjalanan, Bagi Perempuan Ini Pertaruhan
Malam itu saya sadar, predator adalah laki-laki yang moralitasnya tidak pernah tumbuh. Ia tidak menyentuh bukan karena tahu itu salah, tapi karena takut viral, takut dihukum. Dan ketika tidak ada yang mengawasi, dia akan bertindak.
Laki-laki yang beradab hidup dengan prinsip yang lebih tinggi. Ia tidak menyakiti bukan karena takut sanksi, tapi karena punya keyakinan batin bahwa mengeksploitasi orang yang lemah adalah kejahatan. Titik.
Sesaat di tengah perjalanan, sempat muncul rasa bangga di dalam diri. Saya pikir, “Saya laki-laki baik. Saya tidak memanfaatkan kesempatan ini.” Tapi kemudian saya merasa jijik. Sejak kapan tidak melecehkan orang tak berdaya dianggap prestasi?
Standar kita begitu rendah sampai-sampai sopir yang sekadar menjalankan tugas—mengantar penumpang dari titik A ke B tanpa berbuat jahat—dianggap pantas mendapat pujian. Padahal itu seharusnya hal paling dasar dalam menjadi manusia.
Saya menurunkannya tepat di depan gerbang kos. Seorang perempuan sudah menunggu, wajahnya tegang. Ia bergegas membuka pintu dan memapah temannya masuk ke dalam. Saya lega ia selamat. Tapi juga getir.
Karena malam itu, keselamatan perempuan ini sepenuhnya bergantung pada kebetulan. Kebetulan ia tidak bertemu predator. Keselamatan seharusnya bukan hasil dari keberuntungan atau doa semata. Tapi hasil dari sistem sosial yang menanamkan tanggung jawab pada laki-laki.
Budaya kita gagal. Kita sibuk menuntut perempuan menjaga kehormatan, menutup tubuh, membatasi gerak. Tapi membiarkan laki-laki tumbuh tanpa didikan emosional, tanpa pengendalian diri, tanpa tanggung jawab atas kuasa yang dimilikinya.
Kita mudah berkata: “Jangan pulang malam.” “Jangan minum terlalu banyak.” Tapi kita sangat jarang berkata: “Jangan manfaatkan kerentanan orang.” “Jangan sentuh tubuh yang tidak memberi izin.” “Jangan jadi binatang ketika tidak ada yang melihat.”
Baca juga: Laporan Hukum Jalan Terus, Tak Ada Toleransi untuk Elham
Pelecehan seksual tidak terjadi karena perempuan mabuk. Atau karena pakaiannya tersingkap. Itu terjadi karena ada laki-laki yang memutuskan untuk menjadi pelaku. Dan setiap keputusan itu adalah hasil dari kegagalan pendidikan moral kolektif kita.
Pada akhirnya, ini bukan soal etika berpakaian. Ini soal bagaimana kita mendidik laki-laki menjadi manusia. Menjadi pribadi yang tidak menyakiti bukan karena dia takut dipenjara, tapi karena ia tahu itu salah—meski tidak ada kamera, tidak ada saksi, tidak ada suara yang bisa melawan.
Laki-laki yang tidak melecehkan perempuan mabuk bukanlah pahlawan. Ia hanya manusia biasa, yang kebetulan tidak lupa bagaimana caranya menjadi manusia.
Akhmad Yunus Vixroni adalah seorang pengemudi taksi online yang selalu sayang istri.