Ramadan di Tengah Wabah, Ngabuburit Tetap Jalan
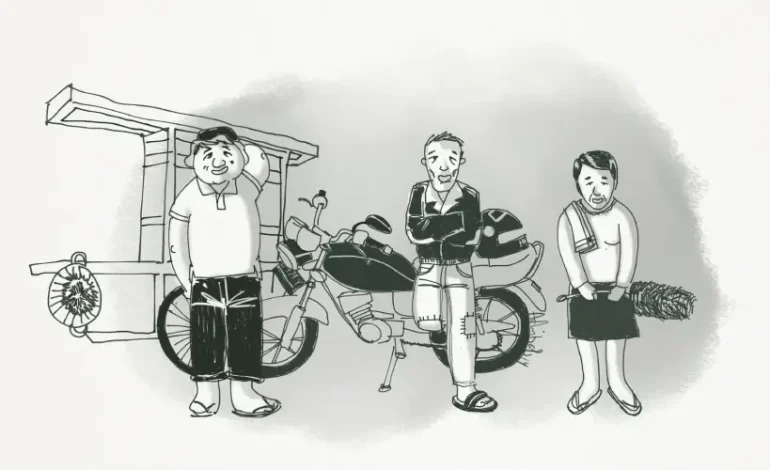
Hari Minggu sore kemarin, saya keluar rumah untuk menyetok beberapa barang yang kosong di rumah. Saya pikir, jalanan akan lengang mengingat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih diterapkan di Jakarta. Imbauan untuk beribadah di rumah serta tidak melakukan kegiatan berkumpul menjelang buka puasa alias ngabuburit pun sudah dikumandangkan di aneka media. Tapi bayangan itu ternyata buyar.
Baru sekitar 300 meter dari rumah di Jakarta Selatan, kendaraan mengular di jalanan yang selebar dua mobil yang mepet. Saya melongok dari sepeda motor, ada sejumlah pedagang takjil membuka lapak di pinggir-pinggir jalan. Ternyata, yang membikin antrean panjang kendaraan adalah banyaknya motor dan mobil yang berhenti di tengah jalan, bahkan beberapa motor berjejer terparkir. Sementara, para pembeli takjil tampak abai terhadap anjuran untuk berjarak minimal semeter satu sama lain walaupun semuanya mengenakan masker.
Sampai di supermarket, saya merasa Ramadan kali ini tak ubahnya dengan tahun-tahun lalu. Tempat itu nyaris sesak oleh pengunjung, bahkan antrean kasir sampai mencapai bagian belakang rak barang-barang dengan belanjaan menggunung di troli.
Yang berbeda kali ini adalah, begitu hendak masuk, ada petugas yang mengecek terlebih dahulu suhu tubuh pengunjung satu per satu. Lalu, ada juga imbauan bagi pengunjung yang datang sekeluarga untuk tidak bersama-sama memasuki supermarket tersebut. Hanya satu ‘perwakilan’ dari setiap keluarga yang boleh berbelanja, selebihnya menunggu di luar.
Tapi, apakah hal ini diikuti?
Ketika saya berjalan dari tempat parkir, ada satu pasangan yang berjalan di depan saya. Alih-alih salah satu darinya menunggu di luar supermarket, keduanya masuk bergantian seolah dua orang tidak saling kenal. Di dalam, saya lihat mereka berjalan berbarengan mendorong troli seakan tidak ada imbauan tadi. Selama belanja pun saya melihat banyak orang seperti itu, mengangkut belanjaan yang sama.
Kemudian, di lantai sepanjang antrean kasir, tertempel lakban bertanda ‘X’ yang berjarak kira-kira semeter antara satu tanda dan lainnya. Di lantai yang tidak bertandalah pengunjung seharusnya berdiri. Namun lagi-lagi, imbauan tersebut tidak digubris, bahkan setelah berkali-kali petugas supermarket mengingatkan kembali lewat pengeras suara.
Baca juga: Penerapan ‘Social Distancing’ Tak Merata, Masih Dipandang Sebelah Mata
Bukan saya saja yang mendapati antrean panjang di tempat perbelanjaan. Beberapa teman saya pun sempat mengunggah Instagram Story yang memperlihatkan panjangnya antrean di supermarket lain. Di Twitter pada 2 Mei lalu, penulis The Naked Traveler, Trinity mencuit soal penuhnya toko furnitur dan perabotan IKEA, Tangerang. Untuk masuk saja, kata dia, orang-orang harus mengantre dari luar. Tempat IKEA pun padat dengan kendaraan.
Trinity menduga, hal tersebut terjadi lantaran adanya kebutuhan mempercantik rumah selama work from home diberlakukan atau karena banyak mal lain yang tutup. Sementara dari pengamatan saya selama berbelanja kemarin, orang-orang lebih banyak menyetok bahan makanan, termasuk camilan dan makanan-minuman manis. Saya pikir, antrean panjang di sana lebih berkaitan dengan kebutuhan sahur dan buka puasa ditambah akhir pekan lalu adalah awal bulan, saatnya orang baru gajian.
Sepulang berbelanja, saya bertemu dengan tetangga saya, Mariyah, yang baru kembali dari membeli makanan berbuka puasa.
“Setengah jam gue antre,” ujarnya. “Boro-boro berdirinya jauhan. Tempat jualannya aja sempit, di depan minimarket. Di kiri kanannya penuh sama motor. Mau enggak mau dempet-dempetan pas beli tadi.”
Walaupun berbuka puasa bisa dengan minuman dan makanan lain, Mariyah merasa ada yang kurang jika tidak ikut jajan takjil selama Ramadan. Hampir setiap sore ia keluar dan bergabung dalam kerumunan para pencari takjil, mengabaikan risiko terpapar COVID-19.
Antrean supermarket dan kerumunan pembeli takjil hanyalah dua contoh pengabaian terhadap imbauan pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Di Purwakarta, sebagian warga tetap berkumpul di jembatan perlintasan kereta api di Cisomang menjelang waktu berbuka puasa pada 3 Mei kemarin. Dilansir AyoPurwakarta, salah satu warga yang ngabuburit di lokasi tersebut menyatakan, kendati ada ketakutan akan terpapar virus corona, rasa bosan karena berada di rumah ditambah adanya ‘tradisi’ untuk ngabuburit di jembatan itu setiap bulan puasa mendorong mereka untuk tetap pergi ke sana.
Di Indonesia, orang-orang sudah biasa melanggar aturan. Penegakan aturan yang masih setengah-setengah atau tidak meratalah yang juga bersumbangsih terhadap perilaku berkerumun selama PSBB.
Tak melulu egois
Sebagian orang menganggap bahwa mereka yang tetap keluar rumah dan berkerumun di tengah wabah seperti sekarang adalah orang-orang egois yang tidak memedulikan keselamatan orang lain. Namun menurut pengajar Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Dicky Pelupessy, hal ini tidak melulu benar.
“Sekarang ini ada beberapa kelompok orang, yang abai terhadap risiko penularan virus dan tidak. Orang yang abai ini terbagi menjadi dua subkategori: Yang telah paham risiko dan yang tidak paham. Yang egois dan bahaya itu adalah kelompok orang yang abai padahal sudah paham risikonya, dan dengan sengaja melanggar imbauan menjaga jarak,” ujar Dicky.
Tudingan egois juga tidak bisa dipukul rata ke semua orang yang berada di luar rumah karena menurut Dicky, ada orang-orang yang mau tidak mau seperti itu karena tuntutan ekonomi, misalnya para pengemudi ojek online.
Selain itu, ia menambahkan, dalam situasi yang dirasa mengancam keselamatan jiwa, orang-orang bisa memilih antara fight atau flight. Orang-orang yang fight mencakup mereka yang harus keluar rumah demi mencari nafkah tadi kendati tahu ada risiko terpapar virus. Sementara opsi flight dapat terlihat dari contoh orang-orang yang berkerumun tidak jelas atau hanya untuk bertemu teman-teman karena sebenarnya mereka menghindari situasi yang tidak ingin ditemui: Terisolasi secara sosial.
Masih banyaknya orang berkerumun di tempat publik atau ngabuburit tidak lepas dari adanya disrupsi di negeri ini, sementara orang belum siap menghadapinya.
“Konteks besar yang perlu dipahami sekarang adalah ada situasi baru, baik menyangkut wabahnya maupun pembatasan aktivitas kita. Disrupsi ini kita hadapi dan masih dalam proses adaptasi. Cukup sulit rasanya untuk berada di situasi penuh kontradiksi, kita sebagai makhluk sosial menghadapi pembatasan sosial,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) ini.
Pelanggaran imbauan juga berkenaan dengan perilaku masyarakat yang telah “membudaya” jauh sebelum pandemi terjadi. Dicky menilai, jika bicara konteks Indonesia, orang-orang sudah biasa melanggar aturan, contohnya di jalanan atau tempat umum. Penegakan aturan yang masih setengah-setengah atau tidak meratalah yang juga bersumbangsih terhadap perilaku berkerumun selama PSBB.
Baca juga: 5 Pekerjaan Paling Rentan Selama Krisis Corona
Walaupun informasi terpercaya soal virus corona dan jumlah orang yang terjangkit telah disebarkan oleh berbagai media, ditambah adanya imbauan dari pemimpin negara, agama, dan komunitas, tidak berarti hal tersebut langsung efektif mencegah orang untuk berkerumun. Pasalnya, ada faktor pengetahuan dan kemampuan memahami pengetahuan tentang penyakit tersebut yang berbeda-beda di semua kalangan masyarakat.
Saat ada ancaman, ada kelompok orang yang begitu cemas dan memutuskan menaati aturan untuk menghindari ancaman tersebut. Di sisi lain, ada kelompok orang yang malah meremehkan ancaman tersebut seperti mereka yang berpikir virus corona hanya akan menjangkiti orang-orang kaya yang bepergian ke luar negeri.
Situasi sekarang juga mengingatkan orang akan kefanaan manusia dan kematian yang bisa datang kapan saja.
“Pemahaman soal kefanaan itu menimbulkan kecemasan. Kemudian, orang berusaha mendapatkan penghilang kecemasan. Ada yang kemudian menjadi spiritual atau religius, lalu mendapat pemahaman yang sepotong-sepotong atau pemahaman yang mau dia yakini saja. Dia lantas berpikir, ini kan soal takdir, yang menentukan Tuhan. Maka, meski ada imbauan untuk tidak beribadah secara komunal dari pemimpin agama, dia tetap melakukannya,” jelas Dicky.
Kurangnya efektivitas imbauan dari para pemimpin agama maupun komunitas juga bisa disebabkan oleh strategi keliru yang diambil para pemangku jabatan. Anggapan bahwa jika pemimpin mengatakan sesuatu maka pengikutnya otomatis menaati tidak selalu benar. Dicky berargumen, sekarang ini, yang didengarkan itu bukan pemimpin, melainkan influencer atau role model, contohnya terlihat di kalangan anak muda.
“Situasi ini menjungkirbalikkan banyak tatanan. Pendekatan yang formalistis dan asumsi bahwa semua bisa diselesaikan dengan pendekatan struktural saya kira harus diperiksa ulang. Misalnya, dari pemerintah meneruskan imbauan ke kabupaten atau kota, ke camat, lurah, sampai RT/RW. Nah, ketua RT/RW itu kan belum tentu orang yang bisa mempengaruhi warga,” ujarnya.
“Karena itu, sebaiknya pendekatan yang digunakan adalah para pemimpin memegang influencer untuk menyampaikan pesannya atau mengombinasikan peran keduanya secara bersamaan agar pesan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.”






















