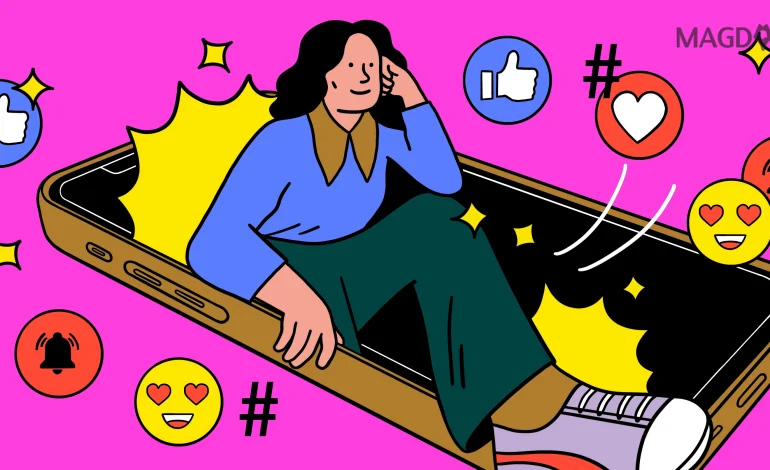‘Budi Pekerti’: Refleksi Soal Penghakiman di Media Sosial dan Satu Hal yang Luput Disorot Wregas

Peringatan: Mengandung Sedikit Spoiler!
Prani Siswoyo (Sha Ine Febriyanti) tak pernah menyangka bahwa aksinya menegur seorang laki-laki yang menyelak antrian saat hendak membeli kue putu legendaris Mbok Rahayu akan mengubah hidupnya. Omongannya yang menyebut “Ah, suwi!” atau kelamaan dalam bahasa Jawa dipotong dan diplesetkan jadi “Asuui” (anjing) viral di media sosial.
Orang-orang lalu melabelinya sebagai orang tua marah-marah yang suka misuh. Kata-katanya bahkan diubah jadi musik koplo oleh para content creator. Keviralannya itu memengaruhi segala lini kehidupan Prani. Latar belakangnya dikulik oleh warganet, sampai pihak sekolah pun harus menunda proses pemilihan wakil kepala sekolah yang sedang diikutinya.
Konsekuensi besar dari viralitas dan jari-jari warganet yang gampang menghakimi di media sosial adalah plot utama yang coba ditawarkan Wregas Bhanuteja dalam film terbarunya Budi Pekerti. Sebagai generasi yang sudah bergantung pada media sosial, tema yang diangkat Wregas tentu sangat dekat dengan keseharian. Tak heran jika jalan ceritanya yang kuat ditambah para pemain kelas atas dengan kemampuan akting jempolan mampu mengantarkan film ini memenangkan 17 nominasi di Festival Film Indonesia (FFI) 2023.
Mengambil setting di daerah Yogyakarta, film Budi Pekerti bercerita tentang Prani Siswoyo yang merupakan seorang guru bimbingan konseling (BK). Suaminya yang didiagnosis bipolar harus terus menjalani konsultasi dengan psikolog. Dan kedua anak mereka: Muklas (Angga Yunanda) adalah selebgram kabupaten yang sering membuat tips-tips kesehatan dengan filosofi hewan (audiensnya ia sebut sebagai Animalus) dan sang kakak, Tita (Prilly Latuconsina), seorang seniman indie yang berusaha bertahan hidup dengan jualan baju preloved yang ia olah kembali.
Baca juga: ‘Penyalin Cahaya’ Soroti Sulitnya Korban Kekerasan Seksual Cari Keadilan

Media Clickbait dan Penghakiman Warganet
Lewat kehidupan keluarga Prani yang hancur setelah videonya viral, Wregas mengajak penonton untuk berefleksi soal bagaimana kita sering kali mudah menghakimi orang yang tak dikenal di dunia maya, tanpa tahu apa dampak yang ditimbulkan pada orang tersebut. Kita kerap lupa bahwa ada kehidupan manusia di balik akun-akun media sosial yang tanpa pikir panjang kita cerca. Adegan saat Prani mengambil jeda dari masalahnya dan memasang earplug di dekat mainan anak-anak yang berisik, cukup menggambarkan kefrustrasian tentang keributan di media sosial.
Dialog-dialog Muklas dengan Prani juga menyentil pertalian media sosial di era post-truth, di mana kebenaran dan fakta sering kali ditentukan oleh siapa yang paling sering berbicara di media sosial. Ketika permasalahan sudah jadi konsumsi media sosial, siapa yang salah dan benar tak lagi penting.
“Hidup kita sudah hancur, tapi bagi netizen ini cuma masalah satu notifikasi,” ujar Muklas.
Situasi ini diperparah oleh para content creator dan media-media clickbait yang menghalalkan segala macam cara untuk riding the wave, begitu pun Muklas sendiri. Muklas yang terobsesi membersihkan namanya setelah ibunya viral adalah gambaran soal iklim influencer yang jadi perpanjangan kapitalisme yang hanya peduli pada adsense dan endorse.
Sedangkan dari sisi media, Gaung Tinta, di mana Gora (Omara Esteghlal)–mantan murid Prani–bekerja juga digambarkan sebagai media penghamba views. Saat Mbok Rahayu tak berjualan beberapa hari setelah viral contohnya. Mereka meliput dengan angle yang seolah menyalahkan Prani karena menularkan virus COVID-19 kepada Mbok Rahayu. Asumsi itu disetir oleh fakta masker yang dipakai Prani terlihat melorot dalam video. Padahal yang membuat video tak mengonfirmasi status COVID Mbok Rahayu pada otoritas atau Mbok Rahayu sendiri.
Selain itu, Gaung Tinta juga membuat diagnosis sepihak soal kesehatan mental Gora yang melakukan testimoni tentang pengalaman membekas saat masih jadi murid Prani. Cara-cara “kotor” mereka yang hanya peduli pada views ini adalah realitas media-media daring sekarang yang dengan baik dikritisi Wregas.
Di industri di mana attention economy dan media sosial adalah emas baru, perusahaan-perusahan media sekarang mengandalkan model bisnis clickbait agar bisa mengeruk pembaca sebanyak-banyaknya. Cara-cara kerja ini sering kali berakhir dengan jalan menjual angle-angle seksis, misoginis, dan tak sensitif. Padahal, pemberitaan tendensius itu nyatanya punya dampak serius terutama bagi kelompok marginal seperti perempuan, anak dan minoritas seksual. Dalam hal ini, nasib Prani yang bekerja di sekolah selama 20 tahun tapi jadi hancur setelah video 20 detiknya tersebar adalah contoh nyatanya.

Baca juga: Catatan dari FFI 2021: Minimnya Juri Perempuan hingga Posisi Festival
Yang Luput Disorot
Sayangnya, meski sudah memotret dengan baik soal dampak dari iklim viralitas di media sosial yang semakin out of hand, film ini luput memotret masalah yang tak kalah penting untuk dibahas: bagaimana industri media sosial punya andil besar dalam mengkondisikan masyarakat yang haus akan viralitas di media sosial.
Film ini masih memotret persoalan moralitas bagaimana masyarakat kita lupa dengan budi pekerti yang dulu diajarkan di sekolah. Seolah jika orang-orang tahu soal tata krama, cancel culture mungkin tak jadi segila ini. Sepanjang film, sebagai penonton kita akan ikut mengumpat dengan kelakuan warganet dan pihak-pihak tertentu yang merasa “si paling benar”. Scene Gora yang marah dengan apa yang dilakukan oleh warganet pada Prani adalah puncaknya.
Masalahnya, obsesi menjadi viral itu sendiri tak lepas dari andil besar perusahaan-perusahaan teknologi yang mengeruk untung dari ekosistem yang tak sehat ini dan juga negara yang tak peduli pada persoalan data pribadi. Di banyak kasus mereka sering kali tak bisa memberikan keadilan sebelum segala sesuatu viral di dunia maya.
Baca Juga: Curhat di Media Sosial: Positif atau Negatif?
Realitas ini pernah dibahas dalam dokumenter-drama garapan Jeff Orlowski, berjudul Social Dilemma (2020) yang tayang di Netflix. Di sini, digambarkan bagaimana algoritma bekerja untuk membuat orang terus ingin engaged dan distracted dengan apa yang terjadi di media sosial.

Algoritma media sosial sendiri sering kali dibentuk untuk membuat orang-orang haus akan perdebatan dan viralitas. Contoh yang paling nyata adalah X (ex-Twitter). Semenjak diambil alih Elon Musk, mereka menerapkan kebijakan bahwa centang biru yang menunjukkan kredibilitas akun bisa dibeli. Terbaru, X, juga memberikan bayaran content creator yang punya engagement besar. Akibatnya, tak sedikit orang-orang yang berlomba untuk menyerang orang dan membuat opini-opini tak sensitif, rasis, dan misoginis hanya untuk mendapat engagement yang besar.
Baca juga: Apa Artinya Perang Threads Vs Twitter buat Nasib Jurnalis dan Jurnalisme?
Selain X, Facebook, anak perusahaan Meta milik Mark Zuckerberg juga sudah lama dituntut karena terbukti menjual data pribadi penggunanya ke Cambridge Analytica yang membantu kandidat dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2014. Mereka juga dituntut karena platformnya menyuburkan hoaks selama Pemilu.
Saya sendiri setuju dengan apa yang ingin disampaikan Wregas soal pentingnya jadi warganet yang lebih bijak dan tak mudah menghakimi. Tapi, rasa-rasanya akan sangat progresif bila film Budi Pekerti juga menyentil pihak-pihak yang juga punya kuasa.