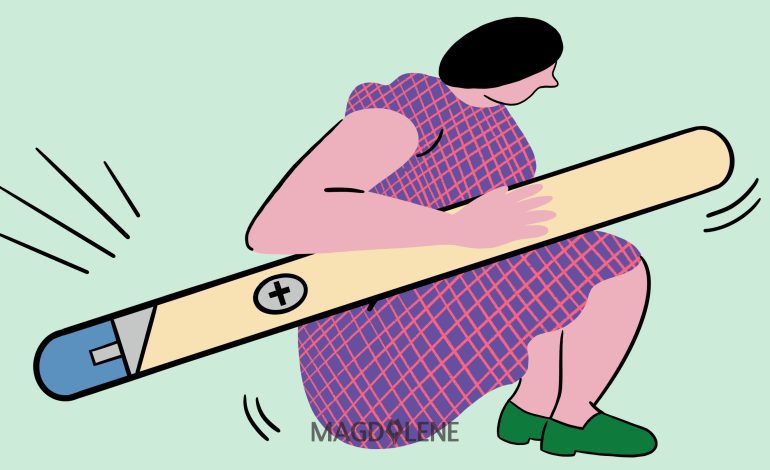Tak Ada Lapangan Bola untuk Perempuan
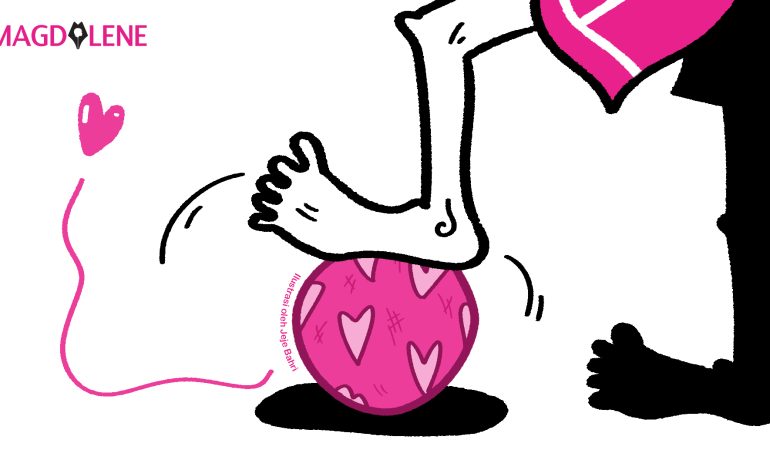
Mumbra adalah kota pinggiran di India Barat bagian Maharashtra. Sebagai “ghetto Muslim”, karena selama bertahun-tahun populasinya didominasi penduduk Muslim, kota ini terbilang tak ramah bagi perempuan. Banyak anak dan remaja perempuan kesulitan mendapatkan izin dari orang tua atau saudara laki-laki mereka hanya untuk menghabiskan waktu di ruang publik, apalagi untuk berolahraga.
Lapangan bermain selalu diisi dengan laki-laki yang bermain kriket atau bermain bola, sedangkan perempuan cuma terlihat di pinggiran, mengamati atau sekadar lewat berjalan kaki.
“Kita jarang melihat perempuan memakai ruang publik seperti laki-laki untuk berolahraga. Kebanyakan perempuan bermain hanya di lingkungan profesional. Untuk anak dan remaja perempuan yang underprivileged, mendapatkan akses ke ruang publik untuk berolahraga itu susah,” kata Sabah Khan, salah satu inisiator Parcham.
Parcham sendiri merupakan aksi kolektif di mana gadis-gadis muda bisa bermain bola bersama dalam tim, yang isinya memang semua perempuan. Dengan mengajak anak dan remaja perempuan untuk main bola di lapangan bermain, Parcham mencoba merebut kembali ruang publik yang selama ini didominasi oleh laki-laki.
Enggak cuma itu, Parcham juga membantu anak dan remaja perempuan untuk mengklaim hak atas tubuh mereka sendiri. Tubuh yang selama ini selalu diberikan batas-batasan sosial sampai perempuan tidak mengenal tubuhnya sendiri. Tidak boleh main ini, tidak boleh melakukan itu, dan sederet aturan lain.
Parcham dipotret dengan apik dalam film dokumenter berdurasi 35 menit, Under the Open Sky (2018). Film tersebut diputar di ShamaBhav Travelling Film Festival yang diinisiasi Men Against Violence & Abuse (MAVA), dan diselenggarakan United Nations Population Fund (UNFPA) bersama Magdalene di Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, akhir Mei lalu.
Baca Juga: Catcalling dan Hak Perempuan Atas Ruang Publik

Ruang Publik yang Berdimensi Gender
Selama ini kita tahu, ruang publik bersifat universal dan milik semua orang, kata Stephen Carr, Mark Francis, Leanne G. Rivlin, Andrew M. Stone dalam Public Spaces (1998). Artinya, ruang publik harus bisa mempertimbangkan berbagai identitas, kelas, dan status sosial masyarakat tanpa kecuali, sehingga semua orang bisa menikmatinya.
Sayang, di lapangan kondisinya berbeda, ruang publik adalah milik lelaki saja. Enggak cuma di India, tapi juga belahan negara lainnya di dunia. Dikutip dari tulisan Playgrounds for all: Designing inclusive public spaces for girls and women in sports, sebesar 75 persen anggaran kota di Perancis dihabiskan untuk fasilitas publik yang sebagian besar digunakan oleh laki-laki.
Pernyataan ini kemudian disusul dengan laporan Hubertine Auclert Center pada 2023 tentang perempuan dan ruang publik. Dalam laporan itu dijelaskan, meskipun fasilitas untuk latihan olahraga gratis (taman skate, stadion kota, lapangan bermain) terbuka untuk semua orang, pada kenyataannya penggunaannya didominasi laki-laki. Bahkan perkiraan tingkat pengguna laki-laki berkisar antara 85 hingga 100 persen.
Enggak jauh berbeda dengan Perancis, Selandia Baru dan Inggris pun sama saja. Di Selandia Baru, studi 2018 tentang penggunaan ruang bermain publik di Auckland menemukan, 58 persen anak laki-laki menggunakan semua ruang lapangan bermain publik. Ini disusul dengan 88 persen taman skate di Auckland yang didominasi oleh anak laki-laki.
Di Inggris, Make Spaces for Girls, NGO yang bergerak pada isu ruang publik bagi perempuan juga merilis laporannya pada 2023. Dalam laporan itu mereka menyatakan hampir seluruh ruang publik di Inggris, yang terdiri dari fasilitas seperti taman skate, Multi Use Game Area (MUGA), dan trek BMX didominasi oleh laki-laki. Di MUGA Inggris, dari 60 pengguna, hanya ada 5 perempuan.
Hal yang sama terjadi dengan setidaknya 1.600 taman skate di Inggris yang tidak pernah dipadati oleh perempuan. Work di York melaporkan keenganan perempuan menggunakan taman skate ini karena 90 persen dari mereka yang menyukai skateboard enggak nyaman berada di sana. Sebanyak 68 persen anak perempuan bilang, beberapa anak laki-laki senang melontarkan candaan seksis.
Fenomena ruang publik yang didominasi oleh laki-laki ini sempat dijelaskan oleh Sarah Thomson dari Departemen Pendidikan, Universitas Keele dalam penelitiannya berjudul ‘Territorialising’ the primary school playground: deconstructing the geography of playtime (2005). Dalam penelitiannya itu dijelaskan, dominasi laki-laki di ruang publik sebenarnya disengaja dan disebut dengan istilah territorialising.
Territorialising membuat penggunaan ruang oleh kelompok tersebut dianggap sebagai ‘hak’ yang kemudian tertanam dalam kesadaran kolektif. Ini mengajarkan anak laki-laki untuk menganggap ruang publik sebagai teritori mereka, sekaligus mengajarkan anak perempuan, hak mereka untuk menggunakan ruang publik bergantung pada laki-laki yang menyediakannya. Maka enggak heran, jika dominasi lelaki di ruang publik dianggap wajar oleh masyarakat.
Baca Juga: Pandemi dan Mitos Pelecehan Seksual di Ruang Publik
Perempuan Dibuat Tidak Nyaman dengan Tubuhnya
Selain mengangkat isu soal ruang publik yang berdimensi gender, dokumenter Under the Open Sky juga membahas tentang hak perempuan atas tubuhnya sendiri. Film itu memperlihatkan, perempuan sedari kecil sudah dibentuk untuk tidak mengenal dan nyaman dengan tubuhnya sendiri.
Mereka berulang kali diberi tahu oleh orang tua dan orang-orang di sekitarnya untuk berhati-hati dengan tubuhnya. Tidak jarang mereka dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, seperti memanjat atau berlari. “Kamu perempuan, kamu harus hati-hati. Tidak boleh melakukan ini”. Sebaliknya, anak laki-laki sedari kecil didorong untuk aktif menggunakan tubuhnya dan bebas bermain apa saja.
Keisha, salah satu mahasiswa UIN Jakarta yang menghadiri pemutaran film ini juga punya pengalaman senada. Dia bercerita sempat jatuh cinta dengan Taekwondo karena gerakannya yang indah dan bikin tubuh bugar. Karena masih tinggal bersama orang tua dan masih sekolah, Keisha meminta izin orang tuanya untuk ikut Taekwondo. Nyatanya, orang tua justru melarang dia ikut Taekwondo. Dalihnya, Taekwondo dianggap tidak cocok digeluti oleh perempuan seperti dirinya.
Pengalaman Keisha ternyata juga dialami oleh keponakan perempuan pembicara pemutaran film Under the Open Sky, Norcahyo Waskito, Gender transformative officer dari United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia.
Norchayo mengatakan keponakan perempuannya punya hobi panjat tebing dan ia mahir melakukannya. Bukannya didukung oleh keluarga besar, keponakan perempuannya justru mendapat cibiran. Mereka bilang tidak seharusnya anak perempuan punya hobi kelaki-lakian seperti itu.
“Kok anak perempuan gitu (melakukan panjat tebing). Nanti kenapa-kenapa, enggak boleh. Keluarga besar justru rewel. Padahal saudara laki-lakinya mau ngelakuin apa pun enggak ada yang komentar,” kata Nurcahyo.
Dari ceritanya ini, Norcahyo menyimpulkan, perempuan secara sosial dibatasi ruang geraknya. Tubuh mereka dikontrol, sehingga mereka tak bebas menentukan apa yang ingin mereka lakukan. Akibatnya fatal, perempuan jadi tidak mengenal tubuhnya sendiri, termasuk mengetahui potensi tubuh.
Di dokumenter ini terlihat dari bagaimana salah satu pelatih sepak bola anak dan remaja perempuan di Parcham yang bilang, perempuan lebih cenderung kesulitan dalam bergerak. Gerakan mereka seperti berlari, menggerakan tangan, hingga menendang cenderung “aneh” dibandingkan laki-laki saat melakukan olahraga yang sama.
Pergerakan tubuh perempuan yang “aneh” dan berbeda dengan laki-laki ini sempat disinggung oleh Iris Marion Young, filsuf feminis asal Amerika dalam esainya Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment, Motility, and Spatiality (2004). Dalam esai tersebut Young menjelaskan, sebagian besar perempuan sedari kecil tidak diberi kesempatan untuk menggunakan kapasitas tubuh mereka secara penuh dan terlibat secara bebas dan terbuka dengan dunia.
Mereka juga tidak didorong sebanyak anak laki-laki untuk mengembangkan keterampilan tubuh tertentu. Ini sesimpel dalam kegiatan sekolah atau di luar sekolah, anak perempuan tidak terlalu didorong untuk terlibat dalam olahraga. Sebaliknya perempuan menurut Young sering kali dituntun untuk bermain sesuai peran gender mereka dan semua itu umumnya bersifat tertutup dan pasif.
Baca juga: Tak Ada Tempat Aman Perempuan di Dunia Ini Kecuali Kuburnya
Akibatnya, perempuan sering menganggap tubuhnya sebagai beban, yang harus diseret dan didorong, dan pada saat yang sama dilindungi. Tidak hanya itu, perempuan juga jadi memiliki kecenderungan lebih besar daripada laki-laki untuk meremehkan tubuh mereka sendiri, menggap diri lemah dan rapuh.
Ini setidaknya tercermin dalam penelitian Global Sport Institute pada 2018 yang menemukan dari 78 anak perempuan Amerika Latin berusia 12 hingga 15 mereka mengakui sering tidak merasa tidak percaya diri dan nyaman melakukan kegiatan fisik seperti olahraga karena takut melakukan kesalahan dan terluka.
Anggapan pribadi ini sayangnya juga disusul dengan anggapan superioritas laki-laki dalam olahraga. Walhasil banyak perempuan jadi enggan bahkan tidak suka melakukan atau terlibat dalam aktivitas yang membutuhkan kemampuan tubuhnya sendiri. Ini tercermin dari data minimnya keterlibatan anak perempuan dalam berolahraga di Perancis.
Dikutip dari tulisan Zelie Heran dan Emilie Faucheux dari DLA Piper, firma hukum asal Inggris, di Prancis hanya 20 persen anak perempuan berusia antara 11 dan 14 tahun yang memenuhi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia untuk melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga selama 60 menit setiap hari. Ini lalu disusul dengan dan sepertiga anak perempuan sekolah menengah pertama tidak lagi berpartisipasi dalam olahraga apa pun pada usia 9 tahun.
Permasalahan tentang tubuh perempuan dikontrol secara sosial dan ruang publik yang masih didominasi oleh laki-laki tentu butuh penyelesaian tepat dan sensitif gender. Setidaknya ada tiga cara yang Magdalene rangkum dari tulisan Heran dan Faucheux serta Learning through Landscapes, kegiatan amal Inggris yang bergerak di peningkatan akses pembelajaran dan bermain.
Pertama, menghapus stereotip gender dalam unit keluarga. Stereotip tradisional tentang maskulinitas dan feminitas merugikan kita semua. Kita bisa mulai dengan mengingatkan anak-anak sejak kecil untuk tidak takut melakukan banyak hal. Berlari-larian, bermain lumpur, atau melakukan aktivitas fisik itu untuk semua orang bukan gender tertentu.
Kedua, mendorong sekolah untuk memberikan anak perempuan memiliki kebebasan untuk belajar dan bermain di luar ruangan tanpa tekanan. Misalnya pihak sekolah harus memastikan seragam, peralatan olahraga, dan jadwal sekolah memfasilitasi olahraga dan bermain untuk anak perempuan, bukannya membatasi mereka.
Ketiga, mendorong ruang publik yang aman dari pelecehan seksual. Keenganan anak perempuan menggunakan ruang publik salah satunya karena dinilai tidak aman untuk mereka. Sudah jadi tanggung jawab kolektif bagi masyarakat untuk memberi penyadaran bagi laki-laki untuk tidak melakukan pelecehan seksual pada perempuan di ruang publik.
Salah satu caranya bisa dengan kampanye. Adidas misalnya baru-baru ini meluncurkan The Ridiculous Run yang bertujuan untuk mendorong kesadaran masyarakat tentang tantangan yang dihadapi perempuan saat berolahraga di ruang publik dan mendorong laki-laki untuk mendidik diri mereka sendiri tentang masalah ini sehingga mereka bisa jadi sekutu yang baik.
Keempat, mendorong perencanaan kota dapat yang lebih inklusif gender. Pemerintah kota Barcelona misalnya sudah melakukan ini dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua kebijakan perencanaan kota untuk mewujudkan kota yang lebih adil, lebih setara, dan lebih aman.
Hal ini termasuk mempertimbangkan detail-detail kecil seperti penempatan bangku dan penyeberangan zebra, serta proyek-proyek yang lebih besar seperti renovasi lingkungan. Strategi ini mengakui peran perempuan di ruang publik dan mendorong universalisasi nilai-nilai kepedulian, menerapkannya pada ekosistem kota (manusia, masyarakat, dan alam).