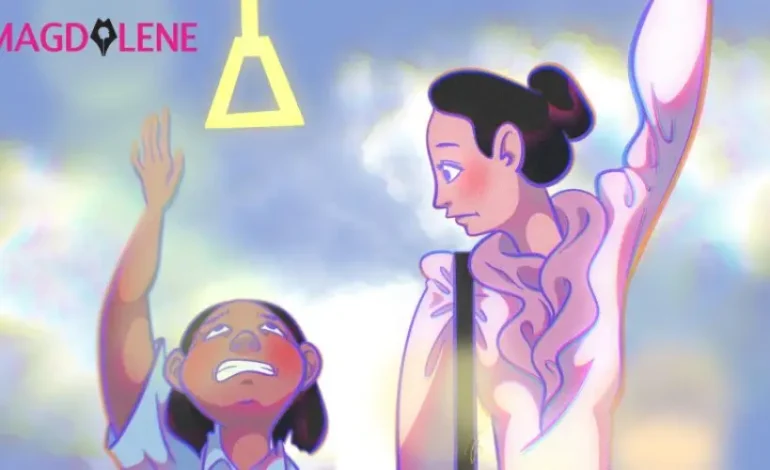Sejarah Pelonco di Indonesia: Warisan Belanda?

Perpeloncoan adalah masalah laten pendidikan. Kerap dianggap sebagai tradisi, ia justru terbukti menghambat proses belajar-mengajar. Artikel ini membahas apa sebenarnya perpeloncoan itu dan bagaimana sejarahnya di Indonesia dan praktiknya di berbagai negara.
Apa Itu Perpeloncoan?
Pada 2017, UNESCO, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan dunia melalui kerja sama internasional di bidang pendidikan, seni, ilmu pengetahuan dan budaya, melalui rilis bertajuk School Violence and Bullying: Global Status Report, melaporkan bahwa sekitar 246 juta siswa di seluruh dunia mengalami kekerasan setiap tahunnya. Dari semua jenis kekerasan yang dialami dalam lingkup pendidikan, perundungan adalah yang paling sering terjadi.
Perpeloncoan, atau hazing dalam bahasa Inggris, dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk perundungan. Namun, berbeda dari perundungan pada umumnya, perpeloncoan berlangsung dalam jangka yang lebih singkat dan identik dengan masa orientasi peserta didik baru.
Secara definisi, perpeloncoan dapat dipahami sebagai upacara inisiasi atau kegiatan yang harus dilalui untuk memperoleh keanggotaan dalam suatu komunitas. Namun, yang menjadi masalah adalah perpeloncoan umumnya melibatkan aktivitas yang bersifat mempermalukan, mengintimidasi, bahkan tak jarang membahayakan pesertanya.
Perpeloncoan juga kerap dianggap sebagai sebuah “harga” yang harus dibayar seseorang untuk dapat bergabung di komunitas barunya. Ia bertujuan menguji komitmen anggota baru melalui aktivitas-aktivitas yang tak jarang abusif. Anggota yang telah menjalani perpeloncoan dianggap sah menjadi bagian dari komunitas.
Baca juga: Perpeloncoan Mahasiswa Baru Masih Saja Terjadi, Apa Solusinya?
Sudah Ada Sejak Lama, Warisan Belanda?
Dalam sejarahnya, perpeloncoan di Indonesia sudah ada sejak era kolonial Belanda, dan difungsikan untuk menyambut peserta didik baru di tingkat perguruan tinggi. Di masa itu, perpeloncoan masih disebut sebagai ontgroening. Secara harfiah, ontgroening dalam Bahasa Belanda berarti “menghilangkan warna hijau” karena mahasiswa baru dilambangkan berwarna hijau, layaknya bibit tanaman.
Salah satu lembaga pertama yang tercatat melakukan perpeloncoan adalah School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) yang menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Berdasarkan kisah Mohammad Roem, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia yang juga alumnus STOVIA, perpeloncoan terjadi selama tiga bulan karena STOVIA merupakan sekolah asrama.
Pada masa tersebut, mahasiswa junior dikondisikan untuk menjadi pelayan bagi seniornya. Misalnya, mahasiswa baru harus memanggil seniornya dengan panggilan “Tuan”, menjadi kurir untuknya, atau mengelap sepatunya.
Istilah perpeloncoan sendiri baru muncul pada masa pendudukan Jepang. Istilah ini awalnya berasal dari kata bahasa Jawa “pelonco” yang berarti kepala gundul. Ini merujuk pada tradisi ketika mahasiswa baru wajib digunduli rambutnya untuk melambangkan anak kecil yang belum tahu apa-apa..
Memasuki periode Indonesia modern, tradisi perpeloncoan tak serta-merta hilang. Namun, resistensi juga muncul, misalnya dari sejumlah kalangan mahasiswa seperti Consentrasi [konsentrasi] Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) yang menyebut perpeloncoan sebagai warisan kolonial. Namun, CGMI yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) kemudian turut bubar seiring naiknya Orde Baru.
Sejak saat itu pula, masa orientasi mahasiswa hadir dalam sejumlah nama berbeda, misalnya Masa Prabakti Mahasiswa (Mapram), Pekan Orientasi Studi (POS), hingga Orientasi Studi Pengenalan Kampus (OSPEK) yang kini nyaris menjadi sinonim bagi kegiatan orientasi mahasiswa baru.
Baca juga: Sekolah Alternatif untuk Transpuan: Melawan dalam Diam
Bukan Hanya di Indonesia
Perpeloncoan bukan hanya masalah negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian Toshio Ohasko, peneliti senior UNESCO dari Jepang, di tahun 1997, menunjukkan bahwa kekerasan di lingkup pendidikan berpotensi sama besarnya baik di negara maju atau negara berkembang. Hal ini diperkuat dengan temuan Motoko Akiba, pakar kebijakan pendidikan dari Mid-continent Research for Education and Learning, Amerika Serikat (AS), yang penelitiannya di 37 negara pada tahun 2002 juga menyimpulkan bahwa kekerasan di lingkup pendidikan rawan muncul di semua negara.
Di negara maju seperti AS pun, perpeloncoan bukan hal asing. Aktivitas yang sayangnya sering memakan korban ini, lazim ditemui dalam proses inisiasi masuk asrama ataupun komunitas-komunitas persaudaraan (fraternity).
University of Maryland di AS mencatat bahwa sejak 1970 hingga 2017, paling tidak ada satu kasus kematian per tahun akibat perpeloncoan di setiap universitas. Wujud perpeloncoan yang kerap muncul di sana adalah pemaksaan minum alkohol, pelecehan seksual, maupun aktivitas fisik di luar batas kewajaran.
Penelitian dari Sonja Pecjak dan Tina Pirc, dosen Psikologi asal University of Ljubljana, Slovenia, juga menunjukkan bahwa 79 persen siswa sekolah menengah atas di Slovenia mengalami perpeloncoan di luar masa orientasi resmi sekolah. Namun, perpeloncoan tersebut kerap diabaikan pihak sekolah karena dianggap ada di luar otoritas mereka.
Baca juga: ‘Bullying’ di Tempat Kerja: Apa Saja Bentuknya dan Bagaimana Menyikapinya?
Bahkan, di Korea Selatan, perpeloncoan ditengarai menjadi salah satu penyebab bunuh diri. Menggunakan studi kasus sekolah militer, Kim Jae-Yop, dosen dari School of Social Welfare Yonsei University, Korea Selatan dan rekan-rekannya, menemukan bahwa sekitar 17,6 persen taruna pernah diperlakukan di luar batas wajar pendidikan. Perlakuan ini, rupanya, konsisten dengan munculnya gejala seperti depresi dan tendensi bunuh diri.
Karena praktik-praktik seperti di atas, kekerasan dalam dunia pendidikan seperti perpeloncoan telah lama dikategorikan sebagai salah satu isu global kontemporer. Kategorisasi ini merupakan bagian dari usaha untuk memutus rantai perpeloncoan dan memastikan terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.