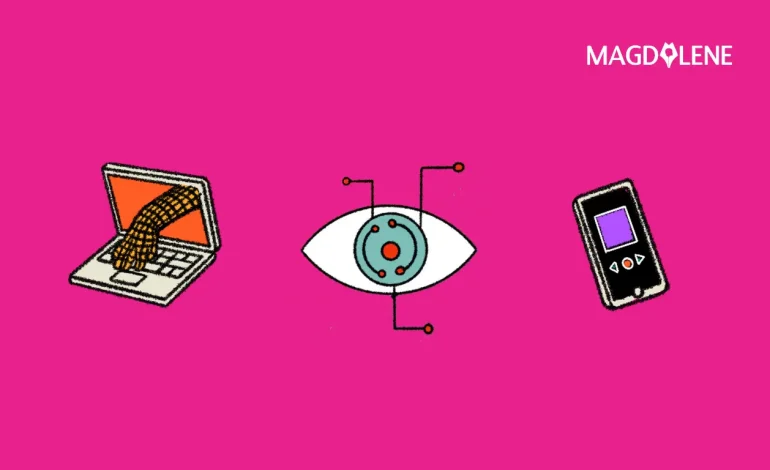‘Sudah Nikah Belum?’ dan Seribu Satu Cara Tubuh Perempuan Diinterogasi

“Mbok, sudah nikah belum? Kalau belum, sama saya aja.”
Kalimat itu meluncur santai dari mulut seorang laki-laki di barisan peserta diskusi. Saya sedang berdiri di panggung, membahas bias sistemik dalam budaya kerja. Topiknya tentang beban ganda, jam kerja panjang, ketimpangan kesempatan. Tapi yang ditodong ke saya justru status pernikahan.
Ruangan tertawa. Saya tidak.
Tujuh tahun membangun organisasi perempuan membuat saya terbiasa dengan momen seperti ini. Tema diskusi boleh berganti—bias gender, kekerasan berbasis gender, interseksionalitas—tapi ada satu pola yang tidak pernah berubah, yakni tubuh dan kehidupan pribadi perempuan selalu jadi bahan interogasi. Dan entah kenapa, komentar seperti itu paling sering muncul ketika ada laki-laki di ruangan.
Dalam kajian psikologi, komentar kecil yang “kelihatannya bercanda” tapi menyimpan pesan merendahkan ini disebut microaggression: serangan halus, komentar sepele, atau gestur ringan yang membawa pesan merendahkan dan pelan-pelan mengikis rasa aman. Laporan internasional seperti McKinsey & Lean In (2024) mencatat bahwa perempuan dua kali lebih sering mengalaminya dibanding laki-laki. Banyak perempuan bahkan mengaku, serangan halus seperti ini lebih melelahkan dibanding diskriminasi yang terang-terangan.
Karena bentuknya “cuma bercanda”, pelakunya jarang merasa bersalah. Tapi kita yang jadi sasaran tahu persis rasanya: seperti disenggol pelan di tempat yang sama, berkali-kali, sampai memar.
Di forum lain, seorang laki-laki berkata dengan nada sok bijak, “Perempuan sekarang kerja boleh-boleh aja, tapi jangan lupa kodratnya kalau sudah menikah.”
Saya menjawab bahwa kodrat perempuan itu perkara biologis: menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Ia menimpali cepat, “Tetap butuh laki-laki, kan?”
Ruangan kembali tertawa. Lagi-lagi, tubuh dan peran domestik perempuan diperlakukan sebagai lelucon publik.
Komentar seperti ini bukan sekadar opini pribadi, tapi cermin cara pikir sosial yang mengakar kuat. Psikologi menyebutnya gender role schema: keyakinan bawah sadar bahwa perempuan “seharusnya” berorientasi ke rumah dan keluarga, sementara ruang publik adalah panggung utama laki-laki. Jadi ketika perempuan hadir dengan otoritas pengetahuan, refleks sosialnya adalah “mengembalikan” dia ke urusan dapur, nikah, dan anak.
Di sisi perempuan, kondisi ini melahirkan role incongruity stress: stres ketika apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan peran gender tradisional. Stress ini bersifat halus tapi konstan, dengan munculnya perasaan bersalah atau “salah tempat” ketika kita mengambil peran di ruang publik. Penelitian menunjukkan, perempuan yang vokal dan tegas sering dilabeli galak atau kurang feminin, sementara laki-laki dengan gaya yang sama dianggap tegas dan kompeten.
Tidak berhenti di depan mikrofon, pola ini ikut berkeliaran di belakang layar. Seorang sahabat saya, sesama aktivis, pernah mendengar seorang rekan media berbisik, “Pantas sibuk terus, makanya belum nikah. Cewek macam mbaknya itu.”
Laki-laki sibuk dianggap berdedikasi, perempuan sibuk dianggap lalai.
Ini yang dalam psikologi sosial dikenal sebagai attribution bias: ketika situasi laki-laki dianggap akibat “kapasitas”, sementara situasi perempuan dianggap akibat “kekurangannya”. Kalau laki-laki telat menikah, alasannya karier. Kalau perempuan telat menikah, alasannya “kebanyakan milih”.
UNESCO dan berbagai lembaga internasional juga mencatat, perempuan profesional—baik di sains, media, maupun organisasi sosial—lebih sering ditanya soal keluarga, usia, dan rencana punya anak, bahkan di forum yang tidak ada hubungannya dengan itu. Di titik tertentu, rasanya seperti prestasi kita hanya dianggap catatan kaki dari status marital.
Candaan kecil, luka yang serius
Bentuk-bentuk serangan halus ini tidak hanya menyasar tubuh, tapi juga kerja intelektual perempuan.
Dalam beberapa diskusi tentang interseksionalitas—bagaimana kelas, gender, ras, pekerjaan, orientasi seksual, dan identitas lain saling bertaut—ada saja yang merespons dengan komentar sembrono: “Oh, jadi feminisme itu mendukung pekerja seks, ya?”
Di sinilah terlihat bentuk intellectual microaggression: menyempitkan wacana kompleks menjadi stereotip tunggal, seolah seluruh pembicaraan tentang interseksionalitas bisa diringkas menjadi “feminisme membela pekerja seks”.
Padahal yang kami bahas adalah struktur ekonomi, relasi kuasa, dan bagaimana kelompok perempuan berbeda mengalami kerentanan yang tidak sama. Pekerja seks muncul dalam diskusi bukan karena feminisme “mempromosikan” profesi, melainkan karena mereka sering berada di titik paling rentan: diabaikan hukum, dimiskinkan secara ekonomi, rentan kekerasan, tapi paling sedikit dilindungi.
Ketika seluruh diskusi kompleks itu disempitkan jadi satu kalimat sinis, yang terjadi adalah bentuk lain dari serangan halus: meremehkan kerja intelektual perempuan dan mengerdilkan wacana yang sebenarnya sedang membongkar ketidakadilan.
Sering juga muncul komentar,“Kenapa feminis marah-marah terus?”
Kemarahan perempuan dibaca sebagai gangguan, bukan sinyal bahwa ada yang tidak beres. Padahal, feminisme tidak lahir karena hobi membenci laki-laki; ia lahir dari cinta—kepada diri sendiri, kepada sesama perempuan, dan kepada dunia yang seharusnya bisa lebih adil. Kritik terhadap patriarki adalah kritik terhadap sistem, bukan serangan ke individu laki-laki. Tapi di budaya yang nyaman dengan status quo, kemarahan perempuan lebih mudah dilabeli “berlebihan” daripada didengar.
Berbagai riset psikologi menunjukkan, serangan halus seperti ini menurunkan rasa aman, meningkatkan kecemasan sosial, dan membuat perempuan lebih berhati-hati bicara di ruang publik. UNESCO bahkan menemukan, perempuan yang terus-menerus mengalami komentar meremehkan cenderung mundur dari posisi pemimpin atau memilih diam di rapat, supaya “tidak terlalu menonjol”.
Di titik itulah saya paham, kenapa setiap kali ada laki-laki di forum, tubuh saya menegang satu detik lebih lama. Bukan karena benci, tapi karena antisipasi: Hari ini, suara saya akan direspons sebagai gagasan, atau sebagai tubuh?
Kami, para perempuan, tidak sedang mencari-cari alasan untuk marah. Kami marah karena suara kami berkali-kali dinomorduakan dari status pernikahan kami. Kami marah karena setiap langkah menuju ruang publik selalu diiringi upaya halus untuk menyeret kami kembali ke ruang domestik.
Kami marah karena sudah terlalu sering dinilai sebagai objek, bukan diakui sebagai subjek yang berpikir.
Tapi di balik itu semua, kemarahan kami juga datang dari cinta.
Kami marah karena kami tahu dunia ini bisa lebih baik daripada sekarang.
Kami marah karena kami ingin generasi perempuan setelah kami bisa berdiri di panggung tanpa harus menjawab pertanyaan, “Sudah nikah belum?”
Membicarakan serangan halus seperti ini adalah cara kami membalikkan arah kuasa. Menamai luka kecil adalah langkah pertama untuk menghentikan pola yang sama berulang terus. Kami ingin perempuan bisa hidup bukan sebagai tubuh yang diinterogasi, tetapi sebagai manusia yang utuh, punya suara, dan berdaulat atas dirinya sendiri.
Anindwitya Rizqi Monica adalah konsultan dan pembicara di bidang kesetaraan gender dan pariwisata. Ia merupakan pendiri Women in Tourism Indonesia (WTID) dan pemilik JogJamu Indonesia. Anindwitya menempuh pendidikan S1 Pariwisata dan S2 Psikologi.
Ilustrasi oleh Karina Tungari