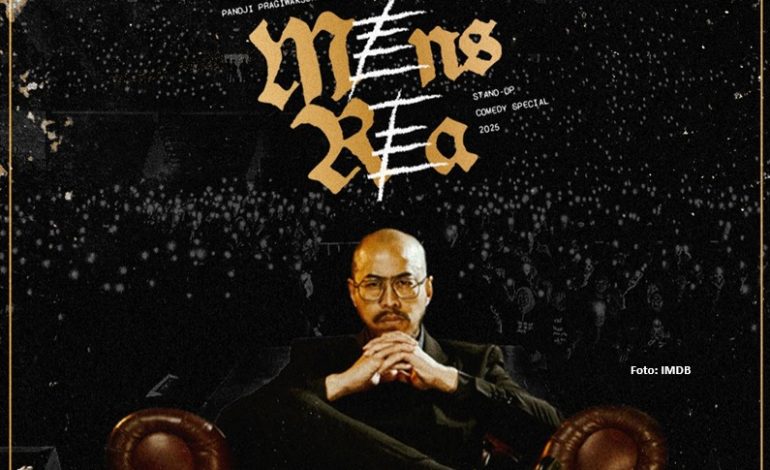‘Thin is in!’, ‘SkinnyTok’, dan Kembalinya Standar Cantik Kurus Ekstrem

Dunia hiburan global dikejutkan oleh transformasi fisik yang drastis dari jajaran pemeran utama film musikal Wicked.
Dalam berbagai wawancara eksklusif dan kemunculan di karpet merah, Ariana Grande dan Cynthia Erivo tampak mengalami penurunan berat badan drastis hingga menciptakan siluet yang mengkhawatirkan. Pipi mereka tirus, tulang selangka menonjol, dan pergelangan tangan mengecil bak hanya dilapisi kulit tipis di atas tulang.
Michelle Yeoh—yang selama puluhan tahun dikenal memiliki tubuh atletis sebagai bintang laga—kini juga tampil dengan fisik yang jauh lebih kurus, menyerupai rekan-rekan mudanya.
Di media sosial, penampilan fisik para aktor ini menjadi bahan bedah publik. Unggahan viral membandingkan foto-foto lama dan terbaru mereka, memicu spekulasi liar, termasuk dugaan mereka mungkin mengalami gangguan makan.
Pada November 2025, Ariana Grande secara terbuka membantah rumor tersebut dan meminta publik berhenti mengomentari tubuhnya. Para penggemarnya pun membela dengan menyebut kritik itu sebagai bentuk body shaming.
Namun bagi banyak pengamat budaya dan pakar kesehatan, polemik ini melampaui urusan privasi individu. Ia menjadi sinyal bahaya kembalinya standar kecantikan yang toksik. Standar yang berpotensi merusak citra diri generasi muda secara sistemik di seluruh dunia.
Baca juga: Saya Feminis, Saya Menentang Narasi ‘Semua Perempuan Cantik’
Thin is in! Hingga SkinnyTok yang Normalisasi Kelaparan
Berbagai laporan media menunjukkan kita sedang ditarik kembali ke era ketika tubuh sangat kurus kembali dipuja sebagai mata uang estetika utama. Fenomena ini membangkitkan ingatan kolektif tentang tren heroin chic yang mendominasi 1990-an.
Kala itu, kecantikan diasosiasikan dengan kulit pucat, lingkaran hitam di bawah mata, rambut tipis dan kusut, serta tubuh yang sangat kurus hingga tampak rapuh dan androgini. Bibir merah gelap dan struktur tulang yang tajam menjadi ciri khasnya. Model seperti Kate Moss diposisikan sebagai ikon ideal.
Tak butuh waktu lama hingga estetika tersebut memicu lonjakan kasus anoreksia dan merusak cara generasi muda memandang tubuhnya sendiri. Tubuh yang tidak sehat dijadikan standar yang harus dikejar.
Tiga dekade kemudian, pola yang sama kembali muncul dalam kemasan baru.
Aktris dan aktivis Jameela Jamil menyebutnya sebagai aesthetic of emaciation—estetika kelaparan. Dalam unggahan TikTok-nya, Jamil menyoroti bagaimana perempuan usia 20 hingga 50-an tiba-tiba tampil jauh lebih kurus, dengan wajah cekung, tulang rusuk dan tulang pinggul menonjol keluar.
Ia mengaitkan tren ini dengan kebangkitan estetika konservatif yang secara historis menuntut perempuan tampil “kecil”, rapuh, dan mudah dikontrol.
Bahaya paling nyata dari tren ini terlihat di media sosial melalui kemunculan SkinnyTok: jaringan influencer TikTok yang secara terbuka mempromosikan kekurusan ekstrem.
Dalam ekosistem digital yang toksik ini, perempuan muda dibombardir pesan manipulatif untuk membatasi makan. Kalimat seperti, “Kamu tidak benar-benar butuh roti itu. Terlalu mahal jika harus mengorbankan target tubuhmu,” disebarkan sebagai motivasi.
Ironisnya, algoritme justru memperkuat paparan tersebut. Sekali pengguna berinteraksi dengan konten serupa, mereka akan terus dijejali video sejenis. Akun-akun seperti @eveolivia_ dan @taylorvvaughn yang agresif mengglorifikasi tubuh sangat kurus mendapat jutaan penonton dan diposisikan sebagai panutan.
Pada April tahun lalu, tagar #SkinnyTok memang sempat diblokir setelah dilaporkan massal oleh pengguna. Namun kontennya tidak pernah benar-benar hilang. Para kreator dengan cepat mengakali algoritma dengan kata kunci baru untuk tetap menyebarkan tips melewatkan makan dan mengecilkan tubuh.
Tren kurus ekstrem, sekali lagi, tidak sekadar soal estetika. Ia adalah mesin budaya yang secara diam-diam mengajarkan satu pesan berbahaya. Bahwa tubuh perempuan baru layak diterima jika ia cukup kecil.
Akibatnya pun nyata. Dr. Jasmine Reese dari Johns Hopkins All Children’s Hospital mencatat adanya lonjakan kasus gangguan makan pada remaja perempuan lebih dari dua kali lipat sejak 2018.
“Akses digital memicu perilaku ‘orthorexia’, obsesi pada makanan sehat yang berujung pada pembatasan kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pertumbuhan,” jelas Dr. Reese.
Sementara itu, Rumah Sakit Anak Colorado melaporkan peningkatan sebesar 73 persen dalam jumlah pasien yang menggunakan Program Gangguan Makanan selama setahun terakhir. Para tenaga medis juga menyebutkan bahwa remaja usia 13 hingga 15 tahun semakin sering datang untuk mendapatkan perawatan.
Kondisi ini kemudian diperparah dengan normalisasi penggunaan obat penurun berat badan atau dikenal sebagai GLP-1 seperti Ozempic, Mounjaro, Trulicity, dan Rybelsus. Penelitian dari Jurnal Asosiasi Medis Amerika (JAMA) menunjukkan resep GLP-1 meningkat sebesar 594,4 persen antara tahun 2020 dan 2023. Kemudian, antara 2023 dan 2025, tingkat resep Wegovy (semaglutide) meningkat sebesar 50 persen, dari 9,9 per 100.000 remaja pada 2023 menjadi 17,3 pada 2025.
Kenaikan ini sejalan dengan endorse besar-besaran GLP-1 yang dilakukan selebriti seperti Meghan Trainor, Oprah Winfrey, Kathy Bates bahkan atlet papan atas seperti Serena Williams. Pada puncaknya pada Juni 2024, Novo Nordisk, produsen Ozempic, bernilai hingga US$615 miliar atau setara Rp9 ribu triliun.
Danni Rowlands, Direktur Program Pendidikan di Yayasan Butterfly, organisasi amal yang berfokus pada gangguan makan mengatakan bahwa tren penggunaan obat pelangsing ini mengkhawatirkan. Di permukaan, tren ini terlihat sebagai pendobrak stigma dan rasa malu terhadap penggunaan obat pelangsing. Namun pada kenyataannya sebut Rowlands, ini tetap merupakan budaya diet destruktif karena memoles standar kecantikan lama.
“Hal ini juga terus menambah rasa malu, bersalah, dan tekanan pada orang-orang yang ukuran tubuh dan penampilannya tidak sesuai dengan ideal tersebut,” sebutnya dalam wawancara bersama ABC News.
Baca juga: ‘Effortless Beauty’: Standar Ganda Kecantikan yang Mustahil Dicapai
Politik Tubuh: Estetika Konservatif dan Penjinakan Perempuan
Tren menjadi sangat kurus ini ternyata tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Seperti yang sudah disinggung Jameela Jamil sebelumnya, tren ini hadir sejalan dengan meningkatnya konservatisme yang ditandai lewat gerakan sayap kanan dan fenomena tradwife (istri tradisional).
Kekurusan ekstrem merupakan indikator pergeseran ideologis menuju nilai gender yang ultra-feminin yang melakat pada konservatisme. Dalam nilai gender ini, perempuan diharapkan tampil lemah, kecil, dan tidak dominan secara fisik maupun sosial.
Dan Hastings-Narayanin, Wakil Editor Riset di lembaga riset strategis The Future Laboratory lebih lanjut mengatakan ada alasan di balik obsesi sayap kanan membuat perempuan kurus. Ketika perempuan disibukkan dengan upaya mengecilkan tubuh dan mencapai kesempurnaan fisik yang rapuh, mereka secara tidak langsung sedang dikondisikan untuk tidak menuntut ruang dalam kepemimpinan.
“Kita melihat hal ini di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, India, dan Korea Selatan,” kata Hastings-Narayanin pada Vogue. “Siapa pun yang mencari identitas, rasa memiliki, atau kendali dalam dunia yang terfragmentasi rentan terhadap ide-ide ini (konservatif), format standar kesuksesan bagi perempuan kembali disempitkan menjadi citra yang performatif,” sambungnya.
Hal yang sama diungkapkan oleh Jessica Grose, jurnalis Amerika dalam siniar The New York Times. Ia menyoroti bagaimana tren fisik ini berjalan seiring dengan berkurangnya pemimpin perempuan di berbagai bidang. Menurut Grose, ide soal perempuan harus secara fisik lebih kecil berkaitan erat dengan penyingkiran mereka dari garis depan ruang publik.
“Gagasan perempuan harus secara fisik lebih kecil berjalan seiring dengan pemikiran bahwa mereka tidak akan menjadi sosok yang berada di garis depan untuk mengambil ruang publik,” ungkap Grose.
Dalam sistem ini, terdapat keinginan terselubung untuk mengembalikan perempuan sebagai “dekorasi” yang lemah, sementara peran strategis dan kekuasaan penuh kembali diambil alih oleh laki-laki, persis seperti tatanan dunia lama yang patriarkis sebelum era emansipasi.
Baca juga: Menentang Standar Kecantikan Agar Tubuh Tidak Terjajah
Mitos Kecantikan yang Terus Diproduksi Ulang
Kebangkitan tren kurus ekstrem ini membawa kita kembali pada analisis klasik Naomi Wolf dalam bukunya, The Beauty Myth (1990). Wolf berargumen bahwa mitos kecantikan bukanlah tentang estetika, melainkan tentang kekuasaan dan kontrol sosial. Ia menulis bahwa semakin banyak hak politik dan ekonomi yang diperoleh perempuan, semakin kuat pula tekanan budaya yang memaksa mereka untuk terobsesi pada penampilan fisik.
Dengan kata lain, kecantikan digunakan sebagai senjata politik untuk melumpuhkan energi perempuan. Ketika perempuan menghabiskan seluruh waktunya untuk menghitung kalori dan merasa benci pada tubuhnya sendiri, mereka tidak akan memiliki sisa energi untuk melakukan perubahan sosial atau melawan ketidakadilan sistemik.
Wolf menekankan bahwa tubuh perempuan telah menjadi subjek terkait penampilannya sebagai bentuk penahanan diri secara psikologis. Estetika emosiasi yang kita saksikan hari ini adalah manifestasi dari “kelaparan paksa” secara kultural yang bertujuan membuat perempuan merasa tidak berdaya secara fisik.
Tubuh yang lapar adalah tubuh yang mudah dikendalikan, pikiran yang dipenuhi obsesi akan kekurusan adalah pikiran yang terdistraksi dari isu-isu yang lebih besar. Bagi Wolf, standar kecantikan yang memuliakan kekurusan ekstrem sebenarnya adalah upaya patriarki untuk memastikan perempuan tetap sibuk dengan “penjara tubuh” mereka sendiri agar tidak mengancam dominasi laki-laki di ruang publik.
Sebab itu, langkah-langkah sistemik untuk meruntuhkan tren kurus memerlukan pergeseran paradigma dari sekadar tanggung jawab individu menjadi gerakan kolektif yang menyentuh akar kebijakan politik dan ekonomi.
Wolf menegaskan bahwa pembebasan perempuan hanya akan tercapai jika kita mampu memutus kaitan antara nilai diri dengan penampilan fisik. Karena itu, Wolf menyarankan agar perempuan secara sadar membangun solidaritas untuk menolak standar kecantikan yang mendorong perempuan jadi “sempurna” sesuai dengan kriteria yang terus berubah.
Solidaritas ini bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Secara sistem misalnya, solidaritas bisa dilakukan dengan mendorong lebih banyak regulasi yang diterapkan untuk menghindari penggunaan obat penurun berat badan sebagai solusi sementara.
Rowlands dari Butterfly Foundation menegaskan masyarakat harus melihat akuntabilitas yang lebih besar dari pemangku kebijakan. Screening yang tepat, tinjauan riwayat medis dan psikologis, konseling, serta pengungkapan penuh tentang efek samping potensial dan risiko psikologis perlu menjadi praktik umum jika seseorang hendak menegak obat pelangsing.
Di sisi lain, Dr. Natalie Jovanovski dari Universitas RMIT menekankan pentingnya perempuan secara kolektif mengadopsi “solusi sehari-hari” karena tren dan obat-obatan baru akan terus muncul dengan beragam polesan. Ia memberikan contoh dari penelitiannya sendiri di mana para respondennya menggunakan stragegi sehari-hari untuk menantang budaya diet.
“Misalnya, memutuskan untuk tidak menimbang diri sendiri, atau tidak membicarakan diet, penurunan berat badan, dan sebagainya saat sedang berbincang dengan rekan kerja itu penting,” jelasnya.