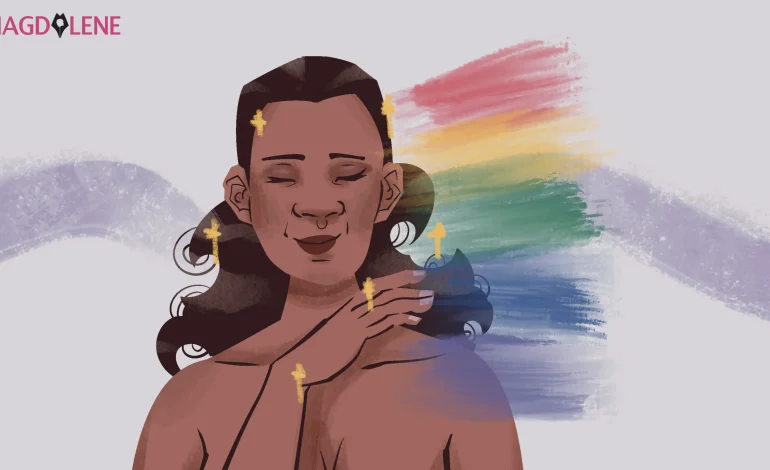
“Katanya, warna biru bikin kulit kusam padahal aku sangat suka warna biru,” ujar Adel, content creator di bidang industri kecantikan.
Komentar tersebut membuat Adel mulai mempertimbangkan untuk mencoba personal color analysis. Terlebih, ia kerap mendapat respons serupa dari orang-orang di sekitarnya soal warna baju, rambut, hingga lipstik yang dianggap “tidak cocok” dan membuat kulitnya tampak kusam.
Personal color analysis sendiri merupakan proses analisis warna yang bertujuan menentukan spektrum warna paling sesuai dengan warna kulit, mata, dan rambut seseorang. Ini diputuskan berdasarkan undertone atau warna dasar di bawah permukaan kulit. Hasil dari analisis ini digunakan sebagai panduan untuk memilih warna pakaian, makeup, hingga aksesori yang dinilai dapat mencerahkan tampilan, menyamarkan noda, dan menonjolkan fitur wajah.
Menurut Bonita D. Sempurno, konsultan penampilan profesional dalam keterangannya di Tirto.id, warna-warna dalam personal color analysis biasanya dikelompokkan ke dalam empat kategori musim: Summer, spring, autumn, dan winter. Masing-masing kategori disesuaikan dengan undertone kulit (cool atau warm), intensitas warna (deep atau light), dan value-nya (bright atau soft).
Bagi Adel, mengikuti personal color analysis bukan berarti tunduk pada standar kecantikan yang dominan. Sebaliknya, ia merasa metode ini justru membantunya mengenali dan menonjolkan karakter unik dari fitur wajahnya.
Pengalaman itu turut meningkatkan rasa percaya dirinya. “Aku jadi lebih percaya diri karena ternyata pemilihan warna yang tepat berpengaruh, apalagi buat content creator kecantikan seperti aku,” kata Adel.
Namun, benarkah personal color analysis benar-benar membuka ruang bagi definisi kecantikan yang lebih beragam? Apakah ia mampu mendekonstruksi standar yang seragam? Ataukah justru menjadi cara baru yang lebih halus dalam menjebak kita pada stereotip lama—yang tetap berpihak pada penampilan, warna kulit, dan imajinasi kecantikan yang terus dikendalikan pasar?
Baca Juga: Sejarah ‘Cantik itu Putih’ dan Kolonialisme di Indonesia
Saat Colorisme Menyusup dalam Tren Kecantikan
Salah satu bias yang sulit dihindari dalam praktik ini adalah colorisme—prasangka buruk terhadap warna kulit gelap. Paham ini secara halus tercermin dalam logika personal color analysis. Dalam bahasa yang biasa digunakan industri kecantikan, kulit terang atau cerah adalah tujuan yang harus dicapai.
Dalam Yearning For Lightness: Transactional Circuits in the Marketing and Consumption of Skin Lighteners (2008), Evelyn Nakano Glenn menunjukkan preferensi terhadap kulit terang telah bertransformasi menjadi alat kapitalisme.
Kulit terang masih dipersepsikan oleh banyak masyarakat sebagai simbol status sosial dan ukuran kecantikan. Nilai sosial perempuan sering ditentukan dari penampilan fisik–menjadi target utama bagi industri kecantikan dalam mempromosikan apa yang mereka sebut “kulit cerah”.
Glenn menyebut light skin bertindak sebagai “symbolic capital” yang dapat menentukan akses terhadap pekerjaan, pasangan, hingga mobilitas kelas sosial-ekonomi.
Logika serupa dapat ditemukan dalam tren personal color analysis yang belakangan marak di dunia kecantikan. Sekilas, praktik ini tampak inklusif karena diklaim membantu menonjolkan versi “terbaik” dari warna kulit atau fitur wajah seseorang. Namun, di balik narasi self-love dan personalisasi, personal color analysis berpotensi memperhalus bentuk colorism yang kini dimodifikasi dan dikemas ulang oleh logika kapitalisme.
Alih-alih merayakan keberagaman warna kulit, personal color analysis justru dapat menciptakan standar kecantikan baru yang tetap berpihak pada kulit terang. Warna kulit yang dianggap flattering akhirnya terasosiasi dengan kriteria estetika tertentu: Enggak pucat, terang, bersih, seimbang, dan bersinar.
Dalam konteks ini, hasil analisis bukan lagi sekadar sarana penerimaan diri, tetapi juga turut mereproduksi nilai-nilai visual yang dikonstruksi oleh pasar—tentang rupa seperti apa yang dianggap ideal, layak tampil, dan pantas ditonjolkan.
Baca Juga: Stop Pandang Kulit Putih Lebih Superior
Waspada Color Analysis Sebagai Alat Kapitalisme
Ramayda Akmal, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, menekankan pentingnya memahami siapa saja aktor-aktor yang berada di balik munculnya tren color analysis ini.
Ia mengingatkan sejak awal, tes ini bukan barang yang netral. Menurutnya, personal color analysis ini sarat kepentingan ekonomi yang berorientasi pada logika pasar–terlihat jelas dari siapa yang memproduksi dan mempromosikannya.
“Yang menciptakan itu tentu saja para kapital, pemilik brand, pengusaha kosmetik dan kecantikan. Tujuannya jelas, untuk mengklaim bahwa produk mereka bisa membantu kita, tentu saja pada akhirnya untuk penjualan biar laris,” ujar Ramayda pada Magdalene (3/7).
Ia menjelaskan cara kerja color analysis mengikuti strategi pemasaran yang menyesuaikan diri dengan imajinasi sosial yang telah lama terbentuk, yakni anggapan bahwa kulit cerah adalah simbol kecantikan.
“Mereka melihat apa yang diyakini masyarakat, which is itu kadang-kadang sangat patriarkal, kemudian mereka memasukkannya ke dalam kriteria-kriteria color analysis itu. Jadi, apa yang ada di masyarakat itu dikuatkan lagi oleh mereka,” tambahnya.
Pengalaman Adel mencerminkan hal tersebut. Hasil analisis warna yang ia terima justru bertentangan dengan preferensi pribadinya. Warna biru yang selama ini menjadi favorit dinilai tidak cocok, sementara warna-warna seperti jingga dan kuning—yang sebelumnya ia hindari—justru dianggap paling “sesuai” untuk menunjang penampilannya.
Meski sempat ragu, Adel akhirnya memutuskan mengikuti rekomendasi warna dari analisator. Ia mulai membeli pakaian, makeup, dan aksesori yang sesuai dengan kategori warna yang disarankan.
Menurut Adel, pengalaman ini memang bisa menjadi hal yang problematik bagi sebagian orang. Ibarat pisau bermata dua, di satu sisi, keputusan berbelanja menjadi lebih terarah dan efisien karena didasarkan pada rekomendasi yang dianggap “cocok”. Namun di sisi lain, praktik ini dapat mendorong konsumsi berlebihan demi memenuhi standar visual tertentu, yakni tampil lebih cerah, bersinar, dan menonjolkan fitur wajah secara optimal.
Baca Juga: How I Learned to Embrace My Chocolate-Colored Skin
Memaknai Kecantikan yang Lebih Inklusif
Di tengah gempuran pasar yang terus menciptakan versi-versi baru dari standar kecantikan, Ramayda mencatat adanya pergeseran dalam strategi representasi industri kecantikan. Ia mengamati kini mulai terlihat upaya untuk menghadirkan keragaman, dari pemilihan brand ambassador dengan warna kulit yang beragam hingga peluncuran produk dengan berbagai pilihan shade.
Fenomena ini, menurutnya, membuka ruang bagi munculnya standar kecantikan baru yang lebih inklusif.
“Artinya cerah itu tidak hanya misalnya merujuk ke cerah putih. Namun cerah secara natural, sawo matang yang bersih, misalnya. Jadi enggak cuma putih saja, tetapi ada berbagai jenis,” jelas Ramayda.
Di lain sisi, Ramayda juga mengingatkan kebebasan dalam memilih standar kecantikan ini, tak sepenuhnya netral. Di tengah euforia perempuan yang bebas memilih, justru sering kali jadi incaran untuk dikomodifikasi oleh industri kecantikan.
Menurutnya, tren keberagaman ini bisa menjadi jebakan baru karena tetap beroperasi dalam logika pasar, yang mendorong seseorang terus berbelanja.
Memaknai kecantikan secara inklusif juga berarti bersikap kritis. Maksudnya, apakah kita benar-benar sedang merayakan keberagaman, atau hanya mengikuti pola lama yang kini dikemas lebih colorful?
“Kamu bisa menciptakan standar kecantikan yang baru, tapi jangan lupa, kalau itu tidak terkendali, bisa menjebak kita dalam konsumerisme,” ujarnya.
Selama “tubuh” masih dianggap sebagai pusat nilai perempuan, standar kecantikan akan terus hadir sebagai alat kontrol sosial. Padahal bagi Ramayda, kecantikan seharusnya bersifat multidimensional. Ia tidak semata melekat pada fisik, tapi juga hadir dalam cara berpikir, berbicara, bermimpi, hingga pada visi dan perspektif hidup seseorang.
Dengan memandang kecantikan secara lebih luas, kita diajak menggeser fokus dari tubuh ke penghargaan terhadap kualitas manusia secara utuh. Ini termasuk nilai, pengalaman, pemikiran, karakter, serta kapasitas intelektual dan emosional.
Pertanyaan pentingnya: Siapa yang berhak mendefinisikan cantik? Menurut Ramayda, pendefinisian sebaiknya tidak dikurasi pasar atau pihak-pihak yang mungkin berakar pada logika patriarki.
Yang lebih penting bukan terlihat cantik, melainkan merasa cantik. Ketika definisi kecantikan lahir dari diri sendiri, kepercayaan diri tumbuh secara otentik. Dampaknya, personal color analysis—atau bentuk lain dari kapitalisme kecantikan—tidak bisa mendikte bagaimana seseorang seharusnya tampil.
Pujian atas penampilan hanyalah salah satu bentuk apresiasi, bukan satu-satunya ukuran nilai perempuan.
“Kata cantik atau beauty itu bukan cuma soal tubuh. Kalau kita melihat lebih menyeluruh, menurut saya kita tidak akan mudah terjebak pada standar kecantikan yang sempit,” ungkap Ramayda.
Ia menutup, kita bisa, bahkan dalam situasi tertentu perlu, mengabaikan saran-saran yang mendikte atau menciptakan standar baru atas nama kecantikan.






















