‘Babel, or the Necessity of Violence’: Benarkah Kekerasan Dibutuhkan dalam Gerakan Pembebasan?
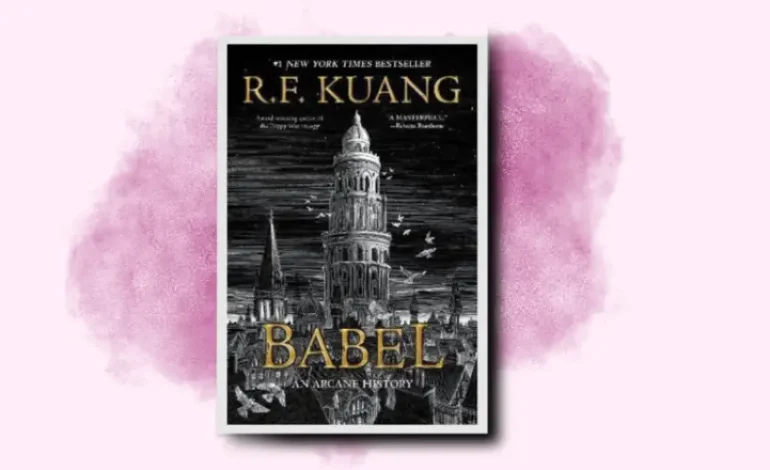
London era 1830-an adalah penanda kemajuan peradaban manusia. Orang-orang paling brilian di dunia tinggal di situ, termasuk akademisi Babel dari Institut Penerjemahan Kerajaan bergengsi di Oxford. Akademisi Babel bisa dibilang adalah tulang punggung paling penting di Kerajaan Inggris pimpinan Ratu Viktoria.
Dengan kecakapan linguistik, akademisi Babel tak sekadar menerjemahkan bahasa tapi juga alih bahasa untuk urusan bisnis sampai negosiasi antarbangsa. Tak heran jika akademisi ini kerap dikirim ke luar Inggris untuk menjadi tenaga alih bahasa. Ketika proses penerjemahan yang disebut silver working ini bekerja, “batang perak” bisa digunakan untuk apa saja. Mulai dari meledakkan sesuatu dengan bom hingga menyediakan tenaga listrik dan uap untuk seluruh kota.
Robin Swift, anak yatim piatu asal Cina adalah salah satu akademisi Babel. Ia dibawa ke Inggris dari tanah kelahirannya oleh Profesor Lovell. Swift diberi kehidupan baru nan nyaman, tapi sebagai gantinya diminta bekerja untuk Institut Penerjemahan Kerajaan.
Di sana Robin mempelajari bahasa. Enggak cuma menghapal, tapi diajari pemahaman tentang akar dan makna bahasa sedalam-dalamnya. Saat ia mulai bisa menavigasikan diri sebagai akademisi Babel, Robin dihadapkan dengan organisasi pemberontak, Hermes Society.
Griffin, salah satu anggota Hermes Society yang ternyata mantan akademisi Babel, mengungkap peran kejam Babel dalam penjajahan Inggris. Sontak Robin gundah. Ia harus membuat pilihan sulit antara tetap mendedikasikan diri pada Babel atau ikut memberontak demi melindungi Cina yang bakal dihancurkan oleh Inggris.
Baca Juga: 6 Rekomendasi Novel Feminisme Terbaru
Bahasa sebagai Senjata Penjajahan Inggris
Kuang menyatakan kepada Pop Matters, sebagai mahasiswa kulit berwarna di Oxford jadi titik mulanya mempertanyakan soal hubungan imperialisme Inggris dan aksesnya mengenyam pendidikan di sana. Apakah ia dapat privilese sebagai balas bukti penjajahan Inggris di masa lalu?
Lewat Robin, Kuang memaparkan sejarah rasisme, identitas, dan kepemilikan di Inggris abad ke-19. Ia menjaga keaslian sejarah cerita dalam catatan kaki dan penelitian yang dikutip di seluruh buku. Catatan ini menarik pembaca dalam sistem yang dihadapi oleh Robin dalam menyingkap fondasi imperialisme di mana Babel dibangun. Fondasi ini tak lain adalah bahasa.
Bahasa dalam novel Kuang adalah senjata kolonialisme dan imperialisme Inggris. Bahasa digunakan dalam proyek kolonial, karena proses penerjemahan dibutuhkan saat Inggris melintasi wilayah yang ditaklukkan. Pengangkutan teks asli ini digambarkan lewat Inggris yang secara sengaja membawa pergi anak-anak kulit berwarna seperti Robin dari tanah kelahirannya.
Saat anak-anak dibawa ke Inggris, proses tak kasat mata dalam memusnahkan bahasa dan pengetahuan non-Inggris pun terjadi. Sebagai akademisi Babel kulit berwarna, mereka harus patuh pada metode pendidikan Bahasa Inggris. Bertahun-tahun mereka belajar menyempurnakan penerjemahan bahasa-bahasa asli ke Bahasa Inggris dan menuliskannya dalam kamus.
Proses penerjemahan ini tapi tak terjadi sebaliknya pada bahasa-bahasa selain Bahasa Inggris. Ini enggak cuma membuat para akademisi kulit berwarna secara sengaja dicerabut dari akar identitasnya, tapi juga membuat mereka tak punya kesadaran lagi untuk melawan. Proses tersebut membuat Inggris dan supremasi kulit putih semakin kuat.
Apa yang disampaikan Kuang ini bukan cuma omong kosong atau fiksi belaka. Dalam pidatonya “Imperialisme Bahasa,” akademisi asal Kenya Ngugi wa Thiongo menjelaskan metode kolonisasi dan imperialisme Inggris lewat institusionalisasi Bahasa Inggris.
Pemerintah Inggris menanamkan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama dunia. Ia adalah segalanya dan puncak dari peradaban dari seluruh masyarakat dan budaya. Di wilayah koloni-koloni Inggris misalnya, Bahasa Inggris diintegrasikan dalam sistem pendidikan dan pemerintahan.
Mengutip artikel Contemporary Review of Genocide and Political setiap komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat harus disampaikan dalam Bahasa Inggris dan diterjemahkan, jika tidak maka komunikasi tersebut tidak resmi. Pejabat pemerintah hanya akan berkomunikasi dengan penduduk asli dalam Bahasa Inggris, meskipun mereka mengetahui bahasa asli.
Cara penggunaan Bahasa Inggris dalam pemerintahan mengasosiasikan bahasa itu dengan kekuatan politik dan sosial. Hal ini membuat orang-orang yang berbicara Bahasa Inggris mempunyai kekuasaan khusus dalam pemerintahan kolonial. Keterkaitan dengan kekuasaan ini menempatkan pemerintahan kolonial pada posisi yang lebih mudah bagi mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut untuk mengendalikan orang-orang pribumi.
Bahasa Inggris kemudian menjadi norma global baru untuk bisnis, inovasi, dan ilmu pengetahuan berskala besar. Misalnya, di Puerto Rico dikutip dari artikel majalah politik Universitas Brown Brown Political Review, perdagangan internasional dan sistem ekonomi-politik Barat melemahkan usaha kecil dan tradisi lokal. Orang-orang mendedikasikan waktu dan sumber daya untuk mempelajari dan menyempurnakan pemahaman dan pengetahuan tentang Bahasa Inggris, daripada melestarikan adat istiadat dan budaya sendiri.
Rafael Trelles, anggota Partai Independen Puerto Rico sampai mengatakan bahwa kolonialisme dan imperialisme telah menghancurkan budaya kerja sektor-sektor paling miskin dalam populasi mereka dan menciptakan budaya ketergantungan. Okoth Okombo, profesor linguistik di Universitas Nairobi lebih lanjut mengatakan kolonialisme dan imperialisme Barat salah satunya Inggris juga berdampak pada punahnya bahasa-bahasa di dunia. Menurut United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), sekitar 231 bahasa telah punah di dunia, 37 di antaranya berasal dari Afrika Sub-Sahara. Bahasa-bahasa asli ini digantikan oleh bahasa-bahasa Barat yang dipaksakan oleh penjajah.
Baca Juga: 7 Novel Wajib Baca Karya Penulis Perempuan Kulit Hitam
Apakah Kekerasan Dibutuhkan?
Selain berbicara soal bahasa yang jadi senjata kekerasan kolonialisme dan imperialisme Inggris, Babel karya Kuang juga tak malu-malu menguliti gerakan pembebasan atau pemberontakan. Lewat eksistensi Hermes Society, pembaca dibawa masuk dalam pembentukan perspektif dan ideologi Robin soal gerakan pembebasan. Proses awalnya dimulai dari kedatangan Griffin, eks Babel yang ternyata adalah saudara laki-lakinya muncul dalam hidupnya.
Griffin meminta Robin membukakan akses batang perak yang hanya dimiliki akademisi Babel untuk kebutuhan gerakan Hermes Society. Selama menjadi perantara pencurian batang perak, Robin terus menerima realitas pahit tentang kekejaman kolonialisme dan imperialisme Inggris. Realitas ini membentuk tekadnya untuk berada pada sisi Hermes Society sampai pada akhirnya ia mendengar cerita bahwa Griffin adalah pemberontak ulung yang kerap menggunakan kekerasan dalam melawan Inggris.
Griffin selalu berdalih pemberontakan harus dilakukan dengan kekerasan. Sebab, kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang mereka pahami. Sistem ekstraksi Inggris, kata Griffin, pada dasarnya adalah kekerasan. Dengan ideologi supremasi kulit putih, mereka bermain nyawa. Mengeruk semua sumber daya yang ada tanpa rasa bersalah. Karena itu, pemberontakan dengan kekerasan bakal mengguncang sistem dan status quo mereka. Dan dengan kekerasan pula mereka tau seberapa besar kesediaan kita untuk berkorban demi tanah kelahiran.
Robin pada titik ini dibuat gundah. Benaknya bergejolak saat mendengar kata-kata Griffin. Ia yang bahkan tak pernah sama sekali melayangkan tinju apalagi pistol, tak mau berjuang demi kebebasan tapi harus menodai tangannya dengan darah. Ia perlahan menjauhkan diri dari Hermes Society. Ia tak mau terafiliasi dengan suatu gerakan yang meromantisasi kekerasan dalam nafas perjuangannya.
Sayang, usahanya ini gagal saat ia tahu Inggris berencana memulai perang dengan Cina. Robin baru sadar apa yang dikatakan Griffin soal Inggris ternyata benar. Bahasa satu-satunya yang mereka ketahui cuma kekerasan dan kekerasan tentunya tak bisa dilawan hanya lewat protes damai apalagi mengingat Inggris juga mengandalkan kuasa absolutnya pada kekuatan militer. Dari titik inilah, Robin memutuskan seutuhnya masuk ke dalam gerakan Hermes Society.
Baca Juga: 8 Buku Fiksi Indonesia Wajib Baca Sebelum Usia 30
Ajaran Griffin soal kekerasan ia resapi lamat-lamat hingga menjadi satu dalam tindakannya. Victoire Desgraves, perempuan kulit hitam yang jadi sahabat dekat Robin jadi semakin khawatir dengan ideologi baru Robin ini. Ia paham fristasi Robin, karena menyadari kekerasan tak bisa dilepaskan dalam gerakan pemberontakan. Namun, Victoire kini telah melihat Robin sudah layaknya orang kesetanan.
Setiap rencana pemberontakannya selalu melibatkan penghancuran dan penarikan pelatuk senjata. Ia seperti dikuasai dendam hingga tak bisa diajak berbicara dengan kepala dingin. Di sinilah Kuang memainkan perannya sebagai narator ulung dalam memberikan refleksi mendalam kepada pembacanya, apakah kekerasan benar dibutuhkan dan dijustifikasi dalam gerakan pemberontakan atau pembebasan?
Jawabannya tak ada yang eksplisit. Kuang sengaja membuat pembacanya menyimpulkan sendiri. Tetapi yang pasti Angela Davis, profesor dan aktivis kulit hitam Amerika jangan sampai pertanyaan ini kemudian jadi mengaburkan isu-isu yang sebenarnya lebih penting dibicarakan dan jadi pusat perjuangan untuk keadilan.
Dalam bukunya Freedom Is a Constant Struggle (2016) Davis memberi contoh Afrika Selatan selama perjuangan anti-apartheid. Nelson Mandela adalah salah satu tokoh perdamaian paling terkenal di dunia, tetapi perjuangannya memerdekakan Afrika tak lepas dari kekerasan. Mandela membentuk Umkhonto we Sizwe (disingkat MK, artinya “Tombak Bangsa”), sayap bersenjata Kongres Nasional Afrika.
Kegiatan MK mengambil bentuk serangan terhadap instansi pemerintah dan militer yang berfungsi memberikan bukti fisik tentang potensi ancaman nyata terhadap rezim apartheid. Mandela dikutuk negeri Barat saat membentuk MK dan mendukungnya. Ia bersama MK dicap teroris.
Namun, di Afrika Selatan, bahkan ketika gerakan solidaritas internasional non-kekerasan sedang diorganisasi ANC (Kongres Nasional Afrika) dan SACP (Partai Komunis Afrika Selatan) sampai pada satu kesimpulan. Bahwa mereka membutuhkan MK untuk gerakan. Davis mengatakan dalam gerakan pembebasan isu-isu penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan keberlangsungan hidup mereka memang seringkali diminimalisasi dan dibuat tidak terlihat oleh mereka yang punya kuasa. Menyamakan perlawanan dengan terorisme jadi senjata paling ampuh untuk membungkamnya.
Karena itu, Davis bilang, masyarakat Afrika Selatan yang selama ini tertindas dan mengalami kekerasan memiliki hak untuk membuat keputusan itu. Demikian juga, terserah kepada rakyat Palestina yang selama ini diduduki Israel untuk menggunakan metode yang mereka anggap paling mungkin berhasil dalam perjuangan mereka.
Kalau kamu, apakah setuju kekerasan diperlukan dalam gerakan pemberontakan atau pembebasan?






















