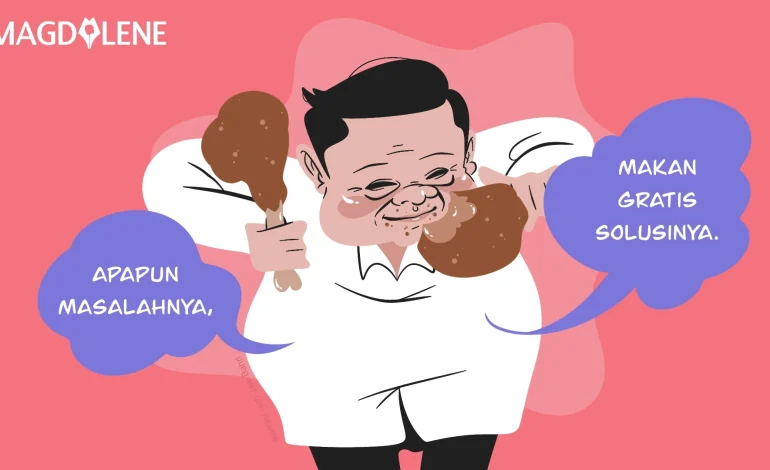‘Dari Rahim ini Aku Bicara’, tentang Tubuh Perempuan yang Dikuasai Lelaki
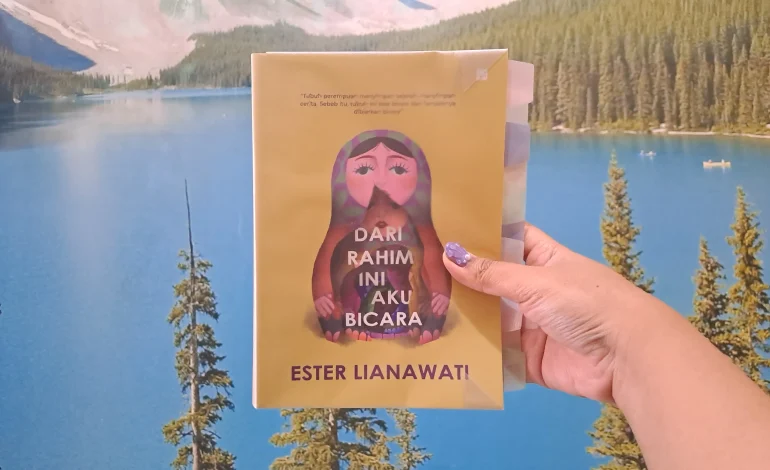
Semua berawal dari rahim. Perempuan menciptakan kehidupan bahkan peradaban baru dari rahim. Perempuan melahirkan perempuan dan laki-laki dari rahim. Enggak heran jika lelaki yang tak punya rahim, diam-diam menaruh ketakutan. Jika tak ada rahim perempuan, maka siklus kehidupan tak berjalan, dan sudah tentu tak ada penerus.
Ketakutan ini akhirnya membuat lelaki mengontrol habis-habisan tubuh perempuan sebagai bentuk pertahanan diri. Hal inilah yang menjadi premis awal yang digugat Ester Lianawati dalam buku “Dari Rahim Ini Aku Bicara”. Dilengkapi dengan riset yang kuat, Ester mengurai tentang bagaimana tubuh perempuan dikuasai dan dikerdilkan oleh lelaki dengan ideologi patriarkalnya.
Lelaki menjadikan detail tubuh perempuan, termasuk rahim sebagai objek sasaran. Perempuan didikte tentang apa yang boleh atau tidak dilakukan dengan tubuhnya sendiri. Untuk membuatnya semakin meyakinkan, laki-laki memproduksi ilmu pengetahuan dan tafsir-tafsir agama yang bias. Semua dilakukan agar perempuan menginternalisasi gagasan bahwa kontrol atas tubuhnya adalah lumrah, sehingga tak boleh diperdebatkan.
Institusi pernikahan pun diciptakan sebagai pintu masuk “penjara tubuh perempuan”. Saat sebagian feminis mengritik perkawinan karena dianggap mengebiri hak-hak bebas sebagai manusia, mereka distempel stigma. Memang ada juga feminis yang bahagia menikah dengan laki-laki kecintaannya, tapi tak semua terberkati hal sama.
Baca Juga: Review ‘Kisah Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang’: Lagu Lama Keegoisan Manusia
Terkait ini, Ester memberi penjelasan panjang lebar. Berbeda dari asumsi masyarakat bahwa institusi perkawinan adalah konsep yang telah lama hadir bahkan sejak Adam dan Hawa pertama kali menjejakkan Bumi, institusi ini sebenarnya dibangun lewat dominasi patriarki. Laki-laki punya ketakutan anak yang lahir dari rahim perempuan bukanlah anaknya sendiri.
Untuk mengatasi masalah ini, institusi perkawinan dibentuk dan diwajibkan. Hanya melalui perkawinan, perempuan boleh dan harus punya anak. Institusi ini jadi jaminan bahwa benar yang dihasilkan rahim perempuan benar anak darah daging mereka. Jaminan yang sangat penting tentunya bagi laki-laki untuk bisa mewujudkan mimpinya meneruskan nama laki-laki dan kuasanya.
Pada prosesnya, keperawanan perempuan jadi harga mati dan zina perempuan dilarang. Perzinaan bahkan dikaitkan dengan kerusakan. Ia bisa mengacaukan garis keturunan dan dianggap merusak nama baik suami, tidak sebaliknya.
Saat kekristenan masuk, institusi ini semakin dijustifikasi. Dengan lahirnya konsep dosa yang dilekatkan pada Hawa semata (padahal dalam berbagai tafsir progresif keduanya sama-sama melakukan dosa bukan Hawa saja), tubuh perempuan jadi penggoda dan ladang dosa. Perkawinan yang direstui Tuhan pun wajib dilakukan untuk meresmikan aktivitas sosial agar tubuh perempuan tak lagi dilumuri dosa “lahiriah” ini.
Pemberkatan nikah dalam bentuk ibadah mulai dilakukan di Gereja dan perkawinan masuk sebagai sakramen. Di Islam, institusi ini hadir lewat akad nikah dengan penyerahan simbolis perempuan kepada laki-laki. Saat institusi ini sudah mendapatkan justifikasinya, fungsi maternal pun perlahan ditekankan kepada perempuan. Untuk bisa mendukung fungsi ini, larangan kontrasepsi, aborsi, masturbasi, dan homoseksualitas ditekankan.
Agar kontrol atas tubuh perempuan tak dapat banyak perlawanan, patriarki menciptakan ilusi kuasa semu dengan membingkai ibu sebagai nyonya atau ratu rumah tangga. Dengan predikat barunya, perempuan seakan derajatnya dijunjung tinggi oleh laki-laki. Merekalah penguasa rumah tangga, institusi terkecil dalam masyarakat, tapi punya peran besar dalam peradaban manusia.
Namanya juga ilusi, lewat predikat ini perempuan tak sadar telah dimanipulasi dalam kontrak perkawinan. Atas nama pengabdian dan kodrat mereka sebagai ibu dan istri yang baik, perempuan dijebak untuk menjalani pekerjaan perawatan seumur hidup tanpa dibayar dan diapresiasi. Alhasil, perempuan juga jadi jauhkan dari ruang publik. Mereka dilarang berpartisipasi setara di dalam pendidikan dan politik.
Pada abad ini, larangan berpartisipasi di ruang publik mungkin bagi sebagian orang sudah jadi narasi usang. Namun di berbagai belahan dunia, bahkan di Indonesia benih-benih kuasa patriarki ini masih subur tertanam dalam alam bawah sadar manusia. Kita lihat saja bagaimana di Indonesia pernikahan anak, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), hingga ketimpangan pendidikan perempuan masih terus jadi masalah yang tak jua menemukan titik terangnya.
Baca Juga: ‘Babel, or the Necessity of Violence’: Benarkah Kekerasan Dibutuhkan dalam Gerakan Pembebasan?
Karya yang Total
Ester tak cuma piawai menuliskan sejarah runut patriarki dalam mengontrol tubuh perempuan lewat jalinan benang institusi perkawinan dengan peran perempuan sebagai ibu dan istri yang baik. Namun dalam bab-bab lainnya, ia juga mahir mengelaborasi lebih dalam konsep keperawanan, pelacur, hingga kecantikan. Semua ia tulis dengan cara yang sama, sistematis dan faktual dengan menyadur berbagai studi dari peneliti dan tokoh-tokoh feminis ternama. Hal ini membuat pembaca jadi mudah memahami dan percaya setiap kata yang ia tuliskan dalam karyanya.
Namun demikian, karya Ester bukan tanpa cela. Memasuki bab terakhir, yakni mengenai konsep kecantikan feminin ideal, Ester mulai kehilangan ketangkasannya dalam menulis narasi kuat berbasis data. Di bab-bab sebelumnya, ia dengan lugas dan terperinci menjelaskan secara runut kapan dan kenapa sebuah anggapan atau konsep di masyarakat terkait kontrol dan apropriasi tubuh perempuan bisa hadir dan langgeng. Di bab ini ada beberapa poin yang luput ia dalami dengan cara yang sama.
Perubahan pemaknaan cermin bagi perempuan misalnya jadi salah satu pembahasan menarik yang Ester tulis, tetapi kapan cermin mulai dimaknai negatif tidak pernah disebut. Ia hanya menuliskan bagaimana sejak dini, sejak punya kesadaran akan tubuh, anak-anak perempuan jadi mengembangkan relasi kecemasan dengan cermin. Padahal jika saja ia bisa mengelaborasi lebih jauh tentang kesejarahan pemaknaan cermin, pembaca bisa dibuat lebih paham bagaimana patriarki dengan kuasanya bisa dengan licik mengubah suatu benda yang tadinya bersifat netral dan bebas nilai, menjadi sesuatu yang lekat dengan kontrol patriarki.
Namanya juga ilusi, lewat predikat ini perempuan tak sadar telah dimanipulasi dalam kontrak perkawinan. Atas nama pengabdian dan kodrat mereka sebagai ibu dan istri yang baik, perempuan dijebak untuk menjalani pekerjaan perawatan seumur hidup tanpa dibayar dan diapresiasi. Alhasil, perempuan juga jadi jauhkan dari ruang publik. Mereka dilarang berpartisipasi setara di dalam pendidikan dan politik.
Selain itu, ketika berbicara soal standar kecantikan kulit perempuan, Ester masih terjebak dalam pemahaman atau asumsi lama masyarakat. Bahwasanya standar tertentu soal kecantikan kulit perempuan baru hadir pada abad ke-20, padahal jika mengacu pada penelitian Ayu Saraswati yang dibukukan dalam buku berjudul Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional (2017), ideologi warna kulit yang membentuk standar kecantikan perempuan Indonesia sebenarnya sudah mulai terbentuk dari zaman Jawa prakolonial.
Lebih dari itu, meski Ester sangat mahir memberikan umpan panas pada pembacanya tentang kelicikan patriarki. Kelicikan yang membuat perempuan meyakini satu-satunya tugas mereka adalah memikat, membangkitkan gairah, dan diinginkan laki-laki, ia luput memahami bahwa konstruksi standar kecantikan sangat heteronormatif.
Dengan demikian, standar kecantikan ini tak bisa dipukul rata bagi semua perempuan. Bagaimana dengan perempuan cis lesbian dan transpuan lesbian? Apakah mereka ingin tampil cantik karena memang ingin memikat dan diinginkan oleh laki-laki? Bagaimana dengan perempuan aseksual aromatis? Mereka ini bahkan tak punya atau sedikit sekali punya ketertarikan seksual dan romantis dengan siapapun. Apakah lantas keinginan mereka untuk tampil cantik bisa semudah itu direduksi karena mereka ingin memikat dan menimbulkan gairah laki-laki?
Lalu bagaimana pula dengan non-biner? Mereka adalah individu yang mengaburkan batasan gender dengan tidak mengidentifikasi baik laki-laki maupun perempuan. Apakah eksistensi mereka yang jadi perlawanan gender biner harus direduksi lewat standar kecantikan feminin ideal yang memikat dan diinginkan laki-laki?
Lebih dari itu, dengan menempatkan bahwa kecantikan feminin salah satunya dengan perempuan menggunakan riasan sebagai bentuk dari ketertindasan perempuan oleh patriarki, Ester luput memahami tentang persaudaraan antar dan agensi perempuan sendiri. Apakah perempuan merias otomatis jadi korban patriarki yang tak punya agensi?
Tentu kita tak bisa memaknainya lewat satu sudut pandang saja. Memang benar sesuai apa yang dikatakan Ester, industri kecantikan dibangun lewat dua kepala binatang buas, patriarki dan kapitalisme untuk menjerat perempuan. Lewat kecantikan atau menjadi cantik (beauty work) ada sebagian perempuan yang justru mendapatkan dirinya terbebaskan dan lebih berdaya. Ada pula yang ingin menjadi cantik karena ingin menyenangkan dirinya sendiri bukan orang lain. Lihat saja bagaimana banyak perempuan, termasuk saya, gemar memakai riasan wajah lengkap di rumah padahal tidak bertemu siapa-siapa dan hanya duduk sendirian di dalam kamar.
Baca Juga: Ulasan ‘Lessons in Chemistry’, Benarkah Perempuan Kini Sudah Setara?
Linda M. Scott dalam bukunya Fresh Lipstick: Redressing Fashion And Feminism (2005) mengatakan beauty work seharusnya dianggap memiliki banyak lapisan makna dan penggunanya tidak boleh digambarkan sebagai korban pasif dari patriarki. Beauty work adalah artikulasi ‘kekuatan feminitas’ yang direbut kembali oleh perempuan, berfungsi sebagai sebuah pernyataan penentuan nasib sendiri dan agensi melalui ekspresi keinginan individu seseorang.
Terakhir, tidak kalah pentingnya sebagai karya yang hampir sempurna ada satu poin yang luput Ester jabarkan dalam membahas soal penyihir. Dalam tulisannya, Ester membahas bagaimana para perempuan yang dianggap penyihir dibantai karena mereka tidak memenuhi standar feminitas yang diharapkan. Mereka adalah perempuan cerdas (pemilik pengetahuan), perawatan tua, mandul, janda, perempuan tua, dan lesbian.
Memang dalam sejarah pembantaian penyihir pemaparan Ester ini betul adanya. Namun, ada lapisan lain yang tak dibahas oleh Ester yang membuat pembahasan soal pembantaian penyihir jadi kehilangan komponen konteks sejarahnya. Pembantaian para penyihir tidak hanya terkait standar feminitas ideal, tetapi juga berkaitan dengan privatisasi lahan demi kapitalisme dan tentunya patriarki.
Dalam buku Silvia Federicci berjudul Witches, Witch-Hunting, and Women (2018), pemicu utama pembantaian penyihir ini adalah upaya pemagaran tanah. Tanah yang semula bersifat komunal diprivatisasi menjadi usaha komersial. Perempuan dijadikan target utama persekusi.
Upaya pemagaran tanah komunal mengakhiri hak-hak adat dan mengusir petani, serta penghuni liar yang bergantung pada tanah untuk keberlangsungan hidupnya. Sebelum terjadinya kebijakan pembantaian penyihir, kaum perempuan memiliki kekuatan di berbagai lini kehidupan sosial.
Tidak satu pun dari mereka memiliki ketergantungan pada laki-laki untuk bertahan hidup. Namun, atas nama pembantaian penyihir, persekusi dilakukan demi mengurangi hambatan dalam proses perkembangan awal kapitalisme. Lebih dari 600 ribu orang yang menjadi korban, 85 persen di antaranya adalah perempuan dan semuanya berasal dari kelas bawah. Mereka ditangkap dan dieksekusi tanpa diadili terlebih dahulu. Mereka juga mengalami siksaan dengan cara diikat dengan rantai besi, lalu dibakar dalam kobaran api.
Lepas dari lubang-lubang kecil itu, “Dari Rahim Ini Aku Bicara” merupakan karya brilian lain dari Ester Lianawati dalam menggugat patriarki yang layak dibaca.