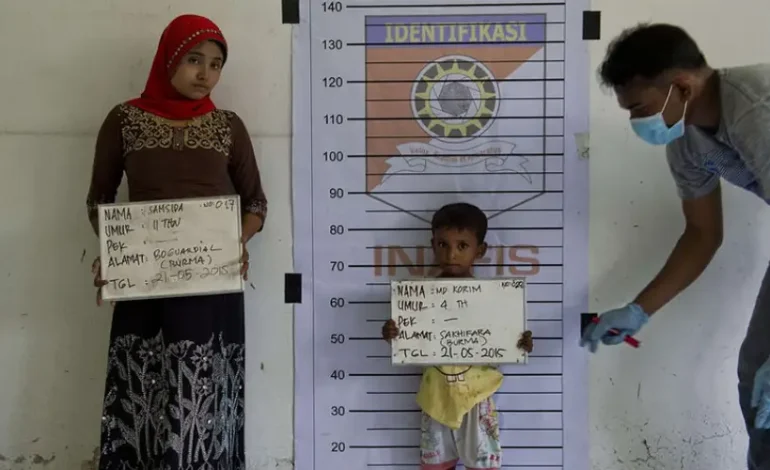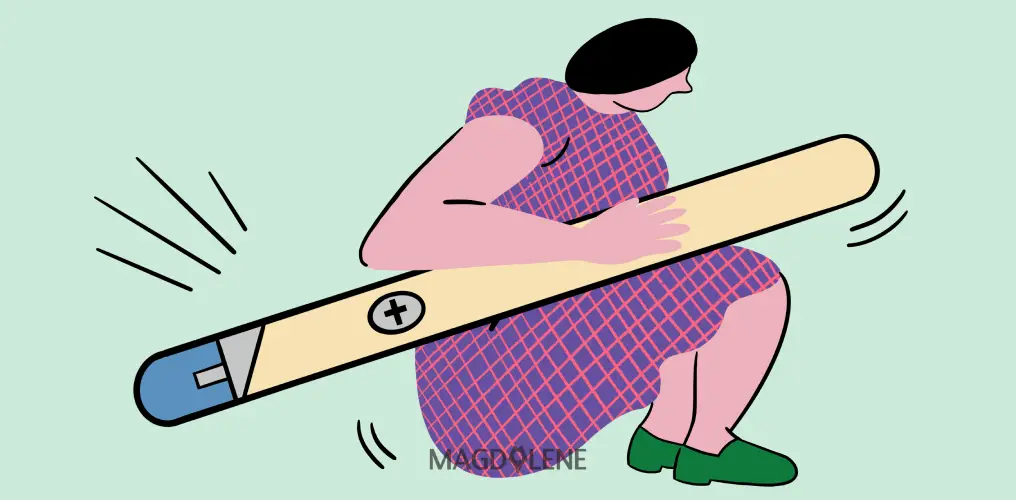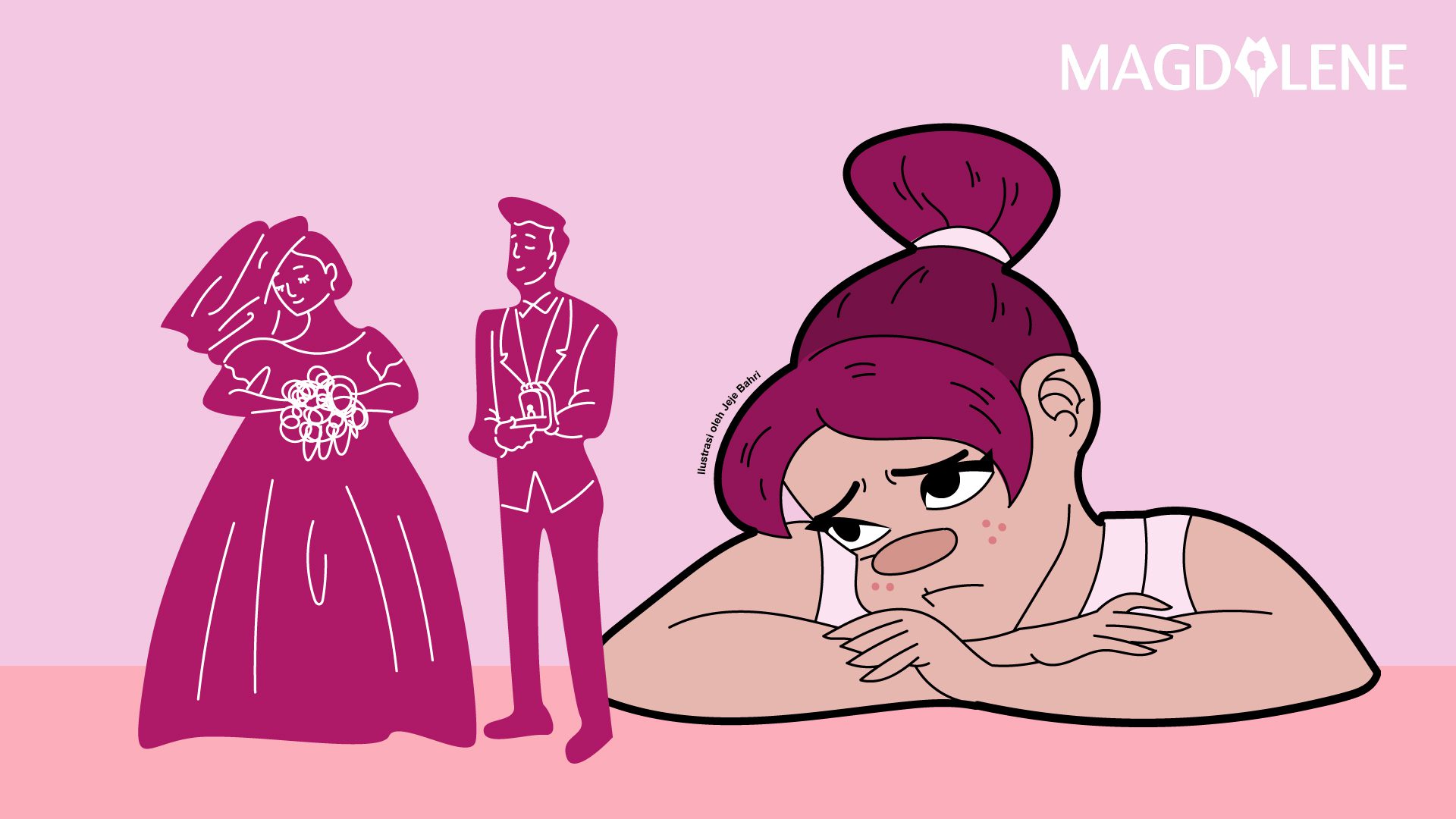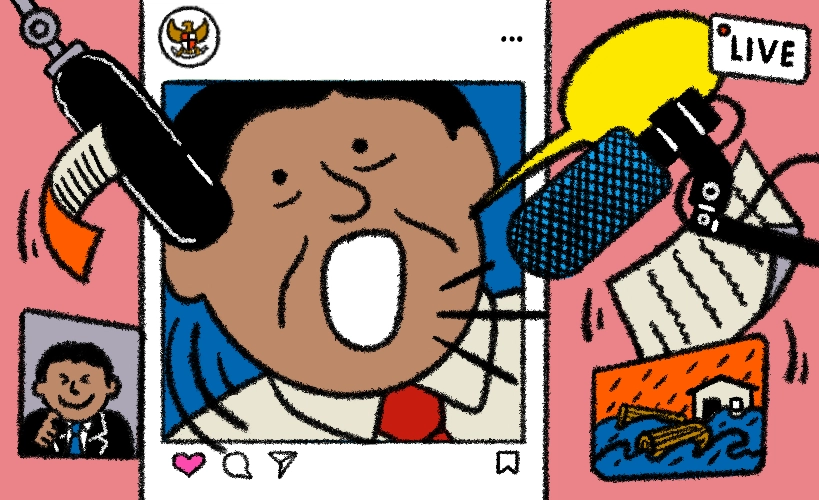#MerekaJugaPekerja: Bekerja 100 Jam Per Minggu tapi Tak Dianggap Produktif

Siang itu, Natalia, 43, mengendarai motor menyusuri jalan raya yang padat sebelum berhenti di kompleks apartemen di bilangan Jakarta Selatan. Sambil menggendong anak yang berusia dua tahun di depan dada, dia mengantarkan tas plastik berisi makanan ke seorang pemesan.
Natalia tak punya pilihan selain membawa anak paling kecilnya ikut bekerja di bidang jasa titip (jastip) makanan. Bahkan itu dilakukan sejak anaknya masih berusia di bawah satu tahun hingga kini. Jam kerja suaminya padat sebagai juru masak di restoran, dan ibunya sibuk mengelola warung kelontong sambil menjaga anak keduanya yang juga masih balita. Menitip semua anaknya sekaligus ke kerabat atau pekerja rumah tangga adalah kemusykilan bagi ibu tiga anak tersebut.
“Iya saya sambil ngajak anak, saya gendong dia di depan naik motor waktu masih bayi. Karena masih (minum) ASI, dia teriak-teriak di lampu merah minta nenen,” kata dia pada Magdalene, (29/11).
Dengan pekerjaan tidak tetap sebagai jastip, penghasilannya rata-rata kurang dari Rp500 ribu per bulan. Pekerjaan ini tidak bisa ia lakukan lebih sering, karena kedua anak masih kecil dan membutuhkan banyak perhatian, termasuk memastikan makanan tersedia, rumah bersih, cucian kering, dan lainnya. Melakoni pekerjaan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja membuat dia hampir tidak ada waktu untuk memikirkan dirinya sendiri.
“Saya selalu bangun dalam kondisi badan capek banget. Rumah kayak kapal pecah juga kadang-kadang saya biarkan saja saking capeknya. Tapi siapa juga yang bakal percaya kalau saya bilang capek,” imbuh dia.
Bagi Natalia, mengeluh tidak akan memberikan solusi, karena ia tak memiliki pilihan lain. Hal yang sama dirasakan oleh empat perempuan, yang seperti Natalia, baru-baru ini berpartisipasi dalam eksperimen sosial tentang kerja perawatan tak berbayar yang diselenggarakan Magdalene bersama International Labour Union (ILO) Indonesia. Sebagai perempuan, kerja perawatan dalam rumah tangga otomatis dibebankan kepada mereka.

Realitas mereka juga terefleksikan dalam survei ILO Indonesia dan KataData Insight Center, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Survei tersebut menunjukkan urusan domestik, yang sering dikecualikan dari kerja perawatan, justru dilakukan oleh 95,3 persen responden di 34 provinsi.
Menurut survei ILO bertajuk “Pekerjaan Perawatan: Tanggung Jawab Perempuan atau Bersama?” (2023), separuh perempuan yang menjalankan kerja perawatan bahkan sampai harus merelakan pekerjaannya.
Kerja perawatan adalah semua pekerjaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik orang tua, anak-anak, lansia, disabilitas, dan lainnya. Meskipun sangat penting dan memiliki kontribusi besar pada produktivitas negara, kerja-kerja perawatan masih tak dinilai sebagai kerja produktif yang berkontribusi pada ekonomi.
Penyebabnya sudah pernah dijelaskan di tulisan Magdalene sebelumnya yang mengutip penelitian “Unpaid Care Work in Indonesia: Why Should We Care?” (2017) dari lembaga penelitian SMERU. Di antaranya, pekerjaan ini dianggap hanya dilakukan oleh orang yang tidak punya pengetahuan dan keterampilan. Sebab lainnya, pekerja perawatan, khususnya perempuan, dinilai punya banyak waktu luang, sehingga sudah sewajarnya melakukan kerja-kerja domestik tanpa imbalan.
Padahal faktanya, menurut Early Dewi Nuriana, Koordinator Program Ekonomi Perawatan ILO, berinvestasi pada kebijakan dan layanan perawatan justru berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, juga meningkatkan angka partisipasi perempuan di dunia kerja.
“Jika tingkat partisipasi kerja perempuan meningkat, dampaknya tentu mereka akan semakin berkontribusi secara ekonomi terhadap negara.”
Tidak dipandangnya kerja perawatan sebagai pekerjaan produktif nyatanya juga dialami oleh lima perempuan yang mengikuti eksperimen sosial ini. Mayoritas dari mereka melakukan kerja perawatan yang sangat menyita waktu, bahkan beberapa lebih dari dua kali lipat dari jam kerja mingguan maksimal yang diatur oleh negara sebesar 40 jam.
Pekerjaan yang dilakukan kelimanya juga kerap kali tak diakui dan nihil dukungan. Selama tujuh hari mereka merekam dengan gawai, serta mencatatkan dan menghitung waktu semua kerja domestik dan kerja perawatannya. Hasil dari pencatatan ini menjadi bahan untuk analisis waktu dan valuasi dan nilai-nilai kerja perawatan yang mereka lakukan.
Baca juga: Kerja-kerja Perawatan, Penting tapi Diabaikan
Magdalene, Kerja Perawatan, dan Jurnalisme Eksperimen
Dalam liputan Magdalene awal 2023 tentang kerja perawatan didapati, isu ini masih belum mendapat perhatian dari pemerintah, pemberi kerja, dan masyarakat. Beberapa indikatornya adalah kekosongan hukum tentang kerja perawatan dan kurangnya infrastruktur pendukung lainnya, baik fasilitas child care, perawatan lansia, dan lainnya.
Pada liputan lanjutan ini, kami menggunakan pendekatan sosial eksperimen untuk membuktikan dua premis. Pertama, kerja perawatan selalu menyita waktu lebih banyak ketimbang urusan di sektor publik. Pun, meski bernilai ekonomi tinggi, kerja perawatan tak pernah dibayar dan diapresiasi. Dalam konteks ini, kami ingin menghitung secara presisi dari sampel yang ada, seberapa bernilai dan seberapa panjang sebenarnya kerja perawatan. Kedua, kerja perawatan bisa jadi sudah dianggap penting oleh perempuan. Namun, masih ada bias-bias gender dan nilai-nilai yang terinternalisasi, sehingga itu berdampak pada minimnya dukungan untuk perempuan.

Dalam beberapa dekade terakhir, ILO telah menjadi salah satu lembaga yang mengarusutamakan isu-isu kerja perawatan. Dalam melakukan eksperimen sosial ini, kami menggunakan pendekatan pilar 5R ILO: recognize (mengakui), reduce (mengurangi), redistribute (redistribusi) pekerjaan perawatan tak berbayar, dan mendorong adanya reward (penghargaan) dan represent (keterwakilan).
Adapun metode eksperimen sosial ini kami pilih untuk mendapat temuan yang akurat dan narasi yang lebih personal dari para partisipan perempuan. Di dunia jurnalisme, eksperimen sosial sebenarnya berakar pada bentuk jurnalisme investigatif yang telah dipraktikkan selama lebih dari satu abad. Salah satu pelopor metode ini adalah jurnalis investigasi Nellie Bly yang pada 1887 menyamar sebagai pasien Rumah Sakit Jiwa Blackwell di AS dan berperilaku sebagai pasien psikotik. Laporannya menunjukkan berbagai kekerasan yang dialami pasien RS tersebut, dan mendorong pemerintah AS untuk merombak total sistem penanganan pasien penderita penyakit mental.
Magdalene sendiri sudah beberapa kali melakukan praktik eksperimen sosial, salah satunya adalah dengan menjadi pengguna sebuah aplikasi poligami, yang menjadi viral dan diliput oleh berbagai media lokal dan nasional, sehingga berakhir dengan dicabutnya aplikasi tersebut.
Lima partisipan perempuan yang kami pilih di kawasan Jabodetabek memiliki berbagai latar belakang. Kesamaan mereka adalah mereka melakukan kerja perawatan tak berbayar, entah membereskan rumah, mengurus anak, atau merawat orang tua lansia.
Berikut detail partisipan yang kami pilih:
1. Ernawati, 49
Ia adalah karyawan swasta lajang. Sehari-hari ia harus menjalani beban ganda karena mengurus ayahnya yang sudah lanjut usia (lansia). Ia bisa melakukan ini karena sejak pandemi, ia bekerja dari rumah.
2. Riris Suryowati, 53
Perempuan ini mengambil pensiun dini pada 2019 dari majalah tempatnya bekerja untuk mengurus ayah yang lansia. Usai pensiun, ia sempat merintis usaha tapi tak berjalan mulus karena diterjang pandemi Covid-19. Sebagai ibu tunggal dengan satu anak, beban mengurus orang tua lansia tak mudah buatnya. Ia harus merelakan waktu istirahatnya untuk merawat ayah 24 jam sehari.
3. Arniati Purnami, 35
Perempuan yang akrab disapa Arni ini harus mengurus dua anaknya yang masih kecil, sembari tetap bekerja di perusahaan swasta. Sebelum berangkat kerja, Arni biasanya sudah sibuk mengurus rumah, membangunkan dan memandikan anak, menyiapkan bekal suami, hingga mengantar dua putranya bersekolah. Saat bekerja, anak dititipkan ke neneknya yang lokasi rumahnya cukup dekat. Malamnya ia gunakan untuk bermain, membantu menyiapkan anak sekolah untuk esok harinya, sampai menidurkan mereka. Bagi Arni, bekerja di kantor adalah salah satu cara ia mendapatkan me time, waktu jeda dari kesibukan domestik.
4. Emmy, 39
Semenjak suaminya meninggal dunia pada 2018, Emmy jadi ibu tunggal untuk anak semata wayangnya yang kala itu berusia 6 bulan. Tentu saja mengurus anak sembari memproses duka tak mudah buatnya. Belakangan, peneliti sosial itu juga mengurus ayahnya di rumah yang mulai rutin check up ke dokter. Beruntung, penghasilan Emmy membuat dia mampu untuk mendelegasikan beban kerja perawatan dengan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di rumah.
5. Natalia, 43
Ia adalah ibu tiga anak, dengan dua anaknya yang paling kecil masih berusia balita. Suaminya bekerja di restoran, dengan jam kerja yang sangat ketat, sehingga tidak memungkinkan untuk membantu kerja perawatan di rumah dengan porsi yang sama. Natalia hingga hari ini juga aktif menjalankan usaha jastip makanan dan mengantarkannya kepada pelanggan. Ia kerap membawa anaknya berkendara motor karena tak ada yang bisa dimintai tolong menjaga.
Dari eksperimen sosial yang sudah dijalankan selama sepekan, kami mendapatkan beberapa temuan kunci yang penting yang melengkapi survei tentang kerja perawatan tak berbayar.
Baca juga: Investasi pada Cuti dan Perawatan di Dunia Kerja Penting Dilakukan
Jumlah Jam Kerja Perawatan yang Melebihi Jam Kerja Berbayar
Temuan kami, sebanyak 4 dari 5 partisipan punya jam kerja perawatan di atas 40 jam per minggu. Padahal dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengatur, jam kerja untuk karyawan di Indonesia maksimal 7 jam per hari atau 40 jam per minggu.
Bahkan untuk mereka yang berusia 40 tahun ke atas, bekerja lebih dari 40 jam seminggu, bisa mengganggu ingatan atau paling buruk merusak fungsi otak. Dalam riset yang disitir BBC dalam artikel bertajuk “Is Full Time Work Bad for Our Brain” (2016) dijelaskan, durasi ideal agar pekerja bisa tetap sehat fisik dan mental adalah 25 jam per minggu.

Dalam “Long working hours can increase deaths from heart disease and stroke, say ILO and WHO” (2021) disebutkan, jam kerja panjang 55 jam seminggu telah memicu 745.000 kematian akibat penyakit kardiovaskular pada 2016. Mereka yang overworked juga lebih rentan terkena risiko stroke 35 persen dan penyakit jantung 17 persen, ketimbang mereka yang bekerja maksimal 40 jam seminggu.
Jika berkaca pada riset-riset tersebut, apa yang dialami oleh para partisipan eksperimen ini tentu sangat tak ideal. Beberapa partisipan harus mengemban beban kerja ganda di ruang publik dan domestik. Angkanya berlipat-lipat lebih banyak dibandingkan standar waktu kerja ideal.
Dalam eksperimen sosial ini, kami mencoba memvaluasi kerja perawatan yang mereka lakukan dalam bentuk rupiah. Metode perhitungan yang digunakan adalah kami meminta para partisipan mengisi berapa pendapatan saat ini atau penghasilan terakhir jika sudah tak bekerja. Mengacu pada aturan jam kerja pemerintah di UU Cipta Kerja, yakni 40 jam per minggu, kami mendapat kesimpulan, beban kerja perawatan para perempuan ini jika dirupiahkan bisa melebihi pendapatan bulanan mereka.
Dalam seminggu, Natalia misalnya, bekerja selama 103,58 jam atau 414,33 jam per bulan. Jika divaluasi, kerja perawatan ini memberikan Rp5.761.823 perminggu atau Rp23.047.292 perbulan.
Riris bekerja sebanyak 103,50 jam per pekan atau 414 jam per bulan. Ini sangat mungkin, mengingat ia tak dibantu oleh PRT. Sementara, seluruh pekerjaan rumah dan mengurus sang ayah tak punya jam kerja yang tetap. Artinya, dari Senin-Minggu, Riris tak memiliki waktu libur. Kerja-kerja yang dilakukan Riris sendiri setara dengan 258,75 persen dari gaji terakhirnya.
Emmy sebanyak 99 jam per minggu atau setara 396 jam per bulan. Beruntungnya, ia mendapat dukungan dari PRT sebanyak 63,42 jam per minggu, sehingga ia cukup mengerjakan 35,58 jam seminggu kerja perawatan. Jika dirupiahkan, kerja perawatan yang ia lakukan mencapai dua kali gaji yang terima sebagai peneliti di bidang sosial.
Sementara, jam kerja perawatan Arniati 50,92 jam per minggu atau setara 203,67 jam per bulan. Andai Arni mendapat gaji atas kerja perawatan tak berbayar yang ia lakukan di rumah, maka gaji yang didapat mestinya berkisar di angka Rp2.704.948 per minggu atau Rp10.819.792 perbulan, di mana lebih besar dari hasil kerja konvensional yang ia jalani.
Kondisi Ernawati agak lebih baik dibanding empat partisipan lainnya, meski belum bisa dikatakan ideal. Ia bisa menghabiskan 25,98 jam kerja perawatan per minggu termasuk mengurus ayahnya selama sebulan. Jika divaluasi, kerja-kerja yang dilakukan Erna setara dengan 64,69 persen dari gajinya saat ini.
Hasil valuasi itu sebenarnya juga mengafirmasi temuan ILO pada 2018 yang menyebutkan masih banyak negara-negara berkembang yang warganya menjalani kerja perawatan berlebihan. Di 64 negara yang menjadi lokus penelitian, kerja perawatan tak berbayar mengambil durasi 16,4 miliar jam. Angka ini setara dengan 2 miliar orang bekerja 8 jam sehari.
Baca juga: Ketika Mama Menua dan Tak Bekerja, Maukah Kamu Menampungnya?
Mayoritas Partisipan Sudah Menganggap Kerja Perawatan Penting, tapi…
Dari lima partisipan Magdalene, sebenarnya sudah ada kesadaran bahwa kerja perawatan sangat penting dan membebani perempuan. Namun, masih ada bias gender yang mewarnai pemahaman mereka. Misalnya yang paling kentara, kerja perawatan bernilai ekonomi tapi sebaiknya perempuan yang melakukannya karena lebih baik kualitas kerjanya ketimbang lelaki. Atau anak saja yang melakukan kerja perawatan terhadap orang tua karena ini menjadi wujud bakti dan balas budi.
Riris misalnya menyebutkan dalam wawancara bersama kami, “Saya nyari pahala dan ibadah, jadi Bismillah aja (merawat ayah sendiri)… Capek sih capek banget, kalau badan capek istirahat kalau psikis susah. Kalau capek, di kamar mandi (saya) menangis sampai sesak, keluarin dulu kalau udah lega, balik lagi (merawat ayah). Saya punya anak. Jadi apa yang saya lakukan ke bapak saya, saya mengharapkan anak mendapat contoh dari itu, diperlakukan sama.”

Pemahaman yang kurang lebih mirip ditemukan pada Arni dan Natalia. Keduanya sama-sama menyadari kerja perawatan sangat penting, dan perempuan melakukan pekerjaan lebih banyak. Namun, ada juga asumsi bahwa itu sudah merupakan peran ganda yang memang mesti dinikmati sebagai istri, ibu, sekaligus perempuan pekerja. Keduanya juga sepakat dan berdiskusi untuk membagi tugas perawatan domestik dengan suami, tapi ujung-ujungnya tetap porsi lebih banyak dilakukan oleh perempuan.
“Kadang kalau di rumah, aku sengaja enggak minta tolong. Biar saja suami inisiatif. Tapi ya namanya cowok ya, masih kurang peka. Dia membantu juga sesekali. Tapi kan nyapu enggak bersih, dia ngepel, motor dia cuci sendiri. Dia cuci piring kadang mau kadang enggak, harus dibaik-baikin baru sadar untuk nyuci piring. Jemuran juga minta tolong, eh enggak sesuai yang biasanya. Tapi (waktu dikomplain), dia cuma komentar, ‘Masih untung dibantuin.’ Enggak ada kesadaran lah,” urai Arni.
Sementara Natalia mengaku sudah lelah meminta tolong pada pasangan. Sebab, biasanya beberapa kali minta tolong, tapi tetap saja ia merasa kurang didukung. “Ape yang rada males ya ngomong pake urat ya, mending (pekerjaan rumah) dikerjain sendiri. Aku cuma sekali ngomong, ‘Tolonglah, Mas.’ Tapi sekali enggak dibantu, ya udah lah kerjain aja sendiri. Kalau pun dibantu, jangan berharap 100 persen hasilnya sama,” ungkapnya.
Pemahaman seperti itu tak muncul dari ruang hampa. Ada konstruksi yang sudah dipelihara bertahun-tahun dan terus dilanggengkan oleh banyak institusi termasuk agama dan pendidikan, lalu diwariskan ke generasi berikutnya. Bahwa anak adalah investasi atau aset, sehingga sudah sepatutnya saat tua, orang tua dirawat anak. Para orang tua lupa, tak semua anak kelak cukup mampu menjalani kerja perawatan.
Ini sejalan dengan keterangan Pengajar Sosiologi Universitas Indonesia (UI) Rosa Diniari. Dalam wawancaranya bersama Magdalene, ia menyatakan, “Kalau umpamanya anak sudah menikah, mungkin dia tidak bisa secara sepenuhnya menanggung orang tua karena ada keluarga sendiri yang perlu dihidupi. Tapi kalau yang lajang ini, dia dianggap harus bertanggung jawab sama siapa lagi kalau bukan kepada orang tua?”
Ia menambahkan, ketergantungan orang tua kepada anak tidak lepas juga dari anggapan masyarakat bahwa anak adalah aset orang tua. Ini berhubungan dengan level edukasi orang tua tersebut.
Sementara, konstruksi bahwa tugas ibulah yang dominan merawat anak, sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh para ahli. Dalam “The Mermaid and the Minotaur” (1976) dijelaskan, kita semua dirugikan secara psikologis dan sosial karena dibesarkan dalam peran pengasuhan yang asimetris. Ibu (perempuan) terlibat lebih banyak dalam tugas pengasuhan, sedangkan ayah (laki-laki) sebagian besar tidak ada.
Kita percaya dengan anggapan itu. Buku-buku di sekolah sejak dini menyebut bahwa ayah Budi bekerja di kantor dan ibu memasak serta membereskan rumah. Karena itu, jika ayah mau mengerjakan pekerjaan domestik, ia akan dianggap sebagai ayah teladan. Sementara, jika ibu yang melakukan, itu dianggap normal dan wajar belaka.
Ini senada dengan laporan foto The SMERU Research Institute bersama Institute of Development Studies (2014) yang menyebutkan, kerja perawatan yang dibebankan pada perempuan sering kali cuma dianggap secara cuma-cuma atau taken for granted saja. Barangkali, anggapan-anggapan ini juga yang membuat Indonesia masuk dalam jajaran fatherless country.

Mayoritas Tak Mendapat Dukungan Cukup
Setelah merekam dan mencatat aktivitas kerja perawatannya selama seminggu, kami juga mewawancarai para partisipan secara luring. Mayoritas mengaku tak mendapat support system yang cukup, baik dukungan fisik maupun mental.
“Aku pernah merawat anak, sampai enggak sadar belum makan. Sementara, nenen gas terus. Nyadarnya setelah merasa bangun tidur sampai gemeteran, nahan lapar, pusing. Bahkan makan aja enggak sempat, nyisir aja enggak sempat, apa lagi lipen (lipstik. Red),” ujar Natalia.
Erna, partisipan yang lain, juga mengaku tak bisa mengharapkan bantuan dari luar untuk menjaga kesehatan fisik dan psikisnya, apalagi dukungan dari pemerintah. Selama ini yang bisa ia lakukan adalah belajar sendiri dari Youtube untuk mencari tahu lebih dalam penyakit ayahnya.

“Aku sebenarnya berharap pemerintah bisa membantu menyediakan satu rumah yang ramah lansia, karena SDM yang memang mengerti psikologi orang tua lansia–enggak cuma perawat yang asal bisa bersihin kotoran–masih jarang,” ujarnya.
“Paling enggak beban pikiran saya bisa berkurang, karena orang tua dirawat dengan orang yang tepat, yang terjangkau aksesnya biayanya,” lanjutnya.
Sementara, Arni berharap ada dukungan yang lebih banyak dari suaminya. Sebab, selama ini ia lebih banyak mengandalkan media sosial atau rekan-rekannya sesama ibu. “Pernah saya kerja pulang malam terus curhat mengeluh capek. Tapi, suami cuma bilang, ‘Ya udah dijalanin aja dinikmatin, itu risiko ibu pekerja. Padahal saya maunya, ya, ada pembagian tugas yang lebih setara lagi porsinya karena anak juga kan anak berdua.”
Adapun Emmy berpendapat, dukungan apa pun jenisnya sangat dibutuhkan. “Saya pikir pengakuan care work sangat penting. Saya sendiri sering terpapar kampanye tentang kesetaraan gender dan care work. At the end of the day pekerjaan ini tetap harus dilakukan. Namun pesannya harus menyeluruh, bahwa ini bukan hanya tanggung jawab perempuan. Secara fisik perempuan mungkin bisa memberi ASI, tapi di luar itu, ada banyak pengaturan untuk mengerjakan pekerjaan perawatan sama-sama,” tuturnya.
Terlebih untuk ibu tunggal seperti dirinya. Menurut Erna, bentuk dukungan lain yang bisa diberikan adalah dukungan yang sifatnya sistematik. Misalnya lewat edukasi dan literasi dari pemerintah, institusi pendidikan, institusi agama. Bahwa anak laki-laki dan perempuan punya peran yang sama. Lalu dari pemerintah atau pemberi kerja juga bisa mendukung dalam penyediaan fasilitas perawatan anak yang terjangkau.
Merangkum harapan dari para partisipan, Early dari ILO menguraikan dukungan-dukungan yang mungkin diupayakan. Menurutnya, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mengakui bahwa kerja perawatan sama pentingnya dan bernilai produktif dengan pekerjaan-pekerjaan lain.
“Jika kita sudah mengakui atau merekognisi itu, maka orang yang melakukan kerja perawatan perlu diapresiasi, perlu dapat reward. Misalnya, ibu dapat cuti hamil dan gaji penuh. Tugas pengasuhan anak juga jangan cuma dibebankan pada perempuan, tapi lelaki juga. Tugas ini harus di-reduce jangan cuma berat sebelah ke perempuan,” ucap Early.
Ia tak memungkiri bahwa merekognisi kerja perawatan tak mudah. Karena itulah butuh langkah berkesinambungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah untuk mengubah pola pikir secara konsisten. Misalnya, dengan menciptakan kebijakan yang mengakomodasi para pekerja perawatan, memberikan perlindungan, dan mengapresiasi mereka.
Setelah direkognisi, bantu kurangi beban kerja perawatan dan distribusikanlah, sehingga tak dominan ditangani oleh perempuan. Dukungan infrastruktur dengan menyediakan rumah ramah lansia, jasa perawatan anak yang terjangkau atau malah gratis juga bisa diberikan kepada orang tua, tak cuma pekerja formal tapi juga informal.
Dalam hal perlindungan pekerja perawatan, dalam Konvensi ILO 102 sebenarnya dijelaskan skema social protection, misalnya dalam bentuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dana Pensiun, dan lain-lain. “Sayang sekali semua belum dijalankan negara secara utuh.”
Pada akhirnya, kita perlu menyepakati, memvaluasi kerja perawatan pada dasarnya adalah upaya berancang-ancang menciptakan generasi yang berkualitas. Jadi, sebenarnya kita tak cuma berinvestasi pada apa-apa yang bernilai ekonomi, tapi juga masa depan. Kita berinvestasi pada umat manusia.
Dalam rangka Hari Ibu Nasional 2023, Magdalene dan ILO meluncurkan series liputan jurnalisme data bertema “Urgensi Ekonomi Perawatan Jilid 2”. Ada satu artikel utama dan 2 artikel lainnya yang tayang setiap pekan. Jika kamu menyukai liputan visual, Magdalene juga membuat laporan berformat video yang bisa diakses di Youtube kami.
Penanggung jawab/Pemimpin Redaksi: Devi Asmarani
Redaktur Pelaksana: Purnama Ayu Rizky
Editor: Aulia Adam
Reporter/ Periset:
Aurelia Gracia, Jasmine Floretta, Chika Ramadhea, Natanael F Gulo
Desainer Grafis: Jeje Bahri, Della Nurlaelanti Putri
Juru Kamera dan Editor: Tommy Triardhikara
Web Developer: Denny Wibisono
Media Sosial: Siti Parhani
SEO Specialist: Kevin Seftian
Community Outreach: Paul Emas