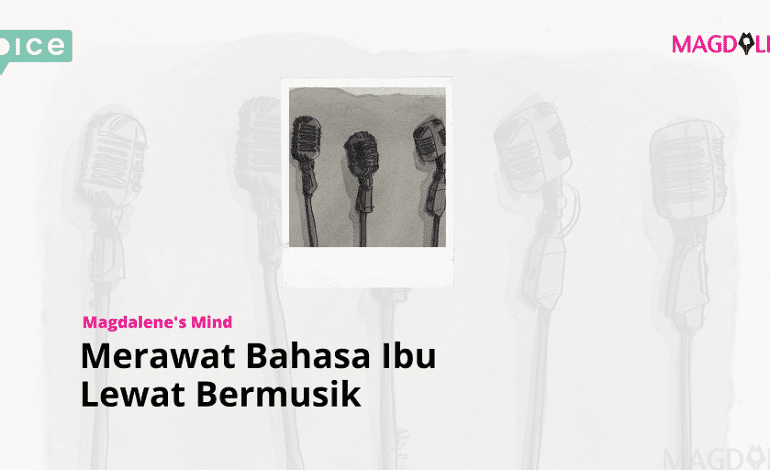Voice Indonesia Berdayakan Minoritas dan Kaum Adat lewat ‘Artivism’

Seni merupakan medium bersifat cair yang dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan kelompok pemegang hak lewat intervensi kreatif. Hal ini dimanfaatkan oleh Voice Indonesia, sebuah fasilitas hibah inovatif yang mendukung kelompok marginal atau yang menerima diskriminasi, untuk memberikan pengaruh dalam mengakses layanan produktif, sosial, dan partisipasi politik.
Adapun kelompok pemegang hak mencakup kelompok orang dan etnis minoritas, lansia dan remaja rentan, perempuan yang menghadapi eksploitasi dan kekerasan, serta penyandang disabilitas.
Upaya yang dilakukan Voice Indonesia ini termasuk bentuk artivism (gabungan kata art dan activism). Istilah ini didefinisikan oleh pemain dan penulis naskah, Eve Ensler, dalam The New York Times sebagai penggunaan media seperti film dan musik, untuk meningkatkan kesadaran atau mendorong perubahan.
Menggandeng sejumlah organisasi dan komunitas yang memproduksi dokumenter dan karya seni, Voice Indonesia berhasil memberdayakan sekaligus membawa perubahan bagi masyarakat yang menjadi bagian kelompok pemegang hak lewat artivism. Berikut ini kami merangkum beberapa karya yang dihasilkan Voice Indonesia.
Baca Juga: Artivisme: Seni Sebagai Medium Perubahan di Akar Rumput
-
The Feelings of Reality
Diproduksi oleh Forum Film Dokumenter (FFD), The Feelings of Reality (2019) mengangkat kisah penyandang disabilitas dari empat wilayah di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Sumbawa. Dibuat oleh delapan filmmaker, penyajian film dengan virtual reality (VR) menjadi angin segar dalam industri film dokumenter.
“Kami ingin menguji sejauh apa VR bisa menciptakan pengalaman berbeda, ketimbang menonton film di layar 2D,” ujar Project Manager FFD bersama Voice Indonesia, Alwan Brilian, saat dihubungi Magdalene (13/12).
“Karena medium ini menjadikan audiens bagian dari keseluruhan film, dan ikut merasakan isu-isu yang dialami penyandang disabilitas.”
Bukan tanpa alasan proyek yang inisiatifnya dimulai pada 2018 ini memilih penyandang disabilitas sebagai fokus utama. FFD ingin berperan sebagai sistem pendukung bagi teman-teman yang aktif menyuarakan disabilitas, sekaligus menciptakan festival yang inklusif, baik dari internal penyelenggara maupun dimanfaatkan sebagai wadah advokasi.
“Ini juga dipilih berdasarkan urgensi dalam industri film. Karena FFD sendiri tidak berfokus pada advokasi isu disabilitas, setidaknya kami menyediakan suatu platform untuk mendukung isu tersebut melalui VR dokumenter ini. Dan, medium ini bisa meningkatkan awareness publik tentang isu disabilitas,” jelas Alwan.
Dari segi internal, sudah menjadi kesadaran bersama bagi FFD untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Misalnya, mereka menyediakan sinopsis dalam bentuk audio, subtitle, juru bahasa isyarat dalam talkshow bersama filmmaker, ram tangga saat festival diselenggarakan, dan rekan pendamping saat menonton film.
“Bagaimanapun, kami ingin FFD ini bersifat inklusif dan bisa diakses semua pihak,” katanya.
Apabila disimpulkan, menurut Alwan, respons audiens dalam penggunaan VR ini berpotensi meningkatkan awareness dalam topik inklusivitas. “Catatan kami, medium VR ini kan enggak reachable untuk semua kalangan. Makanya, ini menarik untuk diuji coba, bagaimana medium alternatif ini tetap harus dipublikasikan.”
Sebagai alternatif memberikan pengalaman menonton serupa, FFD membuat situs thefeelingsofreality.com, agar audiens dapat menduplikasi cardboard VR menggunakan ponsel.
Baca Juga: Ternyata Jokowi Lebih ‘Insecure’ pada Mural Ketimbang COVID-19
-
Suara dari Kampung Wuring
Film yang digarap oleh Komunitas KAHE pada 2020 ini menampilkan kehidupan masyarakat Bajo dan Bugis yang memeluk agama Islam yang berhasil memantik keterbukaan warga Kampung Wuring. Sebagai masyarakat yang terisolasi, mereka tidak banyak berinteraksi dengan warga di luar kampung. Pun jika terjadi hanya sebatas urusan perdagangan karena dikenal kampung itu sebagai pusat pasar ikan di Flores.
Sejak kunjungan Komunitas KAHE, mereka mulai terbuka dan mau bertemu banyak orang.
“Kami tidak mengklaim hal tersebut sebagai jasa Komunitas KAHE, tapi minimal kami membuka akses mereka,” ujar Eka, Direktur Artistik Komunitas KAHE.

Karena itu, mereka melakukan pendekatan dengan terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat Kampung Wuring. Misalnya dengan mengunjungi dapur mereka, ikut berbelanja, dan berjualan. Tujuannya adalah untuk bertemu dan berinteraksi dengan para ibu, kemudian membuat forum masak. Sementara, dengan masyarakat adat, mereka datang ke acara pernikahan mengikuti acara adat, membantu memasak, mendirikan tenda, dan mendokumentasikan acara.
“Cara-cara formal yang kami tentukan di awal akhirnya harus dikesampingkan semua,” jelasnya. Mulanya, sebagian masyarakat Kampung Wuring belum menyadari warisan budaya yang mereka miliki karena keunikan yang mereka kerjakan adalah sebuah rutinitas.
“Setelah kami datang, barulah mereka bisa melihat kalau kebiasaan mereka itu sesuatu yang eksotis, unik, dan keren. Bukan karena mereka marginal, melainkan karena mereka punya karakternya sendiri dan berbeda dari kehidupan masyarakat lain,” kata Eka.
Selain itu, produksi Suara dari Kampung Wuring menghasilkan beberapa dampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat Kampung Wuring. Salah satunya lewat arsip dokumentasi yang dapat diandalkan anak muda. Mereka ingin membuat galeri offline yang menampilkan karakter dan kehidupan masyarakatnya. Sayangnya, keinginan tersebut belum direalisasikan karena pademi.
Baca Juga: Belajar dari Negara Lain Gencarkan Aktivisme Berbasis Karya Seni Digital
Kemudian, para ibu membuat brand abon ikan yang dibantu anak muda menjadikan makanan itu sebagai oleh-oleh lokal. Komunitas KAHE juga membukakan akses ke dinas pariwisata yang memiliki program kuliner. Selain itu, mereka mempertemukan masyarakat adat dengan Kemendikbud Ristek untuk mendaftarkan hak kekayaan lokal agar diakui.

-
Ibu Bumi
Dalam dokumenter Ibu Bumi (2020), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, sebuah koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan, dan sumber daya alam, menggandeng masyarakat adat Sedulur Sikep.
Dengan melestarikan Pegunungan Kendeng Utara yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, proyek ini bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat setempat dalam mengakses sumber daya produktif, seperti tanah, air, dan sumber daya alam lainnya.
Sukinah, 45, seorang petani dari Desa Tegaldowo, Rembang, mengatakan bahwa masyarakat Kendeng terbuka pada kru PWYP dalam pembuatan dokumenter tersebut.
“Kami mempersilakan jika tujuannya untuk kampanye, supaya semakin banyak gerakan dan pencinta lingkungan, sekaligus mengingatkan orang-orang di luar sana yang belum tahu perjuangan di Kendeng untuk melestarikan alam,” kata Sukinah.
Pendekatan semacam itu penting dilakukan mengingat dampaknya dalam jangka panjang, yakni memengaruhi agenda kebijakan yang memberikan kontribusi untuk menetapkan dasar advokasi masyarakat.
Sebagai informasi, terdapat pabrik semen di Pegunungan Kendeng yang merusak alam, serta aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Karenanya, dokumenter Ibu Bumi dimanfaatkan sebagai sarana agar budaya di sana tidak tergerus begitu saja oleh budaya dari luar, sekaligus mempertahankan lahan dan menjaga ekosistem. Pun dalam produksi film ini, kru tidak diperbolehkan masuk ke area tambang dan wilayah luar, sehingga pengambilan gambar dilakukan dari kejauhan.
Selain itu, Sukinah menuturkan adanya perubahan setelah penayangan Ibu Bumi. “Bagi saya, ini bentuk kampanye untuk lingkungan karena kami menyuarakan Kendeng bukan untuk masyarakat di sini saja, melainkan Indonesia. Jadi, kerusakan Kendeng itu kerusakan Indonesia,” ungkapnya.
Namun, para investor tetap bersikeras untuk melakukan penambangan. Maka itu, para petani menginisiasi Rabu Menanam sebagai pengingat dan upaya menjaga Pegunungan Kendeng, agar tidak gundul dan airnya tetap mengalir.
-
Revitalisasi Aset Budaya Tradisional Sumba Timur
Berbeda dengan komunitas lainnya, Sumba Integrated Development (SID) merevitalisasi aset budaya tradisional Marapu lewat pemberdayaan pemuda, perempuan, dan lansia di Sumba Timur. Anto Kila selaku Executive Director SID mengungkapkan alasannya dalam wawancara bersama Magdalene, (14/12).
“Awalnya kami melihat jarak antara generasi muda dan tua dalam pelestarian bahasa maupun budaya. Karena di sekolah-sekolah saja sudah tidak menggunakan bahasa daerah lagi, budaya ini terancam punah,” ujarnya, mengingat pewarisan budaya Sumba dilakukan secara lisan, bukan tertulis.
Karena itu, SID menjembatani kelompok lansia yang memahami budaya Sumba, dengan anak muda sebagai generasi yang mewarisi budaya tersebut. Dalam hal ini, musik tradisional dipilih sebagai medium untuk mendorong perubahan perilaku pelestarian budaya. Hal ini juga termasuk bentuk advokasi peningkatan musik tradisional.
“Ketika bernyanyi, orang Sumba Timur itu menggunakan bahasa sastra seperti puisi, atau disebut lawiti. Secara tidak langsung, cara ini juga bisa digunakan sebagai kritik ketika tidak setuju dengan situasi tertentu, dan mudah sekali masuk ke masyarakat,” tuturnya.
Lirik lagu yang tertulis dalam bahasa daerah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Inggris, sehingga hal tersebut memperkuat suara, cerita, lagu, dan kekayaan budaya masyarakat Marapu di Sumba Timur. Artinya, musik mereka dapat menjadi warisan bangsa maupun dunia.
Sebenarnya, para lansia di Sumba Timur sudah memiliki kesadaran akan warisan budaya yang mereka miliki. Namun, pendekatan untuk melestarikannya secara sistematis yang belum mereka lakukan karena mereka memercayai pewarisan budaya pada keturunan merupakan hadiah dari Sang Pencipta, sehingga akan muncul dengan sendirinya.
“Karena itu, dalam proses pendekatan, kami melakukan assessment partisipatif. Tetap mereka yang menilai dan menggali budaya-budaya di sekitarnya, bagaimana situasinya, apakah masih ada dan sering digunakan, atau sudah hilang. Jadi mereka yang menemukan sendiri,” ucap Anto.
Hasilnya, anak-anak muda mulai terlibat dalam proses kampanye perubahan perilaku sosial berbentuk lagu yang dinyanyikan. Lagu tersebut merupakan salah satu ritual yang tidak dilakukan selama lima hingga 20 tahun. Mereka juga menawarkan diri untuk aktif terlibat dalam kepengurusan organisasi masyarakat adat Marapu, yang sebelumnya didominasi orang tua.
Selain itu, SID juga berusaha mengumpulkan 26 literatur dari peneliti yang mengobservasi budaya Sumba. Kumpulan literatur tersebut dipublikasikan dan diperbanyak dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Ada juga arsip digital untuk melestarikan musik yang diunggah ke kanal YouTube dan disimpan di dalam flashdisk. Selain itu, sekolah-sekolah di sana juga meminta agar program SID tersebut dimasukkan ke kegiatan sekolah.
Voice Indonesia, skema pendanaan yang dikelola oleh Yayasan Hivos, baru saja merilis “Call for Proposal” yang berjudul “Power in Artivism”. Voice Indonesia lagi mencari ide proyek kreatif yang akan mendorong seniman dan komunitas untuk menggunakan seni sebagai alat untuk aktivisme. Karya yang dihasilkan bisa berupa mural, video, film, pertunjukkan seni dan lain-lain.
Total pendanaan yang bisa dapat 400 juta, loh!
Yuk, jangan takut bersuara dan tunjukkan ide kreatifmu lewat seni. Penutupan karya kami tunggu hingga 31 Desember 2021 pukul 17.00 WIB.
Informasi lebih lanjut kunjungi https://bit.ly/PowerInArtivism
Ilustrasi oleh Karina Tungari