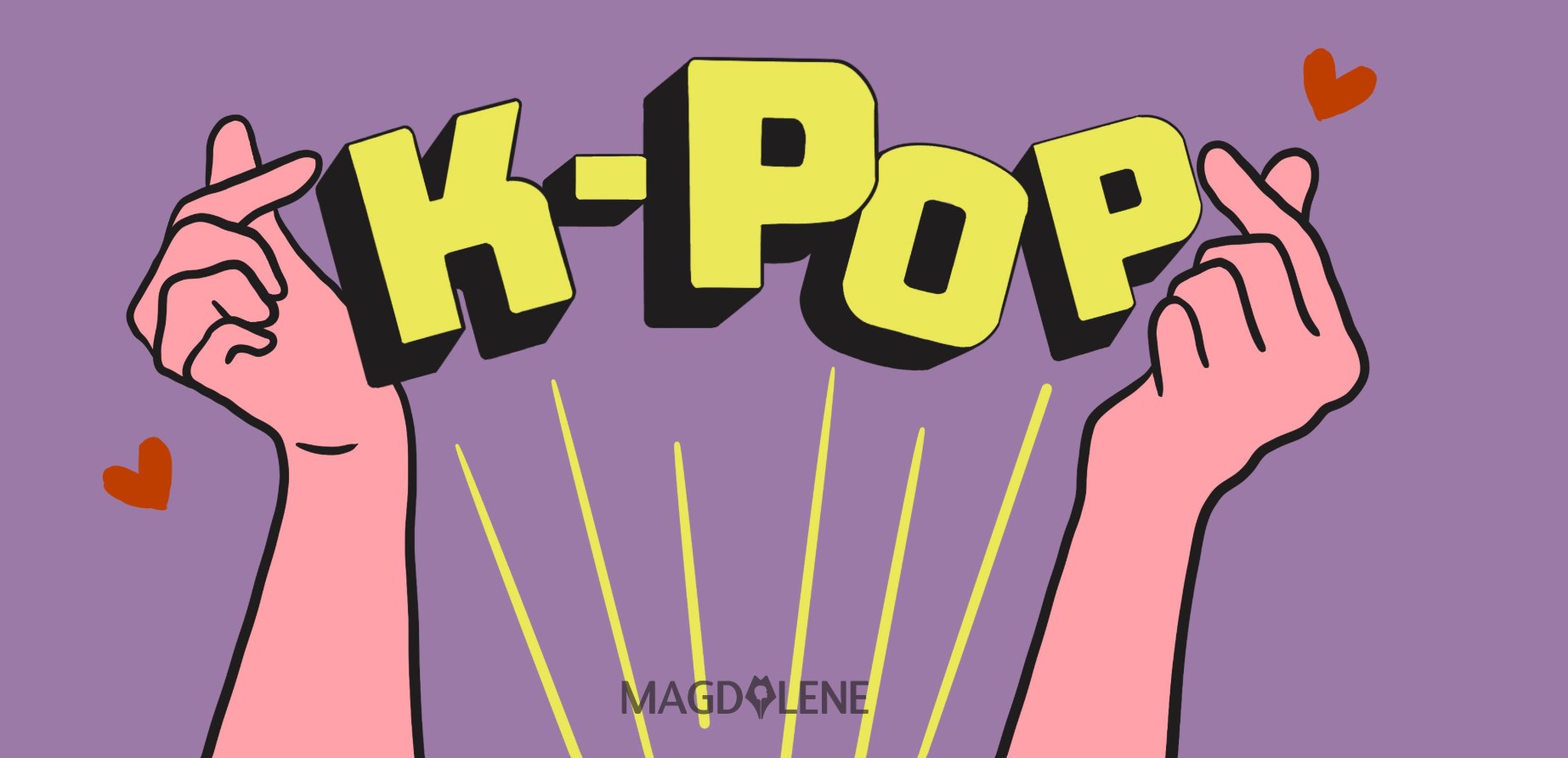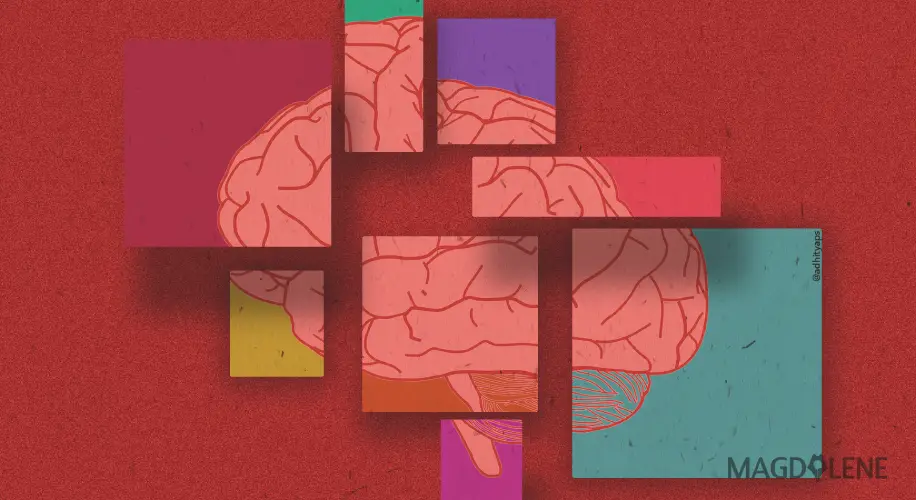‘The Prom’ dan Problematika ‘Gayface’ dalam Film
‘The Prom’ dianggap melanggengkan stigma dan stereotip juga diskriminasi pada kelompok LGBT dalam bentuk ‘gayface’.

The Prom adalah film drama musikal yang diangkat dari pertunjukan Broadway dengan judul yang sama, yang mengisahkan seorang remaja queer bernama Emma Nolan (Jo Ellen Pellman) yang bermimpi untuk menghadiri pesta dansa dengan pacarnya, Alyssa (Ariana DeBose). Sayangnya, karena orientasi seksualnya, Emma tidak hanya dilarang hadir oleh ibu Alyssa yang juga ketua komite orang tua murid, tapi pesta dansa alias prom itu pun dibatalkan.
Mendengar situasi ini, aktris Broadway Dee Dee Allen (diperankan Meryl Streep) dan para koleganya memutuskan untuk membela hak Emma untuk bisa ke prom seperti anak remaja lainnya. Allen melakukan itu demi menaikkan citra baik mereka ke publik yang sedang redup.
Selain sederet bintang besar dalam film ini, dari Streep sampai Nicole Kidman dan Kerry Washington, menyenangkan melihat bagaimana film ini mengangkat tema queer dengan pesan mengenai toleransi. Ryan Murphy, selaku sutradara The Prom dan seorang gay, memang secara konsisten memberikan kesempatan panggung utama kepada aktor dan aktris LGBTQ+. Mereka mulai dari Chris Colfer di drama musikal komedi Glee hingga semua aktor gay di Boys in the Band.
Sayangnya, The Prom mendapatkan banyak kritik, salah satunya karena kurangnya representasi aktor dari kelompok LGBTQ+ untuk salah satu karakter utamanya, Barry Glickman.
Baca juga: Lampaui ‘Love, Simon’: 7 Film Queer Bertema ‘Coming of Age’
Pertama, Glickman dimainkan oleh James Corden, seorang laki-laki heteroseksual. Selain itu, akting Corden masih melekatkan stereotip gay yang feminin dalam lensa orang heteroseksual. Sepanjang film, Corden memproyeksikan dirinya sebagai laki-laki gay yang ngondek atau flamboyan dengan cincin-cincin yang menghiasi tangannya. Ia berbicara, bersikap, bahkan menggerakkan tangannya secara lemah gemulai layaknya stereotip laki-laki gay feminin. Stereotip dikenal dengan istilah gayface, dan menjadi salah satu bentuk tindak kekerasan, dalam hal ini stigma yang dilumrahkan di masyarakat.

Arti Gayface dan Sejarahnya
Menilik dari sejarahnya, istilah gayface ini bisa dilihat dari ditetapkannya Kode Hays atau Code Hays sebagai bagian dari perangkat pedoman industri untuk swasensor konten, yang diterapkan pada sebagian besar film Amerika Serikat yang dirilis oleh studio besar dari tahun 1934 hingga 1968.
Dr. Harry M. Benshoff, seorang akademisi asal Amerika Serikat di bidang film mengatakan bahwa melalui Kode Hays, sebagian besar film-film Amerika tidak diperbolehkan menggambarkan homoseksualitas secara terang-terangan. Kode Hays menyebut perilaku tersebut sebagai sebuah tindakan yang “tidak senonoh” untuk disaksikan oleh publik.
Persinggungan terhadap homoseksualitas diizinkan selama sutradara dapat lolos sensor dengan menjaga orientasi seksual karakter, dengan membatasi karakter tersebut terkait langsung dengan plot utama film, dan tanpa secara terang-terangan memperlihatkan orientasi seksual mereka di layar. Dari ketentuan inilah, arketipe “banci” atau stereotip laki-laki gay feminin yang ngondek muncul dengan istilah baru, yaitu gayface.
Baca juga: ‘RuPaul’s Drag Race’ Ajari Soal Toleransi, Keberagaman, dan Inklusivitas
Gayface di dalam industri perfilman digambarkan sebagai laki-laki yang difeminisasi dengan melekatkannya pada feminitas yang berlebihan (hyperfemininity) dengan kurangnya karakteristik maskulin di dalam dirinya. Karakter gayface di dalam film bertindak sebagai pendorong narasi film hetero. Pembuat film menempatkan karakter mereka yang lekat dengan kurangnya sifat maskulin mereka semata-mata demi untuk menonjolkan karakter protagonis laki-laki hetero utama yang ada.
Gayface pun menjadi sangat problematik, tidak hanya karena sejarahnya yang merepresi orientasi seksual selain hetero, namun juga karena kurangnya representasi aktor atau aktris dari kelompok LGBTQ+ di industri perfilman. Padahal seharusnya aktor queer dan transgender memainkan peran yang mewakili kelompok mereka sendiri.
Aktor Queer untuk Peran Queer
Hollywood pada kenyataannya masih lebih suka memilih aktor hetero untuk memainkan peran gay, meskipun ada aktor LGBTQ+ yang mumpuni. Hal ini bisa dilihat dari hasil survei anggota serikat pekerja aktor SAG-AFTRA yang dilakukan UCLA. Sebanyak 53 persen responden LGBTQ+ dalam survei tersebut menilai direksi dan produser masih memiliki bias terhadap LGBTQ+ dalam perekrutannya, bahkan 34 persen responden non-LGBTQ+ pun setuju.
Tre’vell Anderson, mantan redaktur budaya dan hiburan di majalah Out yang juga seorang transgender, menganggap bahwa masalah para aktor atau aktris hetero yang memainkan peran queer adalah sesuatu yang harus segera diperbaiki. Ia mengatakan melalui USA Today 24 November lalu, bahwa masalah ini penting untuk terus didesak dan digaungkan karena kelompok LGBTQ+ ingin media menjadi cerminan akurat dari dunia yang mereka tinggali. Hal ini harus terjadi tanpa menghapus narasi diri mereka sendiri sebagai kelompok minoritas yang masih kesulitan diterima oleh masyarakat luas.
The Prom telah melanggengkan lingkaran kekerasan berupa stigma dan stereotip serta diskriminasi pada kelompok LGBTQ+ dalam bentuk gayface. Dengan mempekerjakan Corden, seorang aktor hetero dalam memainkan karakter gay yang lekat dengan stereotip laki-laki gay feminin yang flamboyan, Ryan Murphy telah menghapus narasi diri dari sesama queer.
Praktik casting diskriminatif yang berakar pada budaya gayface di Hollywood ini didesak untuk dihentikan, dan kelompok LGBTQ+ perlu direpresentasikan secara setara di industri hiburan. Tak hanya dalam hal aktor, tapi representasi ini juga harus diperluas dalam segala aspek, mulai dari cerita, karakter, sutradara, sampai produser.