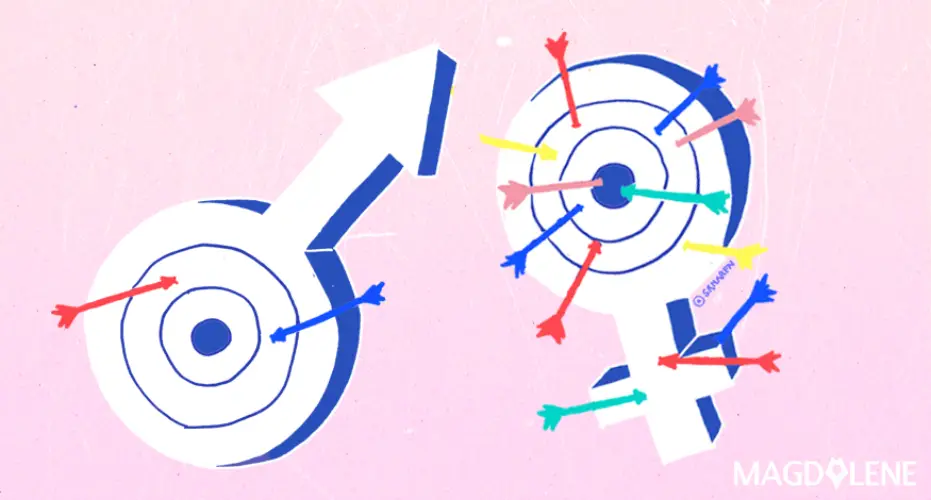Ternyata Rindu Memang Berat, Kisahku Belasan Tahun Tak Mudik Lebaran

Ada pemandangan yang sama setiap musim Lebaran tiba. Di momen itu, mendadak perantau di kota besar berduyun-duyun pulang ke kampung halaman. Stasiun kereta api, terminal bus, dan bandara dibanjiri penumpang. Kendaraan roda empat mengular di sepanjang jalan tol. Pengendara motor tak mau kalah, memadati jalan-jalan alternatif, lengkap dengan barang bawaan mereka.
Kita mengenalnya dengan istilah mudik. Antropolog Universitas Gadjah Mada Prof Heddy Shri Ahimsa-Putra kepada Tirto.id menyebutkan, istilah mudik dikenal luas di medio 1970-an. Tepatnya setelah rezim Orde Baru membangun besar-besaran kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Orang-orang desa yang melihat adanya potensi lapangan pekerjaan baru di sana, lantas melakukan migrasi demi mencari kerja dan penghidupan layak.
Setibanya di kota, orang-orang dari desa mau tak mau lepas dari keluarga dan kerabatnya dalam waktu lama. Mau pulang kampung juga tak bisa seenaknya. Di sinilah Hari Raya Idulfitri jadi momen para perantau untuk beristirahat sejenak dari hiruk pikuk kota. Mudik singkatnya adalah momen melepas rindu para perantau.
Tiap tahunnya, aku hanya bisa melihat segala kehebohan ini lewat layar televisi dan media sosial. Meski tradisi ini cukup familier, tapi aku menjalankannya hanya sampai di awal bangku Sekolah Dasar (SD). Tahun-tahun terakhir jadi siswa SD, mudik sekadar memori untukku.
Apa sebab? Ceritanya, mendiang Eyang Papi (panggilan untuk kakek. Red) saat itu terkena penyakit stroke. Khawatir kondisinya bakal memburuk, orang tuaku dan lima saudara yang rumahnya saling berdekatan, membujuk Eyang Papi dan Eyang Mama untuk menetap di Jakarta. Mereka setuju dan memutuskan menjual rumah di Semarang lalu uangnya dipakai untuk membeli rumah kecil di ibu kota. Jarak rumah baru Eyang Papi dan Eyang Mama cuma terpaut 10 menit dari rumahku dengan berjalan kaki.
Baca Juga: Kenapa Orang Lebih Mudah Saling Memaafkan Saat Lebaran Dibanding Waktu Lainnya?
Ada Enaknya Tak Ikut Mudik
Belasan tahun tak pernah mudik Lebaran bikin teman-teman kepo bertanya, “Gimana sih rasanya enggak mudik? Enak enggak?”
Biasanya aku akan spontan menjawab, “Enak banget!”
Alasannya, mudik Lebaran butuh biaya ekstra. Kita harus menyiapkan biaya transportasi untuk beli tiket kereta, bus, atau pesawat. Kalau pun mau mudik dengan mobil, harus disiapkan juga uang bensin dan tolnya. Selama perjalanan, tentu ada biaya lagi yang harus kita keluarkan untuk sekadar beli kudapan.
Tak berhenti di situ, agar enggak dinyinyirin sanak keluarga, sudah lazim para pemudik mengalokasikan anggaran tambahan untuk “Tunjangan Hari Raya” (THR) ke orang-orang di kampung halaman. Belum lagi buah tangan yang harus disiapkan sebelumnya.
Mengingat budget yang besar, tak mudik jelas jadi keuntungan buatku. Uang THR bisa aku berikan pada orang tua dan Eyang, alih-alih dikuras untuk biaya transportasi mudik. Sisanya, aku tabung dan belanjakan untuk diri. Biasa lah self-reward.
Selain menghemat anggaran, tak mudik Lebaran dan diam di Jakarta membuatku lebih menikmati suasana kota. Jakarta yang biasanya ramai, serba terburu-buru, bising dengan suara klakson dan teriakan, tiba-tiba melambat. Terlebih, di jalan khusus pejalan kaki, tak lagi terlihat ratusan kaki-kaki berjalan cepat mengejar waktu. Sementara, dalam peron atau badan bus, ruang-ruang seketika menjadi lapang. Napasku pun lebih teratur karena tak perlu repot berdesak-desakan sembari menahan emosi.
Jakarta di musim Lebaran bak surga baru. Berkeliling di Jakarta di momen-momen itu menjelma terapi buatku. Menyinggahi taman kota yang tak terlalu sesak sambil membaca buku dan mendengarkan musik lalu disusul dengan makan siang pun jadi opsi terbaik menikmati hari.
Sekali lagi, tak ada suara klakson, bau knalpot yang menyesakkan paru-paru, dan langit yang lebih cerah. Aku bisa merasakan sepenuhnya kebahagiaan atas kesederhanaan hidup yang tak bisa kucicipi saat Jakarta penuh dengan lautan manusia.
Baca Juga: 5 Pertanyaan Nyebelin Saat Lebaran dan Cara Menghadapinya
Mudik yang Tetap Kurindukan
Meski tak mudik Lebaran terasa enak, bukan berarti aku tidak mau mencicipinya lagi. Jujur saja, dengan euforia mudik yang disiarkan media di mana-mana, beberapa kali terjebak dalam nostalgia hingga bertanya kepada Mama, “Mama, beneran enggak ada saudara lagi di Jawa?”
Mama menjawab, sebenarnya ada saudara yang masih tinggal di Bojonegoro, Jawa Timur. Namun, ia tergolong saudara jauh, sehingga tak perlu repot-repot disambangi.
Masalahnya, tradisi mudik yang dulu pernah aku jalani selalu mengingatkan pada perjalanan menyenangkan naik kereta api. Berkat jepretan Papa di kamera digitalnya, aku bisa mengingat kembali euforia mudik kami ke Semarang. Saat menulis artikel ini, aku sibuk memandangi potret diriku sendiri yang tersenyum lebar bersama Mama, Papa, Adik, Om, dan Tante di Stasiun Gambir Jakarta, sembari menenteng koper dan bekal makanan.
Di dalam kereta, senyumku tampak lebih lebar lagi. Rasanya baru kemarin aku naik sepur dan asyik memandangi sawah hijau dan laut di utara Jawa yang berkilauan terkena sinar matahari. Tentu saja aku ceriwis bukan main bertanya pada Mama dan Papa berulang kali tentang pemandangan di balik jendela itu.
Saat sudah lelah berbicara, aku biasa menghabiskan waktu membaca komik sambil mendengarkan lagu Sheila on 7 hingga Padi dari walkman pemberian Papa. Sungguh momen yang membahagiakan, apalagi buat anak kecil yang memang suka jalan-jalan. Momen perjalanan mudik pertama ini terulang dalam mudik-mudik setelahnya. Inilah yang kemudian selalu aku rindukan.
Tak cuma soal perjalanan, hal lain yang kurindukan saat mudik adalah aku dapat kesempatan jalan-jalan keliling kota yang belum aku pernah kunjungi. Selama di Semarang, Eyang Mama dan Om biasanya akan mengantarkanku berwisata. Dalam pengalaman mudik kedua, aku ingat diajak ke Kota Lama, berkeliling melihat Gereja Blenduk dan Pasar Barang Antik. Aku juga diajak ke Pagoda Avalokitesvara, vihara tertinggi di Semarang dan ditutup dengan wisata kuliner legendaris, seperti makan Babat Gongso Pak Karmin, Nasi Gandul Pak Memet, hingga lumpia Mbak Lien.
Meski saat ini aku dan keluargaku tinggal berdekatan, tapi rasanya tak lagi sama. Sebagai informasi, Eyang Mama kini tinggal satu rumah denganku sejak Eyang Papi meninggal dan dirinya jatuh di kamar mandi hingga cedera kaki. Namun, lagi-lagi kedekatan jarak itu tidak bisa tergantikan dengan kedekatan emosional yang aku alami selama mudik Lebaran.
Baca Juga: 4 Dampak Lingkungan Jika Lebaran Tak Ramah Bumi
Saat mudik Lebaran aku merasakan bagaimana bisa tidur di kamar Eyang. Di dalam kamar itu, aku bisa mendengarkannya bercerita semalaman tentang hidupnya yang begitu seru dan mengasyikkan. Setelah lelah bercerita, Eyang akan tertidur dan aku bisa menikmati ketenangan lewat suara dengkuran halusnya bersamaan dengan lantunan radio. Momen itu begitu intim dan akan berlanjut dalam beberapa hari yang semakin dipererat dengan cara Eyang memanjakanku lewat masakan atau ajakannya pergi.
Sudah belasan tahun momen-momen itu tak pernah aku rasakan semenjak ritual mudik terpaksa ditiadakan. Aku pun jadi menyadari terlalu terbiasa hidup berdekatan, terkadang membuat kita berjarak dengan orang terkasih.