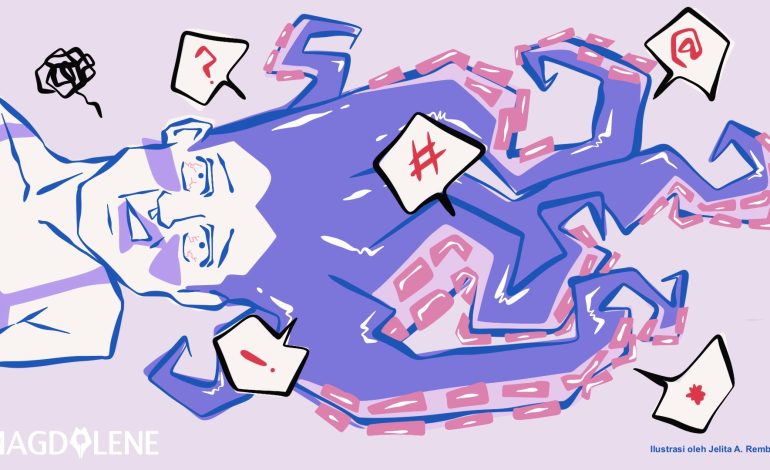Pergub Poligami ASN Jakarta: Diskriminatif dan Ketinggalan Zaman

Baru-baru ini publik dibuat heboh dengan Peraturan Gubernur (Pergub) soal Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta. Pergub DKJ Nomor 2 Tahun 2025 itu salah satunya mengatur soal pemberian izin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan poligami.
Ketentuan soal ASN poligami diatur khusus dalam Bab III dengan tiga alasan yang mendasari, yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah sepuluh tahun perkawinan.
Ditemui Tempo.co, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi bilang, penerbitan Pergub ini sebenarnya bukan untuk mendorong para ASN berpoligami, melainkan demi melindungi keluarga ASN. “Kami ingin agar perkawinan, perceraian, yang dilakukan ASN di DKI Jakarta itu bisa betul-betul terlaporkan. Sehingga nanti juga untuk kebaikan,” ucapnya.
Teguh menambahkan, meski ada pasal yang mengatur perizinan poligami, Pergub tersebut sebaliknya, justru memperketat urusan perkawinan dan perceraian. Ada sejumlah kriteria ketat bagi ASN laki-laki yang hendak melakukan pernikahan dengan lebih dari seorang perempuan. Sehingga, kata dia, pengawasan terhadap perkawinan bisa lebih ketat lagi.
Baca Juga: Bentuk Diskriminasi Gender di Tempat Kerja dan Cara Mengatasinya
Sejarah di Balik Pergub Poligami
Siti Aminah, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai Pergub ini problematik, mengingat praktik poligami sendiri sangat diskriminatif bagi perempuan.
“Praktik poligami adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang menempatkan perempuan sebagai subordinat dari laki laki,” tutur Siti pada Magdalene.co.
Sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, poligami juga tergolong kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak pidana kejahatan terhadap perkawinan. Adanya lapis bentuk kekerasan enggak lepas dari bagaimana poligami yang kerap diawali dari perselingkuhan. Tentu saja ini berakibat pada penderitaan psikologis juga penelantaran yang tidak terbatas pada pemberian nafkah.
Karena itu, Komnas Perempuan dalam rilis pers menyebut poligami sebagai KDRT, khususnya berupa kekerasan fisik dan penelantaran. Pada 2023, Badan Peradilan Agama (Badilag) misalnya mencatat 391.296 pengajuan perceraian. Sebanyak 701 di antaranya karena poligami, 32.646 lantaran ditinggalkan salah satu pihak, dan 240.987 karena perselisihan terus-menerus.
“Baik penelantaran maupun perselisihan terus-menerus ditengarai terkait dengan isu perselingkuhan dan praktik beristri lebih dari satu,” jelas Komnas Perempuan.
Kehadiran Pergub ini pun menambah deret panjang produk hukum diskriminatif yang meminggirkan perempuan. Pasalnya peraturan ini tak lebih dari pembaruan materi dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 maupun Peraturan Presiden (PP) Nomor 10 Tahun 1983 (telah direvisi menjadi PP 45/1990).
“Hulu dari Pergub ini adalah UU Perkawinan dan PP Nomor 45 Tahun 1990. Dicabut atau tidak, Pergub rujukannya tetap ke kedua peraturan di atas,” jelas Siti.
Merujuk arsip Harian Republika, peraturan tentang perizinan poligami di kalangan ASN berawal pada 1980-an saat anggota Dharma Wanita marak melaporkan poligami dan perceraian sewenang-wenang lelaki pejabat negara. Kegaduhan ini semakin semarak dengan isu perselingkungan Soeharto dengan artis ibu kota hingga Soeharto repot-repot menyangkalnya di pidaton ulang tahun Komando Pasukan Sandi Yudha.
Siti Hartinah alias Tien Soeharto, penentang poligami lantas disebut-disebut jadi pihak utama di balik dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Dua produk hukum ini pada intinya bertujuan memperketat dan membatasi poligami dan perceraian yang selama ini merugikan perempuan.
UU Perkawinan sendiri menganut asas monogami sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 tentang suatu perkawinan hanya boleh terdiri dari satu suami dan satu istri. Untuk memperketat poligami, UU Perkawinan memberikan sejumlah syarat, baik syarat alternatif dan akumulatif dalam PP Nomor 45 Tahun 1990. Syarat alternatif ini antara lain, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.
Sementara syarat kumulatif adalah persetujuan tertulis dari istri, ASN laki-laki yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, serta ada jaminan tertulis dari ASN bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
Pejabat pemerintah juga tidak boleh memberikan izin bagi PNS lelaki yang mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang apabila:
1. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
2. Tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat;
4. Dan/atau ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
Seluruh syarat alternatif dan kumulatif dalam UU Perkawinan dan PP Nomor 10 Tahun 1983 (sekarang PP Nomor 45 Tahun 1990) inilah yang disalin dalam Pergub DKJ terbaru.
Baca Juga: Mundurnya Jacinda Ardern dan Tantangan Perempuan Pemimpin
Diskriminatif dan Basi
UU Perkawinan telah berusia 50 tahun sejak ia disahkan. Sedangkan PP Nomor 45 Tahun 1990 kini telah menginjak usia 35 tahun. Menyalin produk hukum jadul ke produk baru menjadi kurang tepat dilakukan. Sebab, produk hukum baru seyogyanya perlu menyesuaikan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang lebih relevan. Ini dilakukan demi tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak yang lebih baik.
Dalam Pergub DKJ 2025, kita semua dapat melihat bagaimana pendasaran alasan diperbolehkan poligami masih ketinggalan zaman, sehingga cenderung diskriminatif. Alasan pertama soal istri tidak dapat melakukan kewajiban menurut Komnas Perempuan bersifat subjektif. Sebab, itu mengacu pada konstruksi masyarakat patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.
Posisi ini mendasarkan pada pembatasan peran perempuan di ranah domestik, yakni pengasuhan dan perawatan. Pembatasan peran ini mengakibatkan ketimpangan relasi suami dan istri dalam rumah tangga, yang bakal meningkatkan kerentanan perempuan pada berbagai jenis kekerasan.
Lalu alasan tidak dapat melahirkan keturunan meneguhkan posisi subordinat perempuan di dalam masyarakat yang menempatkan penilaian pada kapasitas reproduksi perempuan. Perempuan baru dianggap pantas jadi istri kalau ia bisa hamil dan melahirkan, terlepas dari kondisi medis yang mereka alami atau bahkan ketidaksuburan dari pihak laki-laki.
Tak ketinggalan adalah alasan ketiga yang dinilai Rina Prasarani, Wakil Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Bidang Advokasi dan Peningkatan Kesadaran sangat bermasalah. Alasan ini menumpukan diri pada pertalian antara patriarki dan ableisme −diskriminasi dan prasangka sosial terhadap disabilitas yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak mampu, tidak normal, dan “cacat”.
“Di dalam masyarakat seseorang yang dianggap berfungsi itu identik dengan laki-laki dan tidak disabilitas. Jadi jika dia perempuan lalu dia tidak bisa ‘melayani’ suaminya karena disabilitas yang dia miliki, maka ini jadi menambah kerentanan perempuan didiskriminasi dan mengalami kekerasan,” tutur Rina pada Magdalene.co.
Penuturan Rina ini diamini oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mereka mengungkapkan kerentanan ini dua hingga empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan non-disabilitas. Di Indonesia sendiri, kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dapat ditelusuri lewat Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. Berdasarkan catatan 2023, terdapat 105 kasus kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas.
Jumlah kasus ini sayangnya tidak bisa sepenuhnya mencerminkan realitas mengingat banyak kasus tidak terdata atau terlaporkan karena berbagai hambatan perempuan dengan disabilitas. Ini mengapa Revita Alfi, Ketua HWDI menyayangkan tindakan pemerintah daerah Jakarta yang malah memperkuat stigma terkait disabilitas.
Baca juga: Rancangan Perda Anti-LGBT: Lagu Lama di Musim Pemilu
“Perempuan disabilitas masih kesulitan melaporkan kasus kekerasan seperti KDRT. Apa yang kita ketahui sekarang hanya fenomena gunung es. Mereka banyak takut melapor. Pas melapor pun tidak tau bagaimana mekanismenya. Cek kanal juga tidak accessible. Dukungan lingkungan juga kerap kali tidak ada. Ini sekarang malah divalidasi dengan dengan kebijakan tidak berpihak,” kata Revita.
Melihat bagaimana Pergub ini hanya jadi perpanjangan tangan UU Perkawinan yang “ketinggalan zaman”, baik Revita, Reni, maupun Komnas Perempuan mendorong adanya revisi dari UU Perkawinan. Alasan-alasan diskriminatif sebagai dasar perizinan poligami semestinya dihapuskan karena sudah tidak relevan dan malah memperkuat stigma bagi kelompok disabilitas.
Revita dan Reni secara khusus menekankan dibandingkan memuat pasal-pasal diskriminatif, seharusnya perawatan dan dukungan terhadap istri dengan disabilitas menjadi aspek penting yang harus didorong pemerintah. Ini dilakukan agar suami tidak lagi melihat istrinya sebagai suatu beban atau manusia yang tidak utuh.
“Bagaimana dia bisa mendapatkan perawatan dan rehabilitasi terbaik secara sosial dan medis adalah hal yang justru lebih penting didorong pemerintah. Sekarang semua ini belum tersedia. Akhirnya balik lagi ke stigma bahwa disabilitas itu beban, tidak berfungsi. Padahal bisa berfungsi kalau lingkungannya mendukung. Lingkungan ini jadi PR Pemerintah,” kata Rina.
Sementara revisi UU Perkawinan diajukan dan dibahas, pelaksanaan Pergub Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 menurut Komnas Perempuan harus diiringi berbagai hal. Pertama, penegakan hukum untuk pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan dan pelaksanaan KUHP ketika ASN menikah walau diketahuinya ia memiliki halangan perkawinan yaitu masih terikat perkawinan, serta UU PKDRT.
Kedua, diperlukan juga mempertimbangkan komposisi gender dalam Tim Pertimbangan dan memastikan bahwa tim tersebut memiliki perspektif adil gender dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memeriksa dan mengenali kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
Ketiga, memastikan pelaksanaan hak atas nafkah bagi istri dan anak pasca-perceraian akibat atau terkait tindak perkawinan lebih dari satu istri.