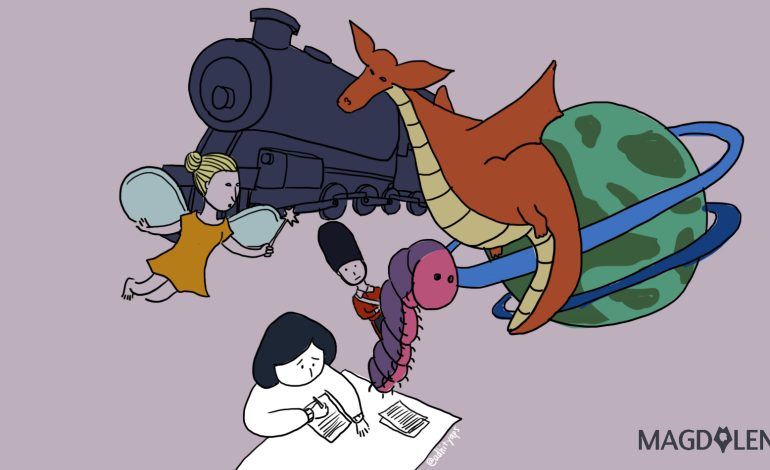Pengalaman Jadi Anak Jaksel Sehari: Lebih Nyaman Jadi Warga Pinggiran

Kepala saya sibuk menoleh ke kanan dan kiri seperti anak kecil yang kehilangan ayah ibunya di pusat perbelanjaan. Bedanya, saya berada di dalam kendaraan roda empat, yang melintas di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.
“Oh ini toh, restoran dan kafe hits yang lagi rame di Instagram,” batin saya, sembari mengingat Instagram story teman-teman dan akun-akun food blogger, yang enggak jarang melabelkan beberapa tempat itu sebagai hidden gem.
Enggak apa-apa kalau kamu berpikir saya kurang gaul atau norak banget. Sebagai anak suburban garis keras—numpang lahir di Tebet, menghabiskan masa kecil di Pondok Gede dan Cijantung, lalu tumbuh dewasa di Cibubur—saya bukan orang yang suka menghabiskan waktu untuk mengunjungi spot-spot baru di Jakarta.
Kalau masalah tahu-menahu tempat hangout ini tak lebih dari laman saved Instagram. Tapi bukan berarti langsung tertarik mengunjungi saat akhir pekan menjemput, alias kapan-kapan aja kalau pengen.
Sudah rahasia umum, kehidupan di Jakarta Selatan setingkat lebih maju dibandingkan distrik lainnya. Pun saya punya gambaran sendiri yang terlintas dengan jelas di dalam pikiran, setiap mendengar wilayah itu disebut; rumah-rumah gedong, ekspatriat, orang-orang muda berpenampilan menarik, Pondok Indah Mall (PIM), tempat dugem, dan Ahmad Dhani.
Baca Juga: Jakarta, Masih Tak Ada Anganku di Sana
Lho kok Ahmad Dhani? Karena kita semua tahu dia tinggal di Pondok Indah.
Dari cara menafsirkan Jakarta Selatan, terlihat bagaimana “perbedaan kasta” tertanam di kepala saya. Tentu salah satu faktornya fakta kalau daerah itu sudah mulai nge-tren sejak 1980-an, dilihat sebagai tongkrongan dan cepat mengadaptasi tren baru. Kalau kata ibu, “Belum gaul kalau enggak main ke Jaksel.”
Ditambah perbincangan di media sosial, bikin stereotip mereka semakin kencang dan menjadi spotlight kehidupan anak muda. Sedikit banyak juga area Jakarta lainnya terlihat enggak seberapa, apalagi wilayah suburban yang enggak ada bedanya dengan remah-remah rengginang di kaleng Khong Guan.
Saya pun selalu bertanya-tanya, apa sih rasanya jadi anak Jakarta Selatan yang tinggal di kawasan serba ada, Jumat malam—atau hampir setiap hari mampir ke bar, serta berapa kocek yang perlu dirogoh untuk menjalani gaya hidup demikian?
Atas dasar rasa penasaran tersebut, saya mengajak beberapa teman dan kenalan, untuk menyelami kehidupan anak Jaksel selama 24 jam.
Hari Pertama: (14/1)
Perjalanan saya berawal pada Jumat siang di Ratangga Coffee and Bites, sebuah toko kopi kecil di bilangan Blok A. Lokasinya bukan tempat hits kelas atas, tapi cukup sering disebutkan oleh @darihalte_kehalte, akun media sosial yang mempromosikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta.
Begitu membuka pintu, cahaya temaram, keheningan, lantunan lagu milik Ed Sheeran, dan aroma biji kopi mengucapkan selamat datang. Sambil menantikan kedatangan segelas es kopi susu dan seorang teman, saya memutuskan membaca “Rest”, bab pertama dari Things Only You Can See When You Slow Down (2012) oleh Haemin Sunim.
Selang 30 menit kemudian, seorang laki-laki mengenakan kaus merchandise milik penyanyi Clairo, menghampiri meja. Namanya Gilang, penulis kreatif di sebuah rumah produksi, yang saya kenal sewaktu bergabung di radio kampus.
Kami duduk berhadapan dan saling bertukar kabar secara singkat. “Langsung to the point aja deh, mau tanya-tanya apa nih?” guraunya sambil menyesap coffee beer.
Baca Juga: Mewah itu Langit Biru
Meskipun bermukim di Depok, ia menghabiskan sebagian besar masa remaja di sekolah swasta di Pondok Indah. Dan setiap diajak bertemu, Gilang pasti memilih di Jakarta Selatan. Karena itu, saya mengulik alasannya merasa nyaman di daerah ini.
“Jaksel tuh posisinya di tengah. Lo mau prestige bisa dapet, ramah di kantong juga bisa,” jawabnya.
Pria 23 tahun itu membagikan beberapa tempat nongkrong favoritnya, yaitu Pertok Pondok Indah, Area 51 di PIM 2, dan kantin sopir di basement PIM 2. Baginya, sejumlah tempat tersebut mudah dijangkau, banyak variasi makanan, dan bisa menemukan barang-barang yang dicari dengan mudah.
“Dari sekolah bisa ke PIM naik bajaj, rame-rame patungan naik taksi biar murah, atau nebeng jemputan yang lewat terus bayar Rp2 ribu,” tutur Gilang, memberikan perspektif lain bahwa kehidupan anak sekolah di sana tidak melulu glamor.
Sebelum menjelajahi kehidupan malam, saya mampir ke restoran Korea legendaris di Senopati, Legend of Noodle. Waktu masih menunjukkan pukul 5 sore, tapi jalanan dan tempat parkir mulai dipadati mobil-mobil, yang saya duga milik pekerja kantoran. Begitu pula dengan rumah makan yang pengunjungnya didominasi warga negeri ginseng, menampilkan salah satu ciri khas di Jakarta Selatan, yakni keberadaan ekspatriat.
Menghabiskan seporsi haemul jjampong dan cheese buldak—ini bukan rakus, teman saya terlanjur mengibarkan bendera putih karena enggak sanggup—bikin ngantuk dan ingin nyender di jok mobil. Padahal masih ada satu agenda tersisa, nongkrong di bar.
Dengan tenaga yang tersisa, saya menuju Amora Sky Lounge yang berjarak 170 meter dari Pasaraya Blok M. Hasil riset kecil-kecilan dari kanal Youtube Jakarta Uncensored sih, bilangnya ini tempat yang sedang digandrungi. Tapi ada beberapa alasan saya memilih tempat ini.
Pertama, nggak bikin saldo ATM sekarat dalam satu malam. Soalnya enggak ada minimum pembelian, dan harga minumannya murah meriah di kantong jurnalis yang baru merintis kayak saya—pesan empat minuman hanya Rp175 ribu. Kedua, bisa berpakaian santai dan enggak timpang dengan outfit mbak-mbak SCBD. Ketiga, playlist-nya ramah di telinga karena saya bukan penikmat musik jedag-jedug.
Ditemani segelas cocktail, saya bertemu Deryan, pengelola media sosial di sebuah media yang memberdayakan anak muda. Perkenalan kami baru dimulai malam itu, lewat teman kuliah yang kebetulan pernah bekerja bareng dengannya. Seperti teman lama, obrolan mengalir dengan santai. Saya pun teringat dengan stereotip anak Jakarta Selatan yang katanya easy going.
“Tipikal anak Jaksel kayak gitu, baru kenalan tapi diajak ngobrol terus biar akrab,” ujar Deryan. “Apalagi kalau udah mabok, si paling bestie,” lanjutnya.
Semakin malam, Amora semakin dipadati pengunjung. Sambil mendengarkan playlist yang diperdengarkan lewat pengeras suara, kami membiarkan keramaian mengisi keheningan. Beruntung malam itu lagu-lagu yang diputar milik musisi lokal favorit saya.
Baca Juga: Menjadi Perempuan Penulis Muda di Jakarta
Setelah berbincang cukup lama, Deryan bercerita kalau ia belum lama tinggal di ibu kota. Sebelumnya ia tinggal di Bandung, kemudian memutuskan bekerja di Jakarta pada 2019. Pun kini lingkungannya didominasi anak-anak Selatan.
“Pergaulan di Jakarta Selatan sama Bandung beda enggak?” tanya saya setengah berteriak, mengimbangi volume speaker yang diperkeras.
“Banget. Di sini terlalu open minded dan dugem udah jadi lifestyle,” akunya. Saat baru hijrah ke Jaksel, seorang kenalan yang baru dikenalnya sehari langsung bercerita kalau ia married by accident. Ada juga yang mengaku dirinya gay secara terang-terangan, atau mengumbar kehidupan seksualnya. Selain itu menurutnya, warga Jakarta seperti tidak punya opsi hiburan selain ke club dan bar.
“Gue merasa di Jaksel kulturnya luar negeri banget,” jelasnya. Awalnya pria 26 tahun itu merasa informasi-informasi itu terlalu berlebihan untuk disampaikan. Namun, ia mulai belajar menerima lingkungannya yang open minded. Yang dikhawatirkan ketika pulang ke Bandung dan bertemu teman-temannya.
“Takutnya gue bakal terlalu open dan cerita kayak gitu juga ke teman-teman di Bandung,” ucapnya.
Hari Kedua: (15/1)
Seorang rekan kerja pernah menceritakan ciri khas fesyen anak Jakarta Selatan. Kasual dan bermerk, tapi tidak ditunjukkan secara eksplisit.
Karenanya, di hari kedua saya mengenakan blouse off shoulder biru tua dari Uniqlo, straight pants berwarna hitam, sepasang Nike Air Force 1 yang tak lagi putih, sling bag Coach, dan kacamata hitam RayBan punya bapak. Ya nggak terlalu branded, tapi cukup buat saya yang mengesampingkan merk dalam berbusana.
Menumpangi taksi online, saya menuju Papilion Kemang untuk melakukan aktivitas yang bukan saya banget, brunch. Tempat yang disebut market place itu justru diramaikan mbak-mbak yang baru pulang nge-gym, bikin saya merasa overdressed.
“Ya udahlah, tujuannya beda,” pikir saya, berusaha mengembalikan kepercayaan diri. Satu hal yang enggak saya sukai mengunjungi tempat baru, kelihatan linglung dan bingung mau pesan apa. Akhirnya pilihan jatuh ke kale caesar salad dan iced pumpkin spice latte dengan total Rp87 ribu. Gesekan mesin electronic data capture (EDC) itu disambut teriakan dompet saya, mengingatkan ini masih pertengahan bulan.
Waktu menunjukkan pukul 11.40 ketika Fasa, kenalan saya tiba. Kami memutuskan duduk di area outdoor, menikmati sisa suasana Sabtu pagi. Perbincangan siang itu rasanya lebih relate dengan kehidupan sehari-hari, tentang persepsi anak suburban yang main ke area selatan Jakarta.
“Aku pernah merasa insecure waktu beberapa kali ke tempat yang cukup high end di sekitar sini,” ceritanya. Ia mengaku khawatir terlihat menonjol di mata orang lain, karena baru pertama kali mengunjungi tempat tersebut. Padahal, dirinya terhitung sering hangout di Jakarta Selatan, karena cukup dekat dari rumahnya di Jakarta Timur.
Sejak SMA, ia senang mengeksplorasi tempat-tempat terkini yang sering muncul di Instagram. Jika semasa remaja karena FOMO, kini mencari tempat nyaman untuk work from cafe atau makan malam sepulang ngantor menjadi alasannya. Bahkan bisa setiap minggu.
“Dulu trying to fit in banget, kadang sampai maksain untuk pergi,” tuturnya mengenang masa-masa putih abu-abu. “Sekarang lebih menyesuaikan budget,” imbuhnya.
Sependapat dengan saya, Fasa mengatakan mampu mengategorikan seseorang sebagai anak Jakarta Selatan berdasarkan penampilannya. Ia menuturkan, mereka berpenampilan lebih kasual, tidak terlihat dress up, dan tidak berusaha mengikuti tren.
“Anak sini tuh pake baju santai karena menurut mereka ‘ah cuma ke situ doang’. Mereka udah bagus without even trying,” katanya sambil tertawa. Sebagai anak-anak pencipta tren, menurut Fasa cara berpakaian mereka selalu satu langkah lebih dulu. Setelahnya baru masyarakat distrik lain “menyontek” lewat TikTok.
Selain penampilan, penggunaan bahasa anak Jaksel yang keminggris juga merupakan ciri khas yang mencolok, dan sering ditiru warganet. Namun menurut Alli, seorang warga Jaksel totok, mengaku cukup terganggu dengan mereka yang hobi mocking.
“Kita tuh bukan mau dilihat Jaksel banget. Tapi bingung, enggak bisa menemukan kosa kata yang tepat dalam Bahasa Indonesia,” terangnya saat ditemui di food court PIM 3. Laki-laki 23 tahun itu menyatakan kerap kali terlalu mempertimbangkan kata-kata yang akan diucapkan, supaya lawan bicaranya enggak nyeletuk dirinya “Jaksel banget”.
Alli pun menepis stereotip pergaulan anak Jakarta Selatan yang harus mewah. “Itu tentatif. Ada saatnya kita pengen hedon banget, ada juga yang makan kaki lima,” ujarnya. “Cuma bisa dibilang pride-nya kita suka tinggi, karena semua tempat ada di Selatan,” tambahnya. Sebut saja club dan bar, hingga tempat makan atau lokasi hangout yang selalu dibicarakan di media sosial.
Suasana PIM sore itu ibarat segelas cendol. Pandangan saya menyapu sekelompok anak muda, maupun kumpulan keluarga sedang quality time. Ingin rasanya segera menghempaskan tubuh di kasur, maklum sudah lebih dari tiga jam mengelilingi mal itu. Tapi berhubung penasaran dengan banyaknya restoran vegan di Jakarta Selatan belakangan ini, saya memutuskan menghabiskan malam Minggu di Burgreens.
Itu kali pertama saya mencicipi chicken karaage dari protein kedelai, ditemani seorang juru bahasa isyarat Ratri Jasmine. Ia beralih menjadi seorang vegetarian sejak 2018, salah satu alasannya ingin berkontribusi ke lingkungan karena banyak jejak karbon yang ditinggalkan ketika traveling atau naik transportasi online.
Di tengah menjamurnya restoran vegan di Jakarta Selatan, Jasmine bersyukur semakin mudah menemukan variasi makanan, terlepas dari motivasi masyarakat sehingga tuntutan gerai vegan meningkat.
“Tujuan tiap orang kan berbeda ya, ada religion restriction, kesehatan, nggak tega dengan hewan, atau sekadar lifestyle.”
Namun berdasarkan informasi yang beredar di grup vegetarian, perempuan 28 tahun itu menyampaikan penyebab terbesar masyarakat memutuskan menjadi vegan adalah pandemi COVID-19, yang penyebarannya berasal dari hewan. Informasi itu merujuk pada penelitian The COVID-19 pandemic: an opportunity to go vegan? (2020) oleh Marie Anne dari Istanbul Bilgi University.
Terkait banyaknya restoran vegan, tak sedikit warganet berkomentar sebenarnya masakan rumahan orang Indonesia sudah cukup mewakili. Dari banyaknya restoran vegan hanya akal-akalan bisnis semata.
“Menurutku makanan itu tergantung siapa yang masak dan menciptakan,” ujar Jasmine. “Orang-orang Indonesia kan mikirnya, ‘gitu aja mahal padahal enggak pake daging’. Kalau aku ikhlas bayar lebih mahal buat teknologi dan kreativitas penciptanya,” sambungnya.
Awalnya saya satu dari sebagian warganet yang nggak memahami penyebab “mahalnya” makanan vegan. Setelah mencicipi dan berbincang dengan Jasmine, opini saya berubah. Usaha mereka patut diapresiasi, mampu membuat cita rasa dan tekstur sedemikian rupa hingga dapat mengobati kerinduan para vegan akan daging. Bahkan, harga yang ditawarkan relatif standar jika disandingkan dengan restoran lainnya.
Petualangan selama 24 jam itu diakhiri dengan memesan taksi online ke Cibubur bertarif Rp121 ribu, menggenapkan pengeluaran lebih dari setengah juta. Tentu ini nominal yang enggak sedikit bagi saya, seseorang yang jarang menghabiskan sejumlah uang hanya untuk melepas penat tanpa kegiatan berfaedah.
Di sepanjang jalan, saya bernapas lega tinggal di suburban dengan gaya hidup biasa-biasa saja. Karena artinya, enggak perlu lelah fisik akibat pergi ke sana ke mari, menguras energi setelah berinteraksi dengan banyak orang, atau berpura-pura merelakan saldo rekening yang mengalir lebih deras dibandingkan air keran.
Yang terpenting, saya bisa menikmati akhir pekan tanpa mengenakan sebuah topeng. Namun, bukan berarti saya enggak akan mampir ke Jaksel lagi lho.