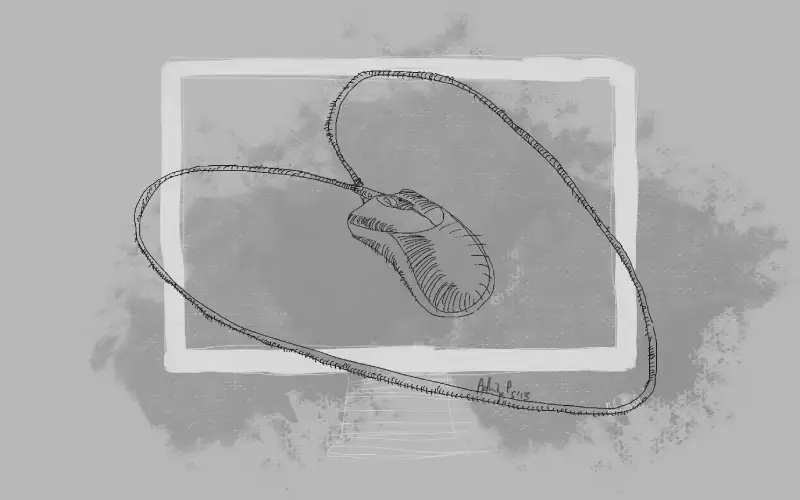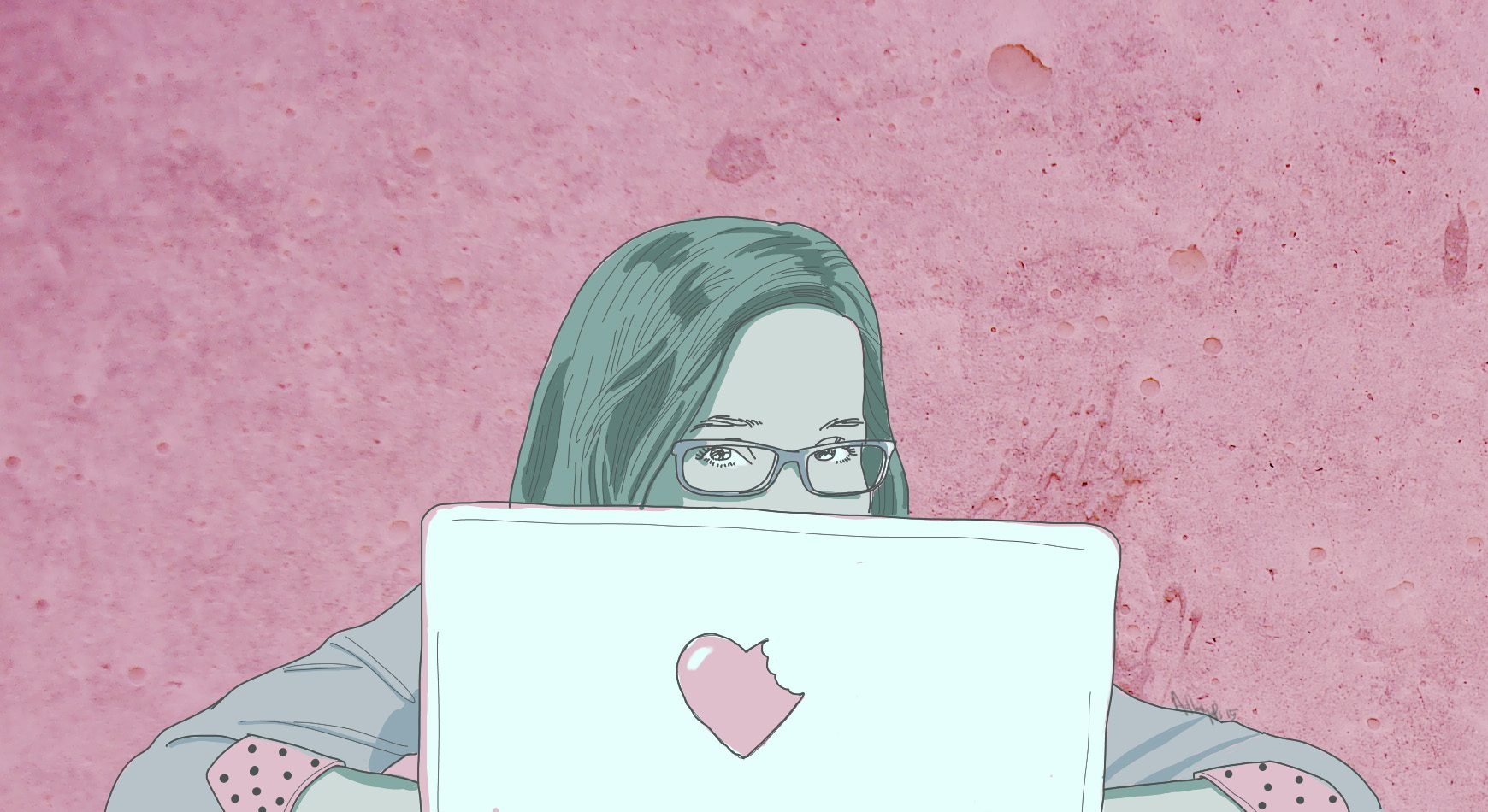Dukung dan Dengar Pasangan itu Baik, tapi Kita Bukan Terapisnya

Beberapa waktu lalu, sebuah akun Twitter mencuri perhatian publik dengan cuitannya. Katanya, laki-laki yang sedang berproses untuk meraih kesuksesan, harus didampingi perempuan dengan mental kuat dan tabah. Pasalnya, kalau pendampingnya sering mengeluh dan tidak pernah merasakan sulitnya kehidupan, malah menambah beban, bukannya mengurangi.
Sepertinya, cuitan si pemilik akun terinspirasi dari kalimat berikut:
“Di balik laki-laki sukses, ada perempuan hebat.”
Mendengar sekilas, kalimat tersebut tampak menyanjung perempuan. Namun, hal itu justru menimbulkan pemahaman keliru tentang definisi peran perempuan dalam hubungan romantis. Di sana terlihat, perempuan ditempatkan di belakang, bukan teman yang berjalan bersama dengan sejajar.
Pun, dari cuitan tadi, kita dapat menangkap perempuan “seharusnya” menjadi orang yang sabar, setia, dan siap sedia menjadi tameng, pelampiasan, serta tetap menemani laki-laki saat ia terpuruk. Di satu sisi, ini dipandang sebagai suatu hal baik, tetapi ada implikasi buruk dari penanaman pandangan ini secara terus menerus.
Pertama, perempuan dicap hebat bukan atas kegigihan dan prestasinya, melainkan karena menemani keberhasilan pasangannya dan berdiri sebagai bayangan laki-laki. Kedua, perempuan akan menanggung beban emosional yang besar bila ia saja yang diandalkan untuk membuat pasangannya menjadi lebih baik.
Baca Juga: Pacar Kamu ‘Needy’? Ini Cara Menghadapinya
Beban Emosional yang Ditanggung Satu Pihak Saja
Seseorang yang begitu banyak menginvestasikan waktunya untuk mendukung orang lain dan kesehatan mentalnya kerap lupa melakukan hal serupa pada dirinya. Padahal, kesehatan mental sendiri adalah hal yang perlu diprioritaskan lebih dulu sebelum bisa mendukung orang lain. Terlalu tinggi tekanan yang dipikul seseorang jika pasangannya mengandalkan dia sebagai sosok utama (atau bahkan satu-satunya) untuk mendengarkan dan memberi saran atas semua permasalahannya.
Seseorang yang mengalami hal ini memiliki tanggungan berupa “emotional labor”. Kepada Well + Good, terapis pernikahan dan penulis Lesli Doares menjelaskan, emotional labor merupakan sejumlah energi emosional yang dikeluarkan untuk menjaga hubungan tetap berjalan.
Istilah ini pertama kali digunakan oleh Arlie Hochschild, penulis dan sosiolog di University of California, Berkeley, Amerika Serikat, dalam bukunya The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Hochschild menggunakan frasa tersebut untuk membicarakan bagaimana orang perlu mengelola emosi mereka dalam pekerjaan untuk menangani konsumen, tetapi kemudian makna ini berkembang dan dipakai dalam dalam konteks hubungan pribadi.
Dalam artikel yang sama, psikolog klinis Ramani Durvasula menyatakan, seseorang yang mengemban emotional labor dalam hubungan, cenderung memendam emosinya sendiri. Ini dilakukannya agar tidak membebani pasangan atau temannya.
“Orang yang membawa beban emosional dalam sebuah relasi seakan berfungsi sebagai ‘terapis’ untuk partnernya yang memberikan suatu kepastian,” kata Dr. Durvasula.
Baca Juga: Sayang Pacar dan Terbuka Boleh, tapi Privasi adalah Kunci
Pasangan Bukanlah Terapis atau Penyelamat
Dalam sebuah artikel di Huffington Post, penulis buku DEPRESSION IS A LIAR: It IS possible to recover and be happy again – even if you don’t believe it right now (2015), Danny Baker menceritakan pengalamannya yang terlalu mengandalkan kekasih saat menghadapi depresi. Pada satu titik, kekasihnya itu merasa letih dan ketakutan menghadapi masalah besar Baker sehingga memutuskan mengambil jarak. Lama setelah berpisah dari kekasihnya, ia baru menyadari mengapa kekasihnya itu pergi dan dia tidak kunjung pulih: Ia telah menanamkan peran terapis dalam diri pasangannya itu.
Dalam konsultasi dengan psikolognya, Danny juga belajar selama ia hanya bergantung pada kekasihnya, dia tidak akan mendapatkan pertolongan yang sebenarnya dia butuhkan. Kata sang psikolog, memang keberadaan orang terkasih begitu berarti, tetapi ini tidak akan bisa menggantikan pertolongan profesional karena kesediaan orang terkasih dalam mendengarkan keluh kesah seseorang sebetulnya adalah bantuan tambahan.
Menurut psikiater dan founder komunitas kesehatan mental Yayasan Teman Baik Nusantara, dr. I Gusti Rai Wiguna, dalam Instagram live Magdalene “Bisik Kamis” (8/7), dalam relasi, kedua pihak harus memiliki keinginan bertumbuh bersama, bukan mencari penyelamat. Jika mentalitas itu terbawa, hubungan akan jatuh pada situasi toksik.
Lebih lanjut ia menjelaskan, penting bagi setiap orang untuk memahami permasalahan dirinya yang terbawa sejak lama sebelum menjalin relasi dengan orang lain. Jika tidak, akan ada kecenderungan dalam dirinya untuk terus mencari “pahlawan” dalam diri pasangannya untuk menebus masalah tak terselesaikannya itu. Tidak jarang juga pasangan yang disalahkan karena tidak mampu mengerti atau menghadapi kondisinya. Ini menjadi tidak adil bagi si pasangan karena ia hanya “memindahkan” masalahnya ke orang lain.
Baca Juga: ‘Toxic Relationsh*t’: Kenapa si Gadis Baik Bisa Terjebak di Relasi Toksik?
Di samping itu, ketika si pasangan gagal memenuhi ekspektasi dia untuk menjadi penyelamat, akan ada kemungkinan seseorang untuk kembali mencari sosok tersebut dalam diri orang-orang lain, sementara ia tidak benar-benar berusaha memulihkan dan merawat diri sendiri. Alhasil, permasalahan berulang dalam relasi akan terjadi.
Dalam hubungan romantis, memang selayaknya sepasang kekasih mendukung satu sama lain. Namun yang patut diingat adalah baik laki-laki maupun perempuan bukanlah problem fixer semata.
Kita tidak memiliki tanggung jawab untuk membenahi kondisi mental orang lain, termasuk pasangan kita sendiri, karena itu merupakan tanggung jawab dirinya. Jika ingin membantu pun, kita harus melihat apakah dia sendiri berusaha untuk bergerak dari keterpurukannya atau tidak.
Alih-alih hanya menemani dan dijadikan “terapis” oleh orang yang tidak mau beranjak dari “zona nyamannya” dengan sekadar mengeluh saja, kita bisa perlahan-lahan mengajaknya untuk berkonsultasi langsung dengan profesional supaya mendapat penanganan yang tepat. Bagaimanapun, kita punya keterbatasan kapasitas dalam menghadapi masalah mental pasangan dan salah-salah, kita malah bisa melakukan tindakan yang justru memperburuk kondisinya.