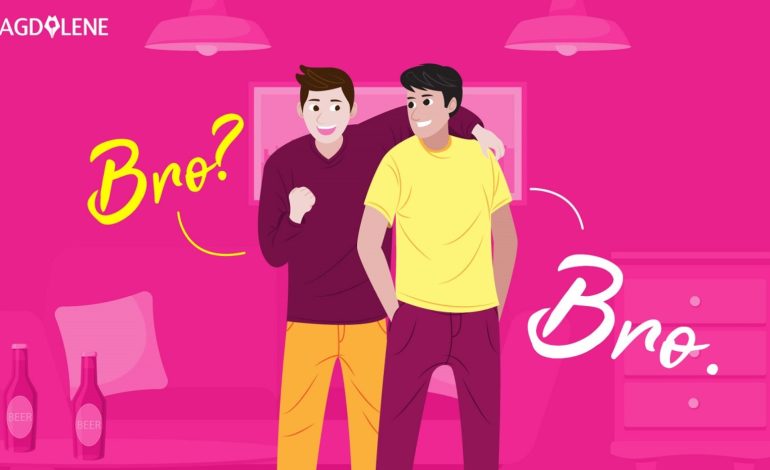RUU PKS Penting untuk Korban, Kenapa DPR Masih Tarik Ulur?
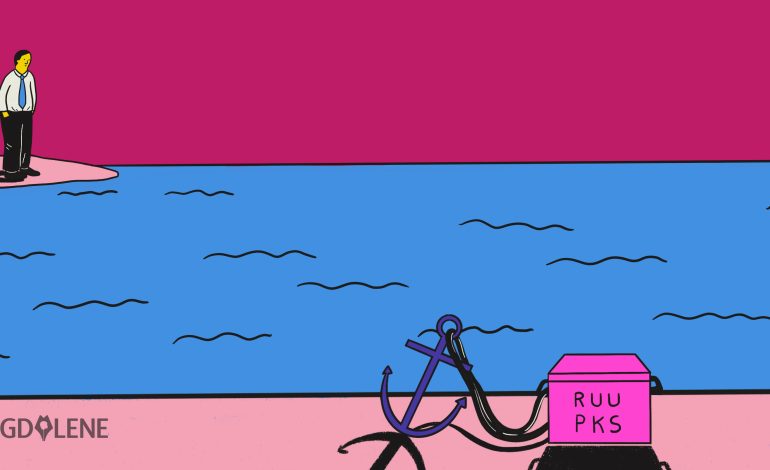
Sejak 2019 hingga Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pekan ini, pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih belum menemui titik terang. Lagi-lagi, dalih penundaan yang dipakai masih seputar RUU PKS yang dinilai melegalkan zina, LGBT, hingga pro terhadap seks bebas dan prostitusi. Perspektif agama dan moralitas diutamakan, tanpa memikirkan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban.
Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Pusat, Wido Supraha misalnya, menilai naskah akademis RUU PKS akan melemahkan peran agama, sehingga publik jadi harus melunak pada paham LGBT. Sebaliknya, ia menyebutkan, seharusnya negara berperan mendampingi masyarakat yang orientasi seksualnya LGBT agar dapat kembali “normal”, alih-alih memberi payung hukum perlindungan.
Padahal faktanya, yang diperjuangkan oleh pengusung RUU ini salah satunya adalah agar kelompok marjinal, dekaden, dan mereka yang sering dilekati stereotip miring, menjadi lebih berdaya di depan hukum. Pun, ketika terjadi tindak kekerasan seksual yang dipaksakan kepada korban, baik di dalam maupun luar pernikahan, para penyintas bisa lebih lantang bersuara. Penyintas yang dilindungi pun tak hanya perempuan, tetapi siapa pun dengan latar belakangnya masing-masing, termasuk lelaki dan anak-anak.
Baca Juga: Mengapa Korban Inses Sulit Melapor dan Keluar dari Tindak Kekerasan
Melihat urgensi RUU PKS ini, lantas apa yang membuat DPR tetap tersandera mitos-mitos absurd di atas?
Kesalahpahaman yang Dipelihara
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Taufik Basari menuturkan dalam RDPU yang disiarkan daring di TV Parlemen, (13/7), RUU PKS berusaha memberikan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk pemulihan trauma dan fisik. Hanya saja, semangat ini dicoreng oleh kesalahpahaman sejumlah kelompok masyarakat yang terus dipelihara. Padahal, kesalahpahaman seperti inilah yang justru menghambat pembahasan dan pengesahan RUU PKS.
“Menurut saya penting ya dalam proses yang berjalan ini kita juga bisa meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Caranya dengan dialog dan edukasi,” ujar politisi Partai Nasdem tersebut.
Selain itu, pembahasan RUU PKS seharusnya dikategorikan berdasarkan kamarnya masing-masing yang relevan, demi meminimalisasi kesalahpahaman. Ia merujuk pada cara berpikir pokok manusia modern yang digagas oleh Descartes, filsuf asal Prancis, yaitu clara et distincta. Artinya, gagasan ini dipahami secara jelas, terang, dan terpilah berdasarkan subjek yang dibicarakan.
Taufik juga menganalogikan RUU PKS dalam klasifikasi kelas biologi. Ia menempatkan kekerasan dalam famili dan kekerasan seksual sebagai genus. Kekerasan digunakan dalam terminologi ini lantaran yang seharusnya menjadi pembahasan di sini adalah kasus kekerasannya, bukan tentang perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan, apalagi seksualitas.
Adanya kekerasan mengakar pada sistem kekuasaan, saat pihak yang berkuasa bertindak terhadap mereka yang tidak memiliki kuasa. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan terletak pada tujuan tindakan pihak yang berkuasa ketika mereka melakukan perbuatan dengan paksaan dan tidak menerima persetujuan.
Untuk mencapai tujuan awal melindungi korban kekerasan seksual, sejatinya permasalahan ini harus dilihat dari berbagai perspektif. Bukan melulu berdasarkan moralitas dan agama yang selalu diperdebatkan di ruang rapat.
Baca Juga: Magdalene Primer: UU ITE Kriminalisasi Perempuan Korban Pelecehan Seksual
Kekerasan Seksual dan Pembahasan Consent yang Bermasalah
Selain persoalan kesalahpahaman yang menghambat pengesahan RUU PKS, pembahasan terkait consent dalam hubungan turut meninggalkan tanda tanya. Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Nurul Amalia, memaparkan dalam RDPU, kita terbiasa menormalisasi kekerasan seksual sebagai “suka sama suka”, sehingga membuat kasus serupa terus-menerus terjadi. Ia memberikan contoh dalam kasus aborsi anak, anak yang lahir tanpa ayah maupun perzinaan, hingga anak yang dibuang atau dibunuh oleh orang tuanya. Padahal, belum tentu anak-anak itu lahir dari hubungan seksual yang didasari consent orang tuanya.
Makna kata consent justru mengandung nilai dan prinsip yang harus dipegang atas dasar hak asasi manusia, bukan sekadar hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Persetujuan ini harus diberikan tanpa adanya paksaan sehingga melindungi seseorang. Perlu diketahui, pemberian consent akan menghindari seseorang dari kekerasan seksual karena aktivitas yang dilakukan tidak berlandaskan pada area abu-abu.
Lagipula, consent tidak hanya berlaku pada hubungan seksual, tetapi juga membatasi orang lain saat memegang anggota tubuh lain. Misalnya, mengelus kepala, menggandeng tangan, dan merangkul. Konsep yang “katanya” diadaptasi dari ajaran negara barat ini malah memiliki nilai positif untuk diterapkan, agar setiap individu merasa dihargai.
Masih terkait consent, Ketua Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Badriah Fayyuni mendukung pengesahan RUU PKS. Dalam hematnya, perlu lahir generasi baru yang lebih adil dan beradab dalam melihat persoalan kekerasan seksual.
“UU PKS penting ada sebagai implementasi tauhid dan akhlak mulia serta instrumen membangun peradaban bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa dan berkemanusiaan yang adil dan beradab,” ujarnya, (13/7).
Sehingga, alih-alih memperpanjang debat kusir soal RUU PKS, ia menegaskan sikapnya agar DPR punya kemauan politik untuk mengesahkan RUU ini. Sebab, RUU PKS mencakup semua bentuk kekerasan seksual dan zina, baik yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga, di lembaga pendidikan, di tempat kerja dan di ranah publik. Ini termasuk pula hubungan sesama jenis yang mengandung kekerasan seksual.

Baca Juga: Kekerasan Seksual di Rumah Sendiri, Mengerikan Tapi Didiamkan
Tawaran DPR: Hilangkan RUU PKS, Sempurnakan RKUHP
Dibandingkan mengesahkan RUU baru, Wido berpendapat lebih baik menguatkan KUHP. Keberadaan RUU PKS secara tegas telah menyebutkan lemahnya penegakkan hukum dan tidak efektifnya berbagai UU yang sudah berlaku, tetapi sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Ia menganggap penyempurnaan UU lebih efisien agar tidak membutuhkan masa sosialisasi dan pendanaan yang tidak sedikit.
Pada konteks ini, ia mengarah pada beberapa UU, seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Menurutnya, RUU PKS dilandaskan oleh perspektif feminisme, bukan ideologi Pancasila sebagaimana mestinya. Dosen Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, Henri Shalahuddin, juga menyebutkan hal serupa. Ia menilai RUU PKS condong pada ideologi feminisme yang radikal, sekularisme, dan alergi dengan nilai-nilai agama dan Pancasila.
Sesungguhnya kita perlu mengetahui bahwa feminisme telah diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Pada kebijakan tersebut disebutkan perlunya identifikasi dan pemahaman terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, beserta upaya yang diperlukan dan indikatornya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Namun, KUHP yang sudah ditetapkan belum berfungsi sebagai pelindung yang mampu menaungi korban sebab mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan justru dikriminalisasi. Sebagaimana yang terjadi pada Baiq Nuril, korban yang melakukan pembelaan diri, tetapi ditetapkan sebagai tersangka hingga harus menurunkan grasi.
Ilustrasi oleh Karina Tungari