Ancaman Terbesar Demokrasi Kita Bukan Prabowo, Lalu Siapa?
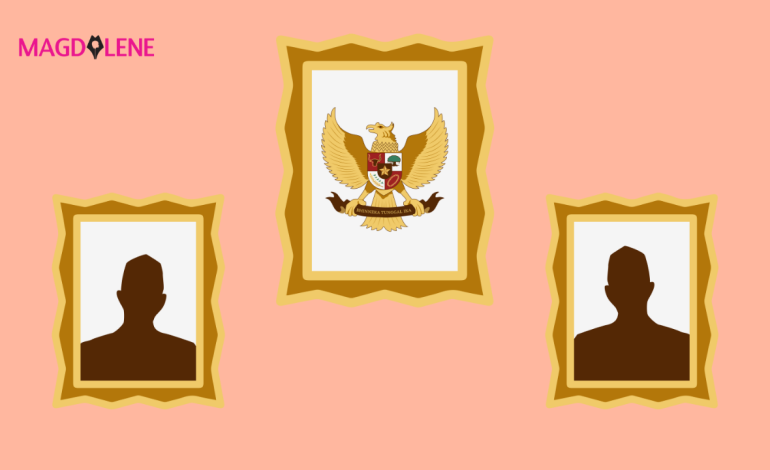
Ben Bland, eks jurnalis dan pengamat politik Indonesia pernah berkomentar soal Prabowo Subianto, sehari sebelum berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. Ia bilang, mantan jenderal angkatan darat yang maju sebagai calon presiden (capres), tidak akan serta merta mampu mengubah Indonesia menjadi autokrasi apabila ia terpilih untuk menggantikan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.
Autokrasi merujuk pada kekuasaan mutlak terpusat pada satu individu.
Ini karena Indonesia, menurut Bland, telah memiliki norma-norma demokrasi yang pada akhirnya akan membatasi kecenderungan Prabowo untuk menjadi pemimpin yang otoriter.
Sebagai seorang peneliti masyarakat sipil dan jurnalis politik, saya berpendapat bahwa argumen tersebut tidak tepat. Bland memberikan jawaban yang salah untuk pertanyaan yang salah tentang politik Indonesia saat ini.
Ini bukanlah awal dari pertarungan antara demokrasi Indonesia versus Prabowo, namun pukulan terakhir dari apapun yang tersisa di era reformasi Indonesia – periode konsolidasi demokratis sejak lengsernya pemimpin otoriter Suharto pada 1998.
Demokrasi Indonesia kini berada di bawah tekanan berat dari kekuatan oligarki yang berputar di sekitar Jokowi.
Baca juga: Skenario Terburuk Jika Prabowo Menang Jadi Presiden RI
Kekuatan Sipil Kalah dari Oligarki
Kemenangan elektoral Prabowo, berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei, nyatanya hanyalah contoh terbaru dari rangkaian kekalahan menyakitkan yang diderita oleh para pendukung demokrasi.
Vedi Hadiz dan Richard Robison mendefinisikan oligarki sebagai
“sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan pemusatan kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif”.
Di Indonesia, oligarki modern terbentuk selama ekspansi kapitalisme pasar di bawah pemerintahan otoriter Suharto (1966-1998), yang membuka jalan bagi aliansi birokrat yang berkuasa dan perusahaan-perusahaan besar untuk mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan.
Aktivis pro-demokrasi dan akademisi telah berulang kali membunyikan lonceng tanda bahaya tentang subversi oligarki terhadap demokrasi Indonesia.
Namun faktanya, iklim demokrasi pun telah memburuk di bawah kepemimpinan Jokowi, sosok yang awalnya dipuji-puji sebagai pemimpin demokratis dan reformis yang mampu mengalahkan Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019.
Jokowi secara tidak langsung telah “memimpin” berbagai upaya oligarki untuk melemahkan, atau bahkan mengacak-acak, lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia.
Pada 2019, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Para oligarki menyambut baik pengesahan UU yang kontroversial itu, kemungkinan besar karena menganggap KPK sebagai ancaman bagi kepentingan mereka.
Pada 2020, DPR juga mengesahkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang isinya menegasikan pencapaian hukum yang dibuat oleh para pendukung gerakan reformasi.
Para oligarki sektor pertambangan, yang beberapa di antaranya adalah mereka yang duduk di kabinet Jokowi, mendukung UU Cipta Kerja karena aturan tersebut cenderung mengakomodasi kepentingan mereka.
Kemunduran-kemunduran ini mendorong para akademisi lokal dan internasional untuk menyuarakan bahwa Indonesia tengah mengalami “kemunduran demokrasi” dan menghadapi “illiberal turn” (berbelok ke arah yang tidak liberal).
Yang lebih mengkhawatirkan bukanlah kecenderungan otoriter Prabowo atau citranya yang antidemokrasi, melainkan kepentingan predatoris para oligarki yang telah menekan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia untuk memajukan kekuasaan politik dan ekonomi mereka pribadi.
Baca juga: 5 Hal yang Perlu Dikritisi dari Rencana Prabowo Impor Sapi
Kemerosotan Demokrasi di Era Jokowi
Sepak terjang politik Jokowi sebelum Pemilu Februari ini menunjukkan betapa rapuhnya lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia di bawah tekanan oligarki.
Jokowi diduga telah mengintervensi Pemilu untuk memastikan Prabowo, yang maju bersama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dapat memenangkan Pilpres dalam satu putaran.
Salah satu contohnya adalah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat minimal usia capres-cawapres. Putusan tersebut telah membuka pintu bagi Gibran, yang saat ini usianya masih 36 tahun, untuk maju sebagai cawapres. Saat membuat putusan itu, MK dipimpin Hakim Anwar Usman, adik ipar Jokowi. Anwar kemudian dinyatakan bersalah atas pelanggaran etika karena tidak mengundurkan diri pascakontroversi ini.
Putusan MK yang banyak dikritik keras tersebut memicu protes publik karena jelas menunjukkan konflik kepentingan.
Pemerintahan Jokowi juga kerap membagi-bagikan bantuan makanan dan uang tunai kepada masyarakat, serta memobilisasi polisi, militer, dan pejabat pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran, dengan cara menekan para kepala desa untuk mendukung paslon tersebut.
Ini semua bukan berarti Prabowo akan melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada Jokowi dalam hal “merusak” demokrasi. Prabowo juga tampaknya akan dibatasi oleh sistem kekuasaan yang sama yang telah memengaruhi keputusan politik para pendahulunya.
Sejauh mana ia dapat memerintah sebagai seorang otokrat, tergantung pada dinamika perebutan kekuasaan di antara para elite nantinya.
Saat ini banyak yang menganggap Jokowi sebagai politikus yang handal. Namun tetap saja, dia tidak bisa lepas dari sistem kekuasaan oligarki yang membatasi pilihan-pilihannya.
Sebagai contoh, Jokowi gagal mendapatkan masa jabatan ketiganya, bukan serta-merta karena idenya bertentangan dengan Konstitusi.
Betul bahwa keinginannya itu bertentangan dengan Konstitusi, tetapi kegagalannya mewujudkan itu lebih karena usulan amandemen Konstitusi tersebut ditolak oleh Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai politik terbesar di Indonesia sekaligus partai yang menaungi Jokowi.
Jadi, pada kenyataannya, yang membuat usulan tersebut gagal adalah bukan karena kuatnya lembaga demokrasi di negara ini, melainkan adanya faktor pertarungan antarelite.
Baca juga: Jokowisme, Trumpisme, dan Dinasti Politik: Nafsu Kekuasaan yang Kikis Demokrasi
Tangan-tangan Oligarki
Manuver politik akrobatik Jokowi untuk membantu Prabowo memenangkan Pemilu juga hanya bisa terjadi utamanya karena para oligarki yang berasal dari industri pertambangan menganggap Jokowi sebagai kekuatan politik yang dapat mengakomodasi kepentingan mereka.
Garibaldi Thohir, pengusaha batu bara dan saudara dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (salah satu anggota tim kampanye Prabowo), sesumbar bahwa sekelompok pengusaha akan membantu Prabowo-Gibran memenangkan Pemilu dalam satu putaran-salah satunya melalui dukungan dana kampanye.
Para pengusaha ini, menurut Garibaldi, termasuk di antara keluarga-keluarga terkaya di Indonesia, termasuk pemilik perusahaan-perusahaan rokok terbesar di Indonesia, seperti grup Djarum (yang dimiliki oleh keluarga Hartono). Pihak perusahaan-perusahaan itu telah membantah klaim kontroversial Garibaldi bahwa mereka mendukung kampanye Prabowo.
Ini bukan berarti dua paslon lainnya bersih dari elemen-elemen oligarki.
Salah satu saingan Prabowo dalam Pilpres, Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, didukung oleh taipan media Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, yang juga memiliki bisnis di industri pertambangan dan properti.
Sementara itu, beberapa nama besar di industri pertambangan, seperti salah satu pendiri Saratoga Investama Sedaya, Sandiaga Uno, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid, mendukung capres Ganjar Pranowo.
Namun, tetap aliansi Jokowi-Prabowo yang memiliki dukungan terbesar dari kelompok oligarki. Dana awal kampanye Prabowo adalah sebesar Rp31,4 miliar, 31 kali lebih tinggi dari rival terberatnya, Anies. Diduga bahwa oligarki adalah salah satu sumber utama pembiayaan politik di Indonesia.
Wajar jika para pengamat asing merasa cemas dengan nasib Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah apa yang akan dilakukan oleh para oligarki setelah Prabowo mulai berkuasa.
Pada titik ini, demokrasi Indonesia sudah terlanjur tercabik-cabik.
Ary Hermawan, Graduate Researcher, The University of Melbourne. Rahma Sekar Andini menerjemahkan artikel ini dari Bahasa Inggris.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.






















