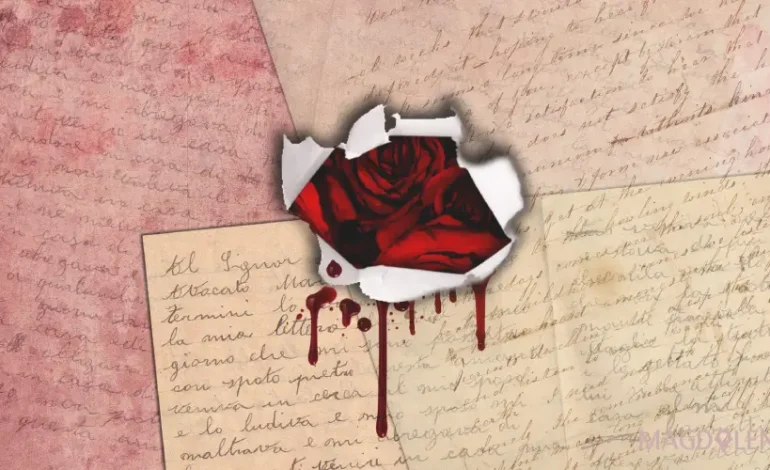Babak Baru Perjuangan LGBT di Indonesia

Gerakan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) memasuki babak baru. Kita sedang dihadapkan pada banyak peluang dan tantangan terhadap perjuangan untuk kesetaraan dan keadilan bagi orang-orang dengan keragaman orientasi seksual, maupun identitas dan ekspresi gender sebagai minoritas – yang populer atau sedang kita populerkan dengan terminologi “LGBT.”
Sebagai sebuah terminologi berbahasa asing, akronim LGBT+ (plus yang merujuk pada kelompok inklusif lainnya, yakni aseksual, queer, questioning) sebagai spektrum gender dan seksualitas penting untuk dilihat sebagai identifikasi kelompok dan gerakan yang berproses pada pendefinisian maupun perjuangan dalam konteks lokal.
Sebagai gerakan sosial, gerakan LGBT relatif muda dibandingkan dengan gerakan perempuan, buruh, tani, dan lingkungan. Maka, harus diakui bahwa gerakan LGBT belum menjadi gerakan yang solid, masih mencari pola, dan dihadapkan pada banyak persoalan, mulai dari kriminalisasi, perilaku anti-LGBT oleh kelompok konservatif berbasis agama, hingga politisasi. Diskusi tentang wacana terminologi penting, tetapi tidak mendesak mengingat ada hal lain yang lebih penting, terutama pada kriminalisasi serta penguatan gerakan LGBT. Selama belum terpenuhinya cita-cita kesetaraan dan keadilan untuk semua, LGBT dan kelompok rentan lain akan selalu punya peluang didiskriminasikan kini dan nanti.
Tulisan ini dibuat untuk merespons artikel berjudul “The dark side of LGBT awareness in Indonesia” (The Jakarta Post, 09/10/2017) yang ditulis Hendri Yulius, penulis buku Coming Out dan pengajar studi seksualitas dan gender. Membaca judul tersebut, ada kesan yang pesimis dalam melihat babak perjuangan LGBT saat ini dengan menyebutnya sebagai “sisi gelap” dan tendensi yang melemahkan terkait “LGBT-isasi”–yang bagi sebagian kalangan dilihat secara positif sebagai pengarusutamaan keragaman seksualitas.
Perkara “LGBT-isasi”
Kita patut sedih melihat betapa opresi terhadap kelompok LGBT menjadi begitu kuat. Dari upaya advokasi, kampanye, edukasi, hingga pengorganisasian yang dilakukan oleh aktivis, tak disangka dan belum pernah terjadi sebelumnya, ternyata berujung pada upaya kriminalisasi kelompok LGBT maupun orang-orang yang diduga LGBT.
Kriminalisasi itu tampak dari adanya pelarangan materi penyiaran berunsur LGBT, penangkapan, pemenjaraan, hingga upaya memasukkan relasi konsensual (romantik maupun seksual) homoseksual dewasa sebagai sesuatu yang kriminal pada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun penggunaan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah yang disebut sebagai suatu babak baru perjuangan.
Baca juga: Diskriminasi LGBT di Dunia Kerja: Tidak Melela Pun Dicerca
Kita boleh sedih, tetapi ini tanda adanya kebutuhan terhadap strategi untuk mengkonsolidasikan kekuatan dari gerakan LGBT. Sebagian dari kita melihat peluang itu pada gerakan interseksionalitas di mana kita bisa melihat representasi individu LGBT mendukung gerakan sosial lainnya. Sebab, individu LGBT pun lahir dengan beragam latar belakang dan profesi, termasuk sebagai perempuan, buruh, petani, masyarakat adat, dan aktivis LGBT sendiri yang telah berjuang mengangkat kesadaran pada keragaman seksualitas.
Pada artikelnya Hendri menulis “… recognition of sexual minorities by local LGBT activists has led to a conservative backlash at the local levels.” Hal itu memberikan kesan menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh aktivis LGBT.
Sebagian kalangan juga menganggap tidak ada relevansi dari apa yang diilustrasikan Hendri antara sikap anti-LGBT dan fenomena industri hiburan yang sebelumnya diramaikan dengan sosok lelaki feminin atau yang berpakaian perempuan, seperti Aming, Tessy, dan lainnya.
Firdhan Aria Wijaya, peneliti dengan fokus gender dan seksualitas, mengatakan: “Situasi dulu, misalnya ada Aming dan lainnya di televisi, enggak masalah. Tapi, itu bukan suatu penerimaan penuh terhadap kelompok LGBT, melainkan penerimaan semu.” Ia melanjutkan, “Justru sekarang harus lebih peka bahwa isu LGBT menjadi sesuatu yang telah muncul di permukaan dan masyarakat perlu tahu bahwa LGBT, terutama waria, bukan sekadar tontonan panggung hiburan.”
Upaya pada popularisasi LGBT bukan soal perdebatan istilah, melainkan bentuk dari fakta bahwa persoalan orientasi seksual, maupun identitas dan ekspresi gender tak lepas dari berbagai kepentingan. Adanya situasi yang mengerucut pada sentimen dan penyudutan terhadap kelompok LGBT adalah potret di negeri ini yang menjadikan kelompok minoritas sebagai sasaran empuk yang bernuansa ekonomis dan politis, terutama oleh para kapitalis dan politis konservatif sayap kanan. Hal itu harus menjadi alarm dan perhatian bagi negara, aktivis di berbagai sektor dan isu, media, akademisi, dan pihak-pihak pelopor perubahan lain, untuk jeli melihat dan merespons pola konflik. Apalagi, Indonesia akan menghadapi kondisi krusial terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019.
Ketika persoalan LGBT mengemuka dan dijadikan “mainan” politisi, maka kita dapat memandangnya sebagai bagian dari pergulatan. Bahwa kita sudah memiliki ruang pertarungan itu dan sedang berusaha merebutnya. Sehingga kita justru patut bingung ketika ada seorang gay atau lelaki homoseksual yang mengaku akademisi studi gender dan seksualitas serta terlibat untuk memopulerkan istilah LGBT selama beberapa tahun belakangan – merasa bingung (“quite perplexed”) ketika ada teman yang mengategorikannya dengan label LGBT. Kita perlu bijak melihat LGBT sebagai suatu payung yang maknanya sedang diperjuangkan dan digunakan untuk menghubungkan kita dengan gerakan global terhadap hak-hak terkait keragaman gender dan seksualitas.
Baca juga: Seksualitas dan Agama: Persetubuhan di Mata Tuhan
Kita harus mengakui bahwa isu kelas atau ego sektoral dalam gerakan LGBT ini adalah nyata. Itu adalah hal yang selalu ada di dalam masyarakat yang terfragmentasi seperti sekarang. Untuk membangun gerakan yang solid, fragmentasi itu seharusnya tidak lagi dipandang sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan, melainkan keunikan yang menegaskan keragaman dan sikap saling mengisi. Kelompok transgender dengan identitas dan ekspresi gendernya tentu berbeda dengan kelompok homoseksual kelas menengah urban yang berpendidikan tinggi.
Perkara Refleksi & Jawaban
Pada bagian akhir artikel, Hendri mengutarakan dua pertanyaan yang terdengar bagai tantangan, yaitu perkara terminologi yang lebih lokal dan politik seksual identitas.
Persoalan menjadi lebih kontekstual daripada memperdebatkan terminologi. Kata dapat diklaim kembali dan bersifat dinamis maupun politis terhadap pemaknaan. Yang diperlukan adalah bagaimana memperjuangkan itu untuk dapat dipahami sebagai representasi dan gerakan perjuangan kelompok yang minor, ditindas, dipinggirkan, dimiskinkan, dilemahkan, dan dijadikan target oleh penguasa.
Jadi, ketika muncul pertanyaan adakah cara untuk mengubah label yang terlanjur tertimpa pada LGBT dan mengadopsi terminologi yang lebih lokal, kita bisa menjawab bahwa itu ada dan banyak. Itu terbukti secara jelas dalam catatan sejarah yang tercecer kalau orang-orang LGBT selalu ada di setiap masa dan tempat. Apakah itu perlu digali? Ya. Tetapi, apakah itu perlu dijadikan sebagai pengganti pada padanan istilah “LGBT”? Bisa jadi itu tak perlu mengingat banyak penamaan dengan bahasa lokal/adat itu telah hilang dan tak lagi punya konteks dengan banyak sebab, mulai dari kolonialisme, monoteisme, modernisme, hingga periodisasi rezim di Indonesia yang mengalahkan tradisi dan budaya lokal maupun mereduksi peran dan makna itu. Kita tak ingin sekadar merangkul romantisme sejarah atau terbuai dengan glorifikasi cerita masa lalu tentang masyarakat atau komunitas adat tertentu menghargai kelompok LGBT.
Maka, yang lebih penting daripada menemukan dan mengadopsi terminologi lokal, adalah memikirkan dengan teliti relevansi dan konteks beragam terminologi lokal tersebut. Bagaimana komunitas tertentu memiliki cara pandang untuk menerima dan menghargai kelompok LGBT? Bagaimana suatu masyarakat bisa memberikan peran strategis kelompok LGBT? Bagaimana kelompok LGBT pada suatu masa dapat bertahan dan begitu kuat mengakar sebagai bagian dari kehidupan? Bagaimana kelompok LGBT mengalami reduksi peran dan makna, lalu akhirnya hilang? Dengan begitu, kita bisa melihat konteks sejarah dan bahasa secara kritis sebagai kritik. Bukan hal yang seharusnya ditantang untuk sekadar dijawab dan ditemukan.
Saat ini, memperdebatkan istilah menjadi terkesan dangkal dan tak krusial. Penemuan terhadap istilah yang dianggap lebih lokal bisa jadi akan semu dan sia-sia belaka ketika makna dari perjuangan kata itu tak dapat dihubungkan dengan konteks perjuangan saat ini dan yang akan datang.
Kedua, tentang politik identitas seksual. Menarik ketika mendengar komentar seorang kawan yang mengategorikan dirinya waria dan aktivis untuk organisasi waria. Ia bilang “Gue waria! Gue enggak mau dibilang trans atau transpuan atau transgender/trans-seksual. Buat gue konteksnya beda. Tetapi, apa dengan begitu gue menolak dikelompokkan LGBT atau enggak bisa berjuang bersama dengan gerakan LGBT? Meskipun enggak ada huruf ‘W’ yang mewakili waria dalam terminologi LGBT?”
Baca juga: Sejarah Gerakan dan Perjuangan Hak-hak LGBT di Indonesia
Perspektif akademis memang sebaiknya tidak terlepas dari pengalaman aktivis. Seperti yang diungkapkan Evelyn Blackwood, akademisi yang banyak menulis isu lesbian. Ia mengatakan, “Apakah para peneliti menyadari kompleksitas relasi antara budaya lokal dan global tanpa menciptakan dikotomi yang hierarkis pada praktik yang tradisional-modern dan yang asli-global?”
Maka, pada babak baru perjuangan ini, kita tidak lagi mencari padanan kategori maupun label. LGBT di Indonesia bisa punya makna dan definisi yang berbeda. Namun, babak yang jauh lebih rumit dan menantang ini menuntut kita untuk mengangkat persoalan LGBT menjadi lebih humanis dan memikirkan bagaimana melakukan kerja-kerja yang strategis untuk konsolidasi yang harmonis dalam menghimpun kekuatan pada pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak LGBT sebagai manusia, warga negara, dan minoritas.
Tidak selalu ada strategi yang berlaku dan berhasil sama, sehingga cara strategis untuk memperkuat gerakan LGBT adalah memulainya dengan cara apa pun dan terus merespons secara bijak dan strategis sesuai dengan perubahan kondisi. Ini bukan menjadi beban bagi para aktivis yang telah bertempur sedemikian hebat di akar rumput dalam melakukan pendampingan kawan-kawan yang dikriminalisasi hingga advokasi kebijakan di parlemen. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk kita melakukan agitasi, edukasi, dan mengorganisir diri secara serempak.
Di sisi lain, kini LGBT telah bertransformasi menjadi kategori, pilihan individu maupun organisasi, gerakan, serta identitas politik yang secara global diperjuangkan sebagai agenda kemanusiaan. Kita perlu mendukung dan menguatkan konsolidasi gerakan sosial LGBT ini karena kontribusinya pada kondisi demokrasi di Indonesia kini dan nanti. Sebab, demokrasi bukan soal suara terbanyak, melainkan bagaimana suara dan kepentingan minoritas dapat didengar dan diakomodasi, termasuk LGBT.