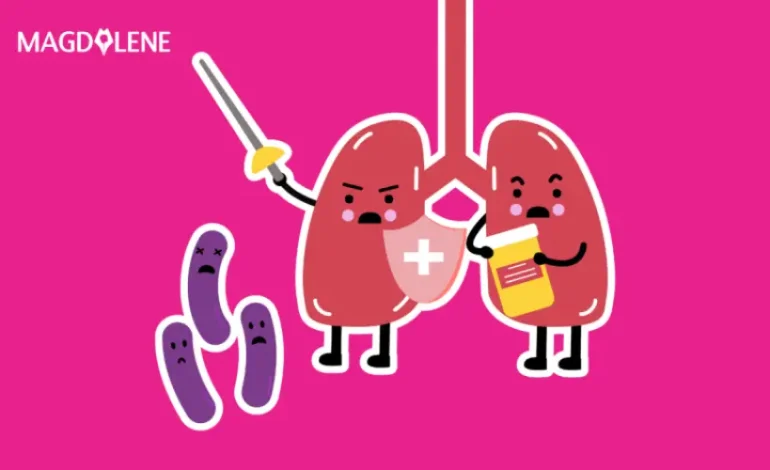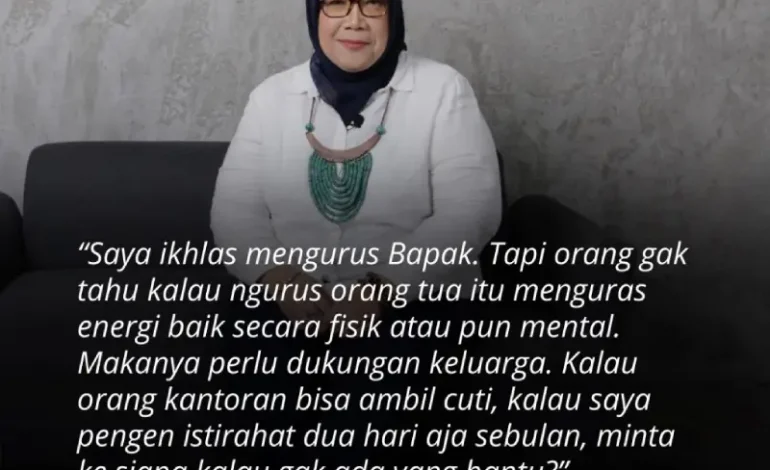‘Panduan 101’ Berkomunikasi dengan Anak Autistik: Agar Stigma Makin Terkikis

Autistik merupakan kondisi yang ditandai dengan adanya gangguan saraf otak (neurologis) yang berpengaruh pada tiga area dalam perkembangan awal anak, yaitu bahasa, perilaku, dan sosial.
Kondisi yang khas ini membuat anak autistik kerap menghadapi stigma di masyarakat. Bahkan di lingkungan pendidikan pun, selain akses layanan yang belum merata dan memadai, beberapa guru belum sepenuhnya berperspektif inklusif, sehingga anak dengan autisme semakin diperlakukan secara diskriminatif.
Hal ini terlihat jelas dalam beberapa kasus. Sebut saja dugaan guru yang menganiaya anak didik disabilitas di Makassar, Sulawesi Selatan atau kekerasan verbal oleh guru pada anak autis di Sekolah luar Biasa (SLB) di Surabaya, Jawa Timur.
Dari kasus-kasus tersebut, tampak jelas beratnya perjalanan individu autistik dalam mendapatkan layanan yang mereka butuhkan atau sekadar mendapatkan penerimaan dari publik.
Apa yang sebenarnya dibutuhkan?
Baca juga: Autisme pada Perempuan Dewasa Kerap Luput Terdiagnosis
Instrumen yang tepat
Saat orang tua datang ke pihak yang dianggap lebih ahli, seperti dokter, psikolog, guru hingga terapis, sebagian dari mereka sering menggunakan instrumen standar untuk menilai anak autistik. Instrumen standar ini pada dasarnya dirancang untuk individu non autistik sehingga tidak pas jika digunakan untuk anak autistik.
Menurut Adriana Ginanjar, Ketua Yayasan Autisma Indonesia, kemampuan kognisi anak autistik belum terukur melalui tes inteligensi standar. Situasi tes ini tidak cocok dengan karakter anak autis karena menuntut respons yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Anak autis juga bisa kewalahan dengan input sensori, merasa tidak nyaman dengan situasi tes serta merasa asing dengan orang baru (penguji). Masalah perilaku seperti hiperaktif, tantrum, gerakan yang berulang membuat anak autis tidak dapat menyelesaikan tes dengan baik. Tes-tes standar juga tidak mempertimbangkan apakah terdapat kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak autis seperti kemampuan melukis, menulis puisi, memasak atau berenang.
Baca juga: Anak-anak dengan Autisme Hadapi Masalah Akses Pendidikan
Ada juga piramida sistem saraf dari Mary Sue Williams dan Sherry Shellenberger, terapis okupasional asal Amerika Serikat (AS). Piramida ini menggambarkan bahwa proses tumbuh kembang anak yang optimal, terjadi ketika semua bagian pada dasar piramida berkembang dengan baik. Baru kemudian bergerak ke atas hingga mencapai puncak piramida yaitu pembelajaran yang lebih akademik. Piramida ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan anak autistik.
Pada individu autistik, proses perkembangan bisa berlangsung kompleks dan tidak selamanya berjalan berdasarkan alur piramida. Ada individu autistik yang masih perlu latihan dengan indra peraba namun menjadi seorang ilmuwan. Ada pula seorang autistik yang menjadi pembicara di berbagai forum namun masih kesulitan mengancing bajunya atau tidak bisa bersepeda.
Woo Young Woo dalam serial televisi Korea Extraordinary Attorney Woo, adalah gambaran dari kondisi ini. Woo adalah seorang pengacara autistik yang tidak bisa melewati pintu berputar di kantornya, pintu yang bisa dilalui dengan mudah oleh individu neurotipikal. Ketidakmampuannya dalam melewati pintu berputar justru berbanding terbalik saat di persidangan. Dia bisa sangat garang sehingga memenangkan banyak kasus.
Dalam kehidupan nyata, ada Temple Grandin, ahli Ilmu Hewan ternama di Colorado State University, AS. Grandin masih berlatih mendekati pintu-pintu otomatis di pusat perbelanjaan sama seperti Woo, meski ia telah meraih gelar profesor.
Kategorisasi yang Hati-hati
Tak dimungkiri bahwa anak autistik harus menjalani serangkaian terapi dan juga latihan agar dapat mandiri dalam keseharian. Namun, individu autistik memiliki kondisi yang khas yang tidak sama satu dengan lain. Maka dari itu, kategorisasi autis juga mesti dipandang secara bijak.
Autistik non verbal, misalnya, dianggap berada pada kategori yang parah, padahal beberapa autistik non verbal justru menunjukkan keterampilan dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ada pula autistik yang dapat berkomunikasi secara verbal, namun masih memiliki tantangan sensori seperti peka terhadap suara dan tidak nyaman di keramaian.
Salah satu penentuan kriteria autisme terbaru memakai Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) yang disusun oleh Asosiasi Psikiatri Amerika. Tujuannya agar terdapat satu sistem klasifikasi diagnostik. DSM-5 ini dianggap sebagai kemajuan dari DSM sebelumnya yang merinci autisme ke dalam beberapa kategori. Pada DSM-5 ini, autisme dengan berbagai gejala digambarkan berada pada payung besar yang disebut dengan spektrum autisme.
Penerimaan Itu Penting!
Kondisi individu autistik sering kali dilihat sebagai keanehan alih-alih perbedaan. Pendekatan dan model medis dalam penanganan anak autis lebih cenderung melihat mereka sebagai sebuah kekurangan dan memandang anak autis sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, bukan bagian dari kepribadian atau jati dirinya.
Karena itu, kita memerlukan perspektif menyeluruh untuk memandang kondisi anak autistik dengan mengidentifikasi kebutuhan serta potensinya serta menyusun program layanan. Inklusifitas adalah cara pandang yang didasari oleh penerimaan. Jika penerimaan tidak dihadirkan, maka orang-orang yang terlibat di dalam proses tumbuh anak autis, seperti guru, keluarga bahkan orang tuanya sendiri, akan mengalami rasa frustasi berkepanjangan.
Baca juga: Kenapa ADHD Berisiko Overdiagnosis?
Di sisi lain, terdapat stigma di masyarakat yang masih memandang individu autistik sebagai kecacatan atau karma karena perbuatan buruk orang tuanya. Masyarakat juga kerap meragukan kapasitas orang tua ketika anak autisnya tidak mengalami perkembangan.
Perspektif inklusif ini nyatanya memang nyaris absen dalam ruang-ruang sosial kita. Berpandangan inklusif berarti dapat menerima, merangkul dan mengikutsertakan anak dengan autisme dalam kehidupan sehari-hari.
Kita membutuhkan sosialisasi dan advokasi untuk menciptakan penerimaan di masyarakat luas. Sebelum itu, penerimaan mesti hadir dari orang tua, kerabat hingga pihak yang dijadikan mitra oleh individu autistik.
Arida Erwianti, Dosen, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kusuma Negara
Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.