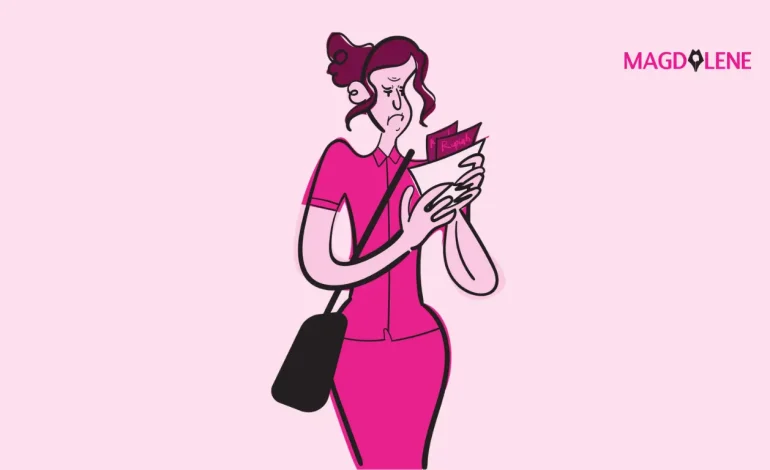Pekerjaan Rumah Usai PP tentang Dana Bantuan Korban Sah
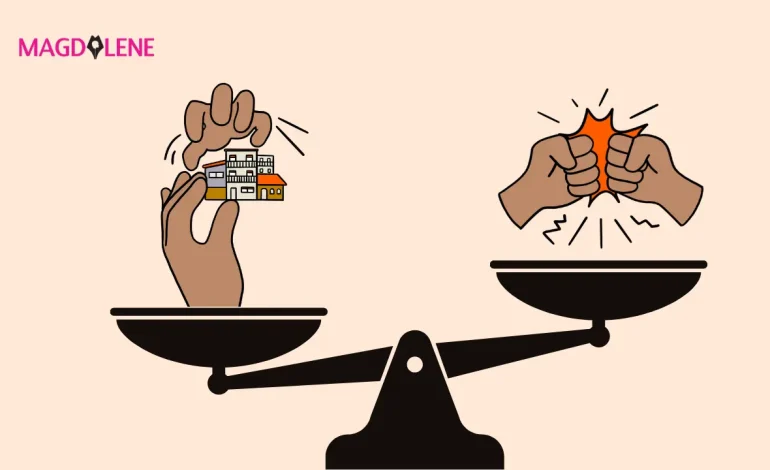
Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), (18/6). Aturan ini diharapkan jadi jaring pengaman ketika aset pelaku tak cukup membayar restitusi—hak ganti kerugian yang dijamin UU TPKS.
Namun, di lapangan, korban kekerasan seksual kerap kesulitan mengakses restitusi. Stigma masyarakat menjadi salah satu penghalang utama.
“Korban awalnya enggak mau mereka pakai restitusi, karena masyarakat itu sudah justifikasi bahwa, ‘kamu mau laporkan kasusmu karena kamu mau dapat duit,’” kata Novita Sari Novelis dari Forum Pengada Layanan (FPL) saat gelar wicara penayangan film dokumenter Hidup. Lagi. Kembali. di Taman Ismail Marzuki, (8/8).
FPL, kata Novita, berupaya mengedukasi korban dan keluarga bahwa restitusi adalah hak yang dijamin hukum. “Itu yang coba kami diskusikan dengan korban dan keluarga. Bagaimana sebenarnya restitusi itu tidak ada hubungannya dengan kamu minta duit (melainkan menuntut hak),” ujarnya.
Selain stigma, proses hukum yang panjang dan melelahkan juga membuat korban mengabaikan hak ini. “Di dalam kondisi korban sendiri (dia harus) berdamai atau bisa menerima kekerasan yang dia alami, (di lain sisi) dia harus menghadapi atau punya energi lebih untuk dia mendapatkan haknya yang lain, misalnya restitusi,” kata Novita.
Restitusi sendiri sebenarnya sudah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, tepatnya di Pasal 30 sampai dengan 38. Kendati sudah dijamin, pemenuhan restitusi masih menemui hambatan di lapangan sebagaimana yang diceritakan oleh Novita. Selain itu, pasal-pasal terkait restitusi di dalam UU TPKS pun dinilai masih memiliki celah.
Baca juga: Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan Victim Trust Fund Masih Hadapi Tantangan
Celah Hukum Restitusi UU TPKS
Restitusi dinilai sebagai produk progresif di dalam UU TPKS. Sebab, restitusi dijadikan sebagai pidana pokok yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Namun, pengaturan terkait restitusi masih punya celah yang memungkinkan pelaksanaannya tidak maksimal.
Ade Solehudin, Jaksa di Kejaksaan Agung, memaparkan setidaknya ada tiga permasalahan di dalam UU TPKS.
Pertama, Pasal 16 Ayat (1) UU TPKS mewajibkan hakim menetapkan besarnya restitusi dalam amar putusan. Menurut Ade ketentuan ini bisa berpotensi menimbulkan masalah karena jika besaran restitusi tidak dicantumkan hakim di dalam putusan, maka korban tidak punya hak untuk menagih restitusi.
Kedua, ketentuan Pasal 16 Ayat (2) huruf c UU TPKS dinilai ambigu. Pasal itu memberi kewenangan kepada hakim untuk merampas keuntungan atau aset hasil kejahatan, tetapi pembatasan lewat frasa “yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual” dinilai dapat menyulitkan eksekusi. Ade menjelaskan, frasa tersebut menimbulkan kebingungan penyidik dalam membuktikan apakah aset yang akan disita bersumber dari tindak kejahatan kekerasan seksual.
“Harus aset yang berasal dari tindak kejahatan seksualnya itu. Penyidik bingung ketika akan menyita. Asetnya ini ada kaitannya dengan kejahatan itu atau tidak,” tutur Ade di gelar wicara.
Ade menekankan perlu adanya kesepahaman bersama antar penegak hukum supaya terdapat kejelasan dari frasa tersebut. Ia memandang frasa di Pasal 16 Ayat (2) perlu diperjelas supaya proses penyitaan tidak terhambat oleh kebingungan polisi. “Paling tidak frasanya gini, lah: ‘Yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan TPKS’ misalnya. Kan enak kalau ada frasa-frasa seperti itu.”
Ketiga, ketidakharmonisan antara Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 31 Ayat (3) UU TPKS. Pasal 31 Ayat (3) UU TPKS memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menyita aset pelaku sebagai jaminan restitusi. Namun, tidak disebutkan kalau aset yang disita harus dibuktikan berasal dari tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Ayat (2). “Ini tarik menarik, nih. Mana yang mau dijadiin pedoman?”
Selain substansi hukum, imbh Ade, implementasi UU TPKS juga kerap menemukan tantangan saat pelaksanaan putusan. Misalnya, ketika hakim memutus korban berhak mendapatkan restitusi, tapi ternyata sejak awal kasus bergulir tidak dilakukan penyitaan aset pelaku.
“Nah, pekerjaan rumahnya apa? Kalau sejak awal (penyidikan) itu tidak dilakukan penyitaan, tau-tau di putusan ada amar restitusi, jaksa ngejar-ngejar (penyitaan) dulu,” papar Ade.
Idealnya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, ketika penyidikan dimulai seharusnya restitusi sudah mulai dihitung. “Artinya (penghitungan restitusi) ada dalam berkas perkara. Ada di dalam dakwaan jaksa. Ada di dalam tuntutan jaksa dan terakhir, ada di dalam amar putusan hakim.”
Tantangan selanjutnya yang ditemui di lapangan adalah harta kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi biaya restitusi. Jika terjadi hal seperti ini, maka semestinya berdasarkan Pasal 35 UU TPKS korban berhak mendapat kompensasi dari negara lewat skema dana bantuan korban.
Setelah menunggu kurang lebih tiga tahun sejak UU TPKS disahkan, akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PP DBK). Namun, PP ini masih meninggalkan beberapa catatan dari Koalisi Masyarakat sipil yang terdiri dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), FPL, dan sejumlah organisasi lainnya.
Baca juga: Tiga Tahun UU TPKS: 4 Pekerjaan Rumah yang Belum Lunas
Catatan PP DBK
Penantian panjang hadirnya PP DBK akhirnya terbayarkan. Walaupun perlu menunggu selama tiga tahun lamanya.
Dana Bantuan Korban atau DBK merujuk pada definisi PP DBK adalah dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 7, DBK dimanfaatkan untuk pemberian kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar kepada korban. DBK juga dapat dimanfaatkan untuk pemberian pendanaan pemulihan.
Namun, masih terdapat beberapa catatan dari PP DBK oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Pertama, PP DBK dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan di lapangan, terutama terkait peran aparat penegak hukum dalam pelaksanaan restitusi. Koalisi menekankan pentingnya koordinasi yang lebih solid antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kejaksaan dalam menghitung aset pelaku serta memproses sita lelang, yang menjadi kunci efektivitas restitusi.
PP ini juga belum mengatur secara jelas mekanisme eksekusi restitusi. Korban atau ahli waris masih dibebani melapor ke pengadilan jika restitusi tak diterima, padahal kewajiban itu seharusnya menjadi tanggung jawab jaksa sebagai eksekutor. Selain itu, tidak ada batas waktu untuk sita lelang jaminan, yang berpotensi memperlambat proses.
Kedua, PP DBK belum mengatur secara jelas sumber pendanaan DBK dari anggaran negara. Padahal, kejelasan pendanaan sangat penting untuk menjamin dukungan finansial bagi korban. ICJR merekomendasikan penggunaan persentase tertentu dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penegakan Hukum menjadi opsi pendanaan.
Ketiga, penggunaan DBK untuk pemulihan masih belum memiliki kejelasan. Meski PP DBK memperluas cakupan pendanaan hingga pendanaan pemulihan, mekanisme pengajuan ke LPSK dan batas waktunya tidak diuraikan. Rincian jenis pemulihan yang bisa didanai pun tidak diatur, sehingga perlu diperjelas apakah mencakup pemulihan dalam UU TPKS, PP No. 30 Tahun 2025, atau bahkan lebih luas.
Keempat, PP DBK belum mengakomodasi kebutuhan pemulihan korban yang bersifat mendesak. Saat ini, dana kompensasi dan pemulihan baru bisa diakses setelah melalui proses restitusi yang panjang, sementara korban kerap harus menanggung sendiri biaya pemulihan. Koalisi mendorong agar DBK dapat diakses sejak awal, tanpa menunggu restitusi, untuk membiayai pemulihan mendesak yang tidak tercakup dalam program layanan kementerian atau lembaga.
“Bagaimana DBK ini nantinya jangan berkaca sama restitusi yang prosesnya rumit, kemudian panjang. Sementara kebutuhan untuk pemulihan korban ini berlangsung terus menerus,” harap Novita.
Baca juga: Penerapan UU TPKS Jalan di Tempat, Di Mana Peran Pemda?
Mendorong Koordinasi Antar-Lembaga
Melihat berbagai catatan penting tersebut, Koalisi mendorong sejumlah langkah untuk memperkuat implementasi DBK ke depan. Di antaranya, meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkoordinasi. Tujuannya agar memperjelas alokasi anggaran negara untuk DBK.
LPSK bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) juga perlu memperjelas konsep pendanaan pemulihan, yang mencakup semua aspek pemulihan korban. Kemudian, Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan berkoordinasi sejak awal proses penyidikan kasus kekerasan seksual untuk menilai aset pelaku sebagai jaminan restitusi.
Terakhir, aparat penegak hukum—mulai dari Kepolisian, Penyidik, Penuntut Umum, hingga Hakim—bersama lembaga terkait seperti LPSK, akademisi, dan masyarakat sipil, perlu secara masif menyosialisasikan hak restitusi dan Dana Bantuan Korban kepada korban TPKS.