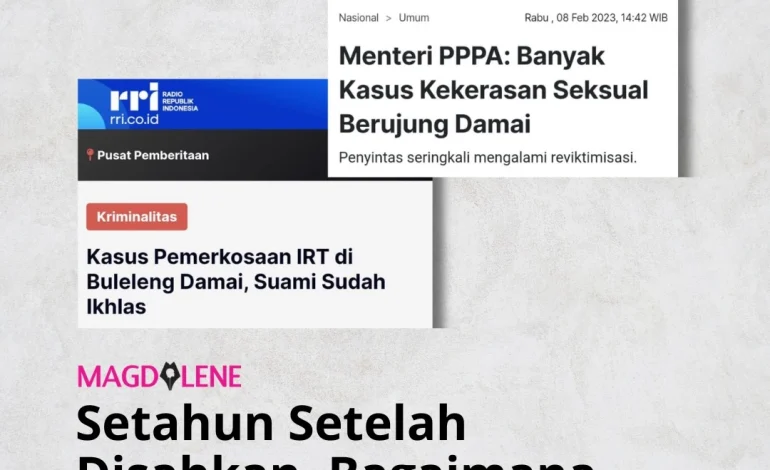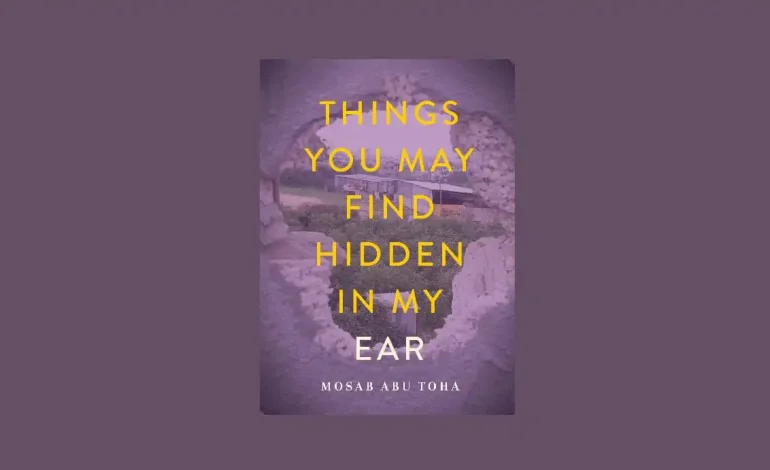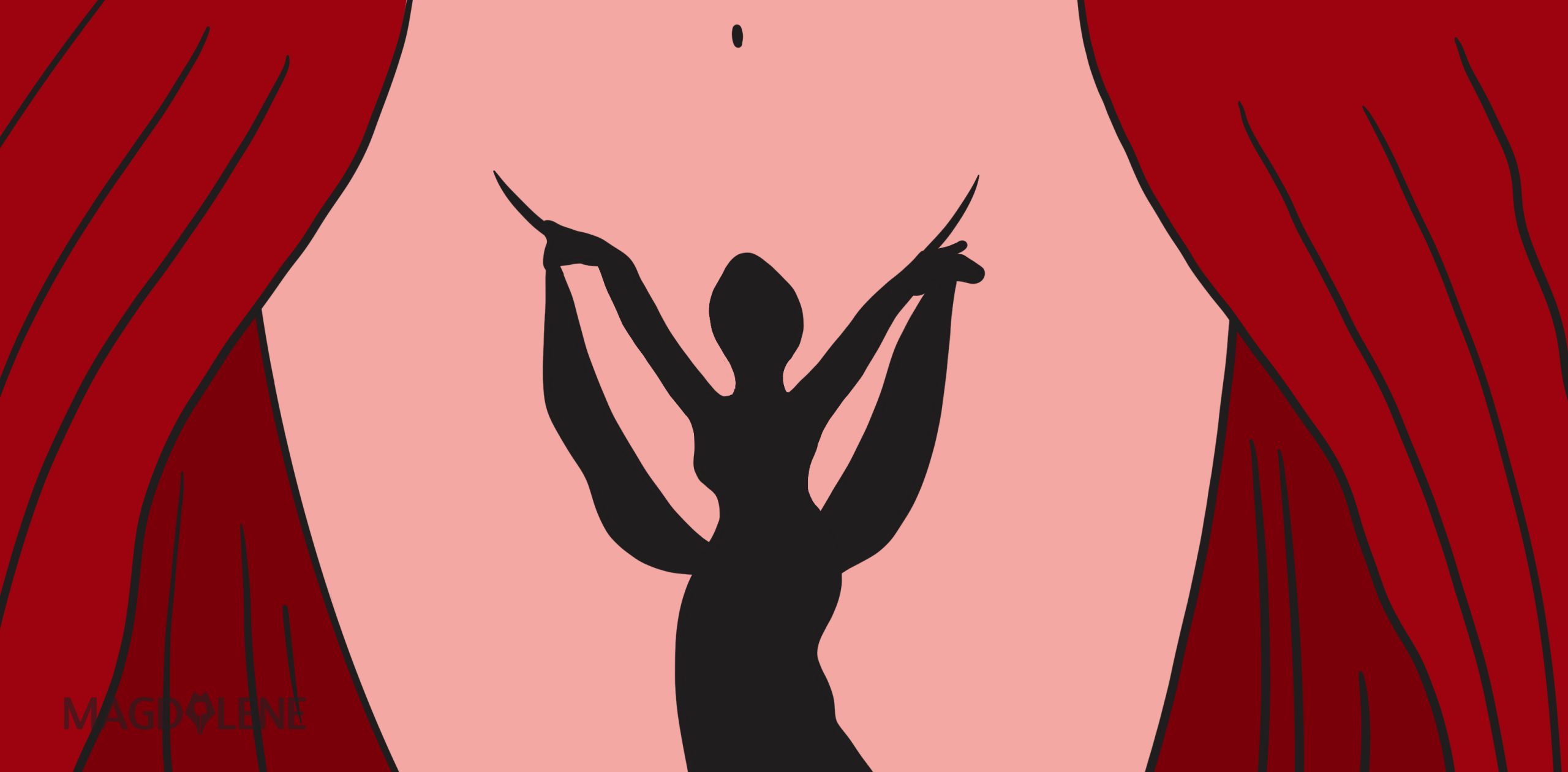Di antara teman-teman seusianya yang berkeluarga, “Ista”, 47, masih ingin melajang. Katanya belum ada keinginan untuk menikah, walaupun Ista punya pasangan dan sudah berpacaran selama enam tahun. Pasangan Ista juga enggak menuntut menikah, dan relasi yang dijalani enggak butuh usaha besar untuk mempertahankan hubungan. Misalnya, mereka enggak mesti bertukar kabar, atau membicarakan relasi melulu setiap berkomunikasi.
“Saya enggak kepikiran pengen mengakhiri masa lajang. Selama pacaran pun enggak ada perasaan mau hidup bersama,” tutur Ista. “Pacarannya udah bukan kayak anak muda yang baperan. Rasanya tetep kayak single, kayak punya sahabat aja. Paling diskusi soal kerjaan.”
Ia mengaku merasa bebas dan menikmati masa-masa lajang. Di sela kesibukan sebagai human resources di sebuah bank, Ista berkumpul dengan teman-teman sebaya yang kebetulan melajang. Misalnya makan bareng, nonton bioskop, atau sekadar ngobrol di akhir pekan maupun sepulang kerja.
Teman-teman itulah yang Ista anggap akan menemani di hari tua, hingga sepakat untuk tinggal berdekatan supaya saling menjaga. Sebenarnya, Ista juga melihat peran tersebut dalam pernikahan—hidup bersama dan saling menemani. Namun, baginya “teman hidup” enggak mesti hadir dalam sosok pasangan. Cukup dengan teman-teman yang sefrekuensi.
Keinginan Ista untuk melajang salah satunya didukung oleh pekerjaan layak yang dimiliki. Ia juga terbiasa melakukan segala sesuatu sendiri sehingga enggak merasa ingin punya pasangan. “Aku udah happy sama teman-teman,” kata Ista.
Keluarganya juga enggak mempermasalahkan pilihan Ista untuk melajang. Dari tiga bersaudara, hanya kakak pertama Ista yang menikah—itu pun di usia 40 tahun. Meski demikian, bukan berarti perempuan lajang bebas dari konstruksi sosial yang mengharuskan untuk menikah.
Baca Juga: Melajang Bukan Karena Tak Ketemu Jodoh, Tapi Karena Jodoh Tak Sesuai Harapan
Menghadapi Konstruksi Sosial
Ruby Astari, 42, memutuskan berhenti mencari pasangan. Sebab, hubungan romantis terakhirnya pada 2018 cukup traumatis, sehingga butuh waktu lama dan seleksi lebih ketat jika nantinya akan kembali membuka diri.
Namun, pilihan Ruby enggak membuat ibu dan adiknya menanyakan “kapan nikah”, ataupun menerima komentar soal status dari orang-orang di sekitar. Sampai pada 2021, saat beberapa netizen laki-laki menghakimi status Ruby.
Waktu itu, Ruby berkomentar di salah satu video tentang kehidupan perempuan lajang, yang dipublikasikan Narasi TV di YouTube. Ruby bilang ingin menikah karena pilihan pribadi, bukan perintah orang lain. Ia mengaku sudah bahagia dengan diri sendiri, dan menurutnya kebahagiaan adalah tanggung jawab pribadi.
Komentar Ruby disambut respons beberapa netizen laki-laki. “Ada yang bilang saya membenci laki-laki, anti pernikahan, enggak butuh laki-laki dan keluarga, sampai nyinggung organ reproduksi dan mengatakan pilihan saya ini tanda-tanda dunia kiamat,” ujar Ruby.
Tanggapan netizen mencerminkan realitas di masyarakat, yang memandang pernikahan sebagai sesuatu yang harus dilakukan setiap orang, bukan pilihan. Terutama perempuan lajang yang kerap distigma.
Seperti Bu Tedjo (Siti Fauziah) dalam Tilik (2018), yang julid dengan karakter bernama Dian—perempuan muda di desa—karena mengejar karier ketimbang memprioritaskan pernikahan. Bu Tedjo kemudian mempertanyakan pekerjaan Dian, dan menyimpulkan ia senang menemani laki-laki sebagai pekerjaan sampingan sehingga punya banyak uang. Sementara anak Bu Lurah, laki-laki yang juga lajang, enggak diperlakukan seperti itu.
Hal itu merefleksikan budaya patriarki dan masyarakat heteronormatif yang meliyankan perempuan lajang. Sebab, masyarakat melabelkan keberhasilan dan keberhargaan perempuan berdasarkan perannya di keluarga, sebagai istri dan ibu—yang juga mendorong perempuan untuk membangun hidup rumah tangga. Ini sekaligus didukung oleh konstruksi gender tradisional, yang menekankan kepedulian dan ketergantungan terhadap laki-laki sebagai tolok ukur feminitas.
Sementara perempuan lajang dianggap kesepian, enggak kompeten mengurus diri, dan enggak punya tanggung jawab selain pada dirinya—sehingga diharapkan bisa melakukan pekerjaan lebih. Yang tak disadari, beberapa hal itu merupakan diskriminasi yang dihadapi perempuan lajang. Belum lagi tanggungan biaya hidup sendiri yang lebih mahal. Seperti tempat tinggal, kesehatan, dan pajak penghasilan—karena tak ada tunjangan negara yang diberikan untuk pasangan dan anak.
Di samping itu, dengan kentara kita bisa melihat perbedaan tekanan, antara perempuan dan laki-laki lajang. Saat laki-laki enggak dipertanyakan, perempuan lajang sering dianggap enggak mampu bertanggung jawab atas dirinya. Tak jarang, perempuan menargetkan pernikahan sebagai salah satu tahapan hidup, terlepas dari keinginan pribadi atau melihat cerminan di masyarakat.
Salah satunya “Aini”, 50, yang pernah menargetkan pernikahan di usia 27. Selain menilai usia tersebut matang untuk menikah, Aini dipengaruhi ketiga kakaknya yang kebetulan menikah saat berusia 27, kemudian melihat contoh kehidupan berumah tangga dari mereka.
Namun, realitas berkata lain. Saat menginjak 27 tahun, Aini tak memiliki pasangan. Alhasil, target untuk menikah dikesampingkan. Sebenarnya ia enggak begitu memusingkan, lantaran pernikahan enggak bisa dipaksakan. Tapi Aini tak memungkiri, sempat stres karena pertanyaan “kapan nikah” suka muncul dari anggota keluarga yang jarang bertemu.
“Misalnya datang ke kawinan saudara, pasti ditanya begitu,” ungkap Aini. “Makanya jadi males ke acara keluarga. Kalau acaranya enggak penting-penting banget, aku enggak datang.”
Mengatakan belum ada yang cocok dan bahagia dengan hidupnya, menjadi jawaban pamungkas Aini tiap status lajangnya dipertanyakan. Waktu itu, ia pun enggak kepikiran mencari pasangan karena fokus meniti karier yang mulai menanjak. Kemudian, Aini mencoba enggak menginternalisasi pertanyaan “kapan nikah”, dan menjawab dengan santai.
“Aku bawa happy, biar yang nanya juga senang dan enggak nanya lebih lanjut,” kata Aini. Meski cara itu, katanya, membutuhkan proses. Sampai akhirnya Aini dapat menerima status lajangnya, dan berdamai dengan situasi agar tidak kesepian.
Baca Juga: Saatnya Berhenti Menghina Perempuan Lajang
Hidup Melajang Belum Tentu Kesepian
Salah satu stereotipe yang melekat pada seorang lajang, adalah mengalami kesepian karena tak ada teman hidup. Ruby pun tak menampik hal ini. Terlebih ia ngekos sendiri.
Saat perasaan itu muncul, Ruby memilih menghindari film-film romansa—katanya biar enggak baper. Alhasil, Ruby memilih nonton film horor dan thriller, atau cat sitting kucing milik temannya jika sedang ditinggal ke luar kota atau luar negeri.
Ketika ditanya hal yang membuat Ruby kesepian, ia menjawab, “Aku suka kepikiran, gimana ya rasanya punya healthy relationship?”
Namun, Ruby memilih tak larut dalam kesepian. Ia tetap merangkul perasaan tersebut, kemudian mengingatkan diri bahwa ada banyak waktu luang yang bisa digunakan untuk baca buku, menulis, nongkrong dengan teman-teman, dan bermain dengan keponakan.
Hal serupa dilakukan Aini. Selain hangout, ia bertukar kabar dengan teman-teman lewat grup WhatsApp dan telepon. Atau menghabiskan waktu untuk nonton film dan serial melalui layanan Over-The-Top (OTT), maupun jalan-jalan sendirian.
“Kecenderungannya pengen ada teman untuk ngobrol, karena enggak begitu suka sendirian. Tapi kalau (teman-teman) lagi enggak bisa dihubungi, I’m fine with that,” jelas Aini.
Lain halnya dengan Ista. Ia bersyukur dengan segala sesuatu yang dimiliki—kehidupan, tempat tinggal yang layak, kestabilan finansial, dan teman-teman. “Tuhan mencukupkan segala sesuatunya sampai saat ini. Dan untungnya punya banyak teman yang kayak aku (melajang), jadi enggak kesepian,” ucap Ista.
Terlepas dari kesepian yang sesekali dirasakan, Aini, Ruby, dan Ista punya rencana untuk hidup mereka ke depannya, jika nantinya tidak akan menikah.
Baca Juga: Distigma dan Direndahkan: Sulitnya Jadi Perempuan Jomblo di Jepang
Pentingnya Dukungan dan Persiapan Jelang Hari Tua
Di tengah konstruksi sosial dan masyarakat heteronormatif, hidup melajang seolah bukan pilihan. Setidaknya ada tuntutan untuk menikah yang terinternalisasi, walau berusaha menepis standar yang berlaku.
Aini bercerita, ia perlu bersikap menerima bahwa setiap orang memiliki jalan hidup berbeda. Ada yang menikah dan punya anak, ada juga yang melajang. Momen ini membuat Aini introspeksi diri supaya enggak sedih. Ditambah mendengar cerita teman-teman tentang kehidupan pernikahan—ada yang harmonis maupun berujung perceraian.
“Pengalaman teman-temanku juga jadi reminder, kalau milih orang jangan asal-asalan cuma karena udah waktunya menikah. Padahal umur itu cuma angka, kedewasaan tiap orang berbeda,” tutur Aini.
Selain penerimaan diri, support system yang kuat juga diperlukan saat menghadapi orang-orang yang menuntut pernikahan. Ruby beruntung memiliki ibu dan adik yang siap membela, ketika orang-orang di sekitar mulai mempertanyakan status lajangnya.
Kata Ruby, ibu terbiasa menjawab dengan lelucon untuk menunggu undangan disebarkan. Sementara adik Ruby pernah marah pada teman-temannya, yang berkomentar kenapa Ruby tak kunjung menikah.
“Adikku bilang ke teman-temannya, ‘Lo enggak kenal kakak gue, enggak tahu kebutuhan dan semua yang pernah dia lalui. Sorry, lo enggak berhak komentar begitu.’” cerita Ruby.
Penerimaan dan dukungan itulah yang mendorong ketiga perempuan ini, untuk terus bergerak dan mempersiapkan hari tua mereka.
Ista dan kedua temannya yang juga melajang, membeli rumah dan apartemen dengan lokasi berdekatan. Tujuannya supaya bisa ingin saling merawat, tapi tetap mengutamakan privasi sekaligus menghindari konflik kalau tinggal serumah.
“Kalau udah tua kan enggak tahu ya sifatnya gimana, makanya tinggalnya sendiri-sendiri. Saya juga mau ajak kakak, biar dia enggak sendirian,” ucap Ista.
Sementara Aini ingin traveling ke luar negeri, tinggal di rumah dengan seekor anjing, dan membangun bisnis di industri jasa. “Aku pengen masih punya kegiatan setelah pensiun. Paling nganggur sebentar, tapi enggak bisa berhenti sama sekali. Nanti stres,” ujarnya.
Sedangkan Ruby ingin tetap bekerja—saat ini berprofesi sebagai guru bahasa asing, lalu menghabiskan waktu dengan keluarga, dan menjadi penulis. Bagi Ruby, yang terpenting adalah kebahagiaannya. Seperti keponakan Ruby yang berusia 12 tahun katakan padanya, “Mau bibi single atau menikah, enggak ada bedanya. Yang penting bibi happy.”