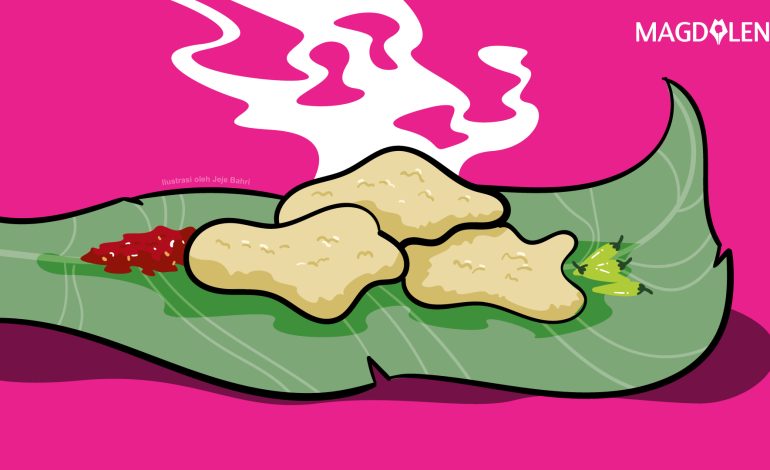Surat untuk Kakak

Aku lelah sekali hari ini. Gaya jalanku sudah terbungkuk-bungkuk membawa ransel hitam yang berat, persis seperti kura-kura. Hari ini panas dan gerah. Aku meniup-niup ke dalam kerah baju karena angin sudah malas berhembus. Buku pelajaran fisika, matematika, kimia dan baju olahraga memenuhi ranselku. Nilai ujianku bersinar seperti matahari: NOL. Ditambah lagi, hari ini pekerjaan rumah tentang Integral menjelma kode aneh yang sangat sulit aku pecahkan sendiri.
Aku membuka pintu rumah. Tenagaku habis terkuras, begitu pula kerongkonganku seperti terbakar. Rasanya aku ingin merangkak saja.
Aku setengah berlari menuju pintu rumah, melepas sepatuku dengan tergesa, dan melangkah menuju kulkas. Kuambil sebotol air dingin dan menenggaknya langsung. Tidak lama kemudian, salam sapa spesial kakakku terdengar dari balik kamarnya “PERMATA MAHARANIIIIIII…SUSUN LAGI SEPATUNYAAAA” teriaknya lengking.
Kakakku memang luar biasa. Aku merasa sepertinya dia memiliki mata ketiga, yang lebih tajam daripada CCTV dengan facedetection.Aku hampir tersedak.
Baca juga: Kita yang Hidup dari Kata-kata
Tidak lama suaranya kembali terdengar, “PAKAI GELAS, DAN ISI LAGI BOTOLNYAAAA”
Kan. Kubilang juga apa. SI-SI-TI-PI.
Aku berjingkat kembali ke depan dalam senyum masam. Aku mengangkat dan menyusun kembali sepatuku dengan tangan kiri, dan menggamit tas dengan tangan kanan.
“KAKAK BAWEL BANGET KAYAK IBUUUUU”, balasku sembari berteriak. Kak Asya keluar dari kamar dengan rambut tergelung. Kain pel di tangan kanannya dan vas bunga tangan kirinya. Wajahnya memerah menahan marah, juga menahan tangis.
Aku sungguh terkesiap mendengar ujaranku sendiri. Bukan maksudku membandingkannya dengan ibu. Aku mempercepat langkahku menuju kamar, menutup pintu, melepas kacamataku, melempar tubuhku ke atas kasur, menarik selimut, dan menutup wajahku dengan bantal.
Aku bersungut-sungut. Betapa mudahnya waktu berlalu, betapa kerasnya perubahan menyapu semuanya. Termasuk pada kakakku, Asya.
Aku dan kak Asya terpaut usia sekitar tujuh tahun. Ayah dan Ibu kami sering sekali bertengkar. Orang tua kami dulu berharap bahwa memiliki anak lagi akan mempersatukan mereka kembali dan mengurangi pertengkaran mereka. Tapi sayangnya, keluarga harmonis yang mereka idamkan tidak kunjung terjadi. Mereka masih bertengkar hampir setiap malam. Ayah akan marah-marah dan menuduh Ibu gagal mendidik kami. Sementara Ibu akan memarahi Ayah yang selalu mementingkan pekerjaannya dibandingkan kami.
Setiap kali pertengkaran Ayah dan Ibu dimulai, aku pergi bermain dengan teman-temanku di luar rumah. Sementara kakak akan menemani Ibu yang menangis, marah, lalu menangis lagi.
Baca juga: Menjadi Aku
Namun, semakin tahun berganti, kak Asya menjadi semakin pendiam dan penyendiri. Kak Asya sibuk menenggelamkan diri dalam buku-buku, musik dari balik headset yang volumenya sungguh memekakkan telinga – aku pernah mencobanya dan aku tidak mengerti.
Suatu malam, aku terbangun dan menemukan kakak tengah menunduk di meja belajarnya. Aku saat itu berpikir bahwa kakak sudah tertidur di meja karena sibuk belajar. Namun kutemukan buku yang menjadi tumpuannya basah.
Aku mengusap punggungnya. Dengan wajah sembab dia berkata, “Aku berharap Ibu dan Ayah bercerai saja. Lelah sekali dijadikan tameng untuk semua permasalahan mereka.”
Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kakak kemudian mengusap air matanya, berusaha tersenyum kemudian menemaniku tidur.
Kak Asya menggantikan peran ibu dan ayahku pada banyak waktu. Ia mengajariku berhitung, meski kadang tidak terlalu sabar. Menjadi pelindungku saat aku dirundung pulang sekolah oleh anak Komplek sebelah. Menghadiri acara pagelaran busana daerah di sekolah, bahkan mengambil raporku. Kehadirannya selalu mengundang “Wah” sebagai pujian dari teman-teman sekelasku, dan mengundang “Hmm” dalam kernyit di kening orang tua lainnya yang hadir. Meskipun demikian, dia tetap berjalan dengan anggun nan nyentrik dalam balutan kaus kuning dan celana merah ngejrengnya.
Karenanya, menjadi adik dari kak Asya juga tidak mudah, menurutku. Apa pun yang aku lakukan, selalu dibandingkan dengan kakak. Aku tidak secantik dan sepintar kak Asya. Kak Asya sang juara kelas, kak Asya yang ikut Olimpiade matematika, kak Asya yang berkuliah di Universitas ternama, kak Asya yang membiayai kuliahnya sendiri. Kak Asya yang bisa segalanya, dan aku yang tertatih-tatih mengikuti jejaknya.
Sampai suatu ketika, kak Asya memutuskan meninggalkan rumah dan menyewa rumah kontrakan dekat dengan kampusnya. Sejak saat itu, kemarahan Ayah semakin memuncak pada Ibu.
Dua tahun setelahnya, Ayah dan Ibu memutuskan untuk bercerai – akhirnya. Aku memilih untuk tinggal bersama kak Asya. Rumah kontrakannya cukup besar untuk ukuran mahasiswa, dengan dua kamar tidur, dapur kecil, dan ruang tamu. Aku akhirnya mempunyai kamarku sendiri.
Ketika memutuskan pindah ke rumah kontrakan, kak Asya memulai usaha kue. Dia menjalankan usahanya di tengah kesibukannya menyelesaikan tesis di jurusan Komunikasi. Aku tahu aku salah. Namun, kadang-kadang kan aku ingin juga diingatkan dengan lembut. Dalam hatiku berpikir, “Apakah jurusan komunikasi tidak mengerti caranya berkomunikasi dengan adiknya sendiri?”
Aku menendang-nendang selimut. Kesal dan kepanasan. Mataku tertuju pada dinding yang kuhiasi dengan foto-fotoku, keluargaku, juga teman-temanku. Foto-foto itu kubawa dari rumah lama. Foto-foto yang aku copoti dari album, sehingga album foto kami terlihat bolong-bolong.Ada satu foto yang selalu kak Asya ceritakan kepadaku, dulu, saat kami masih sering bercerita, waktu kami masih tinggal dalam satu kamar. Foto itu menunjukkan versi mini dari diriku yang tengah memegang boneka penguin. Kak Asya selalu berkata bahwa aku dulu adalah anak yang penakut. Aku menangis karena kaget boneka penguin itu mengeluarkan suara.
Baca juga: Perempuan yang Melahirkan Matahari
Aku sesungguhnya mengetahui bagaimana kak Asya selalu berusaha untukku. Dia melakukan itu semua agar aku punya kesempatan seluas-luasnya. Meskipun demikian, aku tetap merasa jengkel. Aku mengunci kamarku dan memilih tidur. Aku sengaja tak mengindahkan panggilannya untuk makan malam. Gengsi.
Malam itu, rasa lapar mengalahkan gengsiku. Waktu sudah menunjukkan dini hari. Aku membuka pintu dengan perlahan, supaya tidak terdengar derit pintu. Masakan masih tersedia di meja makan, sepertinya sengaja disisakan untukku. Dari dapur aku melihat sosok kakak dari pintu kamarnya yang setengah terbuka.
Kakakku masih duduk di atas meja, sibuk mengemas buku-buku dan catatan-catatan. Wajahnya digurat lelah.
Kuurungkan niatku untuk makan. Aku kembali menuju kamar dan terdiam. Sesak mengisi dadaku. Aku mengambil buku pelajaranku dan menyobek bagian tengahnya. Aku ingin menulis surat untuknya.
Dulu, kami saling berbagi surat rahasia, agar kami bisa bercerita tentang hari-hari kami. Sayangnya, aku tidak tahu kapan terakhir kali kami melakukannya. Semakin kami beranjak dewasa, kata-kata kami seperti dimakan usia: Hilang tanpa sisa.
Dear Kak Asya…
Aku menggumpal kertasku dan membuangnya. Terlalu kaku. Aku sobek kembali halaman lain di bukuku.
Untuk Kakak,
Kakakku, yang makin pandai bertutur, makin jelas berucap, dan makin lancar mengeja. Selayaknya aku harus ganti kacamataku dengan yang baru. Kacamataku yang lama, yang kupakai untuk melihatmu, sudah tak cocok lagi untukmu. Kau semakin jauh dari genggam, semakin samar dalam pandang. Dan aku tertinggal disini, bersama suaramu yang kian meninggi.
Kata-kata kita lapuk dimakan waktu.Aku tak mampu melafal kata, mengeja rasa, dan meraba huruf. Aku tak bisa lagi membaca keseluruhan maknamu.Mencerna rasanya sesulit menelan kenangan bersama.
Aku mengagumi dirimu yang senantiasa menyulap duka menjadi tawa. Kamu akan melupakan luka dan menggantinya dengan barisan gigi yang tak lagi putih cemerlang seperti iklan. Aku ingin mengingat dirimu yang makin pandai tertawa, dan makin jarang menangis.
Kakakku sayang…
Aku mengelap air mata yang tiba-tiba menetes. Menggigit bibir.
Seringkali, aku hanya ingin bertengkar hebat denganmu. Beradu pandang dan bertukar kata. Tapi tidak menghujat, tidak menghujam, tidak merajam. Hanya ingin berbagi beban di pundakmu.
Aku terhenti. Bulir-bulir mengalir penuh di pipi. Aku tak tahu lagi bagaimana cara menyekanya.
Kakakku, adikmu ini ingin berbincang denganmu. Semoga kamu tidak lupa cara membaca bahasanya.