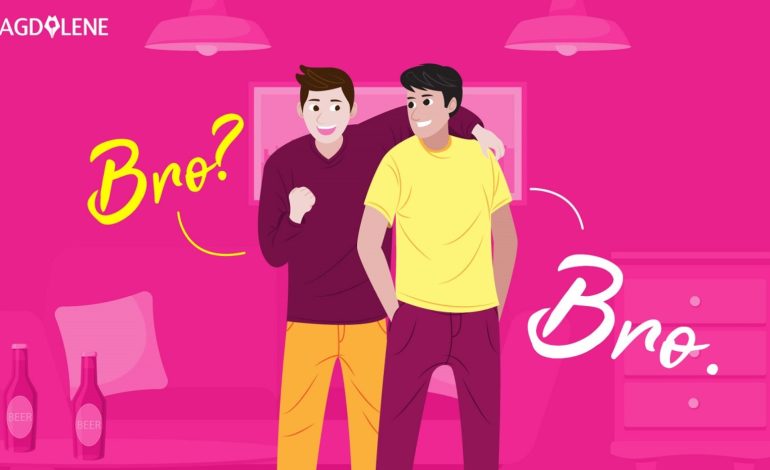Danny Yatim: Gencar Suarakan ‘Active Aging’ demi Lansia Berdaya

Ketika pertama kali berbincang dengan Danny Yatim, saya tak menyangka laki-laki ini telah menginjak usia kepala 6. Sosoknya yang aktif dengan berbagai kegiatan, membuatnya tak kelihatan jauh berbeda dengan anak muda zaman now. Bahkan, pengajar Psikologi paruh waktu di Universitas Katolik Atma Jaya ini juga merupakan penggemar K-Pop, khususnya grup musik XO.
Mulanya, saya hendak mewawancarai pria kelahiran 28 Juni 1957 itu untuk artikel Magdalene bertajuk “Ketika Mama Menua dan Tak Bekerja, Maukah Kamu Menampungnya”. Namun, perbincangan kami sebelumnya, membuat saya mendapat wawasan baru seputar lansia aktif, dan cara menanamkan kesadaran bagi orang-orang pralansia.
Pandangan Danny ini bisa dibilang berseberangan dengan anggapan jamak, lansia merupakan sosok tak berdaya dan senantiasa membutuhkan bantuan. Namun, berbagai petikan pengalamannya menyadarkan kita bahwa anggapan yang digeneralisasi semacam itu tidaklah benar. Pasalnya, ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk membuat lansia tetap aktif dan berdaya, sebagaimana orang-orang kebanyakan.
Pernah sekali waktu saat hendak menerima vaksin COVID-19 di puskesmas kecamatan, laki-laki lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), Connecticut College, dan Harvard University bidang Psikologi ini dihampiri petugas puskesmas dan diantarkan ke arah elevator menuju tempat vaksin.
“Kenapa mesti ke lift?” tanya Danny. Si Petugas menjawab tempat vaksinasi ada di lantai dua.
Seraya tertawa kecil, Danny menceritakan reaksinya waktu itu kepada saya, “Ya ampun, itu kan ada tangga. Tadi saya ke toilet di lantai dua juga naik tangga, tapi, terima kasih atas perhatiannya.”
Pandangan dan berbagai pengalaman sebagai lansia ini tertuang dalam sebuah video sekitar 11 menit yang diunggahnya untuk kompetisi Instagram yang diselenggarakan organisasi Lansia Aktif Ceria Indonesia (@lansia.lari) dan dipublikasi akun tersebut pada 17 Mei silam.
Baca juga: Waduh, Kakak Perempuan Saya Sudah Pensiun!
Berikut petikan wawancara saya dengan Danny Yatim pada Juni lalu seputar pandangannya tentang isu lansia dan cara memberdayakan mereka.
Magdalene: Boleh diceritakan lebih dulu, bagaimana awalnya Mas punya ketertarikan terhadap isu lansia?
Kalau sekarang, karena saya sudah lansia. Dulu waktu saya kuliah di UGM, waktu skripsi, saya tertarik sama Psikologi Perkembangan. Lalu ketertarikan dan pilihan saya ada dua: Remaja atau lansia. Bingung, kan. Cuma, persyaratan skripsi itu harus didukung punya artikel jurnal minimal 10 atau 15, [jurnal isu] remaja saya lebih banyak daripada lansia. Akhirnya jadi [fokus] saya ke remaja, makanya saya dikenal sebagai ahli psikologi remaja, tapi, isu lansia dari dulu saya tertarik.
Saya waktu ke rumah teman dari SMA, kalau teman saya itu punya nenek, saya bisa ngobrol dengan nenek itu. Kalau di Psikologi ada istilah Oedipus Complex, saya mungkin punya nenek complex. Waktu kecil, juga saya dekat dengan Oma. Kalau ketemu nenek bisa langsung attach gitu.
Saya pernah juga nulis memoar tentang nenek dan masuk buku kumpulan cerita: Memoar Bahagia dengan Kakek dan Nenek terbitan tahun ini.

Sepengetahuan dan sepengalaman Mas, bagaimana kebanyakan orang Indonesia memandang lansia?
Agak susah juga kalau kita bilang Indonesia karena Indonesia kan bhinneka. Urban Jakarta, deh. Saya lihat banyak sekali pandangan mendua di sini. Katanya kalau di bangsa-bangsa Timur, kita sangat menghargai lansia/orang tua. Kalau dalam keseharian, “Ih, dia kan udah tua”, kayak merendahkan orang tua.
Jadi benar enggak sih, kita menghormati kakek dan nenek? Itu yang buat saya ambivalen, bagaimana kita menghormati orang tua.
Lalu dikatakan bahwa kita mau ramah pada lansia. Ini sering sekali dikaitkan dengan budaya bangsa kita. Kenyataannya, bangsa Eropa jauh lebih menghargai lansia dibanding Indonesia. Segala macam fasilitas, atau di AS, jadi senior citizen itu privilese.
Di Indonesia baru mulai ada tren seperti itu, misalnya kalau naik Transjakarta bisa gratis untuk lansia. Saya punya, tuh, kartunya. Waktu saya upload kartu gratis untuk penumpang lansia di media sosial, banyak mahasiswa saya yang enggak percaya umur saya 64.
Dari cerita ini, saya mau menepis stereotip lansia adalah orang yang nggak berdaya. Makanya saya sering ngomong tentang active aging, meskipun tidak menyangkal ada lansia yang butuh banyak bantuan karena sudah lemah. Ada variasi dalam kelompok lansia.
Soal stereotip, saya ada pengalaman punya teman, aktivis perempuan, komentar di media sosial ngeledek dosen lansia yang gaptek. Terus saya bilang, enggak semua lho, gaptek. Pengalaman saya, ada mahasiswa yang katanya milenial yang gaptek juga.
Lalu dia bilang, “Tapi kan kebanyakan gitu, Mas.”
“Nah, kalau kamu udah pakai kata kebanyakan, kamu menstereotipkan lansia. Sementara, kamu akan marah kalau kita menstereotipkan perempuan atau LGBT.”
Terus, dia diem aja. Jadi, ternyata ageism ada di Indonesia, tidak hanya yang tua ke yang muda tetapi juga yang muda ke yang tua.
Stereotip soal lansia ini enggak sesuai dengan pengalaman saya dan teman-teman sekolah saya juga. Tahun 2010, kami reuni dan mulai janjian minimal ketemu sekali setahun. Lantas, jadi dua kali setahun, makin lama jadi makin sering, nongkrong di kafe, makan malam, pergi ke luar kota bareng. Lalu kami bilang, “Kok kita enggak memenuhi stereotip ya? Kita jadi lansia aktif-aktif aja.”
Lalu pengamatan saya soal lansia melebar, enggak cuma ke temen-temen saya, tapi juga ke kakak saya yang sekarang lagi kuliah di Institut Kesenian Jakarta. Dia kuliah S1, umurnya 67, ambil Perfilman. Pertama kali dia datang, banyak yang tanya, “Mulai ngajar ya, di sini?” dan dia jawab, “Enggak kok, saya kuliah di sini.”
Dari pengalaman di sekitar saya, banyak lansia yang tetap aktif, enggak seperti bayangan kita dahulu. Memang ada yang rentan, tapi tidak sejelek itu.
Kalau kita lihat di Singapura, yang jaga toko banyak sekali lansia. Jadi, mereka diberikan wadah untuk tetap bekerja. Waktu saya kuliah di Amerika, saya cari tambahan uang ngawasin ujian anak S1. Selain mahasiswa magister, banyak sekali lansia yang juga jaga ujian. Bagi mereka selain jadi tambahan income, jaga ujian juga jadi tambahan aktivitas. Di Indonesia mungkin belum sampai ke sana.
Baca juga: Ketika Mama Menua dan Tak Bekerja, Maukah Kamu Menampungnya?
Bicara soal active aging, seorang yang biasa kerja terus enggak kerja ketika lansia, biasanya ada isu yang disebut post power syndrome. Bagaimana pandangan Mas soal ini?
Bekerja itu kan bagian dari identitas kita. Begitu lepas, itu seakan-akan sebagian dari diri kita hilang, makanya terjadi post power syndrome.
Maka menurut saya, bagusnya semakin kita tua, perlu ada upaya supaya enggak terlalu attach sama pekerjaannya. Ada teman-teman saya yang sudah pensiun, lalu bergerak di bidang bisnis kecil-kecilan. Ada yang gagal karena enggak punya skill [berbisnis] itu lantaran terlalu lama bekerja kantoran. Oleh sebab itu, kita perlu punya kehidupan atau skill di luar pekerjaan utama.
Saya sendiri kan agak tidak mainstream karena bekerja freelance. Aktivitas saya cukup banyak. Saya ngajar sebagai dosen, tetapi bukan fulltime. Saya juga penerjemah, saya nulis, saya jadi trainer. Saya punya banyak channel untuk melakukan banyak hal. Bukan berarti hidup saya otomatis aman, damai, sejahtera. Tapi, saya melihat teman-teman yang dulu itu kehidupannya cuma satu aspek saja [pekerjaannya], sehingga waktu dia hilang, dia enggak punya personal resources untuk melakukan hal yang berbeda.
Di Indonesia sudah lumrah pandangan bahwa anak wajib atau mesti berbakti dengan menampung orang tuanya saat mereka tua, sehingga rantai dependensi lansia terus berlanjut dari generasi ke generasi. Bagaimana pendapat Mas soal ini?
Ada lansia yang bukan hanya attach pada pekerjaan, tetapi juga pada anak. Jadi waktu dia udah tua, dia menuntut anaknya memberi perhatian pada dia yang lantas bisa menimbulkan konflik.
Saya dulu mengalaminya dengan almarhumah ibu saya. Dia sudah kehilangan suaminya, anak-anaknya udah gede [kuliah dan bekerja], sibuk dengan urusan masing-masing, lalu dia stroke. Dia lantas cerita ke orang sekitar bahwa anak-anak enggak perhatian lagi ke dia.
Ibu saya jadi kayak anak kecil, dan saya dengan kakak-kakak saya jadi orang tua yang mengurusnya. Saya melihat, ibu saya enggak punya pegangan apa-apa dalam kondisi seperti tadi saya sebutkan.
Saya sempat bilang ke kakak-kakak saya, secara bawah sadar, kami berusaha tidak menjadi seperti orang tua kita. Kami memilih harus bisa mandiri, lebih memperhatikan kesehatan kami. Kami sekarang ini sudah lebih tua dari usia meninggalnya orang tua kami.
Karena itu, saya juga sering bicara tentang kemandirian pada lansia dalam webinar-webinar kecil karena ini penting diperhatikan bahkan sebelum menginjak masa lansia. Mereka perlu disiapkan jadi mandiri, bagaimana berhubungan dengan anak kemudian hari berkaca dari hubungan-hubungan yang berkonflik saat seseorang lansia. Kalau perlu, redesign hubungan dengan anaknya, maunya bagaimana.
Baca juga: Drama Korea ‘Navillera’ dan Mengejar Mimpi Saat Lanjut Usia
Di tengah pandangan seperti tadi, tentu enggak mudah menjalankan edukasi tentang lansia aktif dan berdaya. Hal-hal apa saja sih, yang penting diperhatikan untuk memulai edukasi tentang ini?
Yang penting adalah menekankan lansia untuk tetap aktif secara fisik dan psikis. Secara fisik, saya melihat orang sekarang ke minimarket aja naik motor atau mobil. Saya pikir, kenapa enggak jalan kaki saja? Itu yang saya lakukan, bukan jalan kaki yang memang benar-benar ditujukan buat olahraga, ya. Pokoknya keep your body active.
Lalu keep your mind active. Misalnya ikutan kuis, meski kadang norak-norak. Ada contohnya di grup Whatsapp itu anagram nama-nama jalan/daerah di Jakarta. Ini bisa dibilang iseng-iseng dalam melewati pandemi, tapi membuat kita tetap aktif. Saya seneng ada yang kayak gitu.
Saya kadang gemes juga kalau belanja, biayanya 38 ribu, lalu saya beri uang 50 ribu. Terus, si mbak atau masnya yang masih muda keluarin kalkulator. “Mbak, itu kembalinya 12 ribu,” kata saya. Ini antara malas berpikir atau karena sudah ada fasilitas yang membantu mereka. Saya jadi khawatir, apa jadinya orang-orang sekarang kalau sudah tua?
Dengan adanya handphone yang bisa menyimpan semuanya, berapa nomor telepon yang kita hafal? Dulu waktu belum ada handphone, saya hafal nomor orang-orang yang dekat sama saya. Sekarang kita dimanjakan untuk enggak mengingat sesuatu.
Makanya, saya suka iseng kasih latihan pikiran, misalnya habis kumpul-kumpul, saya tanya di grup WhatsApp, “Tadi siapa aja sih yang dateng?” Buat saya ini ada gunanya.
Pun, ketika dosen-dosen lain heran saat saya hafal nama-nama mahasiswa saya, saya bilang ini bukan bakat, tapi saya berusaha untuk itu. Setiap semester, begitu dapat daftar mahasiswa, hari pertama masuk, saya tanya nama panggilannya siapa setiap mahasiswa, lalu saya catat.
Bicara soal ingatan, lansia yang demensia itu cuma 10-15 persen secara global. Berarti 85 persen kan biasa-biasa aja. Ini sebuah penyakit, jadi bukan sesuatu yang given. Orang kan suka bilang kalau semakin tua semakin pikun atau “faktor U”. Saya suka marah kalau orang bilang gitu. Kalau sekali-sekali kita lupa itu hal yang sangat wajar, enggak ada hubungannya sama usia.