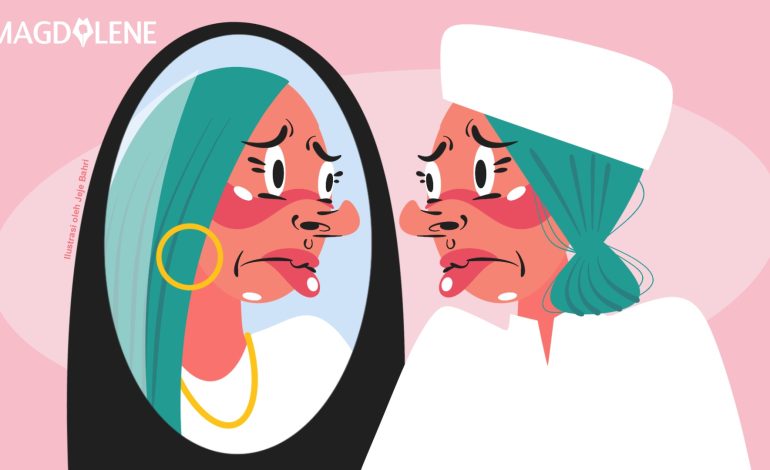Mereka yang Berada di Tepian Negara: Homofobia pada LGBTQ+

Pintu kayu hitam terbuka dan angin air conditioner menerpa. “Welcome, sini masuk,” Tika, 34 menyambut dengan suara yang berat. Asap rokok elektronik keluar dari mulutnya. Ada dua orang duduk-duduk di kasur yang seprainya berwarna coklat muda. Mereka adalah Esther, 33 dan Niko, 27. “Welcomee,” ucap mereka bersamaan.
Tika, Esther, dan Niko (bukan nama sebenarnya) saling memiliki hubungan romansa satu sama lain alias mereka bertiga pacaran, poliamori. Bermula dari Tika yang bertemu dengan Esther di aplikasi kencan hingga bertemu dengan Niko di aplikasi serupa. Niko yang feminin memikat kedua perempuan itu.
Kamar indekos dengan ukuran dua puluh dua meter persegi di area Kuningan, Jakarta Selatan tersebut menjadi taman bermain pasangan kekasih. “Kita mah open house,” ujar Tika tertawa renyah. Hubungan mereka bertiga sudah berjalan hampir dua tahun. Tika dan Esther tidak menutup-nutupi seksualitas mereka, yakni lesbian dan panseksual secara bersamaan.
Baca juga: Bukan Cuma Negara yang Homofobik, Media juga
Melansir PRIDE at work International Labour Office, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia, setidaknya ada 3 juta orang LGBTQ+ di Indonesia. Kebanyakan orang LGBTQ+ merahasiakan identitas karena beberapa alasan, seperti takut akan stigma, dikucilkan keluarga, tidak bisa mempertahankan pekerjaan, dan dipersekusi oleh kelompok agama.
Tika sendiri bercerita, terpaksa harus mengundurkan diri dari salah satu perusahaan makanan ramen ternama di Indonesia. Suaranya berubah pelan ketika bilang alasannya dipecat karena video ciuman lesbian yang ia unggah di Twitter.
Selama ini, Tika secara terbuka mengaku panseksual bahkan di bio Instagramnya. Kasus pemecatan yang terjadi di awal 2023 itu tidak menghentikan keberaniannya dalam mengunggah video atau foto tentang hubungannya dengan sesama atau lawan jenis.
Sekitar awal April, human resources (HR) perusahaan mengontak Tika melalui pesan WhatsApp. Dalam obrolan tersebut masih ada sedikit negosiasi. Tika diberi pilihan: Tetap bekerja, tetapi mengurangi aktivitas mengunggah video atau foto vulgar bersama pacar-pacarnya atau berhenti bekerja dengan mengundurkan diri. Tika memilih yang kedua. Perempuan yang rambutnya berwarna pink, putih, hitam tersebut merasa, ia harus memilih keluar demi jati dirinya sendiri, bebas.
Saya sempat menanyakan bukti surat pemecatan, tapi rupanya tidak ada bentuk fisiknya. Sebab, yang terjadi saat itu, Tika memang dipaksa mengundurkan diri oleh HR perusahaan. Saya ditunjukkan langsung bukti tangkapan layar panggilan dari HR perusahaan. Sebagai informasi, dalam keterangan suratnya, Tika tidak menulis alasan sebetulnya, melainkan hanya ingin mencari peluang baru di luar sana.
Tika bilang, bos di perusahaan tersebut tidak masalah dengan kelakuannya, tetapi yang tidak suka adalah lingkaran dekat bosnya, termasuk artis Indonesia. Mereka semua mengenal Tika. Memang, posisi Tika saat itu termasuk penting, creative director dan graphic designer.

Baca juga: Review ‘Autobiography’: Potret Militerisme di Era Kini dan Representasi Homoerotik yang Homofobik
LGBTQ+ dan Diskriminasi di Lingkungan Kerja
Badgett, dkk. menjelaskan, orang-orang LGBTQ+ di Indonesia sebenarnya sama saja punya kemahiran dan pengetahuan seperti halnya cis-heteroseksual. Hanya saja, negara telah membuat kemahiran mereka tak terwadahi dengan layak. Alhasil, orang-orang LGBTQ+ terpaksa bekerja di sektor yang sama sekali tidak berhubungan dengan keahliannya, seperti pekerja seks, pengemis, pengamen, penata rambut di salon, dan di sektor hiburan dan kreatif.
Hal tersebut terbukti pada Niko. Walaupun Niko sudah biasa dipandang feminin oleh kerabat, ia tetap menyembunyikan seksualitas sesungguhnya dari banyak orang dan keluarga. Diskriminasi ejekan ‘”bencong” yang diterimanya sejak kecil membuatnya berpikir, bahwa tidak apa-apa diejek seperti itu.
“Secara umum gua merasa gapapa, gua tahu mereka bercanda.”
Masalahnya, ejekan serupa terulang di lingkungan kerja. Rekan kerja laki-laki kerap memanggilnya, “Eh Cong, ngomong dong, lu kan bencong. Cong…cong…”
Sama seperti Tika, awal 2022, Esther dan Niko juga dipaksa untuk mengundurkan diri dari salah satu perusahaan liquid rokok elektronik. Saat itu Niko berada di posisi digital marketing dan design visual, sedangkan Esther di posisi digital marketing; direct sales atau public relations yang menangani pihak luar. Alasannya lagi-lagi karena unggahan video vulgar yang disensor sepenuhnya. Tidak terlihat wajah sama sekali, tetapi perusahaan sudah mengenal bagaimana rupa dan bentuk mereka berdua.
Mereka diberi dua pilihan. Perbedaannya adalah dari tingkat agresivitas pihak kantor. Jika di kantor Tika masih diberi negosiasi dan keringanan agar masih bisa tetap bekerja di perusahaan selama mengurangi aktivitas media sosial, Niko dan Esther hanya diberikan satu pilihan. Jika tidak mau mengundurkan diri, mereka berdua akan dilaporkan dan dituntut atas tuduhan mencemarkan nama baik jenama.
Padahal dalam seluruh unggahan mereka berdua di media sosial, tidak ada penggunaan jenama perusahaan sama sekali.
Mereka berdua memilih untuk keluar. Sembari tertawa, Esther merasa biasa saja dan senang bisa keluar dari perusahaan yang homofobik macam itu. Sedangkan Niko mengaku kaget mulanya, tapi berangsur lega sebab ia bisa lepas dari pelecehan beberapa laki-laki di kantor lamanya.
Niko bercerita, saat itu mereka berdua dipanggil untuk masuk ke dalam ruangan. Dua orang dari pihak HR, perempuan dan laki-laki, menegur dan langsung meminta mereka mengundurkan diri saja. Mereka berdua diminta tanda tangan surat yang sudah dituliskan oleh pihak perusahaan saat itu juga. Surat tersebut berisi pengakuan kesalahan beserta sanksi konsekuensinya, yakni mengundurkan diri.
“Saya mengaku salah. Saya menerima ini tidak sesuai dengan yang ada di perusahaan. Dengan demikian, saya mengajukan pengunduran diri.”
Masalahnya, ejekan serupa terulang di lingkungan kerja. Rekan kerja laki-laki kerap memanggilnya, “Eh Cong, ngomong dong, lu kan bencong. Cong…cong…”
Kejadiannya berlangsung di hari yang sama ketika mereka dipanggil sehingga lagi-lagi, tidak ada kertas fisik atau dokumen elektronik yang dapat dibuktikan. Hari itu juga mereka disuruh menulis surat pengunduran diri.
Dari pengalaman ketiganya, bisa ditarik kesimpulan bahwa tempat kerja belum jadi ruang aman untuk LGBTQ+. Dalam wawancara Dédé Oetomo, sosiolog Universitas Airlangga yang juga pencetus organisasi pegiat hak LGBT GAYa Nusantara pada 2023 dijelaskan perbedaan bentuk diskriminasi terhadap komunitas ini.
Diskriminasi paling umum yang dihadapi transgender adalah bentuk fisik dan identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saat transpuan bergaya seperti perempuan dan transmen dengan bentuk fisik atau bergaya seperti laki-laki, tetapi identitas di KTP masih sama dengan jenis kelamin bawaan lahir, sudah tentu mereka jadi sasaran empuk diskriminasi.
Selain diskriminasi dari bentuk fisik, laporan International Labour Organization (ILO) pada 2016 bertajuk PRIDE at work menyebutkan, ada lima bentuk diskriminasi di tempat kerja yang dihadapi oleh LGBTQ+. Di antaranya, komentar atau guyonan terkait identitas gender, marginalisasi sosial, perisakan oleh sesama LGBT, intimidasi, dan kekerasan fisik. Berbagai macam diskriminasi tersebut jadi alasan mengapa banyak LGBTQ+ yang merahasiakan identitas dan kesulitan mendapatkan perlindungan sosial.
Hal senada ditunjukkan dalam survei The Economist Intelligence Unit. Kata mereka, 4 dari 10 LGBTQ+ terhambat kariernya karena keterbukaan mereka sebagai LGBTQ+. Hal itu tentu bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalamnya menjelaskan, diskriminasi dalam bentuk apapun di lingkungan kerja itu dilarang. Pasal 5 berbunyi: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan,” sedangkan bunyi Pasal 6 adalah: “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”
Lebih lanjut, sebagai negara hukum, kita punya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berisi: “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Lalu dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan, masyarakat Indonesia berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
Baca juga: ‘Oppa’ dan ‘Unnie’ Boleh ‘Skinship’, tapi Korsel Masih Homofobik
Masalahnya, peraturan buat banyak orang mungkin sekadar kertas. Karena itulah diskriminasi terhadap teman-teman LGBTQ+ masih ajeg terjadi hingga kini. Mengutip wawancara Dédé Oetomo, pegiat GAYa Nusantara, organisasi masyarakat LGBTQ+ Indonesia, toleransi berbeda dengan penerimaan. Baginya, penerimaan berarti pertemanan dan tidak sungkan untuk berbaur dengan LGBTQ+, sedangkan toleransi tidak sejauh dengan penerimaan. Cukup saling mengenal saja dan tidak berbaur. Menghentikan paksa dan memutus LGBTQ+ dari akses ekonomi adalah contoh betapa tak ada toleransi dan penerimaan di sana.
Sama seperti Niko, Esther, dan Tika yang karena identitasnya terpaksa tidak lagi bekerja. Mereka mengatakan kepada saya, cukup beruntung sebab karena punya privilese ekonomi. Namun, bagaimana dengan mereka yang tidak?
Penelitian PRIDE at work juga menyebutkan, LGBTQ+ yang berprivilese lebih memiliki privasi dan bekerja sendiri serta memiliki lingkungan yang suportif. Namun, transgender lebih berbahaya. Mereka diserang oleh pemerintah dan polisi dengan dalih untuk ‘menertibkan massa.’
Hari sudah sore. Kami berempat terdiam. Saya termenung memandang bingkai foto di atas kasur. Foto jembatan berwarna hitam putih. Bagaimana negara akan melindungi mereka? Lekas saya berpamitan dengan isi kepala yang penuh.
Giofanny Sasmita mahasiswa jurnalistik yang senang membaca buku sambil ditemani teh hangat dan lantunan musik.