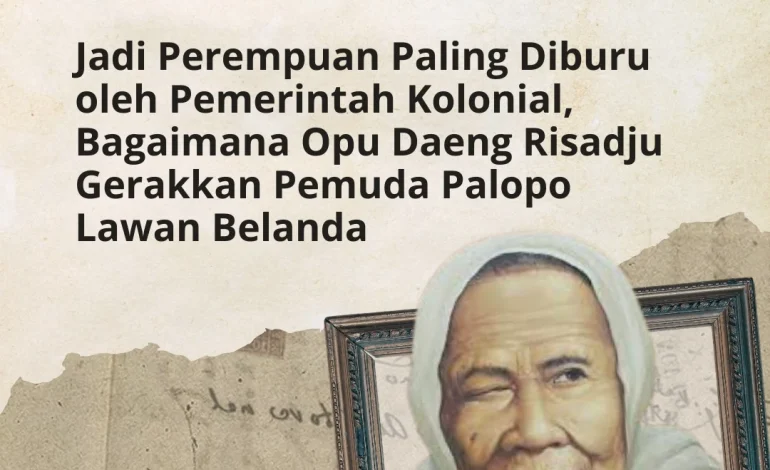Tak Cuma Muslim, Umat Kristen Palestina juga Jadi Korban Genosida

Paskah, perayaan penting Kristen terpaksa harus dirayakan dalam suasana suram di Gaza. Malam itu, sekitar 100 orang Kristen berkumpul di bawah cahaya lilin Gereja Keluarga Kudus. Tak ada selebrasi meriah atau hidangan mewah. Sebab, mereka masih berduka selama enam bulan terakhir. Sejak pasukan Israel membombardir kompleks Rumah Sakit (RS) al-Shifa, lokasi berlindung 30 ribu pengungsi, sejak 18 Maret 2024. Gereja tempat mereka beribadah sendiri berada di area RS tersebut.
Suster Angelica, biarawati Italia dari Perugia merasa sedih, melihat sedikit jemaat gereja yang datang. Bahkan kebaktian Minggu pun tidak pernah penuh. Menurutnya, para peziarah menjauh karena ancaman kematian yang terus membayangi mereka.
Sebagai informasi, setiap tahun umat Kristiani dari seluruh dunia mengunjungi Yerusalem untuk merayakan Paskah, berjalan di Via Dolorosa, jalan yang dilalui Yesus menuju penyaliban lebih dari 2.000 tahun silam.
Sayang, umat Kristen Palestina dari Tepi Barat yang diduduki enggak bisa berjalan di Via Dolorosa tahun ini. Setidaknya 200 pemimpin dari Tepi Barat diberi izin untuk memasuki daerah tersebut, tetapi jemaat enggak diberi akses untuk berpartisipasi dalam kebaktian, kata Imran Khan dari Al Jazeera.
“Ini adalah hari-hari yang sangat kelam, hari-hari yang sangat sulit,” kata Pendeta Munther Ishak kepada Al Jazeera. “Saya pikir pembatasan tahun ini telah meningkat. Bahkan bagi kami di Betlehem, dan Yerusalem yang berjarak 20 menit dari sini, tetap tidak memiliki akses.”
Baca Juga: Elitisida, Kematian Refaat Alareer, dan Pembunuhan Orang Penting di Palestina
Kekerasan terhadap Umat Kristen Palestina
Suramnya suasana Paskah bagi umat Kristen Palestina adalah akumulasi kekejaman rezim apartheid Israel. Merangkum dari laporan Al Jazeera dan The New Arab, kekerasan terhadap umat Kristen Palestina bisa ditarik jauh saat Nakba 1948. Tepatnya, ketika milisi Yahudi menyerang desa-desa dan kota-kota Palestina. Dalam hal ini, umat Kristen Palestina menjadi sasaran bersamaan dengan Muslim Palestina.
Orang-orang Kristen Palestina diusir dari Lydda (sekarang disebut Lod oleh orang Israel). Banyak yang terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer untuk mengungsi di Ramallah sambil menghindari militan Yahudi. Di Yerusalem dan wilayah lain, warga Palestina, apa pun keyakinannya, juga diusir. Daoud Kuttab, jurnalis berdarah Palestina dalam kesaksiannya menyatakan ayah, paman, dan nenek terpaksa mengungsi demi keselamatan nyawa mereka.
Ia bercerita bagaimana bibi serta keluarga yang tinggal di lingkungan Musrara, mencari perlindungan di dekat Kapel Katolik Notre Dame. Sebab, itu dinilai akan aman di sana. Sayangnya, penembak jitu Yahudi men-dor suami, meninggalkannya sebagai janda dengan tujuh anak kecil.
Teror dan perampasan pun tidak berhenti bahkan setelah Israel didirikan. Penduduk di dua desa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen di Palestina, yaitu Iqrit dan Biram, yang pada akhir Perang Arab-Israel berada di wilayah Israel utara, dipaksa keluar pada November 1948. Mereka diberi tahu dapat kembali dalam waktu dua minggu, tetapi Israel yang didirikan di atas darah warga Palestina itu tidak pernah mengizinkan mereka kembali bahkan hingga hari ini.
Pada dekade-dekade berikutnya, umat Kristen Palestina yang tetap berada di wilayah yang diklaim Israel menghadapi rezim apartheid. Sama seperti Muslim Palestina, mereka dikenakan sekitar 65 Undang-undang (UU) diskriminatif. Menurut LSM Adalah The Legal Center for Arab Minority in Israel, UU itu bersifat eksplisit. Beberapa dibuat dengan cara yang tampak netral, tapi berdampak berbeda terhadap warga Palestina.
UU yang dimaksud, membatasi hak-hak warga Palestina di semua bidang kehidupan. Mulai dari hak kewarganegaraan, partisipasi politik, hak atas tanah dan perumahan, pendidikan, budaya dan bahasa, beragama, dan proses hukum selama penahanan.
Salah satu UU diskriminatif yang paling awal adalah UU Kepulangan Tahun 1950, yang menjamin hak orang Yahudi untuk datang ke Israel, menetap, dan secara otomatis menerima kewarganegaraan. UU ini tidak memberikan hak yang sama kepada penduduk asli Palestina yang diusir. Meskipun faktanya PBB telah menetapkan dalam Resolusi 194. Bahwa warga Palestina harus diizinkan kembali ke tanah air mereka dan diberi kompensasi atas kehilangan rumah mereka.
Sementara, UU diskriminatif terbaru yang ditandai pada Knesset menyetujui RUU Negara Bangsa pada 2018. Di dalamnya, secara resmi dinyatakan Israel sebagai negara bangsa bagi orang-orang Yahudi, sehingga semakin memperkuat hukum supremasi Yahudi. Tak ayal UU ini kemudian berhubungan dengan kekerasan dan diskriminasi terhadap umat Kristen Palestina yang semakin meningkat.
Dikutip dari The Times of Israel, serangan teroris oleh kelompok radikal Israel, yang menargetkan gereja, pemakaman, dan properti Kristen telah menjadi kejadian hampir setiap hari yang secara nyata meningkat intensitasnya apalagi selama hari raya Kristen.
Baca Juga: Magdalene Primer: Yang Perlu Diketahui tentang Isu Palestina-Israel
Penghapusan Populasi Umat Kristen Palestina
Lebih dari itu, kekejaman rezim apartheid juga berpengaruh pada penghapusan perlahan populasi umat Kristen Palestina. Populasi penduduk Kristen telah menurun hingga 12 persen atau hanya hanya 11.000 orang saja, catat Third World Resurgence pada 2019. Ramzy Baroud selaku penulis mengatakan penghapusan komunitas Kristen Palestina memang merupakan hal yang menguntungkan bagi Israel. Sebab, mereka ingin menampilkan ‘konflik’ di Palestina sebagai konflik agama, sehingga mereka dapat mengecap dirinya sebagai negara Yahudi yang terkepung di tengah populasi besar Muslim di Timur Tengah.
“Keberlanjutan keberadaan umat Kristen Palestina tidak menjadi faktor yang baik dalam agenda Israel ini,” tulis Baroud.
Hal ini terlihat dari pernyataan jajaran tinggi pemerintah Israel. Pada Desember 2023 misalnya, Presiden Israel Isaac Herzog mengeklaim, perang Israel di Gaza dimaksudkan untuk menyelamatkan peradaban Barat, karena Israel diserang oleh jaringan jihad. Lalu, pada bulan yang sama, Wakil Wali Kota Yerusalem, Fleur Hassan-Nahoum, menanggapi laporan serangan penembak jitu Israel terhadap Gereja Keluarga Kudus di Gaza dengan mengeklaim tidak ada umat Kristen maupun gereja di Gaza.
Para pemimpin Israel sengaja menyamakan identitas Palestina dan Muslim, sehingga menempatkan umat Kristen Palestina di bawah penghapusan retoris dan literal. Inilah mengapa untuk menghapuskan eksistensi mereka, Israel menargetkan komunitas kecil ini dengan berbagai kebijakan diskriminatif dan serangan tertarget pasca-7 Oktober.
Sebelum 7 Oktober, penghapusan eksistensi umat Kristiani Palestina terjadi sistematis. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Dar Al-Kalima pada 2017 yang berdasarkan wawancara dengan 1.000 warga Palestina setengah dari mereka beragama Kristen menemukan tekanan pendudukan Israel, pembatasan yang terus berlanjut, kebijakan diskriminatif, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan tanah menambah rasa putus asa di kalangan umat Kristen Palestina. Itu mendorong mereka ke dalam situasi putus asa saat tidak ada masa depan yang bisa dibayangkan.
Di Gaza, situasinya jauh lebih menyedihkan. Seperti mayoritas Muslim, umat Kristen di Gaza terputus dari dunia luar, termasuk tempat-tempat suci Kristen di Yerusalem, Betlehem, dan Nazareth. Setiap tahun, Israel memberikan sejumlah izin terbatas untuk melakukan perjalanan ke Tepi Barat dan Israel untuk merayakan Natal atau Paskah. Karena memburuknya perekonomian yang disebabkan oleh blokade Israel yang kemudian disusul pemboman berturut-turut selama lebih dari 15 tahun terakhir, komunitas Kristen di Gaza pun telah kehilangan rata-rata lima persen populasinya setiap tahun.
Baca Juga: Epistemisida: Saat Israel Bakar Buku, Bom Sekolah, dan Hapus Sejarah Palestina
Diamnya Umat Kristen Barat
Sudah bertahun-tahun lamanya umat Kristen Palestina mengalami kekerasan. Terakhir terjadi pasca-7 Oktober di mana militer Israel mengebom Gereja Ortodoks Yunani Saint Porphyrius di Kota Gaza, gereja tertua di Gaza yang dibangun pada abad ke-12. Dua minggu kemudian, Israel mengebom dan menghancurkan Pusat Kebudayaan Ortodoks, Gereja Baptis Gaza, Dewan Gereja Timur Dekat, Biara Misionaris Amal, serta Rumah Sakit Al-Ahli di mana hampir lima ratus warga Palestina terbunuh.
Serangkaikan kekerasan ini memilukan bukan hanya karena Israel secara jelas menargetkan warga Palestina yang tengah berlindung. Namun, juga komunitas umat Kristen yang jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Ironisnya dari kekejaman yang diperlihatkan terang-terangan ini, umat Kristen dunia terutama Barat cenderung diam. Pemberitaan terhadap kekerasan sistemik yang mereka hadapi juga tak banyak apalagi sampai viral di mana-mana.
Pada Oktober 2023, dua belas organisasi Kristen Palestina sampai mengirimkan surat kolektif kepada para pemimpin gereja di negara-negara barat. Dalam surat berjudul A Call for Repentance: An Open Letter from Palestinian Christians to Western Church Leaders and Theologians, justru banyak orang Kristen di Barat menawarkan dukungan terhadap Israel melawan rakyat Palestina. Umat Kristen Palestina lalu meminta pertanggungjawaban para pemimpin gereja dan teolog Barat yang mendukung perang Israel atas keterlibatan mereka dalam kejahatan Israel terhadap Palestina.
Mayssoun Sukarieh, dosen senior di Departemen Pembangunan Internasional di King’s College London dalam artikelnya memberikan penjelasan. Standar ganda terkait respons umat Kristen dunia terutama Barat terhadap penderitaan Kristen Palestina bisa dipahami lewat analogi yang diungkapkan Mahmood Mamdani dalam bukunya Good Muslim, Bad Muslim (2004).
Dalam buku ini, Mamdani mencatat perbedaan yang digambarkan di Barat antara Muslim yang baik dan yang buruk. Perbedaan ini tidak terletak pada karakteristik budaya atau agama internalnya, melainkan posisi mereka terhadap Amerika dan Barat. Sebab, penilaian ‘baik’ dan ‘buruk’ merujuk pada identitas politik bukan budaya atau agama.
Sederhananya, seorang Muslim yang baik adalah mereka yang pro-Amerika (modern, sekuler, dan kebarat-baratan). Sebaliknya, Muslim yang buruk adalah anti-Amerika (doktrinal, anti modern, dan anti Barat).
Dengan menggunakan logika ini, Sukarieh menjelaskan posisi umat Kristen di Irak dan Suriah yang digambarkan sebagai umat Kristiani yang baik yang harus dibela, bukan karena identitas atau budaya Kristen yang melekat. Namun karena mereka sedang diserang oleh ISIS (Muslim jahat), musuh Amerika. Namun umat Kristiani di Palestina tidak boleh dibela karena mereka mengalami nasib sial karena diserang oleh Israel, yang merupakan sekutu setia Amerika. Umat Kristen Palestina secara efektif ditafsirkan sebagai umat Kristen yang buruk, yaitu umat Kristen yang menolak bertindak sebagai minoritas.
Sehingga, kata Sukarieh, menjadi seorang Muslim yang baik atau seorang Kristen yang baik di Timur Tengah, kelangsungan hidup seseorang harus selaras dengan kepentingan geostrategis Amerika, Barat, dan Israel. Karena itu, umat Kristen di Palestina tidak dipandang setara. Bahkan kata Pendeta Munther Isaac pada Desember 2023, melansir Al Jazeera, kekerabatan dalam Kristus tidak mampu melindungi mereka.
Karena itu, Pendeta Isaac memberikan saran sederhana yang radikal. Saat kebaktian “Kristus dalam Puing-puing: Liturgi Ratapan” di Gereja Natal Lutheran Injili di Betlehem, ia berupaya membalikkan narasi yang berlaku mengenai umat Kristen yang baik dan buruk yang telah mengatur tanggapan Barat terhadap genosida di Gaza.
“Gereja Afrika Selatan mengajari kita konsep ‘teologi negara’ yang didefinisikan sebagai ‘pembenaran teologis terhadap status quo dengan rasisme, kapitalisme, dan totalitarianismenya. Jika kita, sebagai umat Kristiani, tidak marah dengan genosida ini, dengan mempersenjatai Alkitab untuk membenarkan hal tersebut, maka ada sesuatu yang salah dengan kesaksian Kristiani kita, dan mengorbankan kredibilitas Injil,” tegasnya.