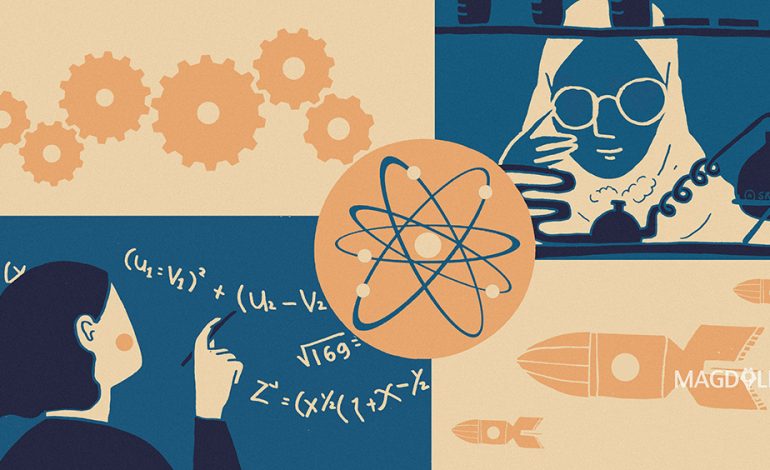Baru-baru ini media sosial diramaikan oleh twit dari Revina VT, pemilik akun @tucarino_, yang menyebut dirinya merasakan “polusi visual” saat berdekatan dengan seorang perempuan di tempat kebugaran tubuh (gym). Revina mengecam orang-orang yang percaya diri menggunakan sports bra serta celana pendek yang memperlihatkan sebagian bokong berkulit hitam. Ia juga menyebut perempuan tersebut berbau badan tidak sedap.
Ketika disebut sebagian warganet bahwa ia melakukan body shaming, Revina bersikukuh jika alasannya mengatakan itu karena ia tidak setuju dengan afirmasi bahwa semua bentuk tubuh itu cantik. Menurutnya, kampanye body positivity yang selama ini banyak disuarakan itu toksik. Pasalnya, kampanye semacam itu mendorong orang-orang berbadan gemuk untuk tidak berolahraga dan nantinya berpotensi terkena beragam penyakit seperti diabetes, stroke, obesitas, dan serangan jantung.
Pernyataan Revina itu problematis karena beberapa alasan. Pertama, dia tidak mengakui sudah melakukan body shaming. Kedua, pernyataan Revina yang mengkritik kampanye body posivitity itu sebenarnya sudah jamak dilakukan banyak pihak, hanya saja kebanyakan dari mereka mengkritik dari segi gerakan dan nilai, bukan dengan mencari justifikasi untuk melakukan body shaming.
Lalu, apakah benar kampanye body positivity itu toksik dan membuat orang jadi tidak mau mengubah bentuk badannya?
Bermula dari fat acceptance
Akar dari kampanye body positivity sendiri sebetulnya berasal dari gerakan fat acceptance pada 1967. Pada periode tersebut, mereka yang berbadan gemuk, apalagi berkulit hitam dan transgender, kerap kali mendapat perlakuan diskriminatif dan perundungan karena bentuk badan dan identitasnya. Di tengah masyarakat dan industri fashion yang mengagungkan bentuk badan kurus dan putih, fat phobia menjadi sesuatu yang normal ditunjukkan oleh orang-orang.
Hal tersebut kemudian membuat mereka yang bertubuh gemuk sulit mendapatkan pekerjaan. Di beberapa tempat umum, bahkan ada larangan bagi mereka untuk duduk karena dianggap membuat orang lain tidak nyaman.
Gerakan fat acceptance muncul sebagai respons orang-orang gemuk melawan diskriminasi yang telah sering mereka terima dari masyarakat. Sebanyak 500 orang berkumpul di Central Park, New York City, Amerika Serikat saat itu, sembari membakar buku-buku diet dan foto model bertubuh kurus mereka mengekspresikan aksi protes.
Baca juga: 5 Kebiasaan ‘Body Shaming’ yang Harus Kita Hentikan
Mereka secara keras mengkritik bagaimana masyarakat secara sistematis dibuat percaya bahwa tubuh terbaik adalah yang langsing dan putih. Dalam aksi protes itu, mereka menuntut agar mendapatkan perlakukan adil, perlindungan, dan kesempatan yang sama terlepas dari bentuk badan atau warna kulit mereka.
Pada tahun yang sama, Llewelyn Louderback menulis sebuah kritik di Saturday Evening Post yang berjudul More People Should be Fat karena istrinya yang gemuk sering mendapat perlakuan diskriminatif. Selain itu, bersama temannya Bill Fabrey, Louderback berinisiatif mendirikan organisasi bernama National Association to Advance Fat Acceptance (NAAFA) yang berfokus pada advokasi dan pelayanan orang-orang gemuk terdiskriminasi.
Sejak saat itu, gerakan tersebut tidak hanya dianggap mengadvokasi orang-orang gemuk saja melalui fat acceptance. Ia juga hadir sebagai simbol perlawanan orang-orang yang termarginalkan karena bentuk tubuh dan identitasnya seperti orang-orang kulit hitam, transgender, queer, dan kelompok disabilitas.
Body positivity dalam budaya pop
Pada 1996, gerakan body positivity semakin populer dengan kemunculan thebodypositive.org yang diprakarsai oleh Connie Sobczak dan Elizabeth Scott. Sebagai platform, mereka berfokus memberikan edukasi dan berkampanye agar orang-orang mencintai dirinya sendiri dengan bentuk tubuh yang beragam, serta berhenti membandingkan tubuhnya dengan standar tubuh ideal yang direpresentasikan oleh media, iklan, dan industri fashion.
Menurut Sobczak, motif awal gerakan ini berangkat dari pengalaman buruknya saat harus kehilangan sang kakak perempuan yang meninggal pada usia 36 tahun. Selama hidupnya, sang kakak mengalami body shaming yang membuatnya melakukan implan payudara dan berimplikasi pada tubuhnya yang mulai digerogoti penyakit. Sobczak pun sempat merasakan bulimia sejak remaja karena terus mengalami hal yang sama. Semenjak itu, gerakan fat acceptance perlahan bergerser ke arah body positivity.
“Kami datang bersama untuk membuat tempat aman, di mana kita tidak berusaha untuk membandingkan, bebas dari penghakiman. Setiap orang bebas mendefinisikan dirinya dan tubuhnya,” kata Sobczak.
Baca juga: Feminisme dan Budaya Pop: Jangan Hanya Mengganti Saluran
Kesadaran orang akan pentingnya representasi dan keberagaman membuat gerakan body positivity bisa diterima masyarakat serta menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Di Hollywood, para selebritas mulai menyelipkan pesan body positivity lewat lagu-lagu mereka. Sebut saja penyanyi plus-size paling digandrungi, Lizzo, dengan berbagai lagunya tentang tubuh serta body shaming; Demi Lovato dengan lagu “Confident”; Anne Marie dengan “Perfect”; Meghan Trainor dengan “All About that Bass”; Mary Lambert dengan “Secrets”, dan yang terbaru adalah penyanyi muda Billie Eilish yang membuat video tentang body shaming.
Di Indonesia, meski belum semasif Hollywood, gerakan body positivity sudah mulai terdengar dalam sepuluh tahun terakhir. Penyanyi pop Tulus misalnya, menulis lagu “Gajah” pada 2014 yang menceritakan pengalamannya sejak kecil mendapat perundungan karena badannya yang gemuk. Baru-baru ini, Tara Basro pun mengampanyekan body positivity. Selain itu, ada musisi Kartika Jahja yang aktif menyuarakan body positivity sejak 2012 dengan slogan “Tubuhku Otoritasku”.
Di negara yang masih kental konservatismenya ini, kampanye yang Kartika lakukan pada awalnya mendapat banyak backlash dari orang-orang. Ia dianggap mengajak orang untuk mengumbar aurat. Padahal menurutnya, esensi dari kampanye body positivity adalah penerimaan bentuk tubuh dan penghentian standar tubuh ideal yang sering kali tidak realistis.
“Pada saat itu [awal berkampanye], jarang banget orang yang paham apa yang gue sampaikan. Sekarang mungkin sudah mulai bisa diterima dan banyak orang yang nanya-nanya emang gimana sih, body positivity itu. Yang ngomongin juga banyak. Dan kabar gembiranya, sekarang ini enggak cuma di lingkaran aktivis aja [kampanye body positivity dilakukan], tapi juga lebih inklusif menggapai orang-orang biasa,” ujar Kartika kepada Magdelene.
Hal serupa juga dirasakan oleh seniman Ika Vantiani. Menurut Ika, masih banyak orang yang salah kaprah memahami body positivity sebagai sesuatu untuk memvalidasi kita berbuat tidak baik pada diri kita sendiri. Padahal baginya, body positivity itu merupakan bentuk perlawanan ide yang kuat dan penting untuk dipahami supaya perempuan bisa mendefinisikan dirinya dan tubuhnya, bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan.
“Kita dari kecil dibombardir berbagai ekspektasi terhadap tubuh kita, entah itu dari orang tua, pacar, iklan, atau media. Ini menjadikan perempuan kesulitan mendefinisikan dirinya sendiri. Kita dibentuk untuk benci badan kita. Padahal, bentuk badan tidak mengurangi nilai kita sebagai manusia. Ini yang gue sebut self-acceptance,” ujar Ika kepada Magdalene.
Body positivity itu merupakan bentuk perlawanan ide yang kuat dan penting untuk dipahami supaya perempuan bisa mendefinisikan dirinya dan tubuhnya, bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan.
Kritik terhadap body positivity dan isu kesehatan
Gerakan body positivity memang telah populer dalam beberapa dekade terakhir. Tetapi, gerakan ini tak lepas dari banyak kritik oleh berbagai pihak, termasuk dari sisi kesehatan seperti yang diutarakan Revina.
Salah satu penggiat body positivity dan penulis buku Fat Girl On A Plane, Kelly DeVos menulis kritiknya di New York Times pada 2018 dengan judul “The Problem With Body Positivity”. Kelly yang sebelumnya sangat pro terhadap body positivity, malah berbalik mengkritik gerakan ini setelah terkena diabetes. Menurutnya, banyak orang dalam gerakan ini justru tidak mendukung ketika orang berusaha menurunkan berat badannya karena dianggap secara psikologis merupakan bagian dari fat shaming.
Ika Vantiani beropini, banyak miskonsepsi terhadap body positivity yang berujung pada penyerangan, padahal secara esensi, pesan body positivity itu bukan berarti melarang orang untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik dan sehat. Penekanan gerakan ini lebih kepada penerimaan seseorang akan tubuh dia apa pun bentuknya, dan usaha membebaskan diri dari penghakiman masyarakat yang punya standar ganda. Karenanya, jika ada orang yang mengku menjalankan body positivity namun masih menghakimi mereka yang mau menurunkan berat badan karena kesehatan, itu bukan lagi disebut body positivity, tambah Ika.
“Intinya gini, apa pun bentuk badan lo, enggak mengurangi nilai lo sebagai manusia. Apa pun bentuk badan lo, lo berhak dapat kehidupan layak. Enggak semua tubuh gemuk itu sakit, yang tahu badan kita ya kita,” ujar Ika.
Aktivis isu kekerasan dan konsultan komunikasi, Shera Rindra menyatakan, banyak orang yang tidak memahami tentang obesitas secara baik dan mendalam. Menurutnya, seseorang yang bertubuh besar atau di luar dari standar tidak melulu karena gaya hidup tidak sehat dan malas berolahraga. Ada banyak faktor yang menyebabkan bentuk fisik seseorang gemuk seperti hormon, pubertas, efek obat, DNA, dan lain sebagainya.
Baca juga: Tubuh Kurus Tak Luput dari ‘Body Shaming’
“Aku kasih contoh diri sendiri, ya. Aku olahraga cukup rutin. Pola makanku cukup teratur, porsi makanku juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan beberapa teman yang tubuhnya jauh lebih kecil dariku. Bahkan, aku jarang sekali mengonsumsi daging, setiap malam aku makannya sayuran saja dan minim karbohidrat. Tapi, karena aku punya masalah metabolisme tubuh, gaya hidup itu tidak membuatku serta merta jadi langsing,” ujar Shera kepada Magdalene.
Kartika pun mengatakan pernah diserang oleh seorang dokter di media sosial yang menuduhnya mempromosikan obesitas. Menurut Kartika, orang-orang yang menyerang gerakan body positivity dengan isu obesitas justru secara tidak langsung melakukan penghakiman dengan menganggap orang-orang bertubuh besar itu tidak sehat, tanpa menggali apa usaha yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Di lain sisi, mereka yang bertubuh terlalu kurus pun bisa saja punya penyakit yang serius.
“Yang bantu nge–counter dokter itu bahkan bukan gue, melainkan ada dokter lain yang bilang kalau kita enggak pernah tahu proses dan dalemnya orang gimana. Masa ada kampanye penerimaan bentuk tubuh disebut mempromosikan obesitas? Satu hal yang pasti, kalaupun orang itu emang bener punya penyakit, emang body shaming bisa bantu [menyembuhkannya]?” ujar Kartika.
Menjadi tokenisme
Seiring populernya body positivity, industri fashion yang terus-terusan dikritik karena hanya menyediakan pakaian untuk mereka yang bertubuh kurus, kemudian melirik pasar plus-size sebagai sesuatu yang menjanjikan. Sekarang ini, banyak merek fashion dan kecantikan yang mulai mengadopsi pesan body positivity sebagai slogan untuk kesuksesan kampanyenya merauk lebih banyak lagi pembeli.
Model-model plus-size pertama yang cukup menggemparkan dunia adalah Ashley Graham yang muncul di sampul majalah Vogue di Inggris dan Amerika pada 2017. Ia didapuk jadi model pakaian renang oleh merek Swimsuits for All. Setelahnya, mulai bermunculan model-model plus size papan atas seperti Tara Lynn, Robyn Lawley, Marquita Pring, Sophie Dahl, Tess Holiday, dan masih banyak lagi.
Gerakan body positivity menjadi kehilangan esensinya akibat komersialisasi. Ini membuat gerakan tersebut tidak lagi menjadi tempat untuk mereka yang terdiskriminasi dan termarginalkan untuk unjuk diri sebagaimana misi awal fat acceptance.
Merek celana dalam terkemuka Aerie misalnya, mulai mengampanyekan body positivity dengan representasi berbagai bentuk tubuh dan perempuan disabilitas pada 2018. Aerie juga melaporkan adanya kenaikan penjualan sebesar 30 persen di kuartal pertama 2018. Di sisi lain, produsen lingerie Victoria’s Secret yang mempromosikan bentuk badan langsing mengalami penurunan pendapatan dan menutup hampir 20 tokonya di seluruh dunia pada 2019. Melihat tren, pada tahun tersebut akhirnya mereka merekrut model plus-size pertama Ali Tate Cutler. Di bidang pakaian olahraga, sejak tiga tahun lalu Nike mulai memproduksi pakaian plus-size.
Baik Aerie, Victoria’s Secret, maupun Nike memang secara perlahan mulai memperhatikan representasi tubuh, namun bukan berarti industri fashion sudah berjalan lebih inklusif. Kebanyakan strategi melibatkan orang-orang plus size yang mereka lakukan hanya menjadi tokenisme–yang penting ada perwakilan.
Komersialisasi gerakan body positivity ini juga menciptakan standar baru bagi model plus-size seperti mereka harus gemuk sesuai dengan standar yang ditentukan, bokongnya harus besar dan menonjol, wajahnya tidak boleh terlalu bulat, lehernya harus terlihat, dan masih banyak lagi. Hal tersebut menunjukkan jika industri fashion tidak benar-benar berusaha membuat produk yang lebih inklusif sebagaimana jargon body positivity.
Kartika Jahja mengaku pernah mengalami hal ini. Suatu kali ia diminta menjadi model pakaian oleh salah satu merek fashion yang sedang mengampanyekan body positivity. Namun ketika proses pemotretan, ia tidak boleh memperlihatkan perutnya karena kata sang editor, orang Indonesia masih “geli” melihat hal itu.
“Pokoknya banyak diatur-atur, deh. Jadi ya, menurut gue itu bullshit, mereka enggak bener-bener pengen nyebarin body positivity. Dan kita harus sadar sama startup activism semacam itu biar enggak terjebak,” ujar Kartika.
Lain halnya dengan Ika Vantiani yang pernah ditawari kerja sama mirip dengan Kartika oleh merek fashion lain. Ia lantas mengetahui bahwa hanya ada satu orang bertubuh gemuk yang diajak kerja sama, sedangkan yang lainnya bertubuh kurus dan sesuai standar “ideal” mainstream.
“Katanya mau inklusif, tapi kok cuma satu orang [yang gemuk]? Jadi, tokenisme ya, supaya ada aja gitu satu. Kan bukan begitu cara kerjanya [inklusivitas]. Yaudah gue enggak ngambil itu tawaran,” ujar Ika.
Baca juga: Kami Perempuan Melanesia, Kami Ada, dan Kami Cantik!
Body neutrality sebagai alternatif
Penulis buku Fattily Ever After: The Fat, Black Girls’ Guide to Living Life Unapologetically, Stephanie Yeboah menyadari adanya standar ganda yang mulai dipakai oleh industri fashion saat mengampanyekan body positivity. Dalam wawancaranya di The Guardian, ia mengkritik hal ini dengan mengatakan bahwa beberapa tahun ini, gerakan body positivity menjadi kehilangan esensinya akibat komersialisasi. Ini membuat gerakan tersebut tidak lagi menjadi tempat untuk mereka yang terdiskriminasi dan termarginalkan untuk unjuk diri sebagaimana misi awal fat acceptance.
Selain kritik ini, konsep self love dan body positivity menurut Yeboah sulit dipahami oleh sebagian orang sehingga muncul lagi gerakan lain yang sekarang ini ramai di media sosial yaitu body neutrality. Gerakan ini sebetulnya sudah muncul dari 2010 dan dicetuskan oleh Women’s Centre for Binge and Emotional Eating di Vermont, Amerika Serikat.
Konsep body neutrality lebih berfokus pada pesan untuk tidak membenci tubuh sendiri, tetapi tidak juga serta merta harus mencintai total tubuh dan menganggap semua bagian tubuh bagus seperti dalam pesan body positivity. Dengan konsep ini, tidak masalah jika kita mengakui kekuarangan dari badan kita, karena itu tidak mengurangi nilai kita sebagai manusia.
Meski tidak secara langsung mengategorikan karyanya sebagai produk body neutrality, Ika Vantiani pernah membuat karya dengan konsep serupa bertajuk I love my body, but.. yang merepresentasikan bahwa kadang mengakui kekuarangan diri adalah bagian dari penerimaan diri yang paling sederhana.
“Baik body positivity maupun body neutrality sama-sama perlu ada self acceptance dulu. Ya lu punya badan begini, lu terima itu, gimana lu melihat diri lu sebagai manusia yang bermakna,” ujar Ika.
Hal itu juga disampaikan oleh Shera, menurutnya secara konsep dan wacana keduanya keduanya tidak memiliki perbedaan signifikan.
“Masing-masing berangkat dari titik yang berbeda. Body positivity diawali dengan self-acceptance dari sisi fisik dulu baru bergeser ke arah lebih dalam ke sisi personal. Sementara, body neutrality langsung berangkat dari titik psikologis atau selama ini dinyatakan melalui titik tengah. Keduanya bisa saling menguatkan,” ujar Shera.