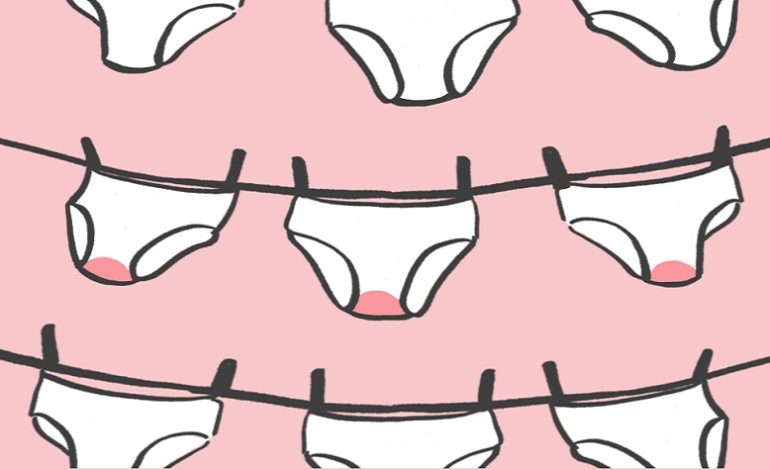
Ketika mendengar atau membaca kata “menstruasi”, yang pertama terlintas di kepala banyak orang pasti berhubungan dengan gender satu ini: perempuan. Terbayang di kepala betapa perempuan yang sedang menstruasi adalah sosok yang penuh emosi, sedang melebih-lebihkan kondisi, dan cenderung moody. Sungguh, berapa banyak mitos, stigma, dan diskriminasi yang tertuju pada perempuan yang sedang menstruasi? Ratusan!
Tapi, menstruasi tidak hanya milik perempuan. Tidak semua yang terlahir dengan rahim adalah perempuan. Sebagai seorang transpria yang baru menemukan diri sendiri kurang dari lima tahun lalu, perjalanan menerima kenyataan bahwa saya adalah laki-laki yang mengalami menstruasi, belum bisa menemui titik henti. Meski kadang disforia gender yang ditimbulkan tak lantas membuat kepala saya dan hari saya jadi berantakan, tapi tetap saja, dementor thoughts (alias pikiran buruk yang mengambil alih kebahagiaan saya) akan berkeliaran tanpa beban. Setiap sedang mandi, pikiran-pikiran seperti, “Ih, cowok kok menstruasi,” atau “Cowok mah coli, situ malah menstruasi,” itu muncul tanpa bisa dikontrol.
Satu racun yang terus menggema dalam kepala utamanya tiap kali saya menstruasi adalah, “Am I man enough?”. Racun yang tidak pernah benar-benar pergi meski sudah saya usir beberapa kali itu ternyata hasil dari didikan lingkungan tempat saya bertumbuh dewasa selama dua puluh sekian tahun. Bagaimana kehidupan seolah memiliki kriteria minimal untuk seseorang bisa disebut laki-laki, juga perempuan.
Baca juga: Asha bukan Oscar: Membongkar Miskonsepsi Soal Transgender
Dari situ, kehidupan memberi cabang lagi; standar laki-laki tampan, standar perempuan cantik. Seolah jika ada satu atau sekian hal dari diri sendiri yang tak sesuai kriteria, maka akan gugur pula identitas gender yang individu itu bawa seumur hidupnya. Laki-laki kok menstruasi? Perempuan kok suaranya berat dan punya rambut di wajah? Sungguh standar gender yang menyusahkan.
Gara-gara doktrin beracun mengenai standar laki-laki yang sudah kadung turun-temurun ini, saya dan banyak transpria lainnya harus pusing menghabiskan hari-hari kami mengkhawatirkan apakah hari ini kami sudah “cukup laki-laki” untuk menjalani hari. Belum selesai dengan disforia gender yang merusuh di kepala tiap menstruasi, kami juga harus berperang melawan stigma masyarakat tentang, misalnya, laki-laki yang membeli berbungkus pembalut.
Pergulatan lain yang harus dihadapi transpria, terutama saya, saat menstruasi adalah bagaimana sekuat tenaga menahan sakit akibat menstruasi hari pertama. Di kantor, saya tidak bisa seenaknya tiduran di sofa memakai krim penghilang rasa nyeri atau minyak. Selain menahan sakit, saya juga harus memikirkan alasan kepada rekan kerja ketika mereka kepo. Biasanya saya mengatakan, “salah makan, kebanyakan sambel.”
Baca juga: Transgender Dambakan Toilet Umum Uniseks
Jangankan dengan leluasa menerima rasa sakit akibat menstruasi, pengetahuan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi saja tidak semua transpria bisa punya. Ketabuan dalam masyarakat serta ketiadaan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah membuat beberapa dari kami jadi tidak mengerti mengapa siklus menstruasi kami bisa berganti-ganti, atau mengapa menstruasi kami terjadi dua minggu lebih tanpa henti. Kami tumbuh menjadi pribadi yang saling merundung apabila salah satu di antara kami sudah ada yang menstruasi atau lebih lambat dari pada yang lainnya.
Perempuan dianggap sumber masalah
Peristiwa biologis yang sejatinya memang milik seluruh manusia dengan rahim, dikerdilkan sedemikian rupa hingga hanya milik satu gender. Lalu disusun skenario sedemikian rupa agar para pemilik rahim yang diklaim semuanya adalah perempuan ini merasa dirinya sumber masalah, sumber aib, sumber keburukan utamanya saat mereka mengalami menstruasi dengan cara melahirkan mitos-mitos menstruasi seperti: “Jangan makan daging kalau datang bulan, nanti darahnya makin amis!”, “Jangan sampe tembus dong kalo lagi mens, jijik liatnya. Bikin malu”, “Emosian banget sih? PMS ya? Gitu mau jadi ketua, ntar kalo rapat pas lagi mens, semuanya dimarahin!”.
Baca juga: Queer Love: Belum Suntik Hormon dan Operasi, Apakah Saya Tetap Transpuan?
Tak hanya menjadikan perempuan merasa rendah terutama saat menstruasi, perempuan juga diajari untuk tidak menyebutkan proses peluruhan dinding rahim yang tidak terbuahi sperma tiap bulannya sebagai menstruasi secara gamblang, tapi “diperhalus” menjadi datang bulan, halangan, tamu bulanan, atau lagi dapet. Lalu pembalut diganti sebutannya menjadi roti jepang. Jadilah kami, para pemilik rahim yang beberapa di antaranya mungkin akan melahirkan manusia-manusia lain, tidak dipandang sebagai manusia secara utuh tanpa memandang apa yang ada di antara selangkangan kami.
Jadi ingat perjuangan kawan-kawan cis female tentang hak cuti menstruasi yang masih diperjuangkan terus menerus tapi terancam hilang begitu saja di Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kawan-kawan cis female saja masih banyak yang susah dapat izin menstruasi, bagaimana dengan kami yang tidak bisa mengambil cuti menstruasi karena kami dianggap laki-laki di mata masyarakat?
Menormalisasi menstruasi sebagai milik sebagian laki-laki mungkin akan jadi tantangan tersendiri. Tapi bagi kami, para transpria yang belum melakukan transisi medis, pola pikir seperti ini akan membantu kami melawan disforia gender bulanan, dan meyakinkan kami bahwa kami tetap laki-laki meski menstruasi. Kami juga akan mendapatkan penguatan dan pengakuan dari lingkungan tentang tidak goyahnya identitas kami meski tubuh kami sedang menstruasi.
Ilustrasi oleh Jemima Holmes.






















