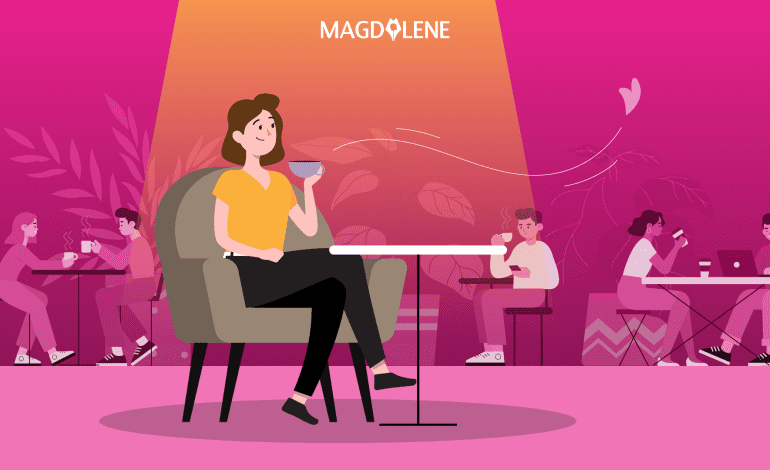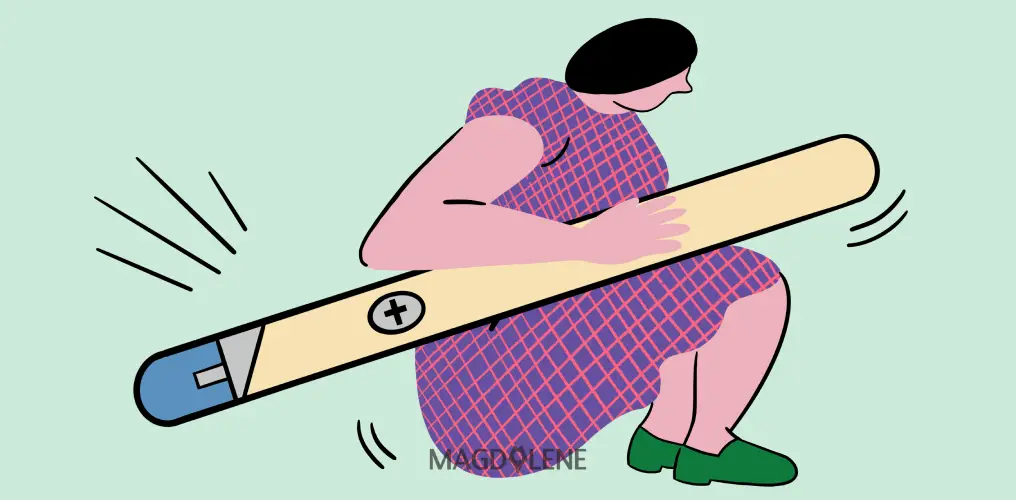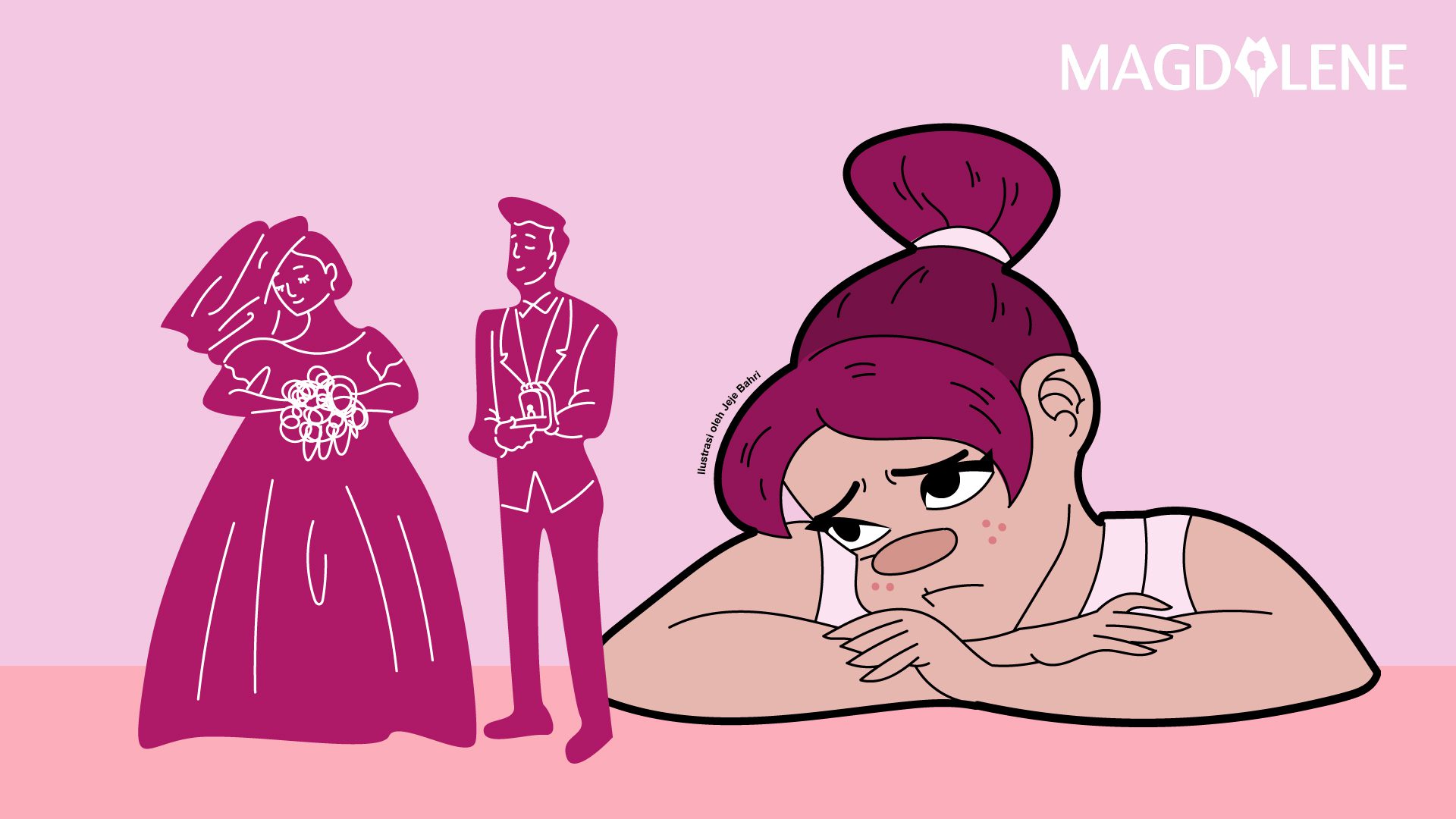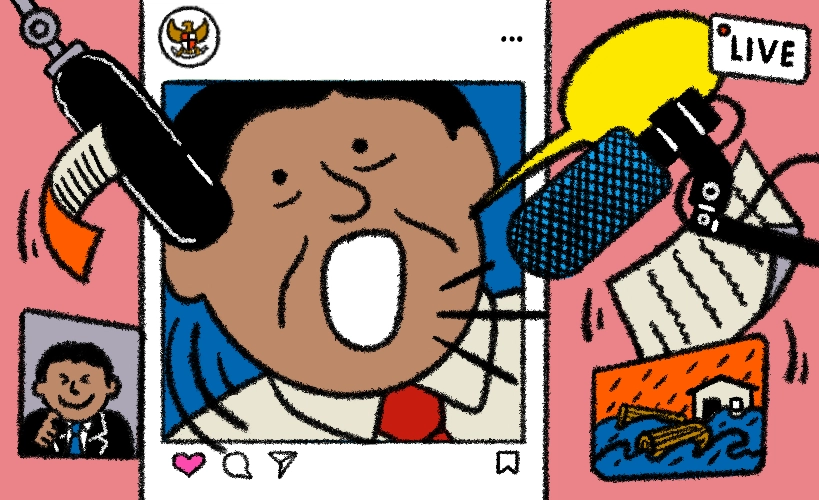Luka Turun-temurun Tionghoa Indonesia

“Pulang sana ke negaramu! Dasar Cina!”
Ucapan rasis begini sering diterima peranakan Tionghoa Indonesia era 70-an. Hanya karena kulitnya putih, mata sipit, dan nama khas Negara Tirai bambu membuat mereka mudah diidentifikasi sebagai “Cina”.
Tindakan rasis begitu juga dirasakan mamaku yang besar di era Orde Baru, masa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memojokkan keturunan Tionghoa–Indonesia secara terang-terangan.
Trauma yang dia rasakan tidak berhenti pada dirinya saja. Saat Tragedi Mei 1998, ia sedang mengandung aku. Dia pernah cerita betapa was-wasnya ia waktu itu. Selalu ketakutan ada orang yang mendobrak pintu rumah sewaktu-waktu, meskipun dia tinggal di kota kecil yang tidak mengalami kerusuhan. Tapi, informasi tentang tindakan rasisme yang menimpa orang-orang Tionghoa di Jakarta dan kota besar lainnya cepat tersebar. Berita di TV juga tidak bikin tenang.
Ketakutan karena perlakuan rasisme dan kebencian yang ia terima, lalu menurun ke aku. Ia mendidik aku dalam traumanya yang tidak terselesaikan.
Hal ini tak hanya dirasakan mamaku, tapi sebagian besar peranakan Tionghoa di Indonesia. Bahkan perilaku ini telah dirasakan sejak lama: Masa kolonial, Orde Baru, hingga kini era Reformasi, trauma menumpuk itu masih ada.
Kepahitan yang kini disebut generational trauma itu disebabkan kebijakan tidak berpihak yang membuat krisis identitas peranakan Tionghoa Indonesia. Namun, kini ada beberapa generasi baru yang menginginkan pembebasan diri dari lingkaran setan trauma sebagai keturunan Tionghoa Indonesia.
Baca juga: Ketika Kita Diwariskan Trauma dan Bagaimana Mengatasinya
Trauma Peranakan Tionghoa di Indonesia dari Masa ke Masa
Menilik dari sejarah, kebijakan diskriminatif di Indonesia bukan baru ada di era Orde Baru. Sudah sejak era Kolonial Belanda, ada sistem kelas sosial masyarakat yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda. Sistem ini yang menjadi bibit perseteruan antara mayoritas Indonesia dan orang Tionghoa–Indonesia, yang jadi minoritas.
Lia Nuralia dalam Struktur Sosial pada Rumah Pejabat Tinggi Perkebunan Zaman Hindia Belanda di Jawa Bagian Barat (2017) menggambarkan pembagian kelas itu dengan detail. Kelas atas adalah bangsa Eropa, kelas menengah terdiri dari bangsa Timur Asing, seperti Tionghoa, Arab, India, sementara kelas bawah terdiri dari bangsa Indonesia asli, atau yang disebut pribumi. Kelas sosial ini lalu menyebabkan ketidaksenangan pribumi kepada orang Tionghoa.
Ketidaksenangan itu dipupuk pemerintah Hindia Belanda agar rakyat tetap terpecah belah dan tidak melawan imperialisme yang sedang mereka jalankan.
Satu penyulut kebencian kepada etnis Tionghoa terjadi di saat Perang Jawa berlangsung. Seperti dikutip dari Rasisme Terhadap Etnis Tionghoa dari Masa ke Masa, Arman Dhani dari Tirto menulis, masyarakat membenci orang Tionghoa karena menjadi bandar pemungut pajak bagi Sultan. Bangsa Eropa melihat kecerdikan orang Tionghoa bisa mereka manfaatkan untuk menagih pajak di area kekuasaanya.
Hingga terjadi pembantaian Perang Jawa membuat hubungan pribumi dan Tionghoa makin renggang dan kebencian makin menyulut. Tragedi pembantaian itu menyebabkan ketakutan oleh orang Tionghoa terhadap warga pribumi, dan sebaliknya warga asli Hindia Belanda menganggap etnis Tionghoa sebagai mata duitan dan pemeras.
Kebencian itu masih tertanam hingga generasi selanjutnya, yaitu di era Orde Lama. Saat itu keluar sebuah kebijakan yang melarang orang Tionghoa Indonesia berdagang. Aturan itu keluar karena mereka dianggap memonopoli perdagangan dan membuat orang yang bukan Tionghoa–Indonesia kalah dagang.
Dalam artikel yang diterbitkan Republika, Menteri Perdagangan saat itu, Rachmat Muljomiseno berhasil membuat Sukarno menandatangani kebijakan rasialis tersebut. Dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1959, berisi larangan bangsa Tionghoa Indonesia berdagang di daerah di bawah tingkat kabupaten.
Sebenarnya Peraturan Pemerintah ini ditujukan hanya untuk orang Tionghoa yang tidak berstatus WNI. Namun, nyatanya kebijakan tersebut juga berpengaruh kepada semua warga Tionghoa yang berdagang di pedesaan, baik yang WNA atau WNI.
Akibatnya, ratusan ribu bangsa Tionghoa WNA terpaksa pulang ke Cina. Melihat kejadian tersebut, pemerintah Cina mengirimkan sebuah kapal untuk mengangkut mereka untuk kembali ke negara mereka berasal. Peraturan Pemerintah tersebut menyebabkan tegangnya hubungan Indonesia dan Cina. Namun, karena adanya perundingan antara Bung Karno dan Perdana Menteri Cho En Lai di Jakarta, permasalahan tersebut terselesaikan.
Trauma yang dialami etnis Tionghoa Indonesia belum berakhir, seperti yang dilihat di buku-buku sejarah di sekolah. Kepemimpinan Soeharto adalah masa-masa suburnya rasisme kepada keturunan Tionghoa Indonesia.
Dalam jurnal karya Leo Suryadinata, Indonesian Policies Toward the Chinese Minority Under the New Order (1976) disebutkan kebijakan diskriminatif yang diterima etnis Tionghoa Indonesia hadir dari spektrum ekonomi sampai sosial budaya.
Kebijakan-kebijakan yang ada di antaranya: Pembentukan “Sekolah Nasional Proyek Khusus” yang dibentuk setelah pelarangan sekolah Tionghoa Indonesia, aturan perubahan nama ke nama yang lebih “Indonesia”, mahalnya proses naturalisasi keturunan Tionghoa Indonesia, pelarangan kebudayaan dan agama yang berbau “Cina”, hingga kecurigaan akan komunisme yang ditempel pada orang Tionghoa.
Masih banyak lagi aturan diskriminatif yang melanggengkan perpecahan antara Tionghoa Indonesia dan orang Indonesia lainnya. Eskalasi tertinggi mungkin terjadi dalam Peristiwa Mei 1998.
Krisis ekonomi yang malah diboncengi kebencian terhadap etnis Tionghoa menjadi luka bagi para korban. Membuat makin renggangnya hubungan orang Tionghoa-Indonesia dan orang Indonesia lainnya.
Baca juga: Kamu Orang Mana, Kamu Orang Apa: Ketika Jadi Orang Indonesia Tak Cukup
Warisan Luka Yang Masih Mendarah Daging
Dalam makalah The Transgenerational Transmission of Memories about May ’98 Among Chinese Indonesians in Jakarta: Preliminary Findings, Nugroho dan Wibawa mengkaji trauma keturunan Tionghoa-Indonesia akibat kerusuhan Mei 1998.
Hasil kajian tersebut menunjukkan generasi terdahulu yang mengalami secara langsung kerusuhan Mei 1998 membentuk “pelajaran hidup” tentang bagaimana mengarungi dunia sosial sebagai anggota kelompok minoritas.
Secara tidak sengaja, untuk bertahan hidup generasi pertama membuat jarak sosial antara peranakan Tionghoa Indonesia dan orang Indonesia lainnya. Jarak ini juga menyebabkan kurangnya representasi orang Tionghoa dalam dinamika politik Indonesia. Mereka enggan atau jarang menceritakan Mei 1998 kepada anak mereka. Sebabnya, rasa tidak dimengerti oleh anak-anaknya, sehingga merasa tidak ada gunanya berdiskusi, atau sedih ketika harus mengingat kekerasan yang dialami generasinya.
Mereka baru mau bercerita ketika ditanya atau ada pergolakan sosial-politik yang sedang terjadi.
Dari “pelajaran hidup” menjadi prinsip hidup orang Tionghoa Inyang mengalami trauma. Untuk bertahan hidup orang tua mengajarkan anaknya untuk tidak boleh menarik perhatian, baik dengan teman, sekolah, atau politik.
Selain itu juga ada prinsip endogami—prinsip harus menikah dengan orang yang berasal dari sosialnya sendiri, misalnya dari lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman. Dalam kasus ini orang tua menganjurkan bahkan melarang tidak menikah dengan yang bukan Tionghoa–Indonesia atau berbeda agama.
Pembelajaran ini mendarah daging ke generasi selanjutnya. Banyak peranakan Tionghoa-Indonesia generasi selanjutnya memiliki pemikiran yang sama, karena memori Mei 1998 masih diajarkan dan mendarah daging.
Namun, ada juga generasi peranakan Tionghoa yang memiliki pandangan yang berbeda, mereka tidak setuju dengan beberapa prinsip tersebut. Kesadaran akan trauma dan sejarah kekerasan dan segregasi yang diterima etnis Tionghoa Indonesia membuat mereka menyadari lingkaran setan trauma ini. Hingga ada yang ada keinginan menjadi cycle breaker generational trauma.
Baca juga: Menjadi Cina di Indonesia: Luka Kami Masih Basah
Menjadi Cycle Breaker dari Trauma Turun-Temurun
Anak muda Tionghoa Indonesia yang sadar akan trauma turun temurun karena rasisme yang diterima. Aku sempat mengobrol dengan beberapa kawan Tionghoa-Indonesia muda yang mengenang Mei 1998 lewat didikan orang tuanya, atau memori samar-samar karena mereka masih terlalu kecil.
Rhenaldy Agustinus Ollo, yang akrab dipanggil Aldy adalah salah satu saksi mata kejadian 1998. Saat itu, ia masih berusia enam tahun.
Ketakutan akan trauma itu membuat cara didik orang tuanya jadi lebih protektif. Mereka berusaha menempatkan Aldy dan kakaknya di lingkungan yang aman dari sekolah hingga tempat tinggal.
“Kakak sekolah dari SD sampai SMA di sekolah swasta , kalau saya hanya SD nya saja, tapi SMP sampai kuliah di negeri,” jelas Aldy mengenai cara orang tua mereka berusaha memberi ruang aman setelah tragedi 1998.
Aldy menambahkan bawah kakaknya sempat mendapatkan perundungan saat masuk SD negeri, hingga ibu mereka memutuskan untuk pindah sekolah.
Latar belakang keluarga Aldy berbeda dengan prinsip endogami. Ibunya adalah perempuan Tionghoa-Indonesia, sedangkan ayahnya bukan. Hal ini berpengaruh langsung dengan keadaan sosial Aldy yang mengatakan dirinya tidak seperti chindo.
“Meskipun saya punya keturunan Chinese, but I don’t look like Chinese, terkadang merasa not belong on both side,” ungkap Aldy.
Selain Aldy ada juga generasi selanjutnya peranakan Tionghoa yang merasakan dampak dari diskriminasi kepada chindo. Charlenne Kayla, mahasiswi tahun terakhir di Jakarta adalah contoh lainnya. Kesadaran akan generational trauma bahkan ia jadikan topik skripsinya.
Menurut Charlenne trauma yang diterimanya bukan trauma personal semata, tetapi lebih ke trauma kolektif sebagai komunitas Tionghoa-Indonesia. Trauma yang terpupuk sejak adanya pembedaan kelas sosial di era kolonial. Ia merasakan adanya ketakutan di dalam orang tua saat mendidik dirinya, yang selalu cemas atas keamanan anak mereka.
“Gue sense ada ketakutan saat membesarkan gue gitu. Terus orang tua gue juga bilang kita orang Tionghoa cuma numpang, tapi itu cuma doktrin sudah lama banget kan,” tutur Charlenne padaku.
Charlenne melanjutkan, Tragedi Mei 1998 juga berdampak langsung pada kehidupannya terutama dalam konteks sebagai kelompok minoritas. Dia bilang, perempuan Tionghoa-Indonesia juga kerap menjadi sasaran tindak diskriminatif.
Sebagai contoh, saat ada tugas kuliah meliput Pemilu 2019–masa-masa kampanye calon presiden—ayahnya melarang Charlenne pergi, dengan alasan dia perempuan Tionghoa Indonesia. Trauma Mei 1998 bikin orang tuanya lebih protektif.
“Karena ada tindakan diskriminatif perempuan Tionghoa Indonesia dari pemerkosaan sampai dimasukin penjara karena dibilang membantu PKI. Gue merasa lebih dijagain banget gitu,” tambah Charlenne.
Ketakutan itu berdampak pada personal Charlenne yang sempat menolak identitasnya sebagai perempuan Tionghoa-Indonesia. Namun, karena bertemu dengan teman peranakan Indonesia dan membaca buku sejarah Tionghoa-Indonesia, ia jadi lebih menerima identitas diri dan ingin mengurai trauma generasi tersebut.
Namun, Charlenne paham proses itu tak mudah dan tak bisa dilakukan generasinya sendiri. Menghadapi lingkaran setan trauma itu perlu adanya komunikasi lintas generasi, dan dimulai dari orang tua yang perlu lebih terbuka. Charlenne berharap lebih banyak perbincangan mengenai sejarah Tionghoa Indonesia. Supaya generasi selanjutnya lebih paham akan generational trauma ini. Dan di sini peran pemerintah juga penting. Pengakuan dari negara dibutuhkan agar masyarakat bisa memproses duka mereka tanpa kebingungan.
“Pemerintah nggak pernah minta maaf kan, sebenarnya itu pelanggaran HAM apalagi ada upaya penghapusan identitas Tionghoa-Indonesia,” ucap Charlenne.
Senada dengan Charlenne, Elizabeth Dixon peneliti dari Universitas South Carolina mengatakan pentingnya keterbukaan akan pengalaman hidup dan trauma yang dialami.
Orang tua, selain membuka komunikasi dengan anak dan cucu tentang pengalaman hidup, juga perlu mengatasi trauma generasi itu sendiri. Hal ini didasari adanya pembuatan narasi baru dan pengulangan siklus, terlebih jika ada anggota keluarga yang membahas trauma tersebut. Anak-anak perlu mempercayai bahwa mereka aman dan dirawat oleh orang dewasa yang terpercaya.
Jika tidak ada kepercayaan anak-anak akan belajar melihat dunia dari perspektif trauma. Sehingga mempersulit terciptanya hubungan yang aman dan saling percaya untuk membangun memori kolektif yang sehat.
Trauma yang dialami peranakan Tionghoa-Indonesia hingga generasi saat ini—generasiku–tidak akan selesai jika tidak ada kesadaran dan komunikasi antargenerasi.