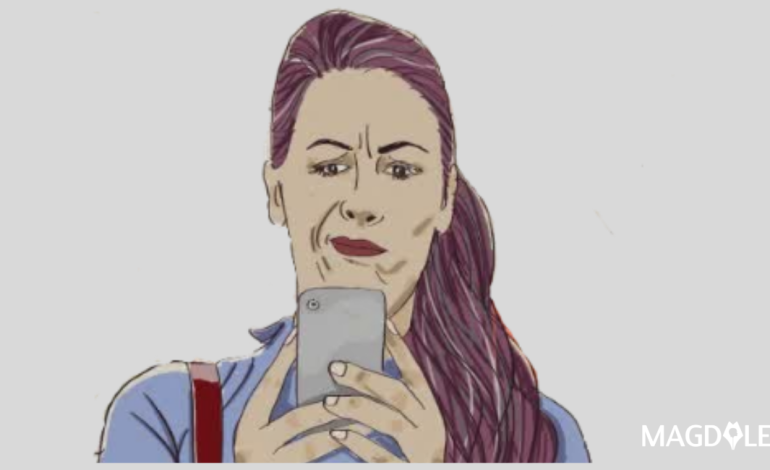Media Indonesia Krisis Pemberitaan Ramah Gender

Baru-baru ini pemberitaan di beberapa media mengenai atlet perempuan di Olimpiade Tokyo 2021 menjadi perbincangan yang ramai, bahkan sempat menjadi trending topic di Twitter. Alih-alih memberitakan tentang prestasi atlet, artikel-artikel tersebut malah berfokus pada bentuk tubuh, pakaian, hingga seksualitas atlet perempuan.
Dengan tujuan untuk meningkatkan klik pembaca, artikel-artikel tersebut diberi judul yang dipandang merendahkan perempuan, seperti “Bikin Ngilu, Pose Maharatu Bulutangkis Dunia Pakai Bikini” yang dimuat di situs viva.co.id, “Cantik Bak Model, Atlet Olimpiade Tokyo ini Pernah Digoda Cristiano Ronaldo” di suara.com, dan “5 Atlet Olimpiade Tokyo 2020 yang Memiliki Wajah Cantik, Bikin Mata Melotot” di bola.com. Judul yang jelas tidak ramah gender tersebut telah memancing kemarahan banyak netizen.
Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menyatakan, “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.” Penafsiran cabul dalam Kode Etik Jurnalistik adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam hal ini, wartawan tidak boleh membuat tulisan yang membangkitkan nafsu birahi.
Judul-judul berita yang melakukan objektifikasi dan seksualisasi perempuan seperti contoh-contoh di atas berpotensi melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Sayangnya banyak masyarakat bahkan korban sendiri belum memahami mekanisme pengaduan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan.
Baca juga: Menjual Perempuan dalam Berita Olahraga
Pemberitaan yang tidak ramah gender sebenarnya bukan hal yang baru di media Indonesia. Masih banyak media, khususnya media daring, yang pemberitaannya sangat seksis, termasuk dalam pemberitaan tentang kekerasan seksual. Sering kali liputan media tentang sebuah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan atau anak berpotensi menyebabkan korban mengalami kekerasan kedua kali.
Pemberitaan yang tidak ramah gender juga kerap menghasilkan sebuah kekerasan berbasis gender online (KBGO) bagi korban. Liputan kekerasan seksual seperti ini menampilkan wajah atau identitas korban, atau memaparkan kronologi atau detail yang sensasional dan tidak sensitif pada korban. Pemberitaan juga sering kali lebih menampilkan detail korban, bukannya pelaku. Hal ini semakin diperparah oleh komentar dari pembaca di artikel atau di media sosial yang kerap tidak berpihak pada korban, bahkan menyalahkan mereka.
Tidak hanya korban kekerasan seksual yang terdampak oleh pemberitaan tak bertanggung jawab seperti ini, namun juga seluruh keluarga mereka. Mulai dari stigma yang mereka dapatkan, doxing, hingga pelecehan susulan dan intimidasi mereka alami karena pemberitaan yang tidak bertanggung jawab.
Praktik seperti ini terus langgeng karena kebanyakan wartawan dan redaktur di perusahaan masih belum memiliki perspektif gender, sehingga pemberitaan mereka mencerminkan nilai-nilai patriarkal, bahkan misoginis. Di satu sisi budaya patriarkal dan pandangan maskulinitas yang usang dari para pemimpin perusahaan media membuat ketiadaan political will untuk berubah. Di sisi lain, perusahaan media melihat pemberitaan seksis sebagai sebuah cara ampuh untuk menarik pembaca dan meningkatkan traffic situs demi kepentingan bisnis mereka.
Baca juga: Percuma Hujat Ridho Permana, Wartawan ‘Online’ Memang Hidup dari Klik
Perspektif pasar memang masih sangat dominan bagi media di Indonesia. Meskipun sudah ada beberapa media yang kritis dalam pemberitaan dan aktif mendorong kebijakan-kebijakan penting seperti disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, namun jumlah mereka masih kalah dibandingkan media yang sensasional dan mengobjektifikasi perempuan.
Upaya mendorong kebijakan editorial yang berperspektif gender akhirnya selalu menemukan jalan buntu karena berhadapan dengan kepentingan sang pemilik media yang mengutamakan bisnis, sehingga mematikan rasa empati mereka. Ditambah lagi, perspektif gender juga masih belum merata dimiliki oleh para pemangku kebijakan seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers.
Kode Etik Jurnalistik jelas tidak cukup untuk memberikan pemahaman bagi wartawan dan perusahaan media tempat mereka bekerja. Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, dan beberapa organisasi pers sebagai lembaga pengawasan kerja-kerja jurnalistik harus memiliki pedoman pemberitaan yang ramah gender.
Tidak kalah penting adalah adanya Standar Operasional pemberitaan ramah gender dan edukasi yang menyeluruh di ruang redaksi di seluruh perusahaan media. Pada akhirnya ini akan berdampak positif bagi media juga, meminimalisir potensi gugatan dan laporan pencemaran nama baik yang dapat mengkriminalisasi wartawan.