‘Mental Load’: Beban Tak Terlihat Perempuan Pemikul Kehidupan
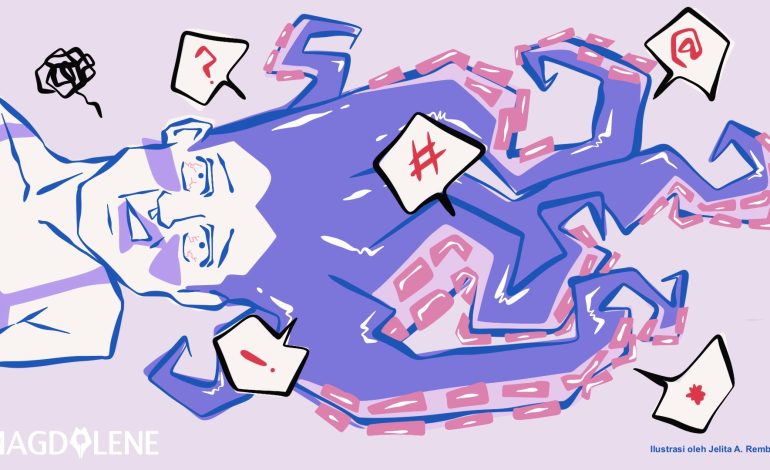
“Besok anak dan suami dimasakkin apa ya?”
Bahkan saat sedang beristirahat malam pun “Ela”, 52 masih memikirkan menu masakan apa yang bakal disiapkan esok hari. Selain menghitung kecukupan bahan makanan di kulkas, ia berencana membeli sebungkus nasi uduk untuk bekal anak bungsu ke sekolah. Enggak cuma itu, Ela perlu bersiasat agar kesibukan pagi di rumah tak membuatnya terlambat datang ke kantor pukul 08.00 tepat.
Memikirkan hal-hal ini bak rutinitas malam buatnya sebelum tidur. “Kadang sudah ngantuk-ngantuk masih kepikiran besok masak apa buat sarapan, cukup enggak bahannya? Belum lagi anak ke sekolah harus bawa bekal. Besok lebih baik naik kendaraan sendiri atau Transjakarta. Ada lagi enggak ya yang harus aku urus pagi-pagi sebelum ke kantor,” cerita Ela pada Magdalene.
Rutinitas mengelola kerja domestik di pagi hari ternyata berlanjut di jam makan siang. Tak jarang ia disibukkan dengan urusan tagihan rumah tangga yang ada saja masalahnya. Beberapa kali, Ela harus menyuap nasi ke mulut sambil mengisi token listrik yang habis, menelepon pekerja rumah tangga (PRT), atau sekadar mengecek kondisi anak.
“Bisa setengah jam sendiri mengurus pekerjaan rumah sambil makan siang di kantor. Memang sepertinya tidak ada waktu tenang buat ibu,” kata Ela lagi.
Sebagai ibu dari tiga anak, Ela mengaku kerap mengalami kelelahan. Meskipun sudah berbagi pekerjaan domestik dengan PRT, ia tetap merasa kewalahan karena ada beberapa hal yang harus ia urus sendiri. Misalnya, menemani si bungsu menyelesaikan pekerjaan rumah di malam hari, alih-alih bersantai sejenak usai bekerja.
“Serba salah, sih, memang. Di satu sisi capek ya capek, tapi kasihan juga anakku. Aku enggak mau kelihatan sebagai ibu yang enggak sayang anak. Enggak peduli. Udah jalannya kali ya jadi ibu tuh memang begini?” tuturnya.
Banyak perempuan yang senasib dengan Ela: Bekerja di ruang publik sekaligus dilimpahi beban mengurus kerja rumah tangga. Beberapa pekerjaan rumah tangga ada yang tampak sepele, tapi sebenarnya menyita energi dan rentan memperburuk kesehatan mental. Terlebih jika pekerjaan itu mesti ditanggung sendirian.
Hariati Sinaga, Dosen Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia menyebut fenomena tersebut sebagai mental load atau beban kerja mental. Dalam artikel “The mental load: building a deeper theoretical understanding of how cognitive and emotional labor overload women and mothers” (2021), Liz Dean mendefinisikan mental load sebagai efek mental dari kombinasi kerja kognitif (cognitive labor) dan kerja emosional (emotional labor) yang dibebankan pada perempuan.
Mulanya, kata Hariati, kerja emosional dimasukkan sebagai bagian dari jasa yang ditawarkan pada sektor pelayanan (hospitality). Dalam sektor ini, bagaimana pun situasinya, pekerja dituntut untuk mengelola emosi mereka sebaik mungkin.
Konsep ini lambat laun dikaitkan dengan kerja-kerja tak berbayar yang kerap dilakukan perempuan. Di rumah tangga, perempuan juga kerap dituntut untuk bisa jadi sosok yang mampu mengelola emosi mereka sebaik mungkin. Selelah apapun, perempuan seolah enggak boleh bilang capek, kata Hariati.
“Dalam konteks rumah tangga, emotional labor ini bisa digambarkan di mana seorang ibu, ketika ngemong anak, harus bisa mengontrol emosi. Ini juga soal bagaimana dia enggak boleh meneruskan rasa lelahnya ke anak. Ini beban tambahan. Ibu enggak boleh bilang capek. Seorang ibu sering kali enggak boleh komplain meskipun tugasnya menuntut dia kerja 24 jam,” ucapnya, (21/1).
Sepaket dengan kerja emosional, kerja kognitif (cognitive labor) juga jadi salah satu penyebab munculnya mental load pada perempuan. Istilah ini dapat diartikan sebagai kerja-kerja yang berfokus pada pikiran dan manajerial. Kerja-kerja itu biasanya tidak terlihat. Contoh, ibu dari luar tampak sedang istirahat atau rebahan, padahal otaknya tidak berhenti memikirkan urusan rumah.
“Cognitive labor merupakan dimensi lain dari bentuk kerja yang enggak kelihatan. Kalau pada konteks perempuan atau ibu, sering kali mereka enggak kelihatan ngapa-ngapain secara fisik, tapi dalam pikirannya melakukan pekerjaan. Misal, ‘besok makan apa? Anak dijemput siapa?’” ungkapnya.
Baca juga: #MerekaJugaPekerja: Banyak Perempuan Berhenti Kerja demi Urus Keluarga, Kenapa Masih Tak Diakui?
Apa Benar Mengurus “Printilan” Rumah adalah Tanggung Jawab Perempuan?
Hariati juga menjelaskan mengapa mental load cenderung lebih banyak terjadi pada perempuan. Penyebabnya adalah konstruksi gender tradisional yang mewajibkan perempuan untuk mengedepankan femininitasnya. Apalagi perempuan yang berperan sebagai istri dan ibu. Ada “tanggung jawab” berlapis yang disematkan pada identitas perempuan tersebut, sehingga sering menyebabkan mental load.
“Kerja emosional dan kognitif masuk ke dalam kerja-kerja reproduktif ya. Jadi, sangat berkaitan dengan konstruksi sosial soal peran gender. Dia sebagai perempuan saja biasanya sudah harus mengedepankan femininitas, seperti harus lembut, sabar, dan lain-lain. Apalagi dia sebagai ibu dan istri. Sudah pasti konstruksi gender yang berlapis ini membuat mereka pada akhirnya kena mental load,” jelasnya.
“Ibu itu memang terbukti memiliki mental load lebih besar daripada ayah. Karena itu tadi, ada banyak beban emosional yang terlibat, dalam kerja-kerja ibu di rumah tangga. Kemudian pada akhirnya makanya banyak ibu yang lebih cepat stres dibandingkan ayah. Pada akhirnya ya jelas, akan muncul banyak mental breakdown, parental burnout, dan depresi pada perempuan,” Kata Khadijah.
Enggak hanya itu, imbuh Hariati, konstruksi gender tradisional ini juga semakin diperkuat dengan double socialization atau sosialisasi dua peran berbeda yang disesuaikan dengan jenis kelamin mereka. Pada konteks kerja-kerja reproduktif, ini sudah disosialisasikan sejak kecil. Imbasnya, perempuan harus menjalani hidup sesuai dengan pembentukan perannya.
Pada artikel “Gendered Mental Labor: A Systematic Literature Review on the Cognitive Dimension of Unpaid Work Within the Household and Childcare” (2023), Natalia Reich-Stiebert menemukan, perempuan memang melakukan proporsi kerja–yang menyebabkan mental load–lebih besar dibanding laki-laki. Hal ini dapat terlihat terutama dalam pengasuhan dan pengambilan keputusan urusan anak. Hal ini turut diikuti dengan konsekuensi negatif yang kerap terjadi pada perempuan. Di antaranya stres, kepuasan hidup yang rendah, sampai dampak negatif pada pengembangan karier mereka.
Baca juga: Survei ILO-KIC: Kerja Perawatan Masih Dianggap Tanggung Jawab Perempuan
Mental Load dan Dampaknya pada Kesehatan Mental
Elizabeth Aviv, kandidat Doktor di University of Southern California, bersama kedua temannya, menemukan kerja kognitif dan emosional berlebihan memperburuk kondisi mental. Dalam artikel bertajuk “Gendered Mental Labor: A Systematic Literature Review on the Cognitive Dimension of Unpaid Work Within the Household and Childcare” (2024) ia menjelaskan, mental load berkaitan dengan depresi, stres, burnout, hingga kondisi hubungan yang buruk.
Khadijah Aulia, Psikolog Our Me Time dan Bicarakan Indonesia, turut mengamini hal ini. Kata dia, beban “printilan” rumah tangga yang secara kultural dilekatkan pada perempuan, berpengaruh pada kondisi kesehatan mental mereka.
“Ibu itu memang terbukti memiliki mental load lebih besar daripada ayah. Karena itu tadi, ada banyak beban emosional yang terlibat, dalam kerja-kerja ibu di rumah tangga. Kemudian pada akhirnya makanya banyak ibu yang lebih cepat stres dibandingkan ayah. Pada akhirnya ya jelas, akan muncul banyak mental breakdown, parental burnout, dan depresi pada perempuan,” Kata Khadijah.
Baca juga: Dari Beban Ganda hingga Bias Pribadi: Lagu lama Hambatan Perempuan Pekerja
Apa yang Bisa Dilakukan Sekarang?
Sebagai solusi, Khadijah bilang merekognisi perasaan dan rasa lelah pada perempuan bisa jadi langkah awal guna mengatasi mental load. Meskipun persoalan ini mengakar pada kultur patriarki masyarakat, tapi mempopulerkan istilah mental load di tengah masyarakat, cukup membantu perempuan untuk setidaknya mengenali dan memvalidasi perasaan mereka.
“Sebenarnya, sekarang ini, sangat bagus kita sudah mulai aware dengan yang namanya mental load. Ketika tahu istilah ini, kita jadi lebih paham dengan perasaan kita,” jelasnya.
Setelah rekognisi, komunikasi efektif bisa jadi solusi lanjutan untuk mengatasi mental load. Bersama pasangan, perempuan bisa mengatakan apa saja hal yang sebenarnya ia rasakan, dan membagi peran dalam rumah tangga sesuai dengan kesepakatan yang lebih adil.
“Harapannya, dari rekognisi ini, perempuan bisa mengomunikasikan bebannya secara efektif ke pasangan. Sebab, sebenarnya komunikasi efektif itu lebih mudah meminimalisasi mental load,” pungkasnya.
Artikel ini diproduksi oleh Magdalene.co sebagai bagian dari kampanye #WaveForEquality, yang didukung oleh Investing in Women, inisiatif program Pemerintah Australia.
Series artikel lain bisa dibaca di sini.






















