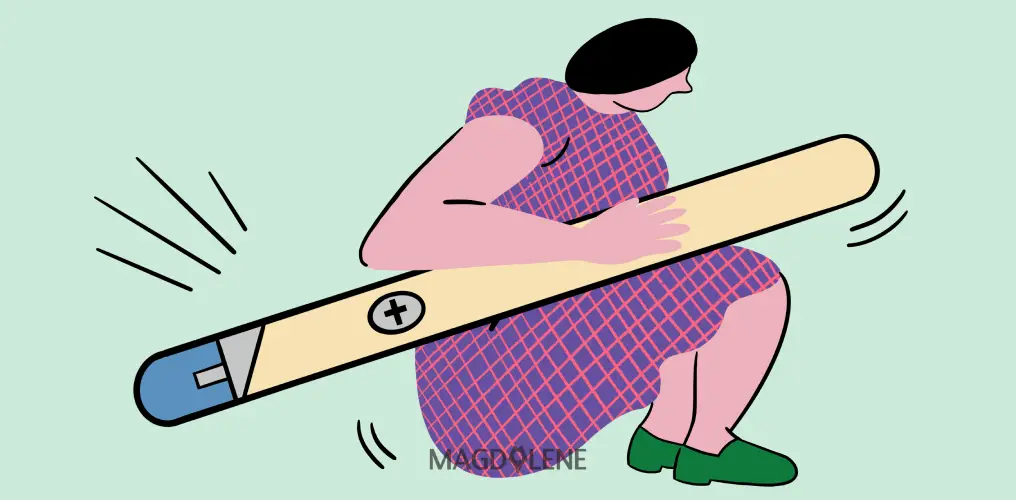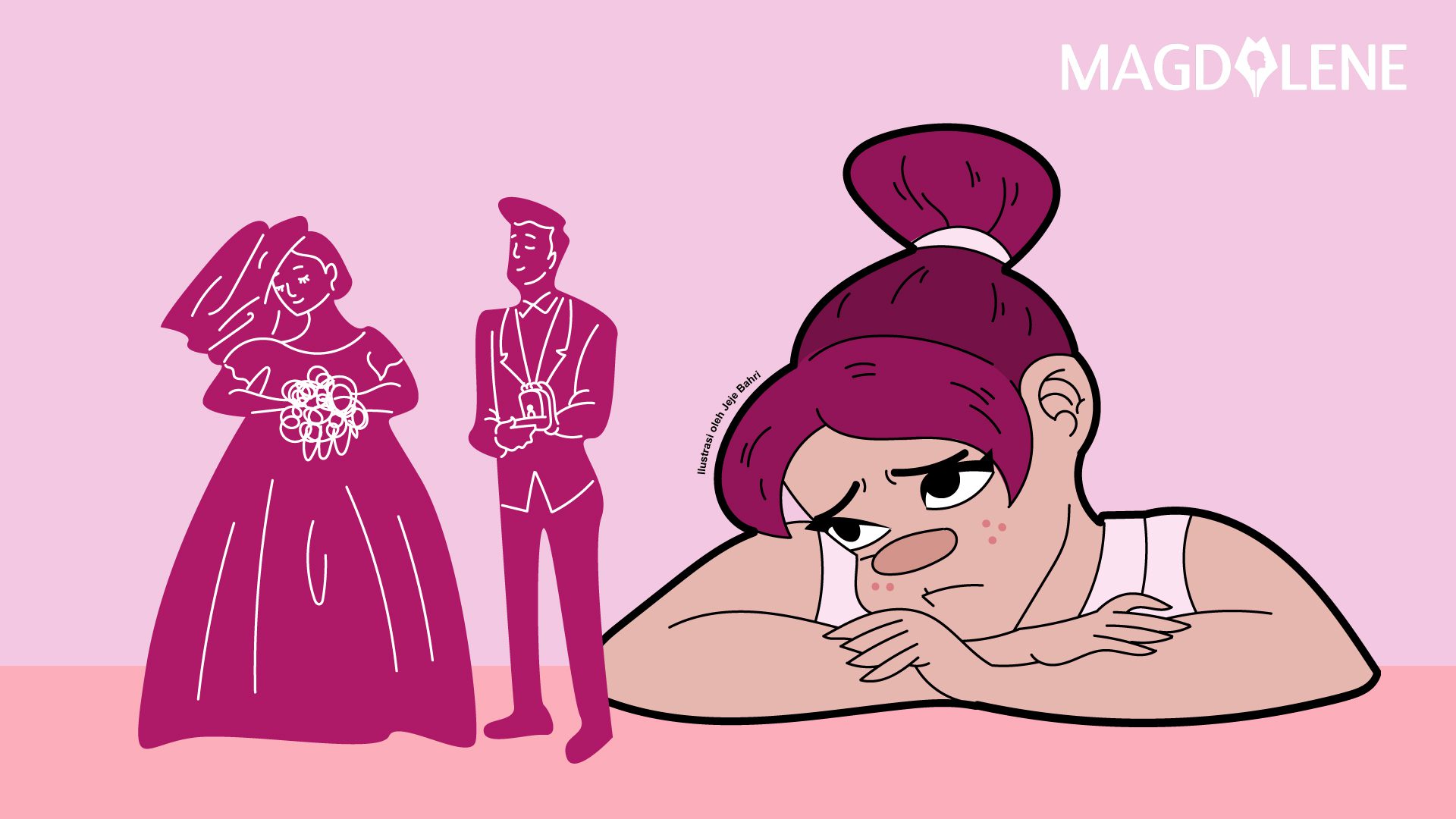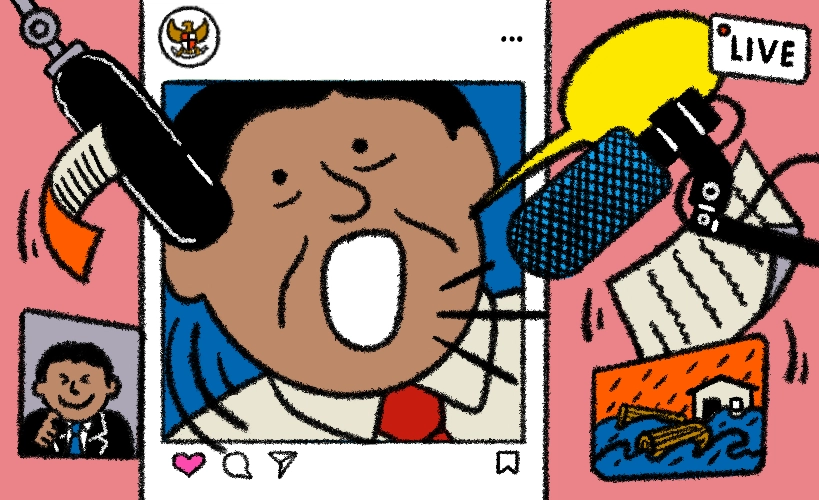Suatu sore di awal musim semi saat saya tinggal di Australia, ibu kost saya, Lucina, mengajak saya jalan-jalan. Ia tampaknya bisa merasakan kalau saya sedang murung. Tanpa banyak bicara, kami masuk mobil dan tiba-tiba ia membelokkan setir ke drive-thru Hungry Jack’s.
“Ayo kita beli es krim,” katanya ceria, lalu memesan dua cone es krim.
Ketika tiba di jendela pembayaran, Ibu Lucina menyerahkan dua dolar dengan santai. Tapi saat petugas menyodorkan dua cone es krim yang sudah meleleh di pinggirannya, ia langsung menolak dengan tenang, “Oh tidak, itu sudah mencair. Itu bukan punya saya.” Lalu ia menoleh pada saya dan berkata, “I paid it with a good two dollar. I’m not taking that.”
Baca juga: Pohon Menjulur ke Rumah Sebelah: Pelajaran Etika Bertetangga dari Australia
Kalimat itu tertanam di kepala saya: a good two dollar. Uang itu memang kecil secara nominal, tapi diberikan secara penuh, jujur, dan sah. Maka pembeli pun berhak mendapat produk yang layak.
Pengalaman itu membuat saya merenung. Di Indonesia, kita terlalu sering memaklumi barang dan jasa yang kualitasnya buruk. Produk yang tak sesuai gambar, makanan yang tak sebanding dengan foto promosi, servis asal-asalan—semuanya kita hadapi dengan pasrah. Bahkan ketika merasa dirugikan, kita memilih diam. Kita terbiasa “mengerti”, bahkan ketika ditipu.
Saya teringat buku The High Price of Materialism karya Tim Kasser. Ia menulis bahwa masyarakat yang terlalu fokus pada harga dan status akan kehilangan kepekaan terhadap nilai sejati dari suatu produk atau pengalaman. Kita terbiasa mengejar murah, bahkan jika itu berarti menerima sesuatu yang jauh dari layak. Akhirnya kita masuk ke siklus puas-sementara dan kecewa-jangka-panjang.
Mungkin hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi pasar. Australia memiliki sekitar 26 juta penduduk, kurang dari 10 persen populasi Indonesia. Loyalitas pelanggan bisa jadi lebih bernilai dalam pasar kecil. Jika satu pelanggan kecewa, dampaknya terasa. Sementara di Indonesia, dengan pasar besar dan terus bergerak, kehilangan satu-dua pelanggan terasa biasa. Konsumen pun mudah tergantikan.
Baca juga: Dari Dapur Komunal di Kotabaru, Saya Belajar Apa itu Memberi
Di sisi lain, Barry Schwartz dalam The Paradox of Choice menulis bahwa terlalu banyak pilihan bisa membuat kita justru menurunkan ekspektasi. Ketika terlalu lelah memilih, kita cenderung menerima apa saja yang tersedia. Termasuk yang sebenarnya tak pantas.
Contoh konkretnya saya temui dalam keseharian. Celana kulot dari toko dua dolaran di pinggiran Melbourne yang saya beli sepuluh tahun lalu masih bertahan karena jahitannya rapi dan bahannya kuat. Sementara celana serupa yang dibeli ibu saya di pasar di Indonesia cepat pudar dan longgar. Baju hangat diskon dari Target Australia masih awet hingga kini, sementara sweater lokal yang lebih mahal cepat letoy. Bahkan hair dryer murah dari apotek di sana bertahan lebih lama dari versi bermerek yang saya beli di sini.
Kita sering lupa bahwa harga seharusnya mencerminkan nilai. Harga bukan cuma soal mahal atau murah, tapi tentang layak tidaknya barang atau layanan yang kita terima. Jika kita membayar penuh, kita berhak menuntut kualitas.
Sayangnya, budaya “maklum” membuat kita seakan tidak berhak untuk menuntut. Seperti saat Ibu Lucina bercerita tentang anaknya yang bekerja di toko elektronik. Suatu kali, mereka menolak satu kontainer bohlam dari Tiongkok karena sinarnya terlalu kuning, tidak sesuai pesanan. Di sana, itu dianggap wajar dan sah, dan ada mekanisme hukum yang melindungi konsumen. Tapi di Indonesia? Menolak barang bisa dianggap rewel.
Baca juga: Belajar Tanpa Kekerasan: Membongkar Stereotip dalam Buku Anak SD
Saya tidak hendak mengidealkan negara lain. Tapi pengalaman kecil seperti ini menyadarkan saya bahwa menghargai diri sendiri bisa dimulai dari hal sederhana: menyadari bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan punya nilai. Dan bahwa kita, tanpa terkecuali, berhak atas kejelasan, kelayakan, dan integritas dari barang dan jasa yang kita bayar.
Sitti Maryam adalah penulis dan pengajar yang sedang belajar memberi ruang bagi hal-hal kecil yang bermakna dalam hidupnya.