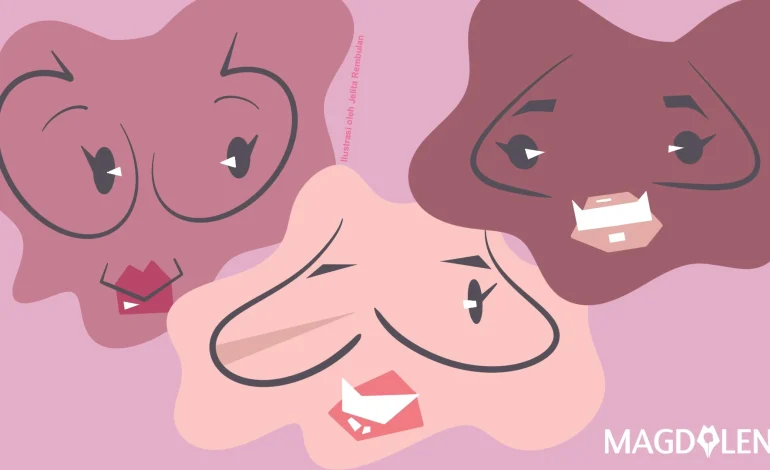#MerdekainThisEconomy: 5 Bukti Perempuan Pekerja Belum Benar-benar Merdeka

“Menurutmu, apa itu merdeka?”
Pertanyaan ini selalu muncul setiap kali Agustus tiba. Bagiku, perempuan pekerja di usia 20-an, merdeka berarti bisa bekerja dengan martabat dan enggak diremehkan. Namun realitasnya, perempuan pekerja masih terikat rantai tak kasatmata, dari upah timpang hingga akses promosi yang tidak setara.
Dari pengalaman pribadi, berikut lima alasan kenapa pertanyaan ‘sudahkah perempuan bekerja merdeka?’ masih penting banget untuk terus diulang:
Baca juga: #MerdekainThisEconomy: Korupsi itu Patriarkal, Pancasila itu Emansipatoris
Ketimpangan Upah
Pengalaman paling membekas terjadi ketika aku melamar pekerjaan. Di wawancara, pewawancara bilang: “Mbak kan masih tinggal sama orang tua, enggak perlu digaji besar. Lagi pula, nanti juga hidup ditanggung suami.”
Kata-kata itu menamparku. Seakan-akan pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang kubawa ke meja wawancara tak ada artinya dibanding statusku sebagai perempuan muda lajang. Nilai kerjaku dihitung bukan dari kemampuan, melainkan dari stereotip gender yang usang.
Sayangnya, ini bukan pengalaman unik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 menunjukkan rata-rata upah perempuan 18 persen lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Senada, laporan Global Gender Gap Report 2024 dari World Economic Forum menempatkan Indonesia di peringkat 100 dari 146 negara, dengan skor kesetaraan gender 68,6 persen. Angka ini bahkan turun dari 69,7 persen pada tahun sebelumnya. Dalam partisipasi ekonomi, skor Indonesia hanya 66,7 persen dan berada di peringkat 89.
Ketimpangan upah ini sering dibenarkan dengan asumsi perempuan bukan pencari nafkah utama. Padahal, kenyataannya banyak perempuan justru menjadi tulang punggung keluarga, entah sebagai ibu tunggal, anak yang membiayai orang tua, atau kakak yang menyekolahkan adik-adiknya.
Menganggap perempuan hanya “pencari nafkah tambahan” sama saja menutup mata pada kenyataan, dan lebih jauh lagi, merendahkan martabat mereka. Bagaimana mungkin bicara soal “merdeka” jika jerih payah perempuan masih dianggap bernilai lebih rendah sejak awal?
Candaan Seksis dan Budaya Kerja Toksik
Jika bicara diskriminasi, hal yang sering dianggap sepele tapi berdampak besar adalah candaan seksis di ruang kerja. Komentar soal pernikahan, keperawanan, atau bahkan tubuh perempuan sering dilontarkan dengan nada bercanda. Kalau ikut tertawa dianggap “asyik,” kalau menolak ikut, langsung dicap kaku atau tidak kooperatif.
Aku sendiri pernah mengalami bagaimana menolak ikut dalam candaan membuat suasana kerja jadi awkward Seolah-olah standar profesionalitas bukan ditentukan oleh kinerja, tapi oleh kesediaan menoleransi candaan seksis.
Masalahnya, candaan seksis bukan sebatas kata-kata. Ia membentuk budaya kerja yang tidak sehat, di mana perempuan harus selalu waspada. Bekerja sudah cukup melelahkan, apalagi jika energi terkuras untuk menangkis komentar merendahkan.
Budaya toksik ini semakin terlihat ketika perempuan justru dipaksa saling menjatuhkan. Dalam kompetisi mendapatkan pengakuan, perempuan sering dilawan dengan perempuan juga. Bukannya saling mendukung, solidaritas terkikis oleh stereotip bahwa hanya ada sedikit ruang bagi perempuan di puncak karier.
Alih-alih aman dan setara, ruang kerja berubah jadi arena yang melelahkan, penuh intrik, gosip, dan tekanan tak kasatmata. Bagaimana mungkin merdeka, jika setiap langkah terasa seperti bertahan di medan penuh ranjau?
Baca juga: #MerdekainThisEconomy: Pesan untuk Putraku: Merdekalah dari Negaramu
Mikroagresi dan Pelecehan Seksual
Di luar candaan, ada bentuk diskriminasi yang lebih halus sekaligus berbahaya bernama mikroagresi. Bentuknya bisa berupa ucapan meremehkan, tatapan yang membuat risih, atau sikap paternalistik seolah perempuan “butuh perlindungan” padahal hanya ingin dihargai setara.
Lebih berat lagi, banyak perempuan pekerja masih harus berhadapan dengan pelecehan seksual. Dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar vulgar, hingga perhatian atasan yang berlebihan—semuanya membuat ruang kerja jauh dari rasa aman.
Ada banyak kasus di mana atasan atau rekan kerja menabrak batas profesional, membuat perempuan pekerja tak nyaman. Namun untuk menolak secara terang-terangan pun pekerja cemas kariernya terganjal.
Akses yang Sama terhadap Promosi
Selain diskriminasi dalam keseharian, hambatan lain yang membuat perempuan pekerja belum merdeka adalah akses yang tidak setara terhadap promosi dan posisi strategis.
Dalam banyak organisasi, perempuan memang dipekerjakan, tetapi jarang diberi kepercayaan menduduki posisi pengambil keputusan. Fenomena ini dikenal sebagai glass ceiling atau batas tak terlihat yang menghalangi perempuan naik ke puncak.
Data dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan, secara global, perempuan masih jauh lebih sedikit mengisi posisi manajerial dibanding laki-laki. Di Indonesia, tren serupa terlihat—meski jumlah pekerja perempuan meningkat, proporsi mereka di level kepemimpinan masih stagnan.
Pengalaman sehari-hari juga menunjukkan hal ini. Ada perempuan yang bekerja keras, tetapi saat promosi tiba, justru disalip rekan laki-laki dengan pengalaman setara. Alasannya seringkali tidak diucapkan, tapi terasa: Perempuan dianggap akan “tersita” oleh pernikahan, kehamilan, atau urusan rumah tangga.
Padahal, kemerdekaan di dunia kerja tidak cukup hanya diukur dari boleh atau tidaknya bekerja. Ia juga harus diukur dari seberapa jauh perempuan bisa berkembang, mengambil keputusan, dan memimpin dengan penuh martabat.
Baca juga: #MerdekainThisEconomy: Berjalan Kaki dengan ‘Happy’, Kemewahan Terakhir Kelas Pekerja
Cuti Haid, Melahirkan, dan Child Care
Kemerdekaan juga ditentukan oleh adanya kebijakan yang mendukung perempuan sebagai pekerja sekaligus manusia dengan kebutuhan biologis dan sosial yang berbeda.
Sayangnya, banyak perusahaan masih abai pada kebijakan afirmasi dasar. Misalnya, cuti haid, cuti melahirkan, hingga fasilitas penitipan anak yang jarang tersedia.
Padahal, cuti haid dan melahirkan bukanlah bentuk keringanan, melainkan hak yang diatur undang-undang. Namun implementasinya sering kali terbentur stigma: Perempuan dianggap kurang produktif jika mengambil haknya.
Tanpa fasilitas childcare, banyak perempuan akhirnya terpaksa memilih antara karier atau keluarga. Sementara itu, laki-laki tidak pernah dibebani pilihan semacam ini. Ketidakadilan struktural inilah yang membuat perempuan pekerja terus-menerus berada di posisi rentan.
Kemerdekaan sejati seharusnya memberi ruang bagi perempuan untuk menjalani hidup utuh: Bekerja, berkarya, sekaligus berkeluarga tanpa harus mengorbankan salah satunya.
Sampai lima hal itu teratasi, pertanyaan “sudahkah perempuan bekerja merdeka?” harus terus kita suarakan. Jangan biarkan isu ini berhenti sebagai wacana; bicarakan, catat pengalaman, dan dorong kebijakan yang adil di lingkungan kerja masing-masing.
Setiap suara dan aksi memiliki kekuatan untuk mengubah budaya kerja. Dorong perusahaan menerapkan gaji setara, cegah seksisme, sediakan ruang aman dari pelecehan, dan pastikan peluang promosi serta kebijakan ramah keluarga tersedia. Dengan begitu, kemerdekaan di dunia kerja bukan lagi sekadar slogan, tapi nyata bagi perempuan pekerja di seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI 2025, Magdalene meluncurkan series artikel #MerdekainThisEconomy dari berbagai POV penulis WNI. Baca artikel lain di sini.