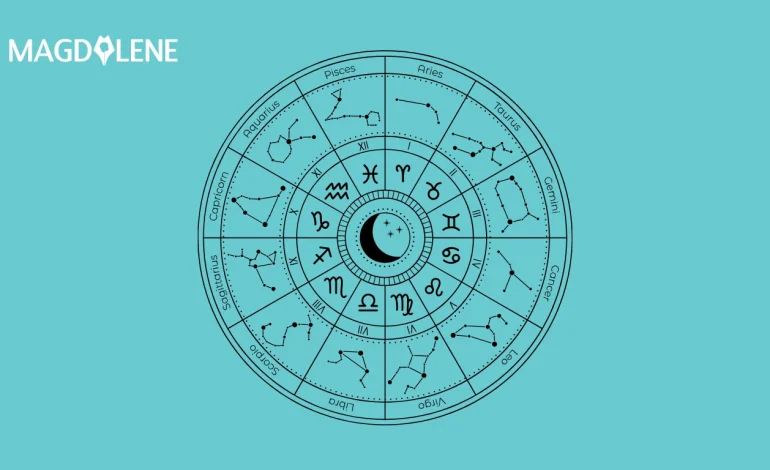
Banyak teman perempuan saya rutin membaca ramalan tarot atau horoskop. AS, 22, misalnya, setiap kali bertengkar dengan pacarnya, langsung membeli koin TikTok untuk pembacaan tarot dari akun viral, yang biasanya dijalankan oleh perempuan juga. Teman lain, BC, 21, selalu membawa sekotak kartu tarot di tasnya untuk “berjaga-jaga” jika harus mengambil keputusan penting. Saya sendiri, di usia 23, sangat memperhatikan ramalan zodiak setiap kali masuk masa PDKT.
Sementara itu, teman-teman laki-laki saya bahkan sering kali tidak tahu zodiak mereka sendiri. Saat saya tanya apakah mereka juga mencari makna lewat tarot atau horoskop, jawabannya sama: tidak.
Pengamatan ini sejalan dengan survei Pew Research Center (2024) di Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa 43 persen perempuan usia 18–49 percaya pada astrologi, atau dua kali lipat dibanding laki-laki di usia yang sama (20 persen). Menariknya, angka ini masih lebih tinggi dari perempuan lansia usia 50 ke atas (27 persen). Artinya, ketertarikan pada spiritualitas simbolik bukan cuma soal generasi, tapi juga gender.
Lantas, apa yang membuat praktik seperti astrologi dan tarot lebih dekat dengan perempuan dan komunitas queer? Apa yang membuat mereka lebih terbuka pada cara berpikir yang bersifat emosional, simbolik, bahkan intuitif?
Baca juga: Menyelami Mereka yang Cinta Astrologi
Stigma sosial atas spiritualitas feminin
Perempuan lebih terbiasa mencari makna simbolik dalam hidup, dalam relasi, perasaan, maupun arah langkah. Ini bukan karena mereka “lebih peka secara alami,” tapi karena dibesarkan dalam budaya yang memberi ruang bagi ekspresi emosi. Sebaliknya, laki-laki sejak kecil dibiasakan untuk menahan rasa dan menjunjung logika sebagai standar kekuatan.
Studi oleh Wei Bao dkk. yang dimuat jurnal Personality and Individual Differences (2022) menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih mengandalkan intuisi dalam mengambil keputusan. Teori skema gender dari psikolog Sandra Bem juga menguatkan bahwa sejak kecil, anak perempuan didorong untuk mengenali dan menamai emosi, dan diberi ruang untuk menangis, mengeluh, atau merengek tanpa dianggap lemah. Sementara anak laki-laki diajarkan untuk tegar dan “rasional.”
Dalam jalur tumbuh yang seperti ini, perempuan terbiasa memakai intuisi sebagai alat navigasi—mengenali suasana, membaca isyarat, dan mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka rasakan. Di sinilah tarot dan astrologi masuk: sebagai cara memahami hidup yang mengandalkan tafsir simbolik, bukan hitungan logis. Praktik ini memberi makna atas keraguan, ketidakpastian, dan emosi yang sering kali tak mendapat tempat dalam dunia yang maskulin dan serba tegas.
Astrologi dan tarot sering dianggap “tidak ilmiah” atau “sekadar hiburan,” apalagi karena diasosiasikan dengan perempuan. Psikolog Barbara Santini menyebut bahwa spiritualitas simbolik telah mengalami “feminisasi”, yakni dihubungkan kuat dengan perempuan dan komunitas queer. Akibatnya, banyak laki-laki menolak praktik ini bukan karena isinya, tapi karena asosiasi kulturalnya.
Seperti halnya makeup, drama Korea, atau novel romansa, tarot dan horoskop diremehkan karena dilekatkan pada hal-hal yang dianggap “feminin.” Dalam masyarakat patriarkal, hal-hal yang feminin sering kali dipandang tidak serius, terlalu emosional, bahkan “lebay.”
Di balik stigma tersebut, ada standar sosial yang menyempitkan maskulinitas hanya pada logika, ketegasan, dan efisiensi. Ketertarikan pada intuisi, spiritualitas, atau pertanyaan eksistensial justru dianggap melemahkan. Padahal, di situlah banyak orang menemukan ruang untuk memproses hidup secara utuh.
Baca juga: Cari Pacar Berdasarkan Zodiak, Perlu Enggak Ya?
Spiritualitas alternatif bagi yang terpinggirkan
Ketika spiritualitas simbolik dianggap “tidak rasional,” maka kelompok yang selama ini berada di luar sistem maskulinitas dominan—perempuan dan queer—lebih mungkin merasa nyaman di dalamnya. Tarot dan zodiak bukan hanya tempat mencari jawaban, tapi juga sarana untuk membangun narasi diri.
Data dari Pew Research Center juga menunjukkan bahwa 54 persen komunitas LGBTQ membaca horoskop minimal sekali setahun—dua kali lipat dari populasi umum (28 persen). Sebanyak 33 persen menggunakan kartu tarot, tiga kali lebih tinggi dari rata-rata orang dewasa di AS (11 persen). Bahkan, 21 persen dari mereka menggunakan astrologi atau tarot saat mengambil keputusan besar, atau empat kali lebih tinggi dibanding kelompok non-LGBTQ (5 persen).
Bagi banyak queer yang terputus dari keluarga atau ditolak oleh institusi agama, praktik alternatif seperti ini menjadi cara merawat diri. Ia menyediakan sistem makna yang lebih lentur, netral dari stigma sosial, dan tidak memihak institusi mana pun. Di tengah runtuhnya kepercayaan terhadap agama, negara, dan keluarga, spiritualitas simbolik menjadi tempat berlindung dari dunia yang tak selalu memberi ruang.
Ia mengabaikan kategori sosial yang sering jadi sumber alienasi: keluarga, asal daerah, bahkan tubuh biologis. Sebagai gantinya, ia memberi penanda identitas yang netral tapi akrab: Virgo, Scorpio, Moon in Leo, dll. Di tengah sistem yang tidak menyediakan ruang aman untuk emosi mereka, spiritualitas alternatif seperti zodiak dan tarot menawarkan kontrol atas narasi diri.
Baca juga: Ini Cara Membaca Grafik Kelahiran dalam Astrologi
Tarot dan astrologi sering dicap “terlalu personal,” “terlalu emosional,” atau “tidak masuk akal”. Tapi justru karena itu, ia memberi tempat bagi yang tersisih. Ia menawarkan bahasa alternatif untuk memahami hidup, tanpa harus tunduk pada logika yang kaku atau norma yang menyingkirkan.
Bagi perempuan dan queer, tarot dan zodiak bukan cuma tren. Ia adalah bentuk perlawanan terhadap sistem makna yang terlalu sempit. Di dalamnya, mereka bisa menjadi subjek, bukan objek. Mereka bisa membangun makna sendiri, tanpa harus meminta izin dari dunia yang terlalu sering menolak keberadaan mereka.
Jasmine Hasna adalah lulusan Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM. Ia menyukai riset sosial seputar media, demokrasi, dan budaya populer. Di sela-sela menulis dan membaca puisi, ia bekerja sebagai associate researcher di LP3ES untuk menafkahi satu kucing yang tidak membalas budi.






















