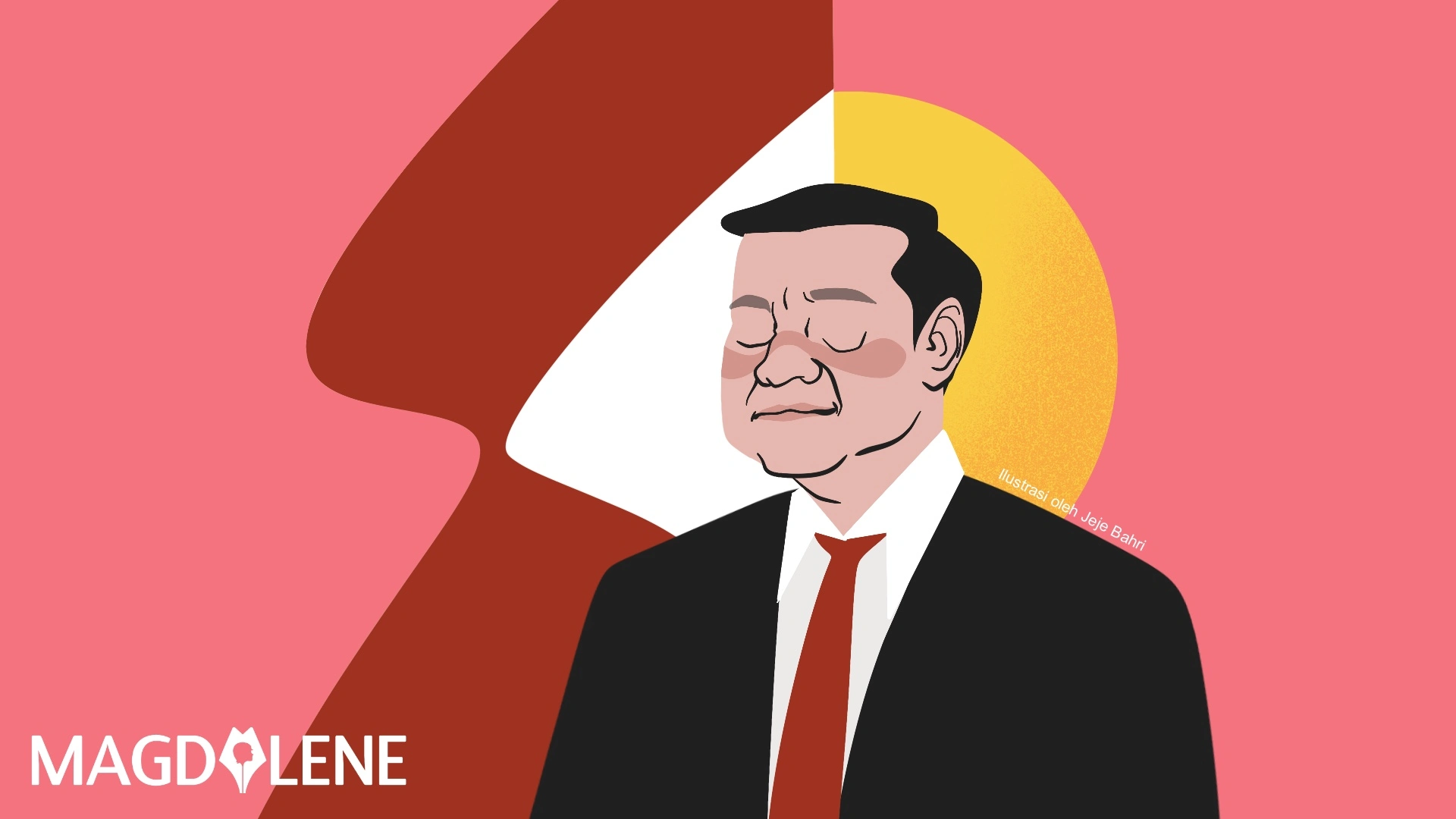Standar Ganda Feminis Barat Kala Bicara Kasus Palestina
Kelompok feminis Barat dipandang koar-koar tentang hak perempuan seluruh dunia, tapi putar badan ketika bicara nasib perempuan Palestina.

Bulan lalu, Magdalene menuliskan tentang serangan Israel ke Palestina adalah isu feminis. Berangkat dari situlah, maka sudah semestinya mereka yang mengaku feminis perlu melawan semua penindasan, termasuk penindasan perempuan Palestina.
Sayang, menurut Maryam Aldossari, Peneliti Ketidakadilan Gender di Timur Tengah, feminis Barat nyatanya gagal membela perempuan Palestina. Dalam tulisanya “Western feminism and its blind spots in the Middle East” di Al Jazeera, ia menilai banyak feminis Barat dan berkulit putih menolak bersolidaritas dengan perempuan Palestina.
Sebaliknya, sejak (7/10), mereka yang mendaku feminis ini lantang mengutuk serangan Hamas terhadap Israel. Di saat bersamaan, mereka mengabaikan pembunuhan jutaan warga Palestina di Jalur Gaza.
Mereka tidak cuma gagal menunjukkan empati atau dukungan, tetapi juga ikut serta membungkam mereka yang mengekspresikan simpati terhadap derita perempuan Palestina.
Baca Juga: Magdalene Primer: Yang Perlu Diketahui tentang Isu Palestina-Israel
Isu Penjajahan Tubuh juga Luput Dibicarakan
Senada dengan Aldossari, Sahar Aziz, Profesor hukum dan Chancellor’s Social Justice Scholar di Rutgers Law School juga mengatakan kegagalan feminisme dalam memperjuangkan kebebasan perempuan Palestina.
Dalam tulisannya “Muslim women in the West in the crosshairs of Zionists, white ‘feminists’” yang terbit di Al Jazeera, Aziz bilang, perempuan Muslim diposisikan untuk tidak boleh mengritik kebijakan dan praktik negara-negara Barat yang melanggar hukum internasional. Ini termasuk membunuh Muslim tanpa pandang bulu, menghukum warga sipil Palestina, atau secara sistematis mendiskriminasi diaspora Muslim dan Arab.
Perempuan Muslim harus membuktikan tidak mendukung terorisme dalam bentuk apa pun. Mereka dipaksa mengutuk berulang kali setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Muslim mana pun di dunia. Lalu ketika perempuan Muslim berbicara tentang diskriminasi yang mereka hadapi, atau mengecam standar ganda perempuan kulit putih, status mereka berganti dari “sesama feminis” menjadi “pengkhianat”.
Aziz kemudian bertanya, apakah memang perempuan Palestina tidak cukup dipandang sebagai perempuan, sehingga tidak layak diperjuangkan kelompok feminis?
Perempuan Palestina sejak lama telah dijajah. Lala Hanifah dalam tulisannya di Magdalene bahkan mengasosiasikan perempuan Palestina sebagai subaltern, liyan yang terliyankan. Mereka adalah kelompok yang tidak punya agensi dan menerima penjajahan dan di waktu yang sama tidak memiliki kesempatan untuk bersuara.
Diperkosa diminta diam, diusir dari tanah sendiri pun tetap dipaksa bungkam. Praktik jamak ini dikenal dengan isqat siyassy–pelecehan dan kekerasan seksual terhadap warga Palestina karena alasan politik.
Pasca-serangan (7/10), kekerasan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan juga ditandai dengan kemiskinan menstruasi (period poverty) yang dialami perempuan Palestina. Dikutip dari Medical News Today, kemiskinan menstruasi adalah situasi kurangnya akses terhadap produk menstruasi, pendidikan, fasilitas kebersihan, pengelolaan limbah, atau kombinasi dari semua hal tersebut.
Setiap perempuan Palestina di Gaza terpaksa tinggal di kamp pengungsian dengan kondisi kehidupan yang penuh sesak, dan kurangnya akses terhadap air dan produk kesehatan menstruasi seperti pembalut dan tampon. Apotek dan toko-toko menghadapi persediaan yang semakin menipis karena pengepungan Israel.
Lebih lanjut, pengeboman Israel di jalan-jalan utama di Jalur Gaza telah membuat pengangkutan produk dari gudang medis ke apotek jadi mustahil. Penggunaan kamar mandi harus dijatah, dan mandi dibatasi hanya beberapa hari sekali. Hal ini tentu membuat banyak perempuan terpaksa harus menyampingkan kebutuhan menstruasinya untuk khalayak lebih banyak.
“Tidak ada privasi, kamar mandi tidak memiliki air yang mengalir, dan kami tidak bisa keluar dengan mudah untuk mencari apa yang kami butuhkan,” ujar Ruba Seif, perempuan Palestina yang tinggal di kamp pengungsi bersama keluarganya.
Dengan situasi terhimpit, perempuan Palestina di Gaza akhirnya menggunakan tablet norethisterone. Tablet ini biasanya diresepkan untuk kondisi-kondisi seperti pendarahan menstruasi yang parah, endometriosis, dan menstruasi yang menyakitkan untuk menghindari ketidaknyamanan dan rasa sakit saat mens.
Menurut Dr Walid Abu Hatab, konsultan medis kebidanan dan kandungan di Nasser Medical Complex, pil-pil tersebut menjaga kadar hormon progesteron tetap tinggi untuk menghentikan rahim meluruhkan lapisannya, sehingga menunda menstruasi. Sayangnya, pil ini memiliki efek samping seperti pendarahan vagina, mual, pusing, dan perubahan mood yang drastis.
“Perempuan-perempuan lain di sekitar saya meminta pil-pil ini kepada saya,” kata Ruba.
“Saya tahu efek samping negatifnya, tetapi pil-pil ini tidak lebih berbahaya daripada rudal, kematian, dan kehancuran di sekitar kami.”
Baca Juga: Akhiri Budaya Pemerkosaan di Indonesia
Gagal Paham Feminis soal Ketidakadilan Reproduksi dan Akses Pendidikan
Selain kekerasan terhadap tubuh dan seksualitas lewat tindak pemerkosaan dan kemiskinan menstruasi, para feminis juga harus paham ketertindasan perempuan Palestina juga meliputi ketidakadilan reproduksi dan pemutusan akses pendidikan.
Shado, majalah daring dan cetak komunitas seniman, aktivis, dan jurnalis berbasis di Inggris menuliskan, tidak hanya perempuan Palestina mengalami ketidakadilan reproduksi karena masih ada pandangan patriarkal dari masyarakat Palestina sendiri, tetapi juga diperparah dengan pendudukan Israel.
Lebih lanjut, pengeboman Israel di jalan-jalan utama di Jalur Gaza telah membuat pengangkutan produk dari gudang medis ke apotek jadi mustahil. Penggunaan kamar mandi harus dijatah, dan mandi dibatasi hanya beberapa hari sekali. Hal ini tentu membuat banyak perempuan terpaksa harus menyampingkan kebutuhan menstruasinya untuk khalayak lebih banyak.
Terdapat lebih dari 700 pos pemeriksaan dan penghalang jalan Israel yang tersebar di sekitar Tepi Barat. Bahkan untuk layanan kesehatan yang mendesak pun mereka masih dibatasi. Imbasnya, antara 2000 dan 2007, 10 persen perempuan hamil di Palestina mengalami keterlambatan di pos pemeriksaan, dengan 69 kelahiran terjadi di pos pemeriksaan, 35 kematian bayi, dan lima kematian ibu.
Penulis Shams Hanieh dan Aude Nasr mencatat tingkat kematian ibu meningkat selama dan setelah setiap serangan Israel terjadi di Jalur Gaza. Ini sebagian disebabkan oleh penembakan dan beban rumah sakit yang berlebihan akibat pengeboman.
Selama serangan di Gaza pada 2014 misalnya, 5.000 kelahiran terjadi dalam kondisi ekstrem dan diperkirakan 45.000 perempuan tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi.
Obat-obatan untuk kesehatan ibu juga sering terkena dampaknya. Zat besi dan asam folat yang digunakan untuk mengatasi defisiensi mikronutrien selama kehamilan seringkali kehabisan stok. Hal ini menyebabkan peningkatan anemia yang berdampak pada 40 persen perempuan hamil di Gaza pada tahun 2018.
Lebih lanjut, pendudukan Israel terhadap Palestina juga berdampak permasalahan akses perempuan terhadap layanan aborsi aman. Dalam studi yang diterbitkan National Institutes of Health pada 2019 disebutkan, memburuknya situasi politik dan krisis kemanusiaan berdampak negatif pada kesehatan perempuan Palestina. Dana dipangkas karena prioritasnya saat itu adalah untuk biaya senjata.
Keterbatasan akses aborsi oleh perempuan Palestina mencakup pembatasan hukum, pembatasan kebijakan rumah sakit, harga yang mahal di klinik swasta, ketakutan akan stigma yang disebabkan oleh pekerjaan, dan pembatasan perjalanan terkait tempat tinggal. Karena aborsi adalah ilegal menurut hukum Palestina dan sangat dibatasi dalam, perempuan Palestina terpaksa harus pergi ke rumah sakit Israel, ke klinik swasta Palestina yang mahal, atau melakukan penghentian kehamilan sendiri.
Laporan International Planned Parenthood Federation pada 2015 menemukan sekitar 50 persen perempuan Palestina menerima pengobatan untuk aborsi tidak lengkap. Pendarahan vagina yang parah jadi komplikasi dialami oleh sebagian besar pasien (52,2 persen) yang disusul 22,9 persen perempuan mengalami nyeri ringan terus-menerus yang berlangsung dalam jangka waktu lama, dan 6,70 persen mengalami infeksi dan demam tinggi.
“Saya tahu efek samping negatifnya, tetapi pil-pil ini tidak lebih berbahaya daripada rudal, kematian, dan kehancuran di sekitar kami.”
Dalam memahami bahwa pembebasan perempuan Israel sebagai bagian dari semangat feminisme, kita tidak boleh luput membahas tentang hak dasar setiap perempuan yaitu akses pendidikan. Disarikan dari Feminist Thought karya Rosemarie Putnam Tong, feminisme Barat yang berkembang pada abad 19-20 ini menggugat hak individu sebagai konstitusi dan bentuk dari keadilan sosial dalam pendidikan, pekerjaan, dan reformasi hukum.
Mereka memperjuangkan hak perempuan dalam ranah politik, ekonomi, dan institusi sosial yang dapat memaksimalkan kebebasan perempuan sebagai individu. Lewat pendidikan, perempuan bisa lebih mengenal potensi diri mereka sendiri dan mengembangkan potensi tersebut untuk kesejahteraan dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Perempuan tak lagi harus menggantung nasibnya pada orang lain, karena lewat pendidikan yang membebaskan perempuan bisa berdaya dan menentukan arah nasibnya sendiri di tatanan masyarakat yang lebih luas.
Sayangnya, apa yang diperjuangkan oleh feminisme liberal terputus di Gaza. Sekolah, universitas, dan gedung kementerian pendidikan Palestina sering menjadi sasaran serangan dan pembongkaran militer Israel. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) melaporkan, selama 50 hari serangan militer Israel di Jalur Gaza pada 2014, 412 pelajar dibunuh dan 14 institusi pendidikan tinggi rusak total.
Baca juga: Mei 1998 yang Mengubah Saya
Dalam perjalanan sehari-hari ke sekolah dan universitas, siswa dan guru Palestina dipaksa melewati pos pemeriksaan, dan mengalami penundaan, penahanan, dan pelecehan oleh tentara dan pemukim Israel. Pemisahan Yerusalem Timur dari wilayah pendudukan Palestina lainnya menghalangi warga Palestina di luar kota untuk mengakses pusat pembelajaran dan kebudayaan Palestina.
Sejak 2000, Israel telah memberlakukan larangan perjalanan bagi pelajar dan akademisi yang kemudian diperluas dengan blokade yang dimulai pada tahun 2007. Hingga ini, warga Palestina di Gaza dilarang melanjutkan pendidikan mereka di Tepi Barat, dan tidak dapat bersekolah di universitas.
Selain itu, dilansir dari data yang dihimpun oleh UNICEF dan Save the Children, per 21 Oktober 2023 dari 625.000 siswa tidak terputus akses pendidikannya. Gedung Sekolah (39 persen atau 206 dari total sekolah di Gaza) mengalami kerusakan akibat serangan militer Israel dan ini berdampak langsung pada 56 persen siswa perempuan Palestina.
Pendudukan Israel secara terang-terangan telah melakukan kekerasan sistemik pada perempuan. Kekerasan yang hingga saat ini terus mengalami eskalasi telah mengambil paksa agensi perempuan Palestina terhadap hak kesehatan reproduksi, seksualitas, hingga pendidikan mereka. Dengan situasi ketertindasan ini, maka pertanyaan Aziz harus terus digaungkan.
Jika memang kebebasan perempuan Palestina adalah bagian dari perjuangan feminisme, maka eksistensi mereka perlu sekuat tenaga dibela tanpa kecuali. Karena seperti apa yang dikatakan Angela Davis: “Menggaungkan suara kita untuk kemerdekaan Palestina tidak akan pernah menjadi sesuatu yang lain selain merangkul cinta dan keadilan untuk semua.”