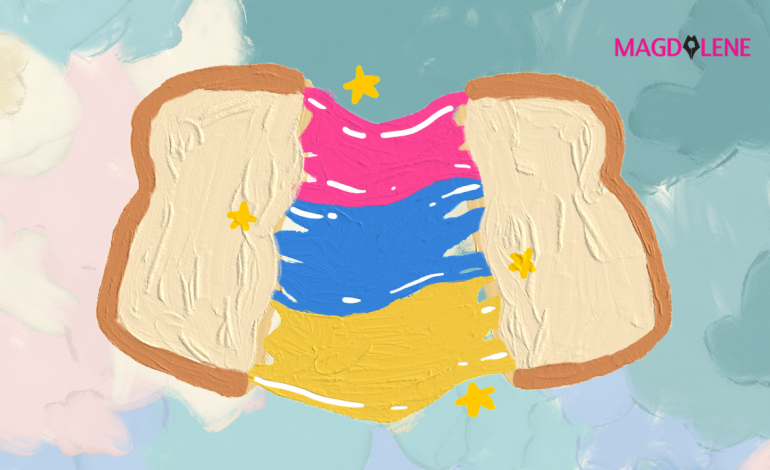Apa itu Panseksualitas: Keintiman Seksual di Luar Jangkauan Label

Kebanyakan orang menginginkan variasi dalam hidup. Hal ini juga berlaku ketika memilih makanan. Sebagai seseorang yang hidup sendiri bertahun-tahun, saya sudah menguasai seni mengatur menu makanan yang lebih variatif. Biar bagaimana pun, tak ada orang yang ingin makan makanan sama tiga hari berturut-turut bukan? Karena itulah saya memasak makanan berbeda dalam jumlah besar, makan secukupnya hari itu, lalu membekukan sisanya dalam porsi satu orang untuk dikonsumsi di kemudian hari.
Masalahnya, saat makanan dibekukan, ia jadi UFO. Bukan, bukan “unidentified flying object” (benda terbang tak dikenal) – benda misterius di langit itu – melainkan “unidentified frozen object” (benda beku tak dikenal). Mereka kehilangan identitasnya, kecuali diberi label. Terkadang saya malas atau terburu-buru dan lalai melakukannya, sehingga itu berakhir jadi UFO. Satu-satunya cara untuk mengetahui “identitas” bongkah makanan beku tersebut adalah dengan mencairkannya.
Hal ini juga berlaku pada manusia. Mereka dinamai, diberi label ras, etnis, agama, gender, dan seksual. Terkadang individu yang memberi label pada diri sendiri, untuk menyatakan identitas dan merasa jadi bagian komunitas. Sering kali, label diberikan kepada mereka oleh keluarga, budaya, agama, negara, dan lain-lain. Hal ini cenderung jadi pemaksaan dan penjara yang menindas.
Label adalah pedang bermata dua karena dapat menciptakan stereotip, kesalahan persepsi, ekspektasi berlebihan, prasangka, serta lebih buruk lagi, stigma dan diskriminasi.
Baca juga: Pekan Kesadaran Biseksual: Mematahkan 5 Mitos tentang Biseksual
Namun, label tidak bisa dihindari dalam masyarakat, sehingga bisa menjadi masalah karena kebanyakan orang tidak mau repot-repot melampaui stereotip tersebut. Jauh lebih mudah memberi label, penilaian, bahkan kecaman, daripada memikirkan dan memahami realitas manusia di balik stereotip tersebut.
Saya telah menjadi sekutu LGBTIQA+ selama lebih dari empat puluh tahun. Artinya, saya heteroseksual-cisgender, tetapi mendukung teman-teman LGBTIQ+ karena percaya pada demokrasi dan hak asasi manusia.
Meski sudah empat puluh tahun mengadvokasi kelompok LGBTIQA+, saya selalu belajar tentang label yang terus berkembang dan apa artinya. Awalnya hanya “homoseksual” (diciptakan di Jerman pada 1869), “gay”, kemudian LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) yang menjadi LGBTIQA+, dengan I untuk “interseks”, “Q” untuk “queer” , “A” untuk “aseksual”, sedangkan + mewakili identitas seksual lainnya, termasuk panseksual. National Geographic menerbitkan artikel tentang evolusi terminologi pada 2021 yang menurut saya sangat berguna.
Sejak 2015, tanggal 24 Mei diperingati setiap tahun sebagai Hari Visibilitas Panseksual. “Hari ini diciptakan untuk mengakui dan mengakui keberadaan individu panseksual di seluruh dunia, serta untuk meningkatkan kesadaran akan panseksualitas dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat panseksual”.
Oleh karenanya, saya sangat senang ketika menemukan buku karya Himas Nur Rachmawati yang berjudul Menjelajahi Diri, Memeluk Intimasi. Kajian Panseksualitas di Indonesia (2023).

Keren! Saya sangat ingin membacanya tidak begitu tahu tentang panseksualitas. Tentu saja mempelajarinya dari buku karya orang Indonesia, akan menjadi bonus karena pasti akan bertaburan kisah-kisah panseksualitas di Indonesia.
Betapa beraninya Himas menulis tentang isu sensitif di lingkungan akademis Indonesia yang tidak selalu dikenal menjaga standar objektivitas, imparsialitas, dan integritas akademis.
Baca juga: Ruang Aman Internet adalah Hak Semua Bangsa, Kecuali LGBTQIA+
Baginya, ini lebih merupakan proses coming in daripada coming out (melela). Yang pertama – pengungkapan orientasi seksual atau romantis seseorang secara sengaja atau tidak sengaja – memberi orang lain kekuatan untuk menerima atau menolak kita. Sebaliknya, yang kedua adalah ketika orang LGBTIQA+ mengajak orang lain masuk, sehingga merekalah yang punya kuasa. Bingung? Jangan khawatir, saya juga.
Untungnya, Himas menjelaskan coming in dalam Glosariumnya di awal buku. Ia merupakan “proses seumur hidup individu dalam menerima, mengenali, memahami dan menghayati identitas gender maupun seksualitasnya. Proses in bersifat sangat personal dan spiritual. Kondisi lingkungan seperti lingkungan yang ramah atas keragaman SOGIESC (orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender dan karakteristik seks) atau lingkungan yang diskriminatif, dimungkinkan berperan mempengaruhi proses ini.” (hlm. x).
Buku Himas didasarkan pada bab satu dan dua dari empat bab tesis pascasarjana tahun 2022 dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Terdiri dari dua rumusan masalah: Pertama tentang keintiman queer/penerimaan diri panseksual, kedua tentang masa depan queer atau bagaimana individu panseksual memaknai masa depannya. Dalam buku tersebut, Himas hanya mengangkat persoalan keintiman panseksual.
Meski hanya separuh dari tesisnya, buku setebal 125 halaman tersebut masih cukup bersifat akademis. Bahkan, mungkin kurang mudah dicerna oleh kalangan non-akademis, terutama bagi mereka yang tidak berkecimpung di dalam isu gender dan seksualitas.
Buku ini terdiri dari empat bagian: Bagian I: Visibilitas, Pencarian dan Ketakutan yang Terlembaga, yang memiliki tiga subbagian: Resonansi Politik Emosi; Media dan Representasi, dan Marginalisasi Queer di Margin Metropolitan.
Bagian II: Monoseksisme dan Penghapusan Panseksual, memuat lima subbagian: Mononormativitas; Ketidaktampakan Panseksualitas; Stigma Panseksualitas; Pembatalan Panseksualitas, dan Panfobia.
Bagian III: Interseksionalitas Spektrum Panseksual, memiliki tiga subbagian: Identitas Gender; Identitas Keagamaan atau Kepercayaan, dan Pengalaman Disabilitas.
Bagian IV: Penerimaan Diri dan Keintiman.
Baca juga: Mereka Tak Pernah Minta Maaf Panggil Saya Bencong
Daftar isi ini sangat membantu memberikan gambaran selayang pandang yang jelas tentang isi buku. Selain itu, Himas mereproduksi banyak wawancara verbatim terhadap respondennya berdasarkan kuesioner yang ia buat yang dikirimkan kepada teman-temannya, LSM, serta komunitas queer dan feminis. Wawancara-wawancara ini memberikan suasana “hidup” dan “warna”, serta membantu mengimbangi nuansa akademis buku tersebut.
Saya tidak bisa membayangkan sulitnya mengidentifikasi responden panseksual karena budaya mononormatif yang memusuhi apa pun selain hubungan heteroseksual. Selain itu, responden sendiri mungkin tidak menyadari dirinya panseksual. Bahkan di kalangan komunitas queer, panseksual masih belum terlalu dikenal.
Ada berbagai kesalahpahaman tentang panseksualitas. Misalnya panseksualitas dan biseksualitas adalah hal yang sama; bahwa panseksual itu serakah (“bagaimana kamu bisa tertarik pada semua orang?”); bahwa panseksual itu bingung, atau bahwa panseksualitas hanyalah tren baru.
Bagi mereka yang tertarik dengan gender dan seksualitas, baik akademisi maupun aktivis, buku Himas merupakan tambahan berharga untuk melengkapi studi-studi lokal mengenai seksualitas dalam Bahasa Indonesia yang masih jarang ada.
Seperti UFO (benda beku tak dikenal) saya, label LGBTIQIA+ termasuk panseksualitas perlu “dicairkan”. Sehingga, realitas kemanusiaan dari individu-individu langka ini dapat “dikunyah” dan “dicerna”, agar kita dapat memahami dan menghargai pluralitas dan kemanusiaan seksualitas di dunia, maupun di Indonesia.
Selamat Pansexual Visibility Day, 24 Mei 2024.
*Julia Suryakusuma adalah seorang intelektual publik, aktivis feminis dan penulis buku “Agama, Seks dan Kekuasaan”.
Ilustrasi oleh: Karina Tungari