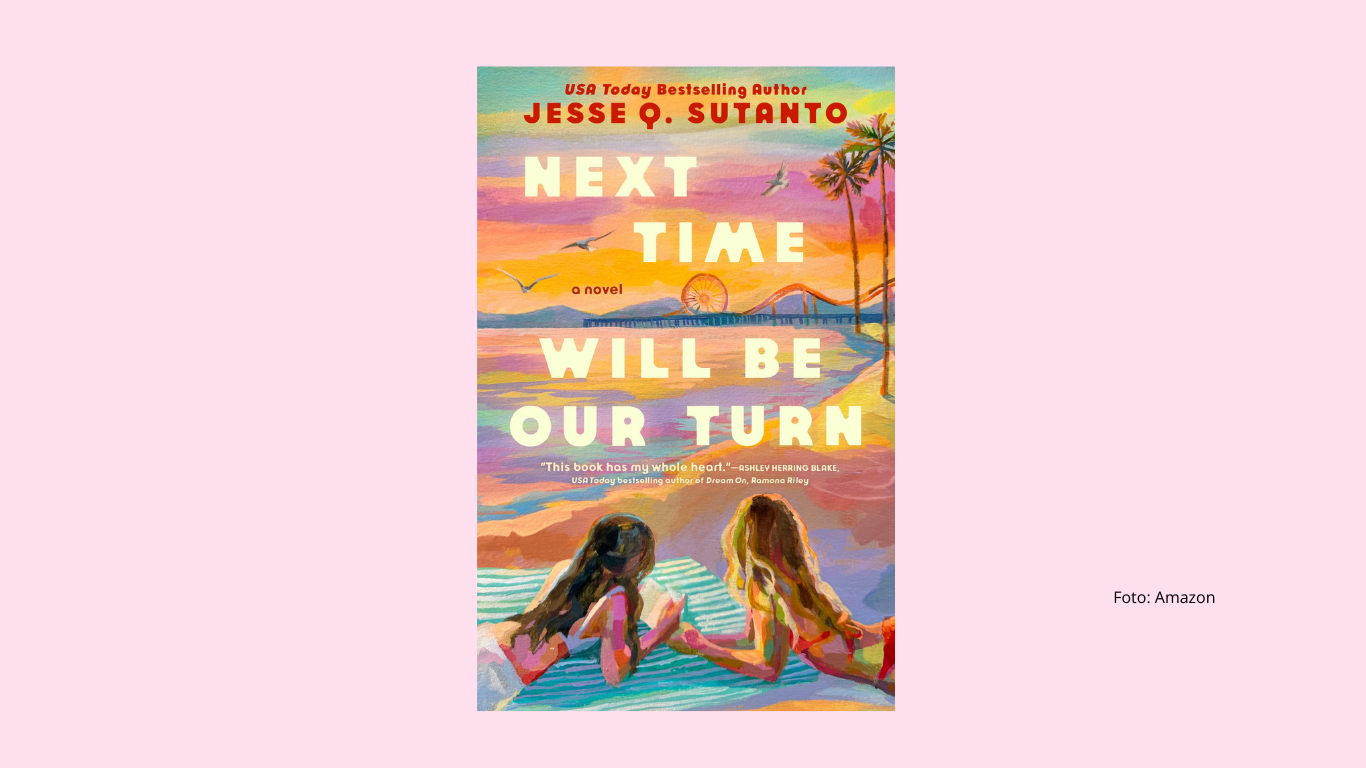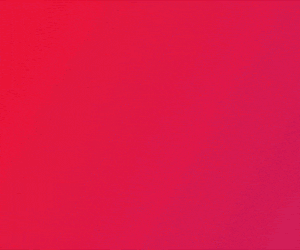Ada Kegagalan Negara Di Balik Lahirnya Serikat Pekerja Kreatif

Belakangan, sejumlah musisi Indonesia serempak mengunggah gambar yang memuat pesan singkat bertulisan “VISI: Vibrasi Suara Indonesia” dengan tagar #SuaraKami. Beberapa musisi yang ikut serta di antaranya, Armand Maulana, Baskara Putra, Duta Sheila On 7, Bernadya, Vidi Aldiano, Rossa, Raisa, Fiersa Besari, Ariel NOAH, dan Pamungkas.
Unggahan ini ini sontak mengundang perhatian publik, termasuk oleh Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum RI. Dalam konferensi pers, (19/2), sebagaimana dilansir dari Kumparan, ia bilang, “Ternyata memang dari zaman dulu sampai sekarang belum pernah ada kumpulan atau serikat gitu ya, penyanyi belum ada. Kayaknya kemarin ketika itu dikumpulkan, terkumpulah sekian puluh penyanyi, akhirnya terjadilah yang BCL bilang, VISI, Vibrasi Suara Indonesia.
Dalam manifesto Kami Peduli, Kami Bergerak: Demi Kesejahteraan Insan Musik Indonesia, VISI mendorong negara untuk memastikan implementasi Undang-Undang Hak Cipta berjalan secara adil bagi seluruh insan musik. Jika ada ketidaksesuaian atau polemik dalam aturan, negara perlu hadir untuk memastikan solusi yang transparan dan tidak berpihak pada segelintir pihak.
VISI menekankan revisi Undang-Undang Hak Cipta agar pelaksanaannya dapat lebih jelas dan tidak ambigu. Tidak kalah penting, mereka juga mendorong pemerintah untuk memastikan perlindungan penyanyi dan pelaku pertunjukan.
Baca Juga: Konglomerat di Balik Pagar Laut: Bukti Ketimpangan Si Kaya dan Miskin Kian Curam
Hidup Hanya untuk Kerja, Kerja, dan Kerja
Kemunculan VISI mengungkapkan kerentanan yang dihadapi oleh pekerja kreatif di Indonesia. Mereka boleh jadi berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) Rp1.153,4 triliun di 2019, menurut Statistik Ekonomi Kreatif yang diterbitkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun, data statistik tersebut berbanding terbalik dengan kondisi para pekerja industri kreatif Indonesia di lapangan.
Inez, 35, adalah ilustrator yang telah mencicipi asam garam bekerja di bidang ekonomi kreatif. Ia sempat menjadi penulis buku anak, lalu pada 2021 memutuskan menjadi ilustrator profesional. Dibandingkan para pekerja di sektor formal bahkan di pekerjaan sebelumnya sebagai penulis, ilustrator terbilang paling rentan mengalami eksploitasi dari pemberi kerja.
“Urusan legalitas, pokoknya terkait hak-hak ilustrator seperti hak cipta, finansial, surat kontrak sampai jaminan sosial itu masih jadi masalah. Itu menurutku karena ilustrator tuh salah satu profesi yang paling sering juga diremehkan, karena dianggapnya cuma gambar-gambar doang, jadi parameter perlindungannya agak rumit gitu,” katanya.
Ilustrator, imbuhnya, sering kali tidak mendapatkan kontrak kerja. Padahal itu adalah komponen penting dalam hubungan kerja karena memuat penjelasan tentang hak dan kewajiban, termasuk hak cipta, upah, lingkup kerja ilustrator maupun pihak pemberi kerja. Kalau pun mendapatkan kontrak, poin-poin di dalamnya tidak dijelaskan mendetail, sehingga membuka celah eksploitasi.
Ilustrator di studio animasi Indonesia itu menambahkan, meski dipekerjakan sebagai ilustrator/ desain grafis, bos meminta ia mengurusi media sosial kantor dengan target tidak masuk akal. Tugas tambahan yang nyatanya tidak terdapat dalam kontrak kerja ini berdampak besar pada jam lembur Inez. Ia mengaku jadi harus siaga selama 24 jam karena bosnya bisa sesuka hati memberikan tugas baru. Inez pun mengaku dengan gajinya yang hanya sebesar Rp4 juta, tidak sepadan dengan beban kerja tambahan yang ia pikul di luar kontrak kerja.
“Dia suka nugasin random di jam enggak ketebak dan planning-nya enggak jelas. Bisa dia tiba-tiba dapet ide jam 2 siang, terus nargetin tayang jam 6 sore. Nah itu aku harus ngebut. Itu full ilustrasi ya ngerjainnya, bukan yang full aset doang atau foto. Terus aku harus mikirin captionnya, ngadminnya kaya apa. Menurutku itu enggak sepada sih,” curhat Inez.
Selain bekerja di luar kontrak, Inez juga tidak mendapatkan jaminan kesehatan sama sekali. Padahal menurut Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, semua anggota perusahaan yang meliputi pekerja tetap dan pekerja kontrak di atas tiga bulan wajib didaftarkan untuk BPJS Kesehatan.
Kondisi yang kurang lebih sama juga dialami animator, Aca, 24. Ia sempat bekerja di di dua studio animasi berbeda. Di studio pertama, Aca bekerja layaknya robot. Dibayar berdasarkan hasil, bosnya banyak mengambil proyek tanpa mau memusingkan kondisi pekerja. Alhasil lembur jadi makanan harian Aca. Ia bahkan menuturkan waktu lemburnya bisa sampai jam dua pagi dan hanya diupah sebesar Rp20.000 per tiga jam.
“Overtime parah sih. Kaya aku pulang jam 5, istirahat sebentar, jam 7 sampai jam 10 lanjut kerja, istirahat bentar, terus kerja lagi sampai jam 2 pagi,” jelas Aca.
Beruntungnya jadwal lembur Aca di studio kedua berkurang. Namun, sama seperti Aca ia juga diberikan pekerjaan tambahan yang tidak sesuai kontraknya dan tidak mendapatkan jaminan kesehatan minimum, yakni BPJS Kesehatan. Sesuai arahan bos, Aca bekerja berganti-ganti divisi. Ada hari di mana ia ditunjuk untuk mengorganisir acara-acara kantor. Ada pula hari ia juga ikutan membantu divisi storyboard. Dengan kondisi kerja seperti ini, upah Aca tak pernah lebih dari Rp4 juta.
Baca Juga: 5 Kebijakan yang Mempersulit Kelas Menengah di 2025
Makin Sengsara karena Negara
Kondisi kerja Inez dan Aca ini adalah gambaran umum kondisi para pekerja kreatif di Indonesia. SINDIKASI (Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi) dalam survei mereka pada 2021 menemukan sebanyak 68,3 persen pekerja kreatif sering lembur. Namun sebagian besar responden mengaku tidak mendapatkan penggantian lembur sama sekali (51,6 persen), baik berupa upah lembur maupun cuti pengganti.
Pada 2024, SINDIKASI lalu membuat riset mengenai upah layak untuk pekerja kreatif. Dalam riset itu ditemukan hanya 23,6 persen responden yang terlindungi asuransi swasta. Sementara 56,36 persen tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 23,64 persen tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Mereka juga mengolah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 dan menemukan rata-rata upah pekerja ekonomi kreatif pada 2021 hanya Rp 2,2 juta per bulan atau lebih rendah dari rata-rata upah minimum provinsi dan lebih kecil dari rata-rata upah dari seluruh sektor industri.
Kondisi yang menghantui para pekerja kreatif ini disebut SINDIKASI sebagai flexploitation atau kerentanan khas yang dialami pekerja dalam hubungan kerja non standar atau fleksibel seperti pekerja lepas, mitra, dan konsultan. Istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Pierre Bourdieu pada 1997 ini ditandai dengan kondisi kerja yang terputus-putus, tidak teratur, dan informal. Flexploitation lebih lanjut juga dicirikan dengan lemahnya perlindungan hukum, ketiadaan jaminan sosial, jam kerja berkepanjangan (overwork), upah tak layak, dan ketidakjelasan masa depan.
Di Indonesia, flexploitation makin menghantui para pekerja kreatif pasca-Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan oleh pemerintah sejak 2020 silam. Ikhsan Raharjo, Ketua Umum SINDIKASI mengungkapkan UU Ciptaker semakin memperparah dan membuat sulit kondisi para pekerja kreatif karena banyak memangkas jaminan hak-hak buruh dalam berbagai aspek dengan fleksibilitas pasar kerja (labour market flexibility) sebagai inti pembentukannya.
UU Ciptaker tidak hanya memudahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga melanggengkan upah murah, dan meluaskan praktik outsourcing yang semakin membuat nasib kelas pekerja jauh dari kesejahteraan.
“Ini terjadi karena salah satu fitur utama UU Cipta Kerja adalah mudah dan murah merekrut dan murah memecat. Itu membuat job security atau keamanan kerja kita semakin berkurang. Bahkan informalisasi di sektor kreatif makin kuat,” jelasnya pada Magdalene.
Informalisasi sektor ini semakin tergambar dari tren aduan dari para pekerja kreatif yang diterima oleh SINDIKASI. Ikhsan tidak membeberkan secara spesifik jumlah kasus yang SINDIKASI terima. Namun ia menyebutkan sejak 2017 berdiri hingga pasca-UU Ciptker disahkan, SINDIKASI menangani aduan para pekerja kreatif terkait pemutusan kerja sepihak, upah yang tidak dibayarkan secara layak, dan kompensasi yang hampir tiap pekan pasti masuk ke dalam kanal aduan mereka.
Hariati Sinaga, dosen dan peneliti di Program Studi Kajian Gender SKSG menambahkan, kerentanan pekerja kreatif kemungkinan bakal lebih besar di era pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menggarisbawahi fokus pemerintahan Prabowo yang lebih condong pada melakukan transformasi ke arah hilirisasi dan industrialisasi secara besar-besaran daripada fokus pada peningkatan kesejahteraan kelompok pekerja. Hariati juga mengingatkan bagaimana sejak awal kampanye, Prabowo-Gibran telah massif menggunakan AI.
Belakangan, iklan program andalan Prabowo Makan Bergizi Gratis juga menggunakan AI. Penggunaan AI tanpa adanya regulasi ini telah dikritisi habis-habisan oleh para seniman hingga saintis AI sendiri, salah satunya lewat aksi #TolakGambarAI yang sempat viral pada Januari 2024 lalu.
Hariati berkomentar, “Bisa makin merajalela ketimpangan kuasanya dan kecenderungan sekarang itu agak represif. Kalau aku bisa berpendapat, bukannya lebih baik, justru bakal lebih buruk. Apalagi dengan masih meneruskan UU Cipta Kerja, ini otomatis akan berdampak kepada teman-teman pekerja kreatif.”
Baca Juga: Di Balik Milenial ‘Childfree’: Ada Masalah Struktural Ekonomi yang Jarang Dibahas
Kesadaran Berserikat Belum Merata di Semua Pekerja Kreatif
Sejumlah kerentanan yang dialami pekerja kreatif mendorong Inez dan Aca untuk berserikat. Keduanya memutuskan masuk ke dalam salah satu pekerja kreatif satu tahun lalu dan mengaku mendapatkan banyak manfaat dari berserikat. Serikat pekerja membantu memastikan hak-hak keduanya terlindungi, termasuk hak atas upah yang adil, jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman lewat pembekalan dan berbagai pelatihan.
“Teman-teman serikat itu selalu mendorong kami untuk selalu punya kontrak kerja. Meskipun kita pekerja kreatif, meskipun freelancer harus punya. Minimal SPK (Surat Perintah Kerja) dapet lah. Jadi jelas SPK ini tuh menentukan jam kerja kalian berapa dan kejelasan upah. Aku sekarang jadinya kalau mau ambil kerja tuh selalu ingat ini,” ungkap Inez
Selain itu berserikat juga dijamin mendapat pendampingan hukum dan bantuan dalam sengketa. Sehingga jika terjadi perselisihan antara pekerja kreatif dan pemberi kerja, serikat pekerja dapat memberikan dukungan hukum dan pendampingan, yang sangat bermanfaat untuk menghindari atau menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul dalam kontrak atau hubungan kerja. Dengan manfaat-manfaat ini, Inez dan Aca yang kerap kali bekerja sendiri atau dalam tim kecil jadi merasa punya jaringan pengaman tambahan.
“Aku jadi merasa aman, lebih kuat. Aku merasa enggak sendiri, kalau mau menyampaikan suara, hak-hak melenceng di perusahaan jadi bisa dibantu,” tutur Aca.
Tergabungnya Inez dan Aca dalam serikat pekerja kreatif mencerminkan kebutuhan akan perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja kreatif. Menurut Ikhsan kebutuhan ini cukup tergambarkan dari jumlah pekerja kreatif yang jadi anggota SINDIKASI. Ikhsan menyebut walau sejak 2017 sudah cukup banyak pekerja kreatif yang tergabung dalam SINDIKASI, setelah muncul UU Ciptaker hingga informalisasi sektor kreatif makin menguat beberapa tahun belakangan, jumlah pekerja kreatif yang mendaftar jadi anggota juga semakin banyak.
“Jadi banyak pekerja kreatif yang awalnya sebagai pekerja tetap kemudian kehilangan pekerjaan. Dan akhirnya mereka beralih status menjadi freelance yang memiliki banyak kerentanan dalam kerja mereka sehari-hari,” katanya.
Namun peningkatan jumlah anggota pekerja kreatif di SINDIKASI serta tergabungnya Inez dan Aca di serikat pekerja tidak bisa jadi tolak ukur dalam melihat kesadaran berserikat para pekerja kreatif. Pasalnya, SINDIKASI sendiri hanya memiliki sekitar 700 anggota (pekerja media dan kreatif) di seluruh Indonesia.
Sedangkan Inez dan Aca mengungkapkan di antara semua teman-teman sesama pekerja kreatif, hanya sedikit bahkan tidak ada sama sekali yang tergabung dalam serikat pekerja. Aca bahkan mengatakan banyak temannya mayoritas tidak tahu apa itu serikat pekerja dan apa fungsinya.
Ikhsan dan Hariati lantas mengomentari hal ini. Menurut mereka, kesadaran yang masih rendah di antara para perkerja kreatif tidak terlepas dari dikotomi kuat makna buruh dan karyawan di masyarakat Indonesia. Buruh hanya dimaknai sebagai pekerja manufaktur saja. Padahal siapa pun yang bekerja mendapatkan upah disebut sebagai buruh.
Dikotomi ini adalah warisan Orde Baru. Soegiri DS dan Edi Cahyono, dalam buku Gerakan Serikat Buruh, Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru (2003) menuliskan rezim otoriter ini sengaja melakukan politisasi bahasa. Itu dilakukan dengan memberangus serikat buruh dan mendirikan “serikat buruh” baru resmi dan diakui pemerintah.
Pada 1960, TNI Angkatan Darat mendirikan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) untuk menggantikan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)-kala itu adalah federasi organisasi buruh terbesar di Indonesia yang dicap sebagai PKI. Istilah buruh resmi berubah menjadi karyawan.
“Nah ini berdampak pada kesadaran mereka (pekerja kreatif) secara kolektif lewat serikat. Mereka ini sering menghadapi masalah yang sama sebetulnya dengan pekerja di manufaktur, tapi merasa bahwa karena dirinya berpendidikan tinggi maka mereka bisa menyelesaikan secara individu. Padahal kenyataan di lapangan tidak seperti itu,” jelas Ikhsan.
Warisan telah mengakar sejak lama ini tentu sulit untuk dihilangkan. Ini menurut Hariati menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi masyarakat sipil dan serikat-serikat pekerja karena pemerintah jelas tidak bisa secara sepihak diandalkan.
Karena itu, untuk memupuk kembali kesadaran para pekerja termasuk pekerja kreatif tentang hak-hak mereka harus melalui usaha kolektif. Berbagai advokasi bisa didorong baik dalam kelompok sosial kecil atau lewat kolaborasi. Advokasi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik terhadap hak-hak pekerja termasuk pentingnya berserikat.
“Bisa membuat diskusi lintas kelompok masyarakat. Di dalam internal kita sendiri misalnya dalam serikat pekerja atau organisasi masyarakat sipil buat program kolektif dengan mengaitkan hak-hak pekerja lewat hal-hal yang dekat dengan mereka. Misal sekarang soal efisiensi anggaran, ada isu kelasnya kan dan ternyata ada hak-hak tenaga kerja masuk di situ,” tutup Hariati.
*Magdalene sudah berusaha menghubungi VISI. Namun hingga artikel ini terbit Magdalene belum mendapatkan jawaban.