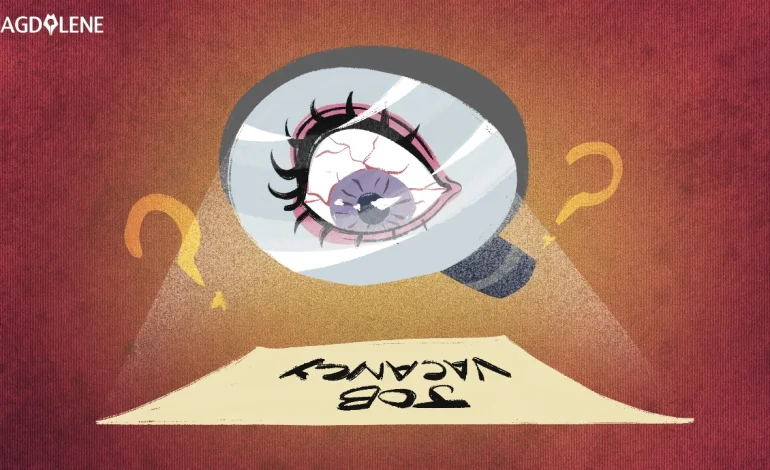Awal 2025 ditandai dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap produk perawatan kulit. Konsumen, kebanyakan perempuan, tidak lagi membeli produk hanya karena klaim atau kemasannya yang cantik, tetapi mulai mencari tahu kandungan, proses produksi, dan dampak ekologis dari produk tersebut. Google Trends mencatat pencarian kata “skintellectual” di Indonesia meningkat 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Istilah skintellectual merujuk pada konsumen yang tidak sekadar menggunakan skincare, tetapi juga memahami formulasi, membaca riset ilmiah, dan mempertimbangkan isu etika serta keberlanjutan produk. Fenomena ini sejalan dengan tren clean beauty, minimalist skincare, hingga sustainable cosmetics yang membanjiri marketplace dan lini masa Instagram.
Bahkan merk lokal besar seperti Wardah ikut mengangkat diskusi publik bertema skintellectual. Dalam wawancara dengan Kompas.com, dr. Cynthia Jayanto M.Biomed (AAM) dari Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia menyatakan bahwa tren perawatan kulit 2025 bergerak menuju penggunaan teknologi canggih yang tetap alami dan tidak mengubah wajah secara drastis.
Baca juga: Aku Membeli Maka Aku Ada: Sejauh Mana ‘Influencer’ Bikin Kita Ketagihan Belanja?
Konsumen pun semakin sadar dan selektif. Di kota-kota besar, perempuan usia 20–39 tahun mulai beralih ke produk ramah lingkungan, seperti kosmetik berbahan herbal dan rempah-rempah lokal. Namun, di balik tren yang tampak progresif ini, ada sejumlah pertanyaan kritis yang perlu diajukan.
Saya menulis bukan sekadar sebagai konsumen, tetapi juga mantan pelaku industri. Bertahun-tahun saya mengelola bisnis kosmetik herbal dan memproduksi krim wajah alami bersama para kosmetolog. Di awal, saya menganggap ini bentuk tanggung jawab sosial, dengan menggunakan bahan alami dan kemasan ramah lingkungan.
Namun perlahan saya sadar bahwa “alami” tidak selalu berarti adil, dan “sustainable” tidak selalu rendah jejak karbon. Misalnya, laporan Agricultural Development Report 2024 dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat bahwa ekspansi kebun lavender di Maroko, Bulgaria, dan Tanzania menggusur tanaman pangan lokal dan menyedot air tanah dalam jumlah besar. Di Kalimantan Timur, investigasi Mongabay Indonesia (Mei 2025) mengungkap bahwa perkebunan kelapa untuk minyak kosmetik memutus akses air bersih bagi perempuan Dayak yang harus berjalan dua jam lebih jauh untuk mengambil air.
Baca juga: ‘Greenwashing’ Kim Kardashian: Saat Fakta Tak Sehijau Kata-kata
Saat skincare jadi soal keadilan ekologis
Di sinilah pentingnya perspektif ekofeminisme seperti yang dikembangkan Vandana Shiva dan Ariel Salleh. Mereka melihat bahwa keberlanjutan bukan semata soal pilihan produk, melainkan juga soal keadilan struktural: siapa yang menanam, siapa yang kehilangan tanah, dan siapa yang diuntungkan?
Shiva menulis dalam Staying Alive: Women, Ecology and Development (1988) bahwa tubuh perempuan dan tubuh bumi sering dieksploitasi oleh sistem kapitalisme patriarkal. Keduanya diperlakukan sebagai objek untuk dikendalikan, bukan entitas yang berdaulat.
Sebagai produsen, saya pun dulu terjebak dalam narasi bahwa “kami hanya memenuhi permintaan pasar”. Padahal, produsen juga punya kuasa besar dalam membentuk preferensi konsumen. Ketika tren sustainability diangkat tanpa refleksi kritis, ia mudah terjebak dalam jebakan green capitalism.
Industri kecantikan kini sangat lihai mengemas kesadaran ekologis menjadi gaya hidup baru, lalu menjualnya kembali sebagai produk premium. Kemasan “eco-friendly” yang diimpor dari Eropa bisa memiliki jejak karbon lebih tinggi daripada plastik lokal daur ulang. Bahan “lokal” bisa saja datang dari hutan yang baru dibabat.
Di titik ini, skintellectual bukan lagi gerakan transformatif, melainkan bagian dari konsumsi gaya hidup yang hijau di permukaan saja. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan tren ini benar-benar berkelanjutan?
Baca juga: Menelusuri Algoritme Kecantikan di Medsos: Masih Terjebak di Standar Eurosentris
Dari pengalaman saya, jawabannya tidak sederhana. Pertama, dibutuhkan transparansi rantai pasok—konsumen perlu tahu asal-usul bahan, siapa yang memproduksi, dan dampaknya terhadap lingkungan maupun komunitas lokal. Kedua, pendidikan kritis yang membongkar mitos-mitos greenwashing, yaitu strategi pemasaran yang melebih-lebihkan klaim ramah lingkungan demi menarik konsumen peduli lingkungan. Selain itu, dukungan nyata bagi produsen kecil yang bekerja langsung dengan komunitas juga sangat penting, agar keberlanjutan tidak hanya menjadi retorika, tapi praktik yang adil dan membumi.
Ekofeminisme mengingatkan bahwa perubahan tidak hanya datang dari kebijakan besar, tapi juga dari jaringan kecil yang saling menopang. Skintellectual, dalam bentuk terbaiknya, bisa menjadi jalan masuk untuk kesadaran ekologi yang lebih dalam. Tapi tanpa keterhubungan dengan isu struktural seperti keadilan rantai pasok dan perlindungan lingkungan, ia akan tetap menjadi tren gaya hidup semata—menyenangkan secara estetika, tetapi tak menggoyang akar persoalan.