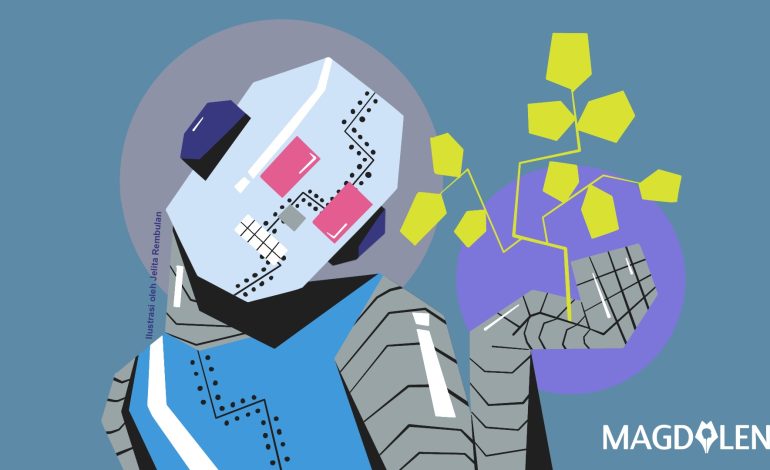Refleksi Anak Sastra: Zaman Berubah, tapi Komik Tetap Distigma

Ada rasa tidak nyaman yang kerap muncul setiap kali Chika, 28, mendapat pertanyaan, “Lagi baca apa?” dari teman atau orang-orang yang baru dikenalnya. Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi Chika, rasanya seperti menjadi terdakwa di ruang persidangan.
Ia kerap berhenti sejenak sebelum menjawab, menimbang-nimbang apakah jawabannya akan membuatnya tampak “bersalah”. Bersalah dalam arti terlihat seperti orang dewasa yang bacaannya dianggap tidak berbobot. Kegelisahan itu muncul terutama ketika ia sedang asyik membaca komik ketimbang novel atau buku tebal bertema filsafat maupun sosial-politik.
“Kalau mau jawab komik, rasanya takut dikira nggak baca soalnya komik bergambar, enggak kayak novel atau buku gitu,” tuturnya jujur.
Kegelisahan Chika mendapat penjelasan ketika Nabila Rosyadah, Editor Bumi Langit, mengisi salah satu sesi di Pesta Literasi 5.0, (22/11). Nabila menyampaikan bahwa meskipun zaman terus bergerak maju, teknologi berkembang, dan manusia semakin sadar akan banyak hal, cara pandang terhadap sastra justru tidak banyak berubah.
Hingga hari ini, komik masih sering ditempatkan sebagai bacaan pinggiran, bukan karya sastra yang layak diperhitungkan. Cara pandang ini berdampak langsung pada Bumi Langit, penerbit yang sejak awal berfokus pada produksi komik.
Dalam berbagai ruang literasi, mereka lebih sering absen bukan karena tidak punya karya, melainkan karena medium yang mereka usung belum dianggap sebagai bagian dari sastra arus utama.
“Ini pertama kalinya Bumi Langit diundang ke acara literasi,” ungkap Nabila.
Baca Juga: ‘Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu’: Kekerasan Perempuan dan Jejak Pembantaian ’65-66
Komik Bukan Bacaan Serius
Ungkapan Nabila itu singkat, tetapi membekas. Kalimat tersebut menyeret ingatan pada perjalanan panjangku menghadiri berbagai acara literasi. Sejak kecil, sebagai pecinta buku, aku banyak mengikuti peluncuran buku, diskusi sastra, bedah karya, hingga festival literasi. Namun di antara deretan meja penerbit, para pembicara, dan ragam tajuk diskusi, ada satu hal yang nyaris selalu absen: Komik.
Aku jarang, bahkan hampir tidak pernah, melihat penerbit komik masuk dalam rangkaian acara literasi. Diskusi tentang membaca pun berputar-putar pada genre, narasumber, dan medium yang itu-itu saja. Kreator komik, penerbit, dan komunitas pembacanya seperti berada di dunia lain. Mereka hadir dan terus berkarya, tetapi tidak pernah diundang. Penghargaan sastra? Jangan harap ada komik dalam daftarnya.
Sebagai lulusan sastra, jarak itu terasa ganjil sekaligus pedih. Di bangku kuliah aku diajarkan bahwa komik adalah bagian dari sastra. Ia dibedah di kelas menggunakan teori semiotika, naratologi, hingga kajian budaya.
Tak sedikit skripsi senior maupun dosen muda yang menggunakan komik sebagai objek penelitian. Semua itu diakui, dinilai, dan dirayakan di ruang akademik. Namun di luar kampus, komik seolah kehilangan martabatnya. Di antara novel ratusan halaman yang mengangkat tragedi kemanusiaan, komik justru diturunkan derajatnya dan diberi label sebagai bacaan anak-anak yang tak berbobot. Kontras inilah yang membuat pernyataan Nabila terasa sebagai tamparan halus: apa yang sah di ruang kelas belum tentu diakui di ruang publik literasi.
Stigma terhadap komik bukanlah problem khas Indonesia. Di berbagai belahan dunia, baik Barat maupun Asia, komik sama-sama diperlakukan sebagai bacaan kelas dua. Di banyak negara Barat, stigma komik sebagai bentuk “bacaan rendah” bahkan menjadi objek kajian tersendiri.
Dalam tesis Comics as Literature? Reading Graphic Narrative (2008), misalnya, disebutkan bahwa banyak peneliti dan pengajar memandang komik sebagai genre sastra inferior—bukan kandidat “sastra serius” untuk dianalisis secara akademis. Akibatnya, para penggemar komik kerap harus berhadapan dengan stigma sosial dan sikap meremehkan.
Anggapan serupa muncul di negara-negara Asia. Studi di Taiwan yang dimuat dalam Charting an Asian Trajectory for Literacy Education (2021) menyoroti adanya stigma publik yang merendahkan komik meski ia dipakai sebagai alat pembelajaran. Penilaian semacam ini membatasi bagaimana komik dan pembacanya diperlakukan dalam wacana literasi.
Hal serupa juga terjadi di Korea Selatan. Walaupun di negeri ginseng komik perlahan memasuki arus utama, stereotip yang merendahkan pembacanya masih bertahan—terutama pada genre tertentu seperti Boys Love. Hal tersebut dijelaskan dalam Women and Their Body: A Cultural and Historical Struggle Against Tradition (2025).
Baca Juga: A.W. Prihandita, Pemenang Nebula Award yang Menentang AI
Stigma yang Dibangun Sejak Lama
Stigma terhadap komik tidak lahir begitu saja. Di Barat, salah satu akarnya dapat ditelusuri ke era 1950-an ketika komik dituding merusak moral anak. Buku Seduction of the Innocent (1954) karya psikiater Fredric Wertham memopulerkan gagasan bahwa komik memicu kekerasan dan penyimpangan.
Akibatnya, lahirlah Comics Code Authority, regulasi yang membatasi tema, visual, dan narasi komik Amerika. Selama puluhan tahun, komik bukan hanya disensor tetapi juga dicap berbahaya. Warisan kultural ini membentuk imajinasi kolektif bahwa komik bukan bacaan intelektual sehingga posisinya merosot dalam dunia literasi.
Indonesia pun tak sepenuhnya lepas dari imbas tersebut. Dalam Komik Indonesia (1998), Dr. Marcell Bonneff mencatat bagaimana komik dihujat sebagai bacaan sampah yang meracuni generasi muda dan dianggap tidak mendidik. Konteks Indonesia semakin pelik karena di tengah gempuran komik Barat, komik sempat dinilai kontra-revolusioner sehingga gagasannya dianggap berbahaya.
Di ranah akademik, resistensi terhadap komik juga bertumpu pada tradisi kanon sastra. Dalam The Graphic Novel: An Introduction (2007), Jan Baetens dan Hugo Frey mencatat ketegangan antara “sastra adhiluhung” dan medium visual, di mana teks bergambar dianggap terlalu “mudah” untuk masuk wilayah elite intelektual. Ini sejalan dengan pemikiran Pierre Bourdieu dalam Distinction (1979) bahwa selera bukan sekadar preferensi, tetapi alat pembeda kelas.
Novel tebal, bahasa puitis, dan rujukan klasik ditempatkan sebagai simbol intelektualitas. Sementara komik—karena mengandalkan visual, mudah diakses, dan memakai bahasa populer—digeser ke sisi yang berlawanan. Hierarki selera inilah yang terus menempatkan komik sebagai “bukan sastra sungguhan”, meski ia memiliki bahasa naratifnya sendiri.
Zaman boleh berubah, tetapi stigma komik sebagai bacaan rendahan tetap langgeng hingga kini. Di level pendidikan, kurikulum sekolah masih jarang memberi ruang bagi komik sebagai teks sastra. Dalam tugas membaca atau menulis resensi misalnya, komik hampir tak pernah dijadikan pilihan bahan ajar.
Di ranah penerbitan, toko buku masih mengelompokkan komik secara terpisah, tidak seperti novel yang ditempatkan berdasarkan genre. Di festival literasi pun yang diundang adalah para novelis, bukan komikus. Struktur ini terus mereproduksi anggapan bahwa komik berada di luar “arus utama”.
Padahal jika bersikukuh komik adalah bacaan tidak berbobot, Scott McCloud dalam Understanding Comics (1993) justru menunjukkan sebaliknya. Komik memiliki kompleksitas bahasa visual yang mampu mengolah isu sosial-politik, trauma, hingga memori dengan cara yang sering kali lebih mudah dijangkau pembaca.
Jika setelah membaca artikel ini kamu masih menganggap komik “tidak serius”, mari uji sekarang klaim itu dengan membaca. Mungkin kamu bisa memulainya dengan membaca 20th Century Boys karya Naoki Urasawa. Komik tersebut secara apik mengeksplorasi tema kultus, paranoia politik, dan trauma kolektif Jepang pasca-perang.
Baca Juga: Queer and Palestine: Cara Priscilla Yovia Melawan lewat Bacaan
Setelah selesai membaca itu, kamu bisa lanjut melahap Monster karya Urasawa lainnya. Komik ini adalah hidangan lezat buat kamu yang suka genre psychological thriller. Dalam sembilan volumenya kamu diajak memahami ulang soal bersoal etika, nihilisme dan tanggung jawab individu di Eropa pasca-Perang Dingin.
Kalau mau mencoba mencicipi komik dari negara lain dan berperspektif gender, kamu bisa membaca Persepolis karya Marjane Satrapi. Komik yang merupakan autobiografi Satrapi ini bercerita tentang masa kecilnya di Teheran, Iran, selama Revolusi Iran, serta pengalaman dan perjuangannya dalam tumbuh dewasa di tengah gejolak politik dan sosial Iran hingga masa remajanya di Wina, Austria.
Jika setelah membaca karya-karya kamu masih menganggap komik bukan sastra serius, maka yang perlu dipertanyakan bukan lagi tentang nilai dari komik itu sendiri tapi justru bias tak sadar yang kamu miliki. Apakah kamu membaca untuk dirimu sendiri atau untuk memenuhi ego yang sengaja dibentuk masyarakat dari stigma yang ada?