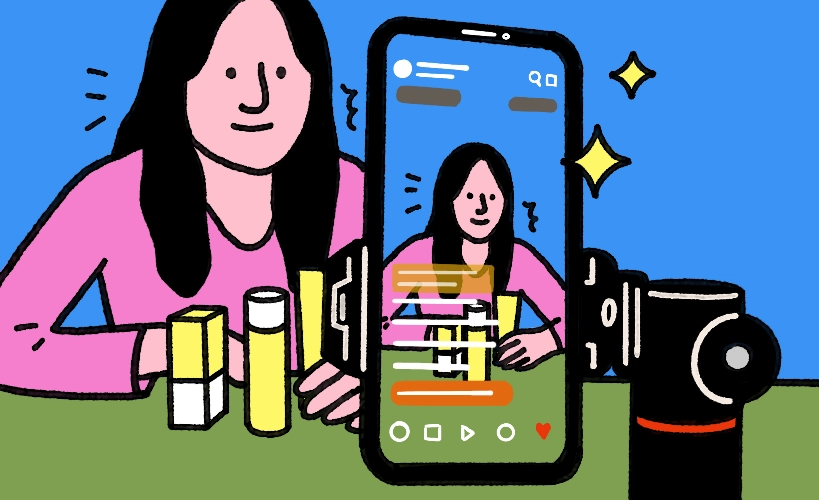Tolak RUU PKS, Mereka Berlindung di Balik Kedok Feminisme

Kampanye #TolakRUUPKS di media sosial sering diasosiasikan dengan tingkah laku buzzer, yang menyebarkan ideologinya lewat media sosial. Namun, penelitian Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia dan Pemerhati Isu Gender, Endah Triastuti bersama timnya menunjukkan hal lain. Para pendengung itu tak ada sangkut pautnya dengan kampanye meresahkan itu.
“Ini lebih dari buzzer di industri, tapi lebih ke struktur yang dibangun pihak-pihak dengan ideologi berbeda dari tujuan RUU PKS,” tutur Endah dalam forum diskusi Denpasar 12 berjudul “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Mewujudkan Kebijakan Berbasis Bukti dalam Proses Legislasi)”, (28/7).
Menurutnya, tagar tersebut bisa ditarik sejarahnya sejak era pasca-Orde Baru. Ini didukung dengan penelitian bertajuk “A Hundred Years of Feminism in Indonesia” (2017) oleh akademisi Gadis Arivia dan Nur Iman Subono. Mereka menyatakan ada perubahan gerakan politik perempuan di Indonesia sesudah Orde Baru yang lebih terfragmentasi berbasis agama. Di saat yang bersamaan, muncul pula gerakan populisme.
Gerakan populisme memiliki kecenderungan menawarkan ideologi yang mereproduksi dominasi terhadap perempuan. Endah menuturkan, terdapat institusi yang berkembang secara organik, tanpa afiliasi tertentu, tapi tergerak secara otomatis karena mengusung narasi yang sama.
“Mereka tidak terafiliasi, tapi di-grooming dan berkembang di institusi-institusi organik dengan narasi yang sama, yaitu menolak RUU PKS,” ujarnya.
Beberapa contoh institusinya ialah Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA), Sekolah Pemikiran Islam (SPI), Center for Gender Studies (CGS), dan feministclass.id. Usut punya usut, para pendirinya berafiliasi dalam mendirikan institusi tersebut. Ketua AILA Rita H. Soebagio, merupakan penulis buku Transformasi Menuju Fitrah: LGBT dalam Perspektif Keindonesiaan. Kemudian, pendiri SPI adalah Akmal Sjafril, seorang aktivis, penceramah, peneliti, penulis, sekaligus pengurus AILA. Sementara CGS dikepalai oleh Rira Nurmaida, salah satu penulis buku Delusi Kesetaraan Gender yang dirilis oleh AILA.
Baca Juga: RUU PKS Penting untuk Korban, Kenapa DPR Masih Tarik Ulur?
Terdapat keragaman pendekatan yang dilakukan. Ada yang beraliansi dengan ad hoc dan memiliki posisi formal pada sistem politik negara, kaum menengah lewat organisasi perempuan dan pengajian, maupun akademik dan mahasiswa.
AILA menjadi contoh yang berani mempengaruhi hukum kita, misalnya dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, memberikan saran ke anggota DPR RI tentang RUU KUHP, hingga “curhat” keresahannya perihal LGBT ke Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
“Berlindung” di Balik Feminisme
Institusi-institusi tersebut dengan gencar “mengedukasi” pengikutnya di media sosial tentang bahaya feminisme, LGBT, kesetaraan gender, hingga perlunya menolak RUU PKS, lengkap dengan tagar #TolakRUUPKS dan #RUUPKSBukanSolusi.
Ada unggahan lain yang dapat ditemukan di Instagram, dengan menulis #feministclass di kolom pencarian. Kita akan menemukan berbagai unggahan “edukasi” feminisme dari perspektif Islam. Salah satu dari institusi tersebut menawarkan para mahasiswa untuk ikut program menulis dan menjadi content creator di media sosial. Mereka memproduksi konten yang menolak RUU PKS, mendistorsi definisi gender, hingga sexual consent.
Endah menjelaskan, ini lebih buruk daripada buzzer karena terdapat proses internalisasi nilai-nilai yang didistorsi pada generasi muda, dan membentuk pseudosains, yakni kepercayaan keliru yang dianggap berdasarkan pada metode ilmiah, dan dapat dipengaruhi oleh informasi yang ditemukan di internet. Dalam konteks ini, mereka cenderung mengabaikan berbagai bukti yang bertentangan dengan pemahaman kelompoknya.
Berbagai institusi tersebut juga turut aktif melakukan diskusi dan kelas terkait gender, feminisme, dan RUU PKS, dengan mayoritas pembicara laki-laki. Sementara dalam pembahasan tersebut dibutuhkan pengalaman dan perspektif perempuan yang disampaikan secara langsung, sehingga tidak mengubah agen utama pembahasan.
Mereka pun berusaha menata ulang marginalisasi dan domestikasi perempuan, serta menafsirkan kesetaraan gender sebagai “musuh” dalam keluarga. Hal ini disebabkan pemahamannya, yang menganggap feminisme memandang keluarga sebagai sumber ketidakadilan dan menyuburkan patriarki, tanpa menyadari penekanan mereka terletak pada “perempuan adalah pelayan laki-laki.”
Baca Juga: RUU PKS Masuk Lagi ke Prolegnas, Kawal Terus Pembahasannya
Ancaman terhadap Pengesahan RUU PKS
Melalui unggahan di Instagram, AILA dan Center for Gender Studies menitikberatkan akar masalah ideologis RUU PKS terletak pada frasa “hasrat seksual” dalam Pasal 1 Ayat 1. Frasa tersebut dianggap sebagai sumber legitimasi berbagai penyimpangan perilaku, seperti perzinaan, pelacuran, dan disorientasi hasrat seksual LGBT.
Dalam perilaku zina, mereka merujuk ke pembahasan consent dalam hubungan seksual. RUU ini dianggap akan melegalkan hubungan seks tanpa ikatan pernikahan yang sah secara agama maupun negara, asalkan hubungan tersebut dilakukan tanpa kekerasan atau paksaan.
Padahal, tindak pidana zina telah diatur dalam Pasal 284 KUHP, pun RUU PKS tidak menindak pidana terhadap subuh seseorang, sedangkan zina mengarah pada perkawinan dan moralitas. Sementara hubungan seksual yang dilakukan berdasarkan consent tidak menimbulkan korban.
Baca Juga: Kiriman ‘Dick Pic’ dan Video Porno Tak Konsensual Naik Selama Pandemi
Kemudian, mereka masih melihat RUU PKS pro terhadap LGBT dan menganggap ada tuntutan pengakuan kebebasan pribadi. Tujuannya agar pernikahan sesama jenis dilegalkan seperti di beberapa negara lain. Interpretasi itu terbentuk akibat penggunaan frasa “hasrat seksual” dalam naskah dinyatakan tidak terbatas pada heteroseksual atau homoseksual, dan “perilaku homoseksual” tidak dinyatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.
Pemahaman tersebut memicu diurungkannya urgensi pengesahan RUU PKS, karena mengedepankan penerapan sistem polisi moral dalam menegakkan hukum. Penetapan ideologi yang dilakukan hanya berdasarkan sudut pandang agama dan menghakimi perbuatan seseorang, berlandaskan apa yang diyakininya benar dan salah.
Kondisi ini bukan hanya merugikan korban kekerasan seksual, melainkan juga masyarakat dengan orientasi seksual selain heteroseksual, yang menurut mereka menyimpang dan layak dipidanakan, karena keberadaannya dianggap sebagai ancaman.
Ilustrasi oleh Karina Tungari