‘We Have Always Been Here’: Saya Queer, Saya Muslim, dan Saya Bangga
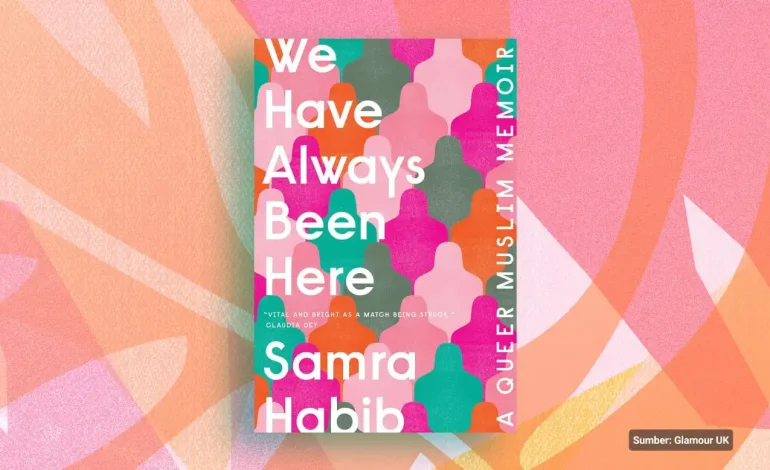
Agama bisa membebaskan, tetapi bisa pula memenjarakan ketika digunakan untuk alat kebencian. Islam, agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam pun demikian. Di tangan orang yang tak paham, Islam digunakan untuk memperkusi sebagian penganutnya. Salah satu kekerasan atas nama agama, dialami oleh Samra Habib, fotografer berdarah Pakistan.
Dalam buku “We Have Always Been Here: A Muslim queer Memoir”, Habib mengisahkan pengalamannya mengalami persekusi berulang kali. Ia lahir dan tumbuh besar di keluarga Ahmadiyah—didirikan Mirza Gulam Ahmad pada 1889–di Pakistan. Identitas ini membaut Habib jadi bulan-bulanan. Terlebih ia adalah perempuan queer. Sebuah identitas yang kerap kali diasosiasikan sebagai penyimpangan seksual, dibenci Islam, dan dilaknat Allah.
Menariknya, meski sering jadi korban persekusi karena identitasnya, Habib tetap menunjukan ketahanan diri. Dengan sekuat tenaga ia berusaha merebut kembali ruang yang telah lama dirampas darinya. Ruang di mana ia bisa mesra dengan Tuhannya, seraya merangkul identitas yang selama ini justru meminggirkan.
Baca Juga: Review ‘Kisah Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang’: Lagu Lama Keegoisan Manusia
Jadi Korban Persekusi
Ahmadiyah dikonotasikan sebagai ajaran sesat, dan penganutnya dilabeli kafir oleh mayoritas Muslim. Hal ini karena penganut Ahmadiyah mengakui Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan Imam Mahdi yang dijanjikan untuk membawa kemenangan akhir Islam. Padahal dalam pemahaman Islam arus utama, nabi Muhammad SAW adalah khatamul nabiiyin (nabi mutakhir). Sementara, kehadiran Imam Mahdi dan al Masih al Mau’ud masih ditunggu hingga akhir zaman sebagai sosok Nabi Isa AS.
Perbedaan inilah yang jadi dasar sejumlah umat Islam untuk mempersekusi Ahmadiyah. Meski dalam praktiknya penganut Ahmadiyah beribadah seperti Muslim pada umumnya, dengan melaksanakan Rukun Iman dan Rukun Islam, mereka tetap dianggap berbeda.
Di Pakistan, Habib tumbuh dewasa dengan ketakutan akan persekusi. Sejak kecil ia dan keluarganya terpaksa beribadah sembunyi-sembunyi karena masjid-masjid milik jemaat Ahmadiyah acap kali dikepung massa dengan senjata dan granat. Sepupu Habib bahkan pernah hampir terkena timah panas ketika sedang salat Jumat di salah satu masjid Ahmadiyah.
Tak cuma soal beribadah, hidup selayaknya warga negara normal saja mereka tidak bisa. Buat berbelanja atau menjalankan bisnis, seorang Ahmadiyah butuh keberanian ekstra, ini. Sebab, toko-toko milik jamaat Ahmadiyah sering dibakar bersamaan manusia yang ada di dalamnya.
Kekerasan terhadap Ahmadiyah semakin parah sejak 1974. Dikutip dari Human Rights Pulse tahun itu, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Ali Bhutto, Ahmadiyah dinyatakan sebagai “bukan Muslim demi tujuan hukum dan konstitusi. Itu tertuang dalam amandemen konstitusi setempat.
Berangkat dari peraturan itulah, negara hadir dalam parade kekerasan terhadap Ahmadiyah. Bahkan sepuluh tahun berselang, di era penguasa militer Jenderal Zia-ul-Haq. Kala itu, ada UU Anti-Ahmadiyah yang diberlakukan di Pakistan, sebagai perubahan Undang-undang Penistaan Agama pada 26 April 1984.
UU tersebut memberi ganjaran pidana kurungan tiga tahun baut pengikut Ahmadiyah yang menyebut diri Muslim atau mengamalkan Islam. Atau hukuman mati di bawah Undang-undang penodaan agama). Jamaat Ahmadiya pun dinyatakan sebagai “Wajibul Qatl” (pantas dibunuh), sehingga pelecehan, kekerasan, dan pembunuhan atas mereka dibenarkan bahkan didukung oleh aparatur negara.
Keluarga Habib juga jadi korban. Sepupu ayahnya tiba-tiba dikeroyok di jalan oleh para ekstremis agama. Kakak laki-laki ayahnya ada yang sampai pindah ke Rabwah karena para imam di daerah asalnya, Lahore mengharamkan warganya untuk menjual makanan kepada para Ahmadiyah, padahal istrinya sedang hamil dan butuh biaya. Sementara sang ayah berkali-kali harus menantang maut hanya demi pergi bekerja, sampai ia memutuskan untuk memboyong keluarga pindah ke Kanada.
Baca Juga: ‘Babel, or the Necessity of Violence’: Benarkah Kekerasan Dibutuhkan dalam Gerakan Pembebasan?
Minoritas Berlapis
Hidup dalam ketakutan akan persekusi bukan satu-satunya kendala buat Habib. Sebagai perempuan yang tumbuh besar di keluarga konservatif, Habib dididik untuk menjadi penurut dan pasif. Sebagai perempuan, ia tak boleh banyak membantah. Ia tak boleh tertawa keras-keras. Ia tak boleh bergaul dengan yang bukan mahramnya. Jika keluar rumah, ia harus menutup aurat walau itu di luar kehendaknya. Ia juga tak boleh menikmati musik apalagi sambil berdansa. Sebab, tak patut Muslimah melakukan sesuatu yang dibenci Allah, kata ayahnya.
UU tersebut memberi ganjaran pidana kurungan tiga tahun baut pengikut Ahmadiyah yang menyebut diri Muslim atau mengamalkan Islam. Atau hukuman mati di bawah Undang-undang penodaan agama). Jamaat Ahmadiya pun dinyatakan sebagai “Wajibul Qatl” (pantas dibunuh), sehingga pelecehan, kekerasan, dan pembunuhan atas mereka dibenarkan bahkan didukung oleh aparatur negara.
Puncaknya, ia harus menerima dirinya dikawinkan paksa dengan sepupu sendiri oleh orang tua di usia 16 tahun. Orang tuanya berdalih itu demi kebaikan Habib mengingat ia kini berstatus sebagai imigran. Dengan dinikahkan, kata orang tua, setidaknya Habib punya jaminan masa depan. Habib enggak bisa menolak keputusan ini. Selama dia hidup, perempuan di lingkungannya hanya bisa menerima nasib yang sudah digariskan kepada mereka tanpa banyak mengeluh.
“I’d only ever been surrounded by women who didn’t have the blueprint for claiming their lives. There,” tulis Habib.
Ada bibi-bibinya yang tidak akan pernah ketahuan bersosialisasi tanpa kehadiran suami. Mereka tidak bisa mengendarai mobil atau motor tanpa suami. Ada ibunya sendiri yang baru diberi tahu tentang perubahan namanya ketika undangan pernikahan sudah keburu dicetak. Tanpa berkonsultasi dengan ibunya, sang ayah memutuskan bahwa Yasmin akan menjadi nama yang lebih cocok dan anggun untuk istrinya dibandingkan Frida, nama aslinya.
Realitas ini membuat Habib pernah menganggap diskriminasi gender yang dialaminya dan perempuan lain sebagai kewajaran. Kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri atau membantah lelaki, tak ada dalam kamusnya. Inilah yang kemudian hari menyebabkan Habib merasa terjebak dalam penjara hidup. Apalagi perlahan ia menyadari diri sebagai seorang queer.
Beruntung, di tahap ini Habib bertemu dengan beberapa orang baru yang mampu mengubah pandangan hidupnya tentang arti kebebasan. Perlahan ia mulai memberontak. Ia sengaja menyibukkan dirinya dengan membaca, banyak bergaul dengan orang-orang baru, dan mengasah keterampilan yang sangat dibenci suaminya. Ia pun memutuskan minggat dari rumah tanpa mengabari orang tua usai mengungkapkan ketidakbahagiaannya tapi justru dicuekin.
Saat minggat, Habib akhirnya punya kesempatan mengeksplorasi dunia, termasuk lewat identitas sebagai queer. Masalahnya, Habib boleh jadi sudah merangkul identitas queernya, tetapi pemahaman dan pengalaman agamanya membuat ia terasa terasing. Muslim queer secara sistematis mengalami kekerasan dalam hal pembatasan kebebasan beragama. Lewat pemahaman bahwa queer dianggap “mengidap” penyimpangan seksual yang dilaknat Tuhan, orientasi seksual Muslim queer selalu dibenturkan dengan keimanan mereka.
Baca Juga: Ulasan ‘Lessons in Chemistry’, Benarkah Perempuan Kini Sudah Setara?
Lantas keberadaan Muslim queer sepenuhnya dinegasikan. Mereka dianggap tak pernah ada dan tak berhak menyembah Allah SWT. Agama pun tak ayal jadi ruang yang eksklusif untuk mereka yang dilabeli lebih suci.
Habib cukup beruntung. Dalam perjalanan menemukan identitas queer, ia dipertemukan dengan Masjid Unity atau Unity Mosque, Toronto, Kanada. Masjid itu ternyata didirikan oleh pengacara pengungsi queer El-Farouk Khaki pada 2009, dan sangat inklusif. Di sana, dikutip dari Buzzfeed News, Muslim queer menemukan kenyamanan “bermesraan” dengan Tuhan. Alih-alih berfokus pada ritual keagamaan, masjid yang juga berfungsi sebagai komunitas berkumpulnya Muslim queer ini lebih fokus kepada memahami agama sebagai ruang penyembuhan yang hangat dan ramah, di mana hubungan antara Tuhan dan individu bersifat langsung dan tanpa perantara.
Masjid Unity menghilangkan rasa sakit dan membantu Habib menyusun proyek fotografi “Just me and Allah”. Lewat proyek ini, Habib melakukan melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk bertemu Muslim queer lainnya dan mendengarkan cerita mereka. Cerita ini ia abadikan lewat lensa, dan menjadi bukti bahwa Muslim queer sama saja di mata Tuhan.






















