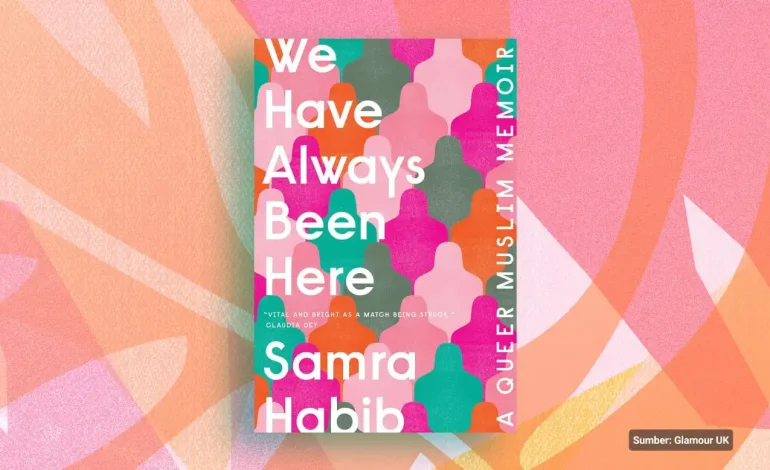#TanahAirKrisisAir: Bagaimana Endang Rohjiani Selamatkan Mata Air lewat Konservasi Sungai?
Endang Rohjiani menceritakan keterlibatannya sebagai ketua komunitas susur sungai, area yang didominasi lelaki.

Sejak Sekolah Dasar (SD), kita mungkin familier dengan dampak pembuangan sampah ke sungai: Pencemaran, pendangkalan, hingga perlambatan aliran air. Namun, siapa sangka di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tumpukan sampah berakibat fatal pada hilangnya mata air. Sungai Winongo salah satunya.
Hal itu diungkapkan Endang Rohjiani, 52, Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA). Forum ini merupakan wadah komunikasi bagi warga bantaran Sungai Winongo, yang melintasi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.
“Kami prihatin dengan kondisi sungai yang dijadikan tempat sampah,” tutur Endang pada Magdalene.
Berangkat dari alasan tersebut, FKWA mengajak warga untuk menjaga kualitas dan kuantitas sungai. Diikuti advokasi ke pemerintah, agar mereka terlibat dalam mengurus sungai.
Sebagai kolektif masyarakat, kegiatan FKWA diikuti sejumlah keberhasilan. Di antaranya mengalihkan pembuangan limbah peternak babi di perkotaan dengan dibuatkan biogas, supaya enggak langsung ke sungai. Kemudian pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal oleh pemerintah, setelah FKWA mendesak penyediaan fasilitas tersebut.
Akhir Januari lalu, Magdalene berkesempatan untuk menemui Endang di kandang maggot milik FKWA. Lokasinya di Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta—bekas TPA Yogyakarta pada 1980-1997. Kami berbincang tentang aktivitas FKWA dalam konservasi sungai, cara mereka melibatkan masyarakat, hingga pendanaan untuk kegiatan merawat lingkungan. Berikut kutipannya.

Baca Juga: Profil Sudarmi, Perempuan Penjaga Hutan Paliyan
Boleh diceritakan, Bu, kegiatan apa saja yang dilakukan FKWA?
Kami melakukan pemetaan mata air sejak 2013. Di 2015-2016, kami menemukan 80 persen mata air di wilayah perkotaan itu hilang. Sedangkan di hulu (sungai), kami memantau pada 2016-2018, setiap tahunnya hilang 100 titik mata air. Ini jadi keprihatinan sendiri. Padahal, mata air bisa dimanfaatkan warga untuk ketersediaan air bersih.
Selain konservasi di wilayah hulu (sungai), kami juga menata kawasan permukiman di wilayah perkotaan padat penduduk. Penataan ini menggunakan konsep M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali)—atau memundurkan, menaikkan, dan menghadapkan rumah ke sungai.
Kami juga melakukan suaka ikan untuk memastikan kualitas air di hilir (sungai) bersih. Di sini, masyarakat—anak-anak maupun orang dewasa—juga dilibatkan dengan melihat ikan-ikan endemik, bisa hidup atau tidak. Kalau udah enggak bisa hidup, berarti ada persoalan. Tapi sebelumnya, mereka diajak memetakan titik sampah yang paling banyak, sumbernya dari mana, ada enggak limbah yang enggak kekontrol.
Gimana cara melihat kualitas airnya, Bu?
Dengan metode biotilik. Indikator pencemarannya begini: Kalau di air banyak cacing merah, berarti kualitas airnya jelek. Kalau banyak udang bersungut panjang, kualitas airnya baik. Indikator ini ada dalam buku saku biotilik, jadi masyarakat bisa mandiri melihat kualitas airnya.

Tadi Ibu sempat cerita, mata air di kota dan hulu sungai itu hilang. Apa yang menyebabkan hilangnya mata air?
Sungai dijadikan tempat sampah oleh masyarakat. Sebenarnya, kebiasaan ini berawal di awal 1990-an, waktu pemerintah membuat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan mendukung MCK (mandi, cuci kakus).
Tadinya kan masyarakat beraktivitas bersama di sungai. Dari mandi, nyuci, sampai buang air besar (BAB). Sejak beralih ke MCK, kegiatan masyarakat ini hilang. Dan itu yang jadi keprihatinan kami.
Bisa dibilang, sungai yang menjadi tempat sampah ini melatarbelakangi berdirinya FKWA ya, Bu?
Iya. Tahun 2009 masyarakat resah dengan kondisi sungai karena itu ruang sosial kami. Kebetulan, pemerintah mencanangkan program sungai sebagai etalase kota. Lalu kami bergerak difasilitasi pemerintah, ketemu 11 kelurahan di kota. Ternyata masyarakat mau diajak melakukan suatu perubahan untuk menjaga sungai.
Berarti dari awal, Ibu menjabat sebagai Ketua FKWA ya?
Dari 2011. Waktu itu saya melihat, enggak bisa nanganin sungai hanya di kota. Soalnya, pas bersih-bersih sungai, ada kiriman sampah dari atas dan (masyarakat) saling menyalahkan. Makanya tahun 2012-2013 saya organisir ke daerah atas, sampai Kecamatan Turi, dan di bawah sampai Kecamatan Kretek. Itu dibantu Balai Besar untuk memfasilitasi pertemuan.
Di 2011-2015 itu saya koordinator kota (Yogyakarta). Baru sejak 2016 sampai sekarang, saya mengkoordinasi DIY, membawahi Sleman kota dan Bantul.
Baca Juga: Panen Air Hujan Sekolah Banyu Bening
Bagaimana cara Ibu mengelola komunitas supaya tetap konsisten?
Berat ya, FKWA ini semuanya relawan, bukan NGO (organisasi non-profit) yang punya pendanaan. Saya enggak nyari funding, meski punya badan hukum di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM). Kami juga enggak bisa memaksa semua (anggota) berdasarkan kesadaran.
Ada berapa relawan yang terlibat?
Yang aktif di DIY sekitar 10 orang. Masing-masing kabupaten ada koordinatornya. Kalau di kota, kami membagi ada 11 kelurahan, delapan titik pembatasnya dari jembatan. Jadi mereka mengkoordinasi berdasarkan RT/RW. Kalau di Sleman dan Bantul, basisnya pedukuhan. Tiap pedukuhan ada seorang ketua komunitas.
Banyak relawan perempuan juga?
Kalau pertemuan, paling perempuannya cuma dua orang—termasuk saya, sisanya laki-laki. Soalnya orang berpikir, aktivitas fisik (seperti bersih sungai) kegiatan laki-laki. Kadang-kadang ya banyak ibu-ibu yang ikut, tergantung yang organisir juga. Mereka kalau diajak ya mau.
Padahal ketika membicarakan air, pemakai terbanyaknya siapa? Perempuan. Kalau air terkontaminasi, siapa yang rentan (terkena) penyakit? Perempuan, yang akan terpengaruhi kesehatan reproduksinya.

Bentuk edukasinya seperti apa?
Misalnya lagi kerja bakti, kami sambil berinteraksi. Atau masuk ke forum mereka, kerja sama dengan berbagai pihak, mengadakan sosialisasi maupun menyusun perencanaan.
Cuma saya enggak mau hitung-hitungan, keterlibatan perempuan harus 30 persen. Enggak masalah kalau lebih banyak bapak-bapak yang berpartisipasi, asalkan bisa mewakili perempuan dalam bersuara dan memutuskan sesuatu. Ketika bapak-bapak enggak mengarah ke sana, saya akan intervensi. Sebagai bagian dari yang mengedukasi, bagaimana pun juga suara perempuan harus ada, di dalam pengambilan keputusan.
Tapi Ibu mau terlibat di kegiatan ini, di tengah citra aktivitas maskulin.
Enggak tahu ya, saya cinta. Saya suka dan tinggal di pinggir sungai, dan itu jadi bagian kehidupan saya. Mau enggak mau ya menjaga sungai, enggak rela kalau kotor. Kehidupan itu kayak terusik, makanya berusaha bareng masyarakat.
Ibu pernah diremehkan?
Enggak, masyarakat bisa menghormati itu. Mereka melihatnya dari segi kemampuan. Menurut saya, kalau kita menghormati diri sendiri, orang lain juga segan.
Sebelumnya ibu bilang, FKWA enggak punya pendanaan. Lalu dana untuk kegiatannya dari mana, Bu?
Kegiatan ini. Untuk mendukung kegiatan konservasi sungai dan penanaman pohon, kami mencoba biokonversi maggot dari pengolahan sampah organik, karena ada nilai jual yang lumayan.
Boleh diceritakan prosesnya?
Kami kasih ember ke setiap warga di sekitar sini, untuk memilah sampahnya sendiri. Kemudian kami ambil, dipilah di sini (kandang maggot), dan dijadikan bubur menggunakan mesin biar lebih mudah dimakan maggot.
Nanti maggot ini akan jadi pupa. Pas udah enggak bergerak, pupa dimasukkan ke kandang lalat. Kemudian, mereka akan jadi lalat. Setelah lalatnya bertelur, menetas, akan jadi bayi maggot. Nah, yang ukurannya besar itu dijual. Kalau sisa maggot bisa jadi pakan ternak atau unggas. Sedangkan sisa tinja untuk pupuk tanaman dan sayuran, yang bisa dikonsumsi. Jadi semuanya kembali ke manusia.
Kalau pertemuan, paling perempuannya cuma dua orang—termasuk saya, sisanya laki-laki. Soalnya orang berpikir, aktivitas fisik (seperti bersih sungai) kegiatan laki-laki. Kadang-kadang ya banyak ibu-ibu yang ikut, tergantung yang organisir juga. Mereka kalau diajak ya mau.
Baca Juga: Profil Sri Hartini, Penjaga Hutan Adat Wonosadi
Berarti enggak ada dukungan materiel ataupun moral, Bu, dari pemerintah?
Enggak ada (secara materiel). Dalam hal kegiatan ya beberapa didukung pemerintah, seperti bersih sungai. Soalnya kami berhubungan baik dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dan Provinsi. Pas FKWA baru mulai berkegiatan juga didukung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Tapi, begitu Bappeda melempar ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Yogyakarta, kami malah ditolak. Mereka enggak mengayomi. Padahal, membicarakan sungai, air, dan konservasi kan termasuk unsur lingkungan—ranahnya DLH. Jadi kadang-kadang, larinya ke Dinas PU (Pekerjaan Umum).
Kalau di Bantul, selain kurang (dukungan pemerintah) juga pergerakan komunitasnya lambat. Padahal anggaran sudah muncul. Jadi kami terus mendorong lewat advokasi, untuk memastikan pemerintah hadir dalam urusan sungai. Alhamdulillah kemarin ada dukungan dari DLH, Bappeda, dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD).
Sedangkan Sleman cukup bagus, karena ada Forum Komunikasi Sungai Sleman (FKSS) dan digandeng oleh DLH. Nah, yang susah di kota karena mereka lagi tertarik dengan forum sampah. Padahal, kami juga berurusan dengan sampah.

Dukungan apa yang paling dibutuhkan FKWA?
Kebijakan pengelolaan sampah. Selama ini kan masyarakat didorong untuk memilah sampah, tapi petugas kebersihan menjadikan satu karena di depo juga sampahnya disatukan. Jadi enggak ada gunanya.
Kalau mau tegas TPA Piyungan tutup, ya sudah desentralisasi. Kembalikan (pengelolaan sampah) ke masing-masing kelurahan. Di sini juga kelurahan harus punya kebijakan untuk pemilahan sampah. Fasilitasnya sudah ada kok, kenapa enggak dimanfaatkan? Kami juga sudah menyediakan diri (untuk mengelola sampah organik), bisa membantu satu kelurahan biar sampah organik dikelola di sini. Tapi enggak direspons.
Ya dukungan seperti itu yang dibutuhkan. Syukur-syukur dikasih fasilitas, karena yang kami gunakan saat ini dari upaya sendiri. Kami harus mencari dari swasta, CSR (corporate social responsibility), tapi pemerintahnya belum (terlibat).
Artikel ini merupakan bagian dari series liputan Krisis Air di Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung oleh International Media Support (IMS). Magdalene berkolaborasi dengan dua media, dari Filipina GMA News dan Timor Leste Neon Metin.