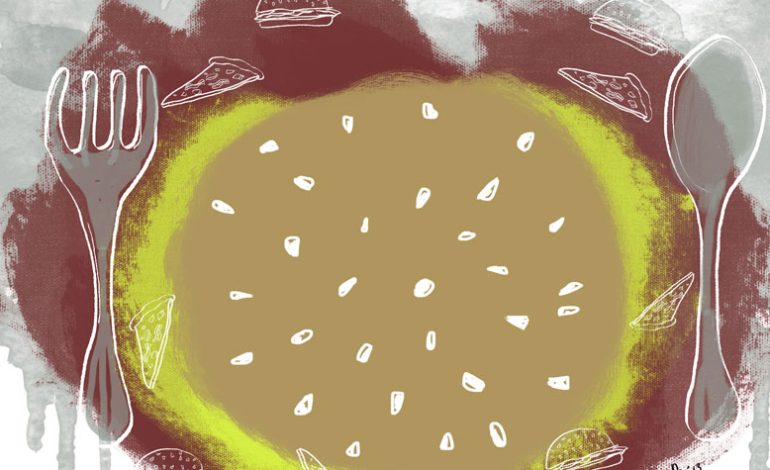Siklus Bahaya di STEM: Bias Gender Sampai Kosongnya Perlindungan Data Pribadi

“Ketika kita masih duduk di Sekolah Dasar (SD) misalnya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kita menemukan kalimat seperti ‘Ibu Budi memasak’, ‘Bapak Budi pergi bekerja’. Bayangkan saja bagaimana stereotip ruang publik dan ruang privat itu sudah ditanamkan sejak kita belajar bahasa,” ungkap Andi Misbahul Pratiwi, peneliti di Pusat Riset Gender Universitas Indonesia (UI).
Dalam panel bertajuk “Breaking the Bias for More Inclusive Technology”, Andi mempermasalahkan bias gender yang ia temukan dalam kurikulum pendidikan kita. Sebagai lulusan pendidikan teknik saat SMA dan lulusan jurusan teknologi, Andi tertarik meneliti mengapa anak-anak perempuan di Indonesia jarang tertarik bekerja di sektor teknologi.
“Anak perempuan telah dikondisikan untuk tidak memiliki imajinasi di luar sterotipnya,” lanjut Andi di perhelatan Pesta Perempuan, 26 Maret lalu.
Baca Juga: Keterasingan Perempuan dalam Transformasi Digital
Menurut Andi, stereotip ini jelas berbahaya. Sejak dini anak perempuan diajarkan untuk tidak terlibat atau menyukai hal-hal yang berbau teknis dan teknologi. Sehingga berdampak ketika mereka memilih jurusan pendidikan dan pekerjaan di masa depan.
Hal ini, yang menurut Andi sangat berpengaruh besar pada representasi perempuan di bidang Science, Technology, Engineering, and Math atau STEM masih sangat minim.
“Misalnya ketika aku melakukan penelitian di jurusan Teknik Metalurgi dan Material UI, di tahun 2000 itu hanya 12 perempuan yang mengisi bidang STEM dan ada kenaikan di tahun 2017 itu naik jadi 27 persen. Tapi ini itu kenaikannya butuh waktu lama ya. Tujuh belas tahun sampai akhirnya perempuan cukup percaya diri dan meyakinkan orangtua mereka dan lingkungan mereka bahwa saya sama cemerlangnya dan sama cerdasnya dengan anak-anak laki-laki,” jelasnya.
Temuan Andi selaras dengan laporan terbaru UNICEF pada 2020, perempuan hanya mengisi sekitar 40 persen dari angkatan kerja STEM di 68 negara.
Baca Juga: Sejarah ‘Computer Girls’ Sebelum Industri IT Berparas Lelaki
Teknologi dan Feminisme
Kurangnya representasi perempuan di dunia kerja STEM diperparah bias-bias dan diskriminasi gender yang masih menghantui perempuan. Tidak sedikit, mereka yang berhasil masuk ke sektor STEM memutuskan keluar karena diskriminasi yang dirasakan.
Representasi minim ini akhirnya berdampak besar pada produk teknologi yang diciptakan. “Peminggiran perempuan dalam teknologi ini tidak terlepas dari bagaimana teknologi digital menjadi ruang perpanjangan budaya patriarki. Perilaku-perilaku yang misoginis seksis bahkan menjadi ekstensi dari kekerasan yang terjadi di ruang fisik,” kata Dhyta Caturani, pendiri Purple Code, sebuah lembaga swadaya yang berfokus pada interseksionalitas feminisme, ham, dan teknologi.
Itu sebabnya, menurut Dhyta, teknologi sebetulnya tidak bisa terlepas dari isu feminisme. Menurutnya, kita butuh mengklaim kembali ruang-ruang yang seharusnya demokratis, terbuka, dan setara untuk membuka jalan perempuan lebih terlibat lagi di isu-isu teknologi.
Sebagian perusahaan-perusahaan teknologi mulai menyadari pentingnya interseksionalitas ini. Puri Kencana Putri, Public Policy Associate Twitter Indonesia menjelaskan Twitter, tempatnya bekerja, jadi salah satu platform teknologi yang mengedepankan agenda non-diskriminasi, termasuk pada perempuan dan minoritas gender.
Komitmen untuk memperkaya dan meningkatkan representasi perempuan di bidang STEM itu dibuka Twitter lewat program business resources group demi menciptakan ruang aman.
“Jadi khusus untuk teman-teman LGBTQ, ada Twitter Open di mana para staf dan karyawan para pengambil kebijakan terdiri dari individu-individu yang memiliki ekspresi gender beragam. Sedangkan untuk teman-teman perempuan itu juga ada yang namanya Twitter Women. Ini adalah bentuk Twitter untuk mendorong gender empowerment di dalam perusahaan kami. Jadi kami berharap kebijakan itu juga selaras tidak di luar tapi juga bisa diimplementasikan di dalam,” jelasnya.
Dengan memberikan kesempatan karier dengan menawarkan ruang aman bagi perempuan dan teman-teman LGBTQ, maka produk teknologi yang dikembangkan pun secara otomatis lebih sensitif gender. Salah satu bentuk keseriusan itu ditunjukkan Twitter dengan mengembangkan fitur-fitur yang berorientasi membangun ruang aman.
Misalnya, lewat fitur cari layanan, pengguna Twitter dapat mengetik kata kunci seperti KDRT, kekerasan perempuan, kekerasan istri, atau kekerasan anak untuk mencari -rujukan informasi Lembaga Layanan yang dapat membantu.
“Selama pandemi ini kami bekerjasama aktif dengan teman-teman Komnas Perempuan, teman-teman LBH Apik sehingga pengguna di Twitter yang ingin mendapatkan perlindungan, pendampingan, atau melakukan konsultasi terkait kekerasan berbasis gender terakomodir dengan baik. Kami berusaha fitur-fitur yang bisa digunakan oleh para pengguna itu juga punya kebermanfaatan dan dampak sosialnya jadi tidak cuma sekedar gaining profit tapi bagaimana produk yang kami kembangkan mampu menciptakan ruang aman dan lebih inklusif untuk semua,” ungkapnya.
Baca Juga: Masalah Besar di STEM: Representasi Perempuan dan Produk yang Bias
Perlindungan Data Pribadi
Teknologi yang masih bias juga mendorong percakapan tentang menciptakan ruang aman. Sektor yang masih didominasi pembuat keputusan laki-laki cisheteroseksual ini ternyata bisa berdampak buruk bukan cuma buat perempuan, tapi gender direpresi lainnya. Rebecca Nyuei, staf Monev dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial yang juga seorang transpuan memberikan contoh penggunaan Automated Gender Recognition atau AGR berdasarkan facial recognition yang bisa jadi senjata untuk mendiskriminasi kelompok LGBT di negara-negara yang mengopresi mereka.
AGR yang menggunakan facial recognition mampu menyimpulkan jenis kelamin dan orientasi seksual seseorang dari data yang dikumpulkannya. Teknologi ini menggunakan informasi seperti nama resmi, bentuk rahang, atau tulang pipi, untuk mengidentifikasi identitas gender seseorang.
“Bisa dibayangkan bagaimana teknologi semacam ini bisa mengidentifikasi identitas gender seorang individu. Jelas ini membahayakan komunitas LGBTQ. Aku bisa tiba-tiba diidentifikasi sebagai transpuan misalnya hanya karena bentuk rahang aku saja. Karenanya ini juga berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi seseorang,” jelasnya.
Penggunaan teknologi ini tanpa regulasi yang melindungi warga bisa jadi malapetaka. Kelompok LGBTQ misalnya, bisa mendapatkan diskriminasi bertumpuk atau bahkan ditangkapi jika teknologi ini diadaptasi aparatur negara queerfobik.
Ketiadaan regulasi perlindungan data pribadi juga menjadi kekhawatiran Dhyta. Menurutnya, data telah jadi minyak yang baru (the new oil), alias komoditas yang diperebutkan dan mahal harganya. Kehadiran korporasi dan industri dalam teknologi yang masih sangat maskulin memiliki kontrol semakin besar pada data pribadi ini.
Mereka memonetisasi data-data kita dalam jumlah besar. Negara, kata Dhyta, di era ini berubah menjadi entitas yang memiliki sumber data pribadi paling banyak karena punya data kependudukan. Sementara itu, Indonesia belum memiliki Undang-undang Perlindungan Data Diri yang sudah didorong koalisi masyarakat beberapa tahun terakhir. Regulasi ini dinilai penting untuk menjaga keamanan identitas warga dan pengguna internet.
“Ini dibutuhkan untuk melindungi kita semua, agar data tidak dipergunakan oleh korporasi, negara atau individu lain atau punya niat atau kepentingan yang berbeda baik dengan sengaja atau tidak sengaja,” tambah Dhyta.