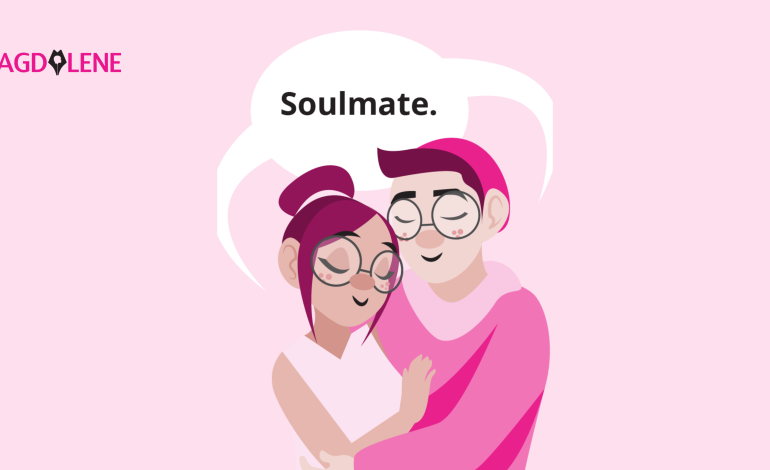Imbalan Bidadari Surga bagi Lelaki: Tafsir Agama yang Bias dan Problematik

Apakah kamu pernah mendengar ceramah tentang imbalan orang beriman di surga kelak? Saya yang notabene belajar di sekolah Islam, dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sangat familier dengan ceramah tersebut. Biasanya, ceramah ini menyitir hadis dari riwayat al-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad.
“Orang yang mati syahid mendapatkan tujuh keistimewaan dari Allah, diampuni sejak awal kematiannya, melihat tempatnya di surga, dijauhkan dari azab kubur, aman dari huru-hara akbar, diletakkan mahkota megah di atas kepalanya yang terbuat dari batu yakut terbaik di dunia, dikawinkan dengan tujuh puluh dua bidadari, serta diberi syafaat sebanyak 70 orang dari kerabatnya,” sabda Rasulullah, dilansir dari Islami.co.
Hanya saja, ditinjau dari analisis sanad, hadis ini termasuk kategori hasan, hadis yang hafalan salah satu perawinya tidak sekuat hadis shahih. Posisinya persis terletak antara shahih dan dhaif (lemah).
Masalahnya yang juga kemudian timbul dari hadis ini, jika lelaki dapat bidadari surga, apa hadiah untuk perempuan? Jarang sekali saya mendengar ceramah keagamaan membicarakan imbalan Tuhan untuk perempuan di surga. Mayoritas isi ceramah selalu dikaitkan dengan laki-laki heteroseksual saja. Dalam hal ini, bidadari menurut Nerina Rustomji, Associate Professor Sejarah dari Universitas St. John dipandang sebagai sosok pendamping seksual bagi laki-laki Muslim di surga.
Sedihnya lagi, iming-iming imbalan bidadari surga ini juga dijadikan alat justifikasi atas tindakan terorisme atas nama jihad, dan memperjuangkan Islam. Dalam surat Mohamed Atta, tersangka dari aksi terorisme 9/11 yang ia tulis dalam Bahasa Arab misalnya, secara jelas memperlihatkan bagaimana imbalan bidadari di surga menjadi salah satu motivasi jihadnya.
Dilansir dari The Guardian, bunyi salah satu penggalan paragraf Mohamed Atta tuliskan adalah sebagai berikut:
“Jangan tampak bingung atau menunjukkan tanda-tanda ketegangan saraf. Berbahagialah, optimis, tenang karena sedang menuju amalan yang dicintai dan diterima Allah. Ini akan menjadi hari di mana insya Allah kamu bisa habiskan dengan para bidadari surga.”
Baca Juga: Menegakkan Kesetaraan Gender lewat Pemahaman Islam Secara Kontekstual
Asal Mula Interpretasi Agama Soal Bidadari Surga
Pertanyaannya, dari mana sebenarnya interpretasi mengenai imbalan bidadari surga ini muncul? Apakah benar Alquran dan hadis menyebutnya secara gamblang?
Dalam hal ini, Prof. Lailatul Fitriyah, Asisten Profesor Pendidikan Antaragama dari Claremont School of Theology yang saat ini menjadi Kandidat PhD. di World Religions and World Church Program di Departemen Teologi di University of Notre Dame memberikan perspektifnya kepada Magdalene.
Sebelum membahas tentang bidadari dalam interpretasi imbalan surga bagi laki-laki, Laily menekankan pentingnya terlebih dahulu memahami dasar pemaknaan kata bidadari surga ini. Kata bidadari yang banyak disebut dalam ceramah-ceramah agama sebenarnya berasal dari kata “houri”.
“Akar kepercayaan dari konsep “houri” dapat dirujuk kepada beberapa ayat Alquran yang menyebutkan tentang kehadirannya di surga. Houri dalam hal ini misalnya dirujuk dalam Alquran Surat Al-Waqiah ayat 22-23, Ar-Rahman ayat 72, Ad-Dukhan ayat 54, At-Tur ayat 20, dan banyak ayat lainnya.”
“Beberapa ayat tidak menggunakan kata ‘houri’, tapi oleh para penerjemah Alquran diasosiasikan dengan konsep ‘houri”, seperti ayat 78:33 yang menyebutkan soal perempuan dengan payudara yang sempurna,” jelasnya.
Walaupun demikian, menurut Laily, Alquran tidak pernah secara jelas menyebutkan bentuk, karakteristik, dan konteks sosial-politik dari “houri” itu sendiri. Alquran hanya menyebutkan “houri” adalah makhluk surgawi feminin, teman bagi laki-laki beriman yang masuk surga.
“Dalam penggambarannya, ‘houri’ memiliki mata lebar yang indah. Alquran juga menyebutkan, mereka tidak pernah tersentuh oleh manusia maupun jin. Kemurnian dalam hal ini dalam beberapa penafsir kemudian disamakan dengan ’keperawanan’ perempuan,” tukas Laily.
Hal yang kemudian menurut Laily perlu dicermati adalah bagaimana bahasan tentang ‘houri’ seharusnya dilihat dari kacamata yang lebih kompleks. Konsep “houri” dalam Islam tidak boleh dikeluarkan dari konteks orientalisme dan imperialisme dalam obsesi global. Merujuk pada buku The Beauty of the Houri: Heavenly Virgins, Feminine Ideals (2021) karya Nerina Rustomji, bisa dilihat bagaimana perkembangan konsep “houri” menjadi lebih pada wujud duniawi yang mengacu pada perempuan “perawan”, tidak terlepas dari pemaknaan orang-orang Barat.
Rustomji menjelaskan bagaimana istilah “houri” masuk ke Bahasa Prancis pada abad ke-17 dan Bahasa Inggris pada abad ke-18, dengan teks-teks abad pertengahan yang menyajikan visi sebuah surga Islam di mana laki-laki dapat menikmati seks. Pada abad ke-13, Marco Polo mengulangi kisah Assassins dan surga palsu mereka dari perempuan cantik. Pada abad ke-14, Perjalanan Sir John Mandeville membandingkan kerajaan ideal Prester John dengan surga Islam yang dilengkapi dengan “perawan” abadi.
Mulai abad ke-15, perawan-perawan ini diberi nama horhin dan hora dalam polemik anti-Islam Confusión o confutación de la secta Mahomética. Pada abad ke-17, pelancong Perancis, du Loir memperkenalkan kata “houri” dalam diskusinya tentang perlakuan laki-laki Turki terhadap perempuan.
Pengenalan kata tersebut dikaitkan dengan polemik anti-Islam, perjalanan Prancis dan Inggris, serta kepedulian terhadap kesejahteraan kaum Muslim, khususnya perempuan Turki. Begitu istilah “houri” diperkenalkan ke masyarakat pembaca Prancis dan Inggris, istilah itu digunakan untuk menggambarkan perempuan cantik di Kekaisaran Ottoman.
Lalu bagaimana di Indonesia sendiri? Mengapa imaji soal “houri” ini kurang lebih sama? Laily mengungkapkan Imaji soal “houri” sebagai bidadari surga berakar pada konteks masyarakat Indonesia dengan cerita rakyat soal bidadari. Dalam cerita rakyat Indonesia, bidadari banyak digambarkan sebagai perempuan jelita, suci (baca: perawan), dan memikat secara seksual.
“Tiap masyarakat Muslim mungkin memiliki imajinya masing-masing soal “houri” yang sesuai dengan folklore lokal mereka. Itu tidak masalah. Yang masalah adalah ketika imaji tersebut digunakan sebagai proksi untuk menjustifikasi sexual abuse dan patriarki di dunia nyata saat ini.”
Baca Juga: Dicari: Khatib Nikah yang Tidak ‘Cringey’
Memaknai Ulang “Houri” dan Imbalan Muslimah di Surga
“Saya tidak setuju dengan penerjemahan ‘houri’ sebagai bidadari surga. Perempuan tentu saja mendapatkan imbalannya di surga. Saya sendiri yakin bahwa surga tidaklah berbentuk heteroseksual di mana laki-laki mendapat bidadari, dan perempuan mendapatkan laki-laki yang tampan,” ungkap Laily kepada Magdalene.
Jika dilihat dari penjelasan di atas, konsep “houri” tidak pernah lepas dari gambaran perempuan cantik jelita. Pemaknaan ini juga sebenarnya juga mengurangi kemampuan laki-laki untuk memilih, bertindak, atau menjalankan kehendak bebas. Bahwa mereka nyatanya adalah makhluk yang diberikan akal oleh Allah SWT.
Dengan pemaknaan demikian pula,maka seakan-akan perempuan Muslimah yang beriman dikecualikan dalam pandangan Tuhan. Bahwa mereka tidak mendapatkan imbalan apa-apa selain posisinya di surga. Oleh sebab itu, dalam memaknai konsep “houri”, selayaknya juga dilakukan dengan kehati-hatian. Ia tidak bisa dimaknai dalam dimensi tunggal, yang mana tidak berdasarkan pandangan atau pengalaman dari satu kelompok saja.
Dalam hal ini, terdapat dua pemahaman mengenai “houri” yang bisa kita telusuri bersama.
Pertama, jika sebelumnya “houri” selalu dikaitkan kepada makhluk feminin, khususnya perempuan, maka ada beberapa ada penafsir Muslim yang mengungkapkan adanya kemungkinan bidadari laki-laki. Penafsiran sebagian bergantung pada pengidentifikasian jenis kelamin kata benda hur. Beberapa orang berpendapat, istilah tersebut dapat digunakan untuk laki-laki dan perempuan.
Dalam buku yang sama, Rustomji misalnya mencontohkan penafsiran dari Zakir Naik, pendiri Islamic Research Foundation. Ia menyinggung ayat-ayat Alquran tertentu dan menunjukkan, kata “houri” dipahami dengan benar sebagai jamak dari “mata putih besar yang indah,” yang ditafsirkan sebagai pasangan atau pendamping. Bagi Naik, kata itu tidak memiliki jenis kelamin.
Dia menyimpulkan, “Untuk laki-laki itu, ia akan mendapatkan perempuan yang baik dengan mata besar yang indah dan untuk seorang perempuan, ia juga akan mendapatkan laki-laki yang baik dengan mata besar yang indah.”
Baca Juga: Surat Terbuka untuk Ustaz Gaul Pujaan Ukhti dan Akhi
Selain Naik, Yasir Qadhi dari Institut al-Maghrib yang berbasis di AS juga mengungkapkan Muslimah beriman di surga nantinya juga akan mendapatkan imbalan berupa pendamping yang diciptakan khusus oleh Allah SWT.
Qadhi menyimpulkan, “Tujuan kita adalah mencapai al-janna. Begitu kita berada di sana, kita akan diberikan semua yang ada di dalamnya juga. Jangan khawatir, begitu kamu mencapai al-janna, kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan.”
Jika ada beberapa penafsir Muslim menekankan bagaimana “houri” dapat mengacu pada perempuan dan laki-laki karena bersifat jamak, maka pemahaman ulang kedua mengenai “houri” lebih bersifat metafor. Dalam hal ini Laily mengungkapkan bagaimana perempuan tentu saja mendapatkan imbalannya di surga. Ia sendiri yakin, surga tidaklah berbentuk heteroseksual di mana laki-laki mendapat bidadari, dan perempuan mendapatkan laki-laki yang tampan.
“Saya setuju dengan pendapat Nerina Rustomji, daripada menerjemahkan ‘houri’ sebagai bidadari, kita lebih baik memahami ‘houri’ sebagai simbolisme kenikmatan dan keindahan yang ada di surga,” ungkapnya.
Rustomji dalam bukunya memang mengungkapkan penggambaran “houri” yang misoginis ini salah satu diakibatkan karena ketidakmampuan manusia untuk memaknai hal di atas. Kenikmatan dan keindahan yang dipahami manusia atau penafsir laki-laki terpaku pada kenikmatan duniawi yang selalu berhubungan dengan seksualitas perempuan. Padahal apa yang dijanjikan oleh Allah mengenai pendamping atau “houri” tidak pernah secara terang dijelaskan dengan karakteristik duniawinya.
Rustomji dalam bukunya juga mengutip penjelasan Amina Wadud yang berusaha mengembangkan hermeneutika feminis Alquran dengan mengembangkan argumen yang lebih filosofis mengenai “houri”. Dalam hal ini, setelah mencatat ayat-ayat tentang “houri”, ia menemukan ayat-ayat ini semua berasal dari periode awal Mekah, sedangkan ayat-ayat dari periode selanjutnya, periode Madinah menggunakan istilah zawj atau pendamping.
Wadud kemudian memaknai pendamping ini pada makna “companionship” yang lebih besar, yaitu “cosmic companionship”. Dalam kerangkanya, Cosmic companionship adalah esensi dari pasangan manusia yang merupakan langkah penting bagi penyempurnaan jiwa. Bagi Wadud tujuan akhir lebih tinggi daripada mereplikasi dan memperkuat kemungkinan kepuasan di bumi. Sehingga, pendamping di sini tidak bisa disamakan dalam kerangka pendamping seksual yang heteroseksual.
Pada akhirnya, layaknya memahami ayat Alquran dan hadis lainnya pemaknaan “houri” nyatanya tidak bisa dilihat dalam satu dimensi tunggal saja. Konsep yang begitu misoginis ini lahir lewat kompleksitas sejarahnya dan butuh ketelitian dengan nafas kesetaraan gender untuk memaknainya. Hal ini dilakukan agar agama tidak hanya dipahami sebagai produk yang melanggengkan diskriminasi dan ketidakadilan gender, namun sebagai agama yang memberikan kedamaian dan rahmat bagi setiap manusia.
Ilustrasi oleh Karina Tungari