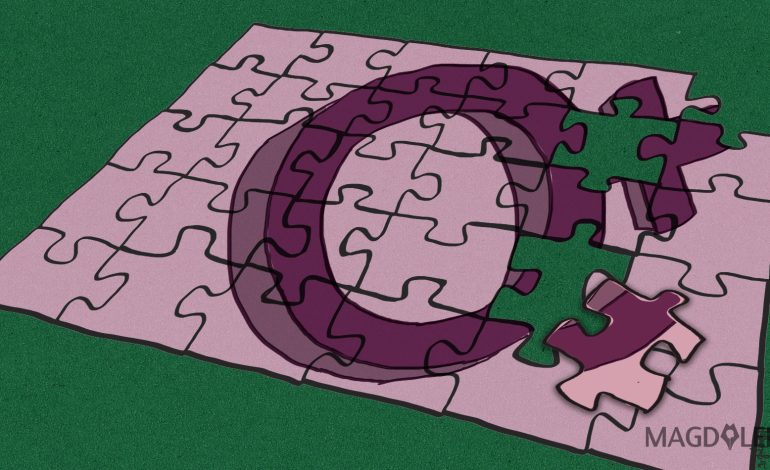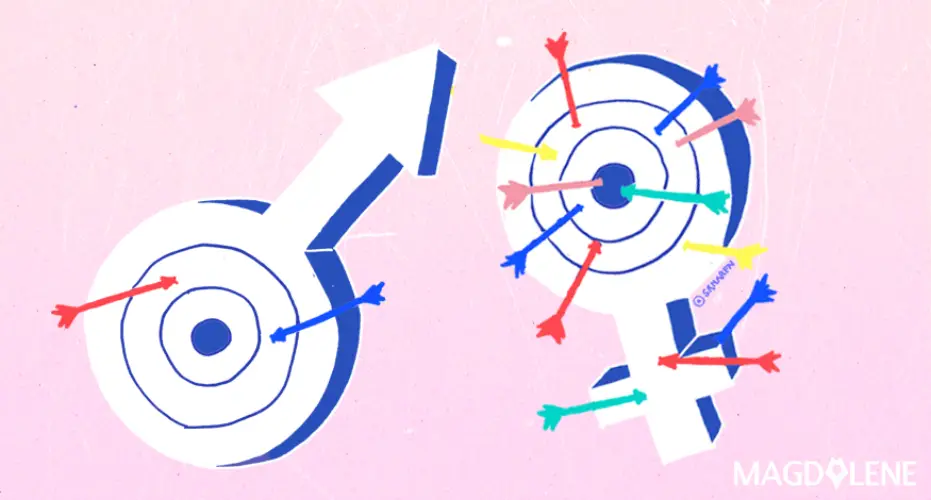Mengenal amina wadud, Bintang Rock Feminisme Islam

amina wadud membagikan kertas-kertas berisi ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Islam dan feminisme pada suatu kelas di Jakarta tahun lalu. Acara ini digelar pada bulan Ramadan oleh Rumah KitaB, lembaga riset swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok marginal yang menghadapi diskriminasi karena sudut pandang sosio-religius.
Ada 35 peserta dari latar belakang profesi yang berbeda-beda, termasuk tokoh-tokoh publik seperti aktivis perempuan Nursyahbani Katjasungkana, dan juga cendekiawan Muslim Ulil Abshar Abdalla dan Nur Rofiah. Namun kami semua memiliki ketertarikan yang sama terhadap Islam dan gender, dan kami semua terpana dengan sosok “Lady Imam” di hadapan kami.
Saya pertama kali mendengar tentang filsuf muslim Amerika berumur 68 tahun ini pada tahun 2005, ketika ia menimbulkan kontroversi dengan memimpin salat Jumat untuk sebuah jemaah di AS, padahal peraturan umum menyatakan hanya laki-laki yang boleh menjadi imam dalam jemaah campuran. Sebagai seseorang yang mempertanyakan dan pernah ditanya tentang ,aturan tersebut oleh non-muslim, saya langsung menjadi penggemar dan pengikutnya sejak itu.
Menerima PhD dalam Kajian Bahasa Arab dan Islam dari University of Michigan, AS, pada tahun 1988, wadud (yang lebih suka namanya dieja dalam huruf kecil karena huruf Arab tidak mengenal huruf kapital), telah lama fokus pada hubungan gender dan Islam. Ia menulis buku Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective, yang telah menjadi karya berpengaruh tentang topik tersebut. wadud telah menjadi bagian dari beberapa lembaga masyarakat sipil dan gerakan-gerakan yang mendorong prinsip-prinsip kesetaraan bagi perempuan berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti Sisters in Islam dan Musawah.
Sebagai cendekiawan Islam, ia memiliki fokus progresif pada penafsiran Quran. Itulah yang ia ajarkan kepada kami tahun lalu di kelas di Jakarta: Untuk membaca kitab suci tersebut menggunakan metode-metode kontekstual.
wadud mengatakan bahwa kita perlu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam memandang ketidakkonsistenan gender dalam Quran: Apakah itu cerminan dari konteks sejarah? Apakah itu kekurangan dari bahasa Arab? Apakah itu cerminan dari patriarki? Atau permasalahan niat Ilahi? Bagaimana kita tahu?
Kami dibagi menjadi kelompok berisi dua sampai tiga orang, dan setiap kelompok membaca ayat-ayat yang berbeda. Kelompok saya mendapatkan Surat Al-Ankabut 28-35, mengenai kaum Nabi Luth dan kekejian mereka, contoh yang digunakan banyak muslim untuk menolak homoseksualitas.
“Cek ayatnya. Siapa yang berbicara? Apakah Tuhan? Apakah Nabi? Tentang apa atau siapa pernyataan ini dibuat? Apakah pesannya jelas? Jika ada perempuan, apakah dia berbicara?” kata wadud.
Ketika kami membedah ayat-ayatnya kata per kata untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, semakin terlihat bahwa ayat-ayat tersebut tidak sepenuhnya jelas dalam membahas homoseksualitas. Ada disebut “ketidakpatutan” dan “orang-orang korup,” serta “orang-orang yang bersalah” dan “kecabulan”. Naratornya berganti-ganti antara Tuhan dan Nabi Ibrahim yang bercerita tentang kisah Nabi Luth, serta narator-narator lain yang kurang jelas siapa. Ada beberapa bagian yang menyebut istri Nabi Luth, seperti, “Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang yang tetap tertinggal.” Namun tidak dijelaskan perbuatan keji apa yang ia lakukan dan, apakah ia berbicara untuk diri sendiri? Tidak sekali pun.
Latihan ini luar biasa mengesankan.
“Bandingkan setiap ayat dengan ayat-ayat lainnya. Jika kita menemukan kutipan atau ide yang bertentangan satu sama lain, pilih yang selaras dengan kesetaraan dan keadilan. Jika orang lain membaca dalam (sudut pandang) patriarki, kamu dapat membaca dengan (sudut pandang) kesetaraan dan keadilan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan kontradiksi adalah dengan berpikir,” kata wadud.
Baca juga: Apakah Feminisme Bisa Selaras dengan Ajaran Islam?
“Tidak perlu takut pada orang-orang. Kamu tidak perlu menjadi akademisi untuk menafsirkan teksnya, kamu berhak melakukannya.”
Selagi membahas batas-batas biner yang menghegemoni dalam konteks Islam, wadud juga mengutip Playing in the Dark: Whiteness and the Literary Imagination (1992), karya kritik sastra Toni Morrison, yang membuat kelasnya lebih menyenangkan.
Di antara kelas-kelasnya, saya mendapatkan kesempatan untuk duduk dan berbincang dengan amina wadud. Berikut rangkuman obrolan saya dengan wadud.
Magdalene: Jadi sekarang Anda pindah ke Indonesia. Boleh tahu kenapa?
amina wadud: Saya menyukai wilayah ini; saya senang iklimnya. Saya mengidap arthritis (radang sendi), jadi saya lebih cocok tinggal di sini. Saya sangat senang di sini. Anak-anak saya, yang bungsu ulang tahun ke-30 hari ini. Mereka punya kehidupan sendiri dan menjalani hidup mereka masing-masing, dan saya selalu bisa mengunjungi mereka karena lebih murah untuk tinggal di sini dan mengunjungi mereka di sana. Jadi, saya berharap dapat menemukan tempat, mungkin beli atau pindah ke sana.
Sebagai anak dari pendeta Metodis, bagaimana Anda mulai tertarik pada Islam?
Sepertinya karena tumbuh di rumah tangga yang berpusat pada Tuhan, sejak awal saya melihat dengan jelas bahwa ada lebih dari satu cara. Dan pada saat itu, saya hanya tertarik mencari tahu tentang berbagai cabang agama Kristen untuk melihat apa yang sama, apa yang berbeda. Waktu di SMA, saya tinggal bersama beberapa keluarga, ada yang Yahudi, Unitarian Universalist… jadi ada ide yang muncul bahwa agama bukan hanya satu.
Ketika saya kuliah, saya sudah sangat tertarik dengan tradisi spiritualis Timur dan saya menjadi Buddhis dan tinggal di Ashram selama setahun, serta melakukan meditasi dan praktik tekstual. Tahun berikutnya, ketika saya berumur 18 atau 19, saya mulai membaca tentang Islam.
Ada gerakan sangat kuat di Amerika Serikat saat itu, jadi siapa pun yang menyuarakan ketertarikan apa pun tentang Islam, mereka akan didorong untuk pindah agama. Jadi saya sebenarnya pergi ke masjid untuk mendapatkan informasi dan mereka bilang, “Oh, kamu baca syahadat (pengakuan iman muslim) saja.” Lima bulan kemudian, saya diberi Quran, yang saya pikir seharusnya itu dilakukan terlebih dahulu. Meski begitu, saya sudah berkomitmen pada suatu tingkatan praktik, pada semacam komunitas. Dan suatu ketika, saat saya membaca Quran, saya benar-benar jatuh hati dan pada saat itulah timbul perubahan yang mendalam.
Apakah Anda menghadapi penolakan dari keluarga?
Tidak, karena saya memang selalu jadi yang beda sendiri. Cuma saya yang berpendidikan universitas. Saya vegetarian saat itu. Keluarga saya bilang, “Ok, apa lagi yang akan dia bawa pulang hari ini?” (tertawa). Dan saat itu saya sudah berkuliah, tidak lagi tinggal di rumah, jadi tidak ada masalah besar. Ayah saya juga sudah punya penyakit, dan kesehatannya memburuk selama dua tahun pertama saya menjadi muslim hingga ia meninggal dunia. Jadi tidak pernah ada kesempatan untuk melakukan diskusi teologis.
Sepertinya ayah saya juga tidak mengetahui tentang versi lain Islam selain gerakan Black Muslim di Amerika Serikat. Pada saat itu, gerakan ini non-esoterik. Mereka tidak percaya pada surga dan neraka; mereka tidak percaya dengan Yesus kulit putih. Dan saya yakin itu terlihat seperti masalah walaupun itu bukan pintu masuk untuk saya. Saya tidak masuk lewat pintu itu, tapi banyak muslim yang melaluinya.
Mereka juga punya gerakan internal yang kemudian menjadi kelompok muslim Sunni yang religius. Tapi pada awalnya, itu gerakan yang berbeda dan saya tidak terlibat di dalamnya. Tetapi sepertinya ayah saya mungkin berpikir (Islam) seperti itu. Walau demikian, seperti yang saya katakan, saya tinggal jauh dari rumah, jadi jika saya bertemu dengan Ayah dan menjenguknya di rumah sakit sampai ia meninggal, kami tidak pernah memiliki waktu untuk membicarakan, “Apa sebenarnya yang kamu lakukan—apakah aku setuju, apakah aku tidak setuju.”
Menjadi seorang muslim di AS saat itu pasti sangat berbeda dari Amerika Serikat pada era Trump sekarang.
Saya yakin demikian karena itu lebih dari 40 tahun yang lalu. Saya telah menjadi Muslim selama 46 tahun. Pada saat itu, sebenarnya ada gerakan sangat kuat di komunitas Afrika-Amerika terhadap Islam. Dari tahun 1930-1970-an, ada gerakan pindah agama yang sangat kuat di komunitas Afrika-Amerika. Dan karena kuliah S1 saya di University of Pennsylvania, saya berada tepat di jantung Philadelphia. Dan bahkan sampai sekarang pun, dari semua kota yang mungkin kamu kunjungi di Amerika Serikat, jika kamu ke kota Philadelphia, Islam sangat terlihat. Keberadaan Islam sangat kuat dan kebanyakan dipeluk oleh orang Afrika-Amerika walaupun ada muslim dari mana saja. Jadi saat itu bukanlah hal yang aneh, walau sebenarnya masih sangat langka.
Tetapi Islamofobia tidak separah hari ini, kan?
Tidak, ada kekurangan pengetahuan dan orang-orang hanya berpikir sampai situ. Dengan Islamofobia, ada semacam pengelompokan/generalisasi golongan. Dulu, para muslim tahu “tipe” apa saat itu dan kelompok muslim sudah tahu kami masuk “tipe” mana. Jadi, kami tidak menghadapi kebencian dan mengalami diskriminasi yang menggeneralisasikan semua orang seintens sekarang.
Bagaimana Anda mulai fokus pada feminisme dalam Islam?
Saya tidak pernah belajar feminisme dalam Islam. Sebenarnya, saya memisahkan diri dari feminisme selama 35 tahun menjadi seorang muslim. Saya mempelajari Quran karena saya tertarik pada Quran, dan ketika saya mempelajari Quran waktu kuliah S1, saya kebanyakan belajar sendiri karena belum tersedia tingkat lanjutan.
Saya belajar bahasa Arab di awal tahun 70-an, kemudian saya tinggal di Libya dan kefasihan bahasa Arab saya meningkat. Saya bekerja, mengajar dan jadi tutor di sekolah-sekolah swasta Islam, lalu saya kuliah S2, mengambil Kajian Islam dan Bahasa Arab. Dan pada saat itu, saya yakin bahwa saya benar-benar ingin memahami peran perempuan seperti yang dijelaskan dalam Quran.

Peserta kelas Islam dan Feminisme bersama amina wadud. (Foto: Rumah KitaB)
Saya sudah tinggal di luar negeri; saya pernah tinggal di negara tempat muslim menjadi mayoritas. Saya sudah mengamati komunitas-komunitas di AS yang eklektis, juga muslim dari seluruh dunia, serta muslim lokal yang biasa disebut muslim asli.
Saya paham ada ketidaksesuaian antara ide-ide mengenai hak apa yang dimiliki lelaki muslim dan hak apa yang dimiliki perempuan Muslim. Saat itu saya sangat penasaran tentang dari mana perbedaan-perbedaan ini muncul. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, apakah ini kehendak Allah? Dan jika memang kehendak Allah, dari mana sumber informasi terbaik yang dapat saya akses? Jawabannya, Al-Quran.
Baca juga: Saat Semua Orang Merasa Jadi Tuhan: Wawancara dengan Musdah Mulia
Proses pembelajaran saya berjalan lancar karena saya sudah jatuh hati dengan Quran, saya yakin bahwa saya ingin mencari tahu tentangnya (isu perempuan dalam Islam)… Walaupun pada awalnya saya tidak menyebutnya gender. Buku pertama saya berjudul Quran and Women, padahal seharusnya disebut Quran and Gender. Namun, saya tidak mengambil studi feminis yang baru saja berkembang saat itu. Saya mengambil beberapa mata kuliah pada Kajian Perempuan, tetapi semua kuliah yang saya ambil mengatakan bahwa Islam adalah jalan terbaik. Semua riset tersebut mengatakan mengapa Islam adalah jalan terbaik, dan mereka selalu memberi saya nilai A, tetapi tidak terlalu kritis.
Sepertinya setelah saya menyelesaikan S2, PhD, dan menulis disertasi saya, yang kemudian menjadi buku Quran and Women… mulai saat itulah terlihat jelas bagi saya bahwa jika kamu benar-benar mendemonstrasikan ketidaksesuaian antara ritual budaya tertentu sepanjang sejarah Islam dan muslim, dari jejak Quran berdasarkan pengetahuan Quran, itu sangat mengusik zona nyaman dan otoritas yang diberikan kepada lelaki, sehingga mereka resisten.
Jadi, saya sudah menjadi kontroversial walaupun kepribadian saya tidak seperti itu. Saya sebenarnya dulu sangat konservatif. Bahkan Quran and Women sebagai buku juga konservatif, tetapi dalam konteks akademis, sangat teliti. Dan sayangnya, dalam proyeksi patriarkal Islam, buku ini tidak mendukung proyeksi tersebut. Jadi buku itu sendiri sudah mulai menimbulkan masalah. Padahal saya tidak tertarik memicu masalah; saya hanya tertarik dengan kebenaran.
Setelah saya menyelesaikan disertasi dan mendapatkan PhD, saya pergi ke Malaysia dan bergabung dengan International Islamic University untuk mengajar tentang Quran dan Kajian Quran kepada mahasiswa-mahasiswa S1. Saya mulai menjalin hubungan dengan para perempuan di komunitas-komunitas dan pada permulaan Sisters in Islam. Dan itu sangat mengubah pikiran saya, dari hanya berkutat dengan teori dan teologi menjadi tataran aktivisme dan realitas. Ketika pemikiran tersebut sejalan dengan jejak ajaran Quran yang saya pahami, tantangan bagi orang-orang di arus utama adalah ketika landasan perlawanan terhadap perlakuan yang timpang terhadap perempuan dan laki-laki bukanlah feminisme liberal sekuler, melainkan berbasis Quran. Itu bahkan lebih kuat.
Alhasil, saya mulai mengalami relevansi dalam karya saya. Sebab sebelumnya, semuanya terasa utopis, seakan-akan Islam adalah agama terbaik di dunia, hanya melakukan hal-hal yang indah, dan Quran mengatakan berbagai hal yang baik, tetapi dalam kenyataannya berbeda. Ketika kamu memulai perbincangan antara dua kosmologi ini, menurut hemat saya, Quran adalah yang utama, namun mengapa kita tidak hidup seperti ajaran di dalamnya? Dan mencari tahu bukan hanya mengapa kita tidak hidup seperti itu, tetapi bagaimana caranya hidup seperti itu. Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengikutinya, agar mengikuti jalur yang benar-benar revolusioner?
Saya meninggalkan Malaysia pada 1992 dan Sisters in Islam berdiri pada 1987, tetapi saya baru bergabung pada tahun 1989. Dan Musawah diluncurkan pada 2009 dan pada saat itu, saya sudah mengidentifikasi diri sebagai feminis Islam. Saya sebenarnya menulis secara kritis tentang… pembentukan feminisme, yang sangat sekuler, sangat “putih”, dan sangat bias kelas dan elitis bagi saya yang seorang Afrika-Amerika. Ada banyak yang perlu ditelaah lebih dalam.
Sebenarnya pada tahun 1995 di Beijing World Conference of Women, jelas bahwa permasalahan perempuan Muslim diletakkan pada semacam medan perang antara feminis sekuler dan Islamis. Dan para Islamis seratus persen memihak kepada interpretasi patriarkal Islam dan itu tidak dipermasalahkan karena Islam itu sempurna. Sementara, yang sekuler seratus persen mengatakan “kita tidak mengenal agama” dan mereka bersepakat bahwa kita tidak boleh menyatukan Islam dan feminisme. Sampai akhirnya ada yang berada di tengah-tengah mengatakan, “Siapa yang mendefinisikan Islam dan bagaimana mereka mendefinisikannya? Dan siapa yang mendefinisikan feminisme atau hak asasi manusia? Bagaimana mereka mendefinisikannya? Dan kapan kita akan diberi otoritas sebagai muslim dan perempuan untuk mendefinisikan feminisme, Islam, dan hak asasi manusia untuk diri kita sendiri?” Dan saat itulah perubahan datang bahkan dalam pekerjaan Sisters in Islam, hak untuk menggunakan otoritas bukan hanya untuk mendefinisikan feminisme, tetapi juga untuk mendefinisikan Islam dan itu telah menjadi landasan kerja kami.
Baca juga: Kelompok Tarbiyah: Bagaimana Gerakan Islam Konservatif Menembus Kampus
Karena sebelum itu, orang-orang hanya mengatakan, “Ya, memang Islam seperti itu.” Islamnya siapa? Bagaimana Islam mereka definisikan? Dan dari mana mereka mendapatkan otoritas itu? Tiga pertanyaan itulah yang perlu ditanyakan terus menerus karena orang-orang dengan strategis membuat batasan untuk Islam sesuai dengan agenda yang mereka miliki, dan patriarki adalah salah satu agenda yang memiliki sejarah panjang. Jadi orang-orang hanya menerima begitu saja tanpa mengkritiknya. Dan ketika kami menantang sejarah itu untuk mengatakan, “Itu memang satu cara untuk melakukannya, tetapi ada cara lain juga,” dan inilah sumber-sumbernya, inilah metodologi untuk mendukung ide bahwa ada banyak jalan lain dalam Islam, pada saat itulah kami menjadi lebih berdaya, tetapi juga jauh lebih kontroversial.
Saya bisa memahami apa yang Anda sebut medan perang karena Magdalene sering kali membahas tentang trajektori itu dan meredefinisikan Islam, seperti apakah feminisme dalam Islam sebuah paradoks, atau apakah benar ada titik pertemuan. Dan kami diserang dari kanan oleh yang mengatakan kami liberal, dan dari kiri yang mengatakan kami pembela Islam.
Ya, itu yang terjadi kepada kami di tahun 90-an, dan ternyata secara strategis merupakan titik perubahan yang sangat baik, karena kemudian kami harus mencari tahu tentang identitas kami. Karena para Islamis mengatakan bahwa kami feminis sekuler, sementara feminis sekuler mengatakan bahwa kami Islamis. Kami bukan keduanya. Jadi secara teknis, kami tidak memiliki identitas, dan mengklarifikasi, baik untuk diri kami sendiri maupun gambaran hasil kerja kami dan hubungan kami dengan komunitas besar, membutuhkan 10-15 tahun lagi. Ketika Musawah diluncurkan, kami sudah menjadi bagian dari gerakan global.
Jadi sekarang, kami mengajarkan metodologi yang menggabungkan Islam dan hak asasi manusia demi kehormatan perempuan. Ini perjalanan yang menyenangkan buat saya karena semua hal terbuka sendiri, membuat saya bisa berkembang, berubah, serta belajar dan mengajar, dan pada saat yang sama menjadi bagian dari gerakan untuk mengimplementasikan apa yang sedang dikembangkan dan yang sedang diajarkan. Jadi iya, itu sebuah anugerah besar. Tetapi saya tidak mengetahuinya ketika baru memulainya, saya waktu itu hanya tahu bahwa disertasi yang saya tulis menjadi buku. Saya baru mendapatkan bayaran royalti, dua kali setahun dari Quran and Women, buku ini masih menghasilkan uang. Sudah sekitar 27 tahunan… jadi benar-benar anugerah jika saya pikir-pikir lagi.
Musawah fokus kepada hukum keluarga, mengapa begitu?
Alasannya adalah kami harus bekerja dalam sebuah instrumen, mengimplementasikannya dalam konteks negara bangsa. Di banyak negara muslim atau negara non-muslim—dengan jumlah muslim besar namun minoritas—akan ada pengadilan terkait isu-isu yang dekat dengan perempuan dan kesentosaan mereka, seperti pengadilan untuk isu hukum agama, atau hukum status pribadi. Dalam pemahaman fundamental, dalam pengadilan semacam itu, laki-laki adalah pemegang otoritas utama.
“Tantangan bagi orang-orang di arus utama adalah ketika landasan perlawanan terhadap ketimpangan antara perempuan dan laki-laki bukanlah feminisme liberal sekuler, melainkan berbasis Quran.”
Untuk menghilangkan superioritas laki-laki di tingkat pragmatis berarti menantang hukum-hukum yang mendukung pemikiran yang sebenarnya melanggar kesetaraan konstitusional, padahal itu telah dijamin bagi perempuan dalam konteks negara-bangsa langsung. Jadi secara strategis, itu adalah alat yang kuat, tetapi dalam keadaan lain itu terlalu besar.
Kami bekerja sejalan dengan proyek-proyek yang sangat spesifik. Contohnya, setiap negara harus melapor secara resmi ke CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tentang kondisi kesejahteraan perempuan di tempat mereka, tetapi setiap negara juga diperbolehkan memiliki laporan bayangan. Laporan bayangan adalah laporan tidak resmi yang dibuat aktivis perempuan setempat yang menyatakan bahwa mereka telah berkecimpung dalam isu-isu tertentu dan memaparkan kondisi yang sebenarnya terjadi.
Ini menjadi alat yang sangat kuat karena meletakkan negara bangsa di bawah koneksi internasional yang memberdayakan perempuan setempat untuk berkomunikasi dengan negara. Tetapi itu pun memakan waktu karena CEDAW bukan bagian dari PBB dan seluruh lembaganya tidak terkualifikasi untuk menginterogasi interpretasi Islam yang ada. Mereka juga percaya bahwa tugas mereka adalah untuk tidak campur tangan.
Salah satu cara Musawah bekerja sama dengan CEDAW dan dalam agenda antar-negara bangsa untuk perempuan adalah dengan mengajarkan pihak-pihak di PBB mengenai definisi-definisi Islam. Misalnya, siapa yang mengartikannya dan bagaimana, dan jika kami mengatakan diartikan oleh suatu hal, mengapa hal-hal ini tidak termasuk dalam prinsip-prinsip Islam tertentu atau dalam dokumen-dokumen internasional dan sebagainya. Itu memakan banyak waktu dan pemahaman lama, dan tidak seratus persen diganti, tetapi pengajaran kami semakin efektif seiring berkelanjutannya kegiatan kami.
Pada akhirnya, bahkan di PBB, mereka mengatakan, “Kalian mengartikan Islam, bagaimana dengan cara-cara ini berdasarkan prinsip-prinsip ini” dan lalu kami tidak dapat mendatangi badan ini dan mengatakan, “Ya kalian tidak dapat melakukan apa-apa terkait hal tersebut karena ini berkenaan dengan Islam” karena badan ini juga menanyakan “interpretasi Islam siapa yang kalian gunakan?”. Prosesnya perlahan, tapi itu terjadi.
Salah satu isu yang sensitif di antara perempuan Muslim adalah hijab. Apa yang sebenarnya dinyatakan dalam Quran tentang hijab?
Pertama-tama, tidak ada perkataan tentang hijab dalam Quran. Ada beberapa pernyataan dalam Quran tentang pakaian perempuan dan itu seratus persen diambil dari jenis pakaian yang ada pada zaman dan tempat saat itu, dan saya menggunakannya berdasarkan hal yang saya presentasikan di dua sesi pertama di sini. Saya menggunakannya sebagai cerminan prinsip umum, yaitu kesederhanaan. Namun kesederhanaan tidak dapat dibatasi hanya pada satu bentuk.
Saya tidak percaya bahwa hijab adalah persyaratan dalam Islam. Tetapi hijab adalah pilihan pribadi untuk pekerjaan-pekerjaan publik saya. Saya tidak mengenakannya di rumah, saya tidak mengenakannya di lingkungan rumah saya, saya tidak mengenakannya ketika berbelanja, tetapi di muka publik, saya mengenakannya dan itu karena saya memiliki hubungan berbeda dengan simbol-simbol. Ini salah satu representasi Islam yang paling jelas dan simbolis. Dan dengan cara itu, saya menganggapnya sebagai tampilan publik. Tetapi, saya tidak melihatnya sebagai persyaratan atau satu-satunya bentuk kesopanan.
Tetapi, karena hijab sangat dipolitisasi dengan cara yang negatif, di bawah naungan Islamofobia, saya semakin terdorong untuk memakainya. Misalnya, setelah 9/11, saya selalu diperiksa lebih lama, karena saya mengenakan hijab dan rambut saya juga dreadlocks panjang, rasanya seperti mimpi buruk. Saya kadang hendak memilih tidak mengenakannya karena orang-orang mengatakan, “Mengapa kamu tidak melewati (pemeriksaan) saja dan melepaskannya?” Lalu saya berpikir, “Tidak, tidak, kenapa saya tidak mengidentifikasi dengan orang-orang yang paling ditindas?”
Baca juga: Al-Quran Tak Ajarkan Membenci Kelompok LGBT: Akademisi Muslim
Saya juga mengidentifikasi diri dengan mengenakan hijab, dan baru-baru ini saya pergi ke Bali atau tempat semacam itu, dan saya sadar, “Oh, aku ada di negara berpenduduk mayoritas Muslim, mereka akan membiarkanku memakainya, dan kalaupun tidak memakainya, aku juga tidak kena masalah apa-apa.” Jadi, untuk pertama kalinya dalam 18 tahun, saya melewati petugas keamanan tanpa mengenakan hijab. Itu sangat berarti bagi saya, karena kita harus melihat bahwa politik juga terlibat dalam hal pakaian ini, dan saya berpikir bahwa pakaian saya tidak harus menyinggung kenyamanan para Islamofobik. Kamu tidak dapat menentukan caraku berpakaian. Bahkan kebencianmu dan hukummu mengatakan bahwa kau tidak dapat menentukan caraku berpakaian. Jadi, tentu saya percaya pada pilihan untuk mengenakan atau tidak mengenakan sesuatu. Karena saya pernah mengenakan dan tidak mengenakan hijab, saya hidup di tempat penuh pilihan, dan di situlah saya berada.
Bagaimana dengan niqab atau burqa?
Pertama-tama, saya sendiri pernah memilih mengenakan niqab selama empat tahun. Saya tinggal di AS dan kemudian saya pindah ke Libya dan saya tetap mengenakannya di sana. Dan ketika di Libya, saya berhenti mengenakannya. Namun, saat itu memungkinkan juga untuk mengenakan niqab berdasarkan pilihan juga. Sayangnya, karena politisasi diskusi tentang hal ini, masih jauh perjalanan kita untuk mengetahui apa yang dapat seseorang lakukan jika mereka benar-benar bebas dalam hal mengenakan apa pun yang mereka inginkan, tidak ada yang mengkritik, apakah akan menjadi hal yang sangat penting? Bahkan untuk pemakainya? Sama dengan mereka yang menolaknya? Saya tidak tahu.
Jadi, sampai kita benar-benar menerima orang sepenuhnya dengan pilihan mereka, kita tidak dapat mengetahui spektrum sepenuhnya dari perempuan Muslim dan pakaian mereka. Kita tidak bisa tahu. Jadi, saya mendukung gerakan di Iran seperti halnya saya mendukung protes soal pelarangan burkini di Perancis. Mereka menekankan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tentang perempuan yang mengatakan ini tubuhku, pilihanku.
Sejak Anda tinggal di sini, bagaimana Anda melihat konservatisme yang meningkat?
Ini menarik karena banyak orang telah memberitahu saya tentang konservatisme di sini. Saya agak terisolasi di Bogor dan tidak berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Tetapi karena saya pernah tinggal di Malaysia, sebenarnya kondisinya lebih buruk di Malaysia. Malaysia kelihatannya sedikit lebih modern, sedikit lebih sejahtera secara ekonomi, tetapi Islamis ekstremnya lebih marak.
Jadi, saya sudah hidup di tengah itu, dan kelihatannya di Indonesia tidak semarak itu, namun memang meningkat. Akan sangat baik bagi orang-orang Indonesia untuk menghentikan itu dengan menyuarakan berbagai jenis representasi Islam yang toleran dan beragam. Caranya dengan menekankan kembali sikap toleran yang sudah secara historis ada pada orang Indonesia sejak lama. Kita harus mendorong suara itu menjadi yang paling keras di publik.
“Bandingkan setiap ayat dengan ayat-ayat lainnya. Jika kita menemukan kutipan atau ide yang bertentangan satu sama lain, pilih yang selaras dengan kesetaraan dan keadilan. Jika orang lain membaca dengan (sudut pandang) patriarki, kamu dapat membaca dengan kesetaraan dan keadilan. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan kontradiksi adalah dengan berpikir.”
Masalahnya, kita memberi perhatian lebih ke suara-suara ekstrem dan dengan demikian, jumlah mereka terlihat lebih besar dari aslinya. Atau mereka memiliki dukungan lebih besar. Mereka petarung, mereka membuat orang takut, jadi kita perlu membanjiri publik dengan pembicaraan tentang Islam Indonesia yang generik. Baru saat itulah, konservatisme tidak akan terlihat begitu membuat kewalahan. Itu memang membuat kita kewalahan secara negatif, dan itulah bagian dari dampaknya. Kita seharusnya tidak menginginkan dampak itu, dan menurut saya mereka tidak memiliki pengaruh sebesar yang seolah-olah mereka miliki. Tetapi mereka memiliki cukup daya untuk membuat orang lain takut dan itulah pengaruhnya. Itulah sebabnya kita perlu menyebarkan pesan yang lebih ramah.
Tetapi ini mengkhawatirkan, sekolah-sekolah negeri, misalnya, menjadi lebih konservatif. Dan ke mana pun kita pergi, lebih banyak perempuan mengenakan hijab. Teman saya mengatakan bahwa ketika ia pergi ke gereja, ia terkejut, “Wah, aneh tidak ada yang mengenakan hijab. Eh, sebentar, aku kan di gereja.”
(Tertawa) Itu benar, ke mana pun kita pergi kita selalu melihatnya…. Memang tambah banyak. Lucu juga karena kalau saya jalan pagi di kompleks rumah, saya selalu mencoba jalan pagi karena usia dan radang sendi saya, dan biasanya saya pakai kaos, kadang celana gym. Dan terkadang saya berpikir, karena semua orang di lingkungan sekitar mengenakan hijab, “Apakah kalian ini sedang pamer?” Dan sebenarnya, pada waktu saya keluar, ada sangat sedikit orang yang juga keluar, dan saya selalu mengucapkan, “Pagi, Bu/Pak. Apa kabar, Ibu” hanya mencoba untuk ramah, tetapi kesempatan untuk saya berjalan dengan kaos saja itu jarang. Saya tidak dapat melakukannya di negara seperti Amerika Serikat karena ada hal lain yang terjadi di sana dan saya perlu merepresentasikan diri sebagai muslim karena saya tidak ingin hal lain terjadi… Saya muslim di sini, saya tidak perlu pakaian tertentu untuk menunjukkannya.
Saya pergi ke masjid dengan pakai kaos, saya hanya membawa selendang untuk salat, dan saya melepasnya dan melakukan macam-macam, saya akhirnya merasa utuh. Tubuh saya utuh. Saya tidak berperang dengan tubuh saya sepanjang waktu, jadi saya akan memiliki pilihan itu sebagai perempuan Muslim. Saya juga tidak perlu bertarung seperti itu di sini, jadi sangat nyaman. Tetapi kadang-kadang saya khawatir, saya berpikir, “Apakah ini pamer?” Karena saya tidak akan pernah, maksud saya, berdiam di pulau… Saya pernah ke Madagaskar, yang merupakan pulau, kami ada di pantai yang privat, jadi saya mengenakan baju renang biasa, seperti one-piece, tetapi bukan burkini. Dan teman saya yang juga muslim dari Inggris, suka pergi ke desa untuk membeli makanan, dan dia sering hanya pakai kemeja saja dan baju renang. Saya tidak bisa sejauh itu, saya harus mengenakan lebih banyak pakaian. Saya tidak bisa pergi dengan dada terbuka, dengan baju renang saya, jadi saya harus pakai kaos dulu. Saya tidak nyaman dengan tingkat berpakaian tertentu. Bahkan di pulau, kalau saya mau bertemu orang lain, saya tidak bisa memakai baju renang seperti itu saja. Jadi sangat lucu karena saya lebih memperhatikannya seiring waktu bahwa hak untuk membuat keputusan pada tubuh saya sendiri jarang diberikan. Jadi, ketika saya berjalan di sekitar rumah saya, saya bisa melakukannya, tetapi ya, saya tidak dapat melakukan itu di banyak tempat.
Tapi iya, saya sadar ada lebih banyak (orang mengenakan hijab). Sejak pertama kali saya tinggal di sini, tahun 2008-2009, jadi dari sepuluh tahun itu, saya menyadari ada lebih banyak (pemakai hijab). Karena saya juga memakai dan melepas sesuka hati juga, dan saya baru melakukannya sejak saya di sini. Tinggal di sini untuk pertama kalinya, saya baru menyadari bahwa saya tidak perlu membela Islam. Saya bukan poster berjalan untuk Islam, saya hanya seseorang dalam komunitas ini, dan kebanyakan dari mereka muslim, jadi saya lega. Jadi, pengalaman pertama saya di sini tanpa hijab dan saya merasa OK-OK saja. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya tidak mungkin pergi keluar pakai tank top, itu bukan saya. Saya kembali ke sini agar dapat menikmati melepasnya. Saya bukan di sini untuk kesenangan atau inspeksi siapa pun, jadi jika kamu tidak suka saya tidak pakai hijab, itu masalahmu. Sama seperti yang saya katakan pada orang-orang Amerika, jika kamu tidak menyukai saya pakai hijab, itu masalahmu.
Kami juga mendapatkan lumayan banyak artikel dari perempuan-perempuan yang melepas hijab dan mereka mendapatkan tanggapan negatif.
Saya dulu bilang bahwa orang memberi tanggapan negatif karena mereka iri, “Kenapa kamu boleh melepas pakaianmu sementara aku harus memakai milikku?” Ya, itu masalahmu, ya.
Apakah Anda melakukan penelitian di sini?
Di tahun pertama ini, harus saya akui, saya menikmati masa pensiunan, jadi saya hanya cari teman untuk diajak safari, saya akan ke Afrika Selatan bulan depan. Saya menikmati tidak perlu melakukan apa pun kecuali yang ingin saya lakukan, karena saya workaholic dan saya memiliki lima anak. Jadi, saya belum pernah memiliki kesempatan untuk melakukan apa pun yang ingin saya lakukan selama lebih dari semenit, jadi saya menikmatinya.
Namun saya perlu menulis, itulah alasan saya meninggalkan Amerika Serikat. Saya tidak berencana untuk tinggal, tetapi semua berjalan dengan sangat baik. Tapi ya, saya ingin menulis dari sebuah riset tentang keberagaman seksual dan martabat manusia, dan saya juga mengajukan proposal untuk sebuah buku tentang ide-ide progresif terkait puncak spiritualitas dan praktik-praktik ibadah. Semacam versi progresif dari rukun Islam, agar saya dapat membahas imam perempuan, dan juga membahas cara-cara orang menghubungkan diri kepada Allah, yang melibatkan rukun Islam yang juga meluas jauh.
Setelah saya beribadah haji, saya mengajukan proposal yang akhirnya diterima. Baru satu bab, kemudian saya tidak pernah melanjutkannya. Jadi, saya ingin meneruskan membuat buku itu, terkadang ketika orang berpikir tentang sebuah buku, untuk mengetahui bahwa imam perempuan itu ada. Karena jika mempelajari tentang imam perempuan, biasanya harus dalam diskusi marginal, pada aspek marginal, tetapi tidak. Ini hanya bagian dari doa, jadi Insya Allah. Doakan saja, karena idenya bagus tetapi disiplinnya sulit.
Artikel ini diterjemahkan dari versi aslinya dalam bahasa Inggris.