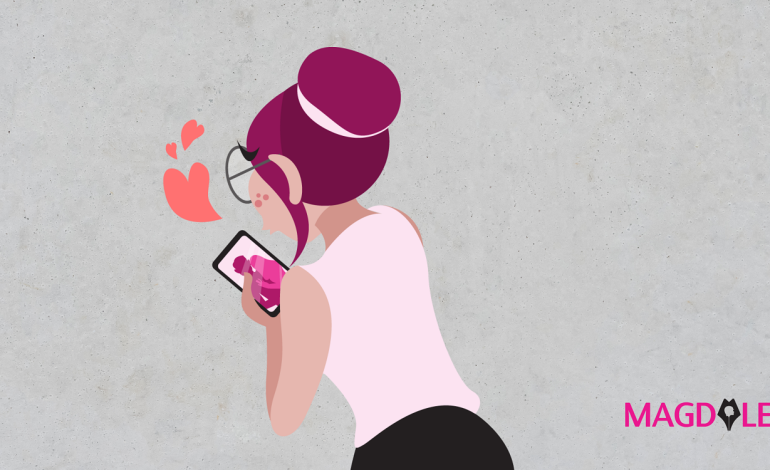5 Artikel Pilihan Sepekan: ‘The Tinder Swindler’ hingga Idola Lesbian
‘Tiga Diskusi Menarik dari Dokumenter ‘The Tinder Swindler’
Di minggu pertama rilis, The Tinder Swindler dapat respons yang cukup baik. Nama Tinder, aplikasi cari jodoh yang populer di kalangan milenial dan Generasi Z ini tentu saja punya peran. Tak sedikit penontonnya, atau mereka yang mengulas dokumenter ini di media sosial, tertarik menonton karena teasing “penipu” dan “Tinder” dipampang sebagai judul.
Diskusi yang muncul setelah menonton pun ternyata cukup beragam. Banyak yang suka, ikut geram, atau bersimpati pada korban-korban Hayut. Namun, tak sedikit yang melabeli para korban perempuan ini bodoh, kecuali satu orang (yang muncul di akhir-akhir dokumenter).
Baca selengkapnya di sini.
‘Comphet’: Lesbian Juga Boleh Punya Idola Laki-laki
Compulsory hetereosexuality atau comphet digunakan untuk menjelaskan lingkungan kita yang menganggap heteroseksual sebagai standar hidup dan satu-satunya orientasi seksual yang valid. Sehingga, semua yang di luar dari heteronormatif dianggap aneh atau tidak semestinya.
Zakia Nisa dari organisasi Solidaritas Perempuan Sabay Lampung mengatakan, comphet tidak hanya didorong heteronormativitas. Gagasan ini berasal dari pola pikir patriarkal yang mengagung-agungkan laki-laki. Sehingga identitas gender dan orientasi seksual lain, selain heteroseksual, tidak dianggap valid.
Simak artikelnya di sini.
‘Silent Treatment’ Orang Tua ke Anak: Kekerasan Emosional yang Tak Terlihat
Saya duduk di kelas 5 sekolah dasar (SD), ketika pertama kali menerima silent treatment dari ibu. Jika tak salah ingat, penyebabnya adalah “penyalahgunaan” uang yang seharusnya digunakan untuk memesan pin bergambar pada wali kelas. Alih-alih menggunakan Rp25 ribu itu sebagaimana mestinya, saya menggunakannya untuk jajan.
Namun, itu bukan satu-satunya silent treatment yang orang tua berikan pada saya. Memasuki usia 20 tahun, saya menyadari tindakan itu dianggap lumrah dan layak dilakukan setiap terjadi kesalahan. Tanpa kata maaf, apalagi membicarakan jalan keluar.
Simak artikelnya di sini.
Negara ‘Ngadi-ngadi’, Polisi Mengompori, Perempuan Wadas Teguh Melawan
Sebenarnya celaan tentang status saya yang jomblo tidak pernah benar-benar mengganggu. Namun, semua berubah saat saya sakit dan harus berobat ke dokter. Saking jarangnya sakit, kartu berobat di klinik kecil, bilangan Pamulang, Tangerang Selatan saya terselip entah kemana. Karena kartu raib, saya terpaksa mengisi kembali formulir berisi data-data pribadi.
Tiba-tiba juru rawat yang mengurus administrasi kembali mendatangi saya di tempat duduk ruang tunggu dan meminta isian formulir dilengkapi. “Tolong diisi nama suaminya,” katanya. Saya menjawab,”Tidak ada Mbak.”
Namun, sepertinya perawat tersebut tidak puas dengan jawaban saya. Dari pandangannya, ia terkesan menuntut saya untuk mengisi kolom nama suami, entah bagaimana caranya.
Selengkapnya di sini.
The Real Problems behind Telling Women to be Confidence
The need for self-confidence has become so much a part of our common sense that it is presented as beyond debate. Cast as a feminist intervention, and aimed at the obvious good of empowering women, who could possibly be against it?
But, as we argue in our new book, the problem with these imperatives, programmes and interventions – what we call Confidence Culture – is that they encourage us to undertake extensive work on the self and direct us away from calling out structural inequalities that are the real source of the problems women face.
Read the article here.